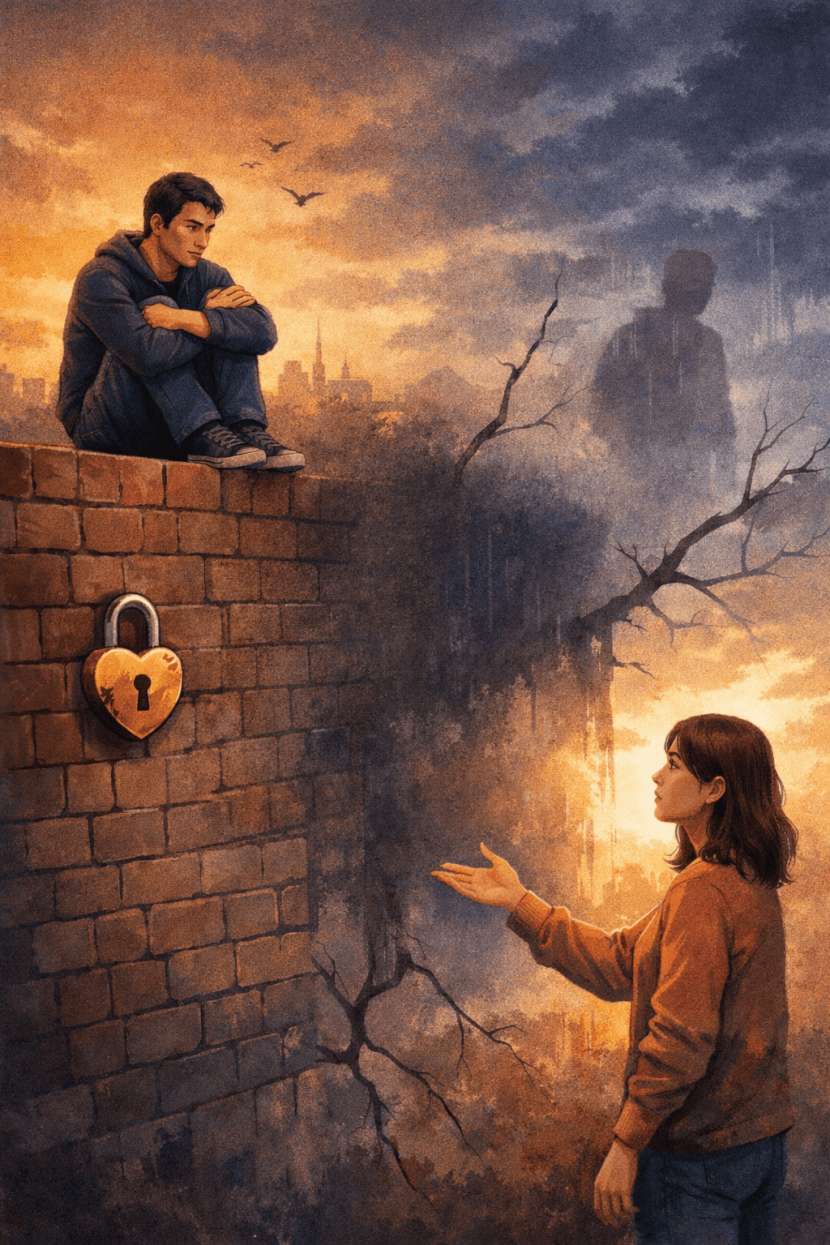Litza Nadya Marita
Litza Nadya Marita
Dari Seruan Melawan ke Rasa Malu Bangsa: Dua Puisi, Dua Zaman
Sastra | 2025-12-29 20:28:16
Dalam kajian sastra, puisi kerap dipahami bukan sekadar sebagai ekspresi personal penyair, melainkan sebagai produk sosial yang lahir dari relasi antara pengarang, masyarakat, dan kekuasaan. Pandangan ini sejalan dengan teori sosiologi sastra, yang menempatkan karya sastra sebagai refleksi sekaligus kritik terhadap realitas sosial tempat ia dilahirkan. Dua puisi yang merepresentasikan fungsi tersebut adalah “Peringatan” karya Wiji Thukul (1986) dan Malu (Aku) Jadi Orang Indonesia” karya Taufiq Ismail (1998). Keduanya menyuarakan kegelisahan terhadap ketimpangan sosial dan represi politik, namun dengan gaya yang berbeda sesuai dengan zaman masing-masing.
Menurut pemikiran Lucien Goldmann, karya sastra mencerminkan pandangan dunia (world view) kelompok sosial tertentu (Faruk, 1999). Dalam puisi Wiji Thukul merepresentasikan pandangan dunia rakyat tertindas yang masih berada di tengah tekanan kekuasaan, sementara puisi Taufiq Ismail merepresentasikan pandangan intelektual kritis yang berada pada fase refleksi pasca-represi. Perbedaan posisi sosial dan temporal inilah yang memengaruhi cara kedua penyair bersuara.
Puisi “Peringatan” karya Wiji Thukul terbit pada tahun 1986, ketika rezim Orde Baru berada dalam fase paling represif. Pada periode ini, pembatasan kebebasan berpendapat berlangsung ketat; kritik terhadap penguasa dapat berujung pada intimidasi, pemenjaraan, bahkan penghilangan paksa. Wiji Thukul sendiri hidup sebagai bagian dari kelompok rakyat kecil dan aktivis yang mengalami langsung tekanan tersebut. Karena itu, world view yang muncul dalam puisinya adalah pandangan dunia rakyat tertindas yang masih berada di tengah situasi represi, negara tidak lagi hadir sebagai ruang dialog, melainkan sebagai otoritas yang memutuskan kebenaran secara sepihak.
“Apabila usul ditolak tanpa ditimbang Suara dibungkam kritik dilarang tanpa alasan” (Wiji Thukul, 1986)
Bait tersebut tidak sekadar menggambarkan penolakan terhadap usulan rakyat, melainkan tentang matinya rasionalitas politik. Frasa “tanpa ditimbang” menandakan hilangnya proses deliberasi, sementara “kritik dilarang tanpa alasan” menunjukkan bahwa kekuasaan bekerja bukan melalui argumentasi, melainkan melalui represi. Dalam konteks ini, puisi berfungsi sebagai rekaman kesadaran kolektif rakyat kecil yang menyadari bahwa jalur-jalur konstitusional tidak lagi dapat diandalkan.
Lebih jauh, penggunaan diksi seperti “dibungkam” dan “dilarang” mencerminkan bahasa kekuasaan Orde Baru yang menstigmatisasi kritik sebagai ancaman keamanan. Dengan demikian, konteks yang dibangun oleh bait ini adalah situasi sosial di mana berbicara menjadi tindakan berisiko, dan diam sering kali dipilih sebagai strategi bertahan hidup.
Ketika kondisi tersebut mencapai titik jenuh, puisi ini tidak lagi bergerak pada ranah deskriptif, melainkan berubah menjadi pernyataan sikap, hal ini tampak pada penutup puisi.
“Maka hanya ada satu kata: lawan!” (Wiji Thukul, 1986)
Seruan ini harus dibaca dalam konteks kegagalan total ruang dialog yang telah digambarkan pada bait-bait sebelumnya. Kata “maka” berfungsi sebagai penanda keputusan logis untuk melawan bukan pilihan emosional, melainkan konsekuensi rasional dari sistem yang menolak mendengar. Dengan demikian, seruan “lawan!” bukan sekadar ajakan individual, tetapi artikulasi world view rakyat tertindas yang memahami bahwa perubahan tidak mungkin lahir dari mekanisme yang telah dibajak oleh kekuasaan.
Sebaliknya, puisi “Malu (Aku) Jadi Orang Indonesia” karya Taufiq Ismail terbit pada tahun 1998, bertepatan dengan runtuhnya Orde Baru. Tahun ini menandai fase transisi, ketika berbagai keburukan rezim—korupsi, kolusi, pelanggaran HAM—mulai dibicarakan secara terbuka. Taufiq Ismail berbicara bukan dari posisi rakyat yang sedang berteriak di tengah represi langsung, melainkan dari posisi intelektual yang melakukan refleksi historis atas perjalanan bangsa. Puisi ini bekerja sebagai evaluasi moral pasca-kekuasaan, bukan sebagai seruan perlawanan segera.
Peristiwa tersebut pertama-tama dibangun melalui memori personal yang ditempatkan dalam sejarah kolektif bangsa, sebagaimana tampak pada bait awal puisi.
“Dulu dadaku tegap bila aku berdiri Mengapa sering benar aku merunduk kini” (Taufiq Ismail, 1998)
Bait ini tidak hanya menyatakan perubahan perasaan personal, tetapi membangun jarak temporal antara masa lalu dan masa kini. Frasa “dulu” dan “kini” menandai pergeseran Sejarah, dari masa idealisme revolusi menuju masa kekecewaan. Subjek lirik di sini adalah warga negara yang pernah mengalami fase kebanggaan nasional, sehingga rasa malu yang muncul bersifat reflektif dan berakar pada kesadaran historis, bukan reaksi spontan.
Peristiwa sosial puisi kemudian dipertegas melalui metafora keruntuhan moral dan hukum dalam bait berikut.
Langit akhlak rubuh, di atas negeriku berserak-serak Hukum tak tegak, doyong berderak-derak (Taufiq Ismail, 1998)
Metafora ini membangun gambaran kerusakan struktural, bukan sekadar kegagalan individu. Kata “langit” menandakan nilai-nilai luhur yang seharusnya menaungi kehidupan bersama, sementara “rubuh” dan “berserak-serak” menunjukkan kehancuran yang sistemik. Dalam konteks tahun 1998, bait ini merefleksikan terbukanya praktik korupsi, manipulasi hukum, dan penyalahgunaan kekuasaan yang sebelumnya ditutup rapat oleh negara.
Puisi ini lalu bergerak pada fase inventarisasi kejahatan sosial dan politik melalui deretan larik panjang. Strategi ini tidak bertujuan menciptakan efek estetis semata, melainkan membangun kesadaran tentang akumulasi dosa struktural negara. Puncak refleksi tersebut berulang dalam larik penutup:
Malu aku jadi orang Indonesia. (Taufiq Ismail, 1998)
Pengulangan larik ini berfungsi sebagai vonis moral, bukan sekadar ekspresi emosi. Rasa malu di sini tidak diarahkan kepada identitas bangsa itu sendiri, melainkan kepada praktik kekuasaan yang telah mengkhianati nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Dalam konteks sosiologi sastra Lucien Goldmann, puisi ini mengekspresikan world view kelompok intelektual kritis yang berada pada fase pasca-represi, kelompok yang tidak lagi hanya melawan, tetapi menilai, mengadili, dan mengingat.
Dengan demikian, berbeda dari puisi Wiji Thukul yang lahir di tengah tekanan langsung dan bergerak menuju seruan perlawanan, “Malu (Aku) Jadi Orang Indonesia” membangun konteks refleksi historis dan tanggung jawab moral. Puisi ini mengajak pembaca untuk tidak sekadar marah, tetapi memahami bahwa rasa malu adalah langkah awal untuk membangun kesadaran etis sebagai warga negara.
Dengan demikian, perbedaan pandangan dunia dalam kedua puisi ini tidak hanya ditentukan oleh gaya personal penyair, tetapi oleh posisi sosial dan temporal mereka. Taufiq Ismail menulis setelah tekanan itu mulai runtuh, sehingga puisinya bersifat reflektif, evaluatif, dan moralistik. Wiji Thukul menulis dari dalam tekanan kekuasaan, sehingga puisinya bersifat konfrontatif dan mobilisatoris. Dalam perspektif Goldmann, perbedaan inilah yang menjelaskan mengapa dua puisi dengan tema kritik sosial yang sama dapat menghadirkan suara yang sangat berbeda, namun sama-sama autentik sebagai representasi zamannya.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.