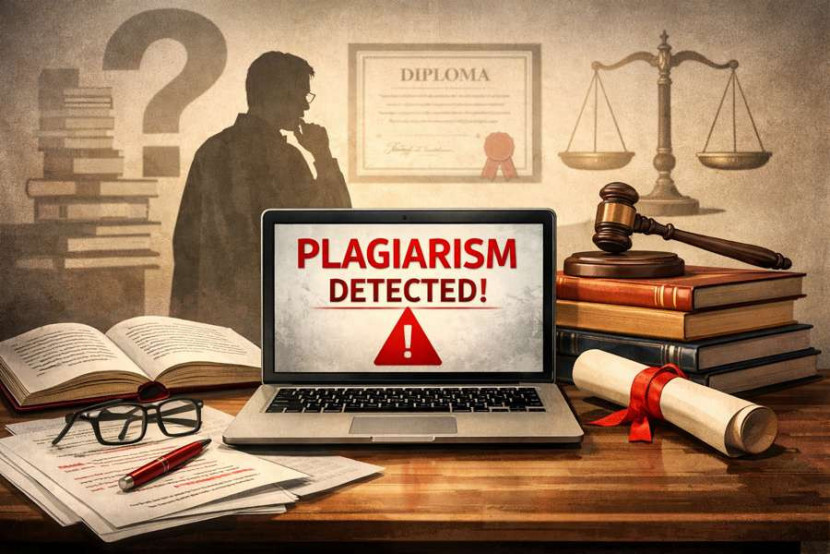AQILA ZAHRA MALIKA
AQILA ZAHRA MALIKA
Lelah Itu Prestasi? Membaca Hustle Culture dari Kacamata Kesehatan Sosial
Info Terkini | 2025-12-14 15:18:40
“Tidur nanti kalau sudah sukses.” Kalimat semacam ini sering kita temui di media sosial, poster motivasi, hingga obrolan sehari-hari. Di baliknya, tersembunyi sebuah pola hidup yang kini semakin menguat: hustle culture. Bekerja tanpa henti, selalu sibuk, dan menumpuk pencapaian dipandang sebagai tanda orang yang ambisius dan bernilai. Namun, pertanyaan pentingnya adalah: sejak kapan kelelahan dianggap sebagai prestasi?
Hustle culture bukan sekadar gaya hidup individu, melainkan fenomena sosial yang lahir dari tuntutan masyarakat modern. Dalam budaya ini, produktivitas menjadi ukuran utama kesuksesan, sementara istirahat sering kali dianggap sebagai kemalasan. Tubuh dan pikiran dipaksa terus bergerak mengikuti ritme kerja yang cepat. Tanpa disadari, cara pandang ini perlahan membentuk definisi baru tentang sehat dan sakit dalam kehidupan sehari-hari.
Dari perspektif sosiologi kesehatan, kesehatan tidak berdiri sendiri sebagai urusan tubuh, melainkan dipengaruhi oleh nilai dan norma sosial. Ketika masyarakat memuja kesibukan, rasa lelah pun dinormalisasi. Kurang tidur, stres berkepanjangan, hingga kelelahan mental sering dianggap sebagai “risiko wajar” dari orang yang ingin sukses. Padahal, kondisi tersebut merupakan sinyal bahwa tubuh sedang berada dalam tekanan serius.
Ironisnya, dalam hustle culture, sakit sering kali tidak diberi ruang untuk diakui. Seseorang yang merasa tertekan secara mental tetap diharapkan hadir, bekerja, dan tampil maksimal. Kesehatan mental masih sulit diterima sebagai alasan yang sah untuk berhenti sejenak. Banyak orang akhirnya memilih memendam kelelahan demi menjaga citra sebagai pribadi yang kuat dan produktif.
Tekanan ini semakin berat ketika dikaitkan dengan kondisi ekonomi. Bagi sebagian orang, hustle culture bukanlah pilihan, melainkan keharusan. Ketidakpastian pekerjaan, tuntutan hidup di kota, dan minimnya jaminan sosial membuat bekerja tanpa henti terasa sebagai satu-satunya jalan untuk bertahan. Dalam situasi seperti ini, kesehatan sering kali menjadi hal yang dikorbankan demi rasa aman secara ekonomi.
Masalahnya, budaya kerja semacam ini kerap memindahkan tanggung jawab kesehatan sepenuhnya kepada individu. Ketika seseorang mengalami kelelahan atau burnout, yang disalahkan adalah kurangnya manajemen diri, bukan sistem kerja yang menekan. Padahal, sosiologi kesehatan justru mengajak kita melihat bahwa penyakit dan gangguan kesehatan sering kali lahir dari struktur sosial yang tidak sehat.
Membicarakan hustle culture berarti membicarakan ulang makna kesuksesan. Apakah sukses selalu harus dibayar dengan kelelahan? Apakah bekerja tanpa henti benar-benar mencerminkan kehidupan yang baik? Pertanyaan-pertanyaan ini penting diajukan di tengah masyarakat yang semakin memuja produktivitas. Menghargai istirahat, menjaga batas kerja, dan memberi ruang bagi kesehatan mental bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk kepedulian terhadap diri sendiri.
Pada akhirnya, hustle culture mengajarkan kita banyak hal tentang bagaimana masyarakat memandang kerja, tubuh, dan nilai diri manusia. Dengan melihatnya melalui kacamata sosiologi kesehatan, kita disadarkan bahwa kesehatan bukan sekadar tanggung jawab pribadi, melainkan hasil dari budaya dan sistem sosial yang kita bangun bersama. Jika lelah terus dianggap sebagai prestasi, maka yang sedang sakit bukan hanya individu, tetapi juga masyarakatnya.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.