 Raden Arfan Rifqiawan
Raden Arfan Rifqiawan
Kode Etik Dosen di Era Deteksi Plagiarisme: Antara Sanksi, Teknologi, dan Keadilan Akademik
Eduaksi | 2026-01-29 06:18:15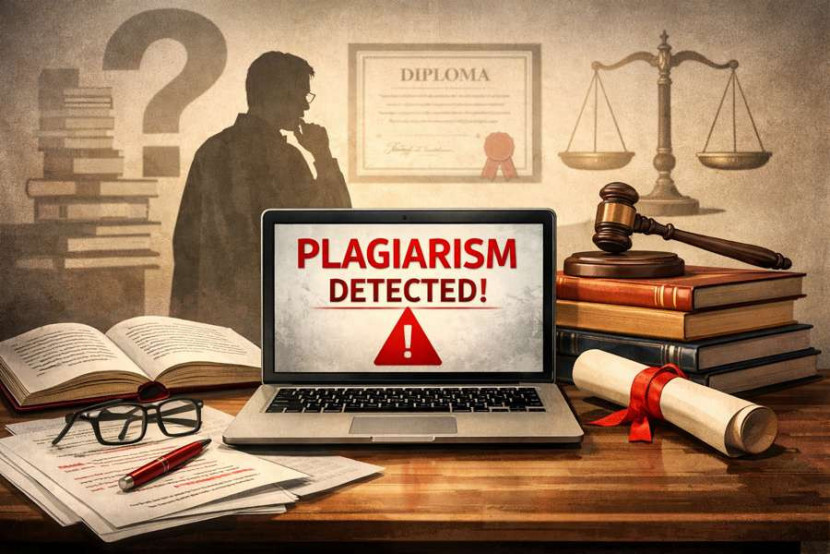
Belakangan ini, dunia pendidikan tinggi kembali diusik oleh kasus plagiarisme yang melibatkan dosen. Sanksinya tidak ringan. Regulasi membuka ruang sanksi administratif hingga akademik, mulai dari pembatalan kelulusan, pencabutan ijazah, sampai pencabutan gelar akademik dosen yang terbukti melakukan pelanggaran serius.
Penegakan kode etik tentu penting untuk menjaga marwah ilmu pengetahuan. Namun, di tengah gelombang penindakan tersebut, muncul pertanyaan mendasar yang jarang dibahas secara terbuka: apakah ekosistem akademik kita sudah cukup adil dan siap sebelum sanksi dijatuhkan?
Konteks akademik hari ini sangat berbeda dengan masa lalu. Dulu, aturan plagiarisme belum seketat sekarang. Alat pendeteksi plagiarisme pun belum secanggih dan semasif hari ini. Banyak dosen menulis dan meneliti dalam tradisi akademik yang longgar, dengan standar sitasi yang belum terinternalisasi secara kuat dan merata.
Kini situasinya berubah drastis. Undang-undang sudah tegas, regulasi makin rinci, dan teknologi deteksi plagiarisme, termasuk berbasis kecerdasan buatan, digunakan secara luas. Apa yang dulu luput, hari ini mudah terbaca. Namun, kesiapan setiap perguruan tinggi tidaklah sama.
Di sinilah persoalan keadilan mulai mengemuka. Harga lisensi perangkat pendeteksi plagiarisme seperti Turnitin atau pendeteksi AI tergolong mahal. Tidak semua universitas mampu mengaksesnya, terutama perguruan tinggi di daerah terpencil, kampus kecil, atau perguruan tinggi swasta dengan keterbatasan anggaran. Bahkan, tidak sedikit dosen yang akhirnya harus membeli lisensi secara mandiri, sesuatu yang jelas memberatkan secara ekonomi.
Masalahnya tidak berhenti di situ. Dalam kondisi keterbatasan akses tersebut, sebagian dosen berada pada pilihan yang serba salah. Mereka tetap dituntut patuh pada standar etik yang ketat, tetapi tidak difasilitasi alat resmi untuk memastikan kepatuhan itu. Pada titik ini, sebagian dosen akhirnya terjebak membeli lisensi murah yang tidak resmi dan ilegal.
Pilihan ini tentu bukan solusi. Justru sebaliknya, praktik tersebut berpotensi menurunkan akuntabilitas dosen. Hasil pemeriksaan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara institusional maupun hukum. Alih-alih memperkuat integritas akademik, praktik abu-abu semacam ini justru membuka persoalan etik baru yang lebih rumit.
Ironisnya, dosen yang sebenarnya ingin patuh dan berhati-hati justru berada dalam posisi paling rentan. Mereka dituntut menjaga integritas, tetapi tidak disokong oleh sistem yang memadai. Pada titik ini, persoalan plagiarisme tidak lagi semata soal moral individu, melainkan juga soal tanggung jawab struktural negara dan institusi pendidikan tinggi.
Perlu pula disadari bahwa tidak semua kasus plagiarisme lahir dari niat tidak jujur. Sebagian berakar dari ketidaktahuan teknis. Banyak dosen belum pernah mendapatkan pelatihan memadai tentang cara parafrase yang benar, pengelolaan referensi, batas aman kesamaan teks, atau perbedaan antara kesalahan sitasi dan pelanggaran etik. Secara niat mereka jujur, tetapi secara teknis mereka rapuh.
Karena itu, kode etik dosen semestinya tidak diposisikan semata sebagai alat penghukuman. Ia harus menjadi instrumen pembinaan. Etika akademik bukan hanya soal apa yang dilarang, tetapi juga bagaimana agar tidak melanggar secara benar dan sah.
Solusi pertama adalah penguatan literasi akademik dosen secara sistematis dan merata. Pelatihan sitasi, parafrase, manajemen referensi, dan pemahaman batas kesamaan teks harus menjadi program institusional, bukan beban individual dosen.
Kedua, negara dan pemangku kebijakan perlu hadir dalam soal akses teknologi etik akademik. Jika plagiarisme diposisikan sebagai pelanggaran serius secara nasional, maka alat deteksinya semestinya dipandang sebagai infrastruktur akademik dasar, bukan barang mewah yang hanya bisa diakses kampus tertentu.
Ketiga, alat deteksi plagiarisme perlu direposisi sebagai sarana edukasi, bukan alat vonis semata. Dosen perlu diberi ruang untuk melakukan pengecekan resmi dan legal, memperbaiki naskah, serta belajar dari hasil pemeriksaan sebelum karya dinilai secara etik.
Keempat, penegakan sanksi harus proporsional dan kontekstual. Menyalin utuh karya orang lain jelas berbeda dengan kesalahan teknis sitasi. Keadilan etik menuntut pembedaan antara niat jahat dan ketidaktahuan akademik.
Menjaga integritas akademik memang tidak bisa ditawar. Namun integritas tidak tumbuh dari ketakutan, apalagi dari ketimpangan akses yang mendorong praktik-praktik abu-abu. Ia tumbuh dari pemahaman, pembinaan, dan keadilan struktural.
Di era ketika hukum dan teknologi sudah tersedia, tantangan terbesar kita bukan sekadar mendeteksi plagiarisme, tetapi memastikan seluruh dosen, baik di pusat maupun di pelosok, memiliki akses yang adil dan legal untuk menjaga integritasnya.
Kode etik dosen, pada akhirnya, bukan hanya pagar pembatas, tetapi kompas moral yang harus ditopang oleh sistem yang adil, akuntabel, dan berkeadaban.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.





