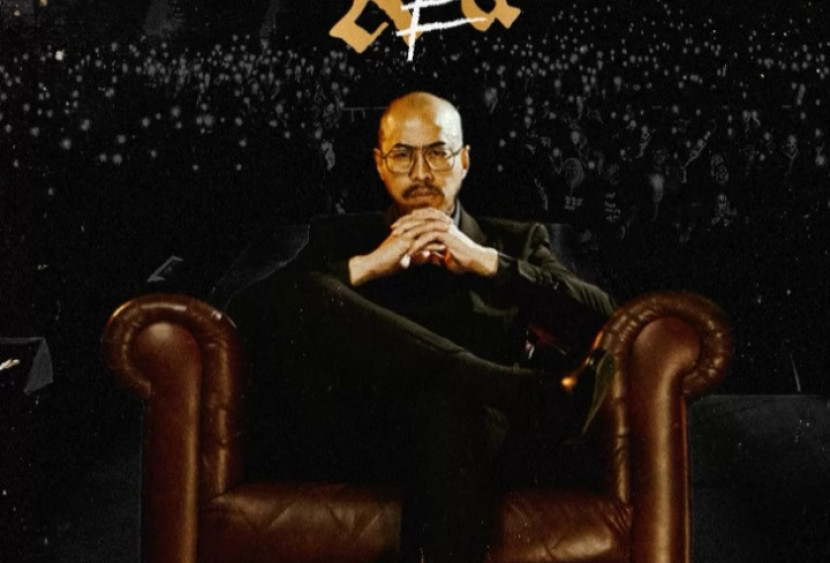Rafi Hamdallah
Rafi Hamdallah
Salah Paham Rakyat Tentang Kritik
Politik | 2026-01-04 23:46:49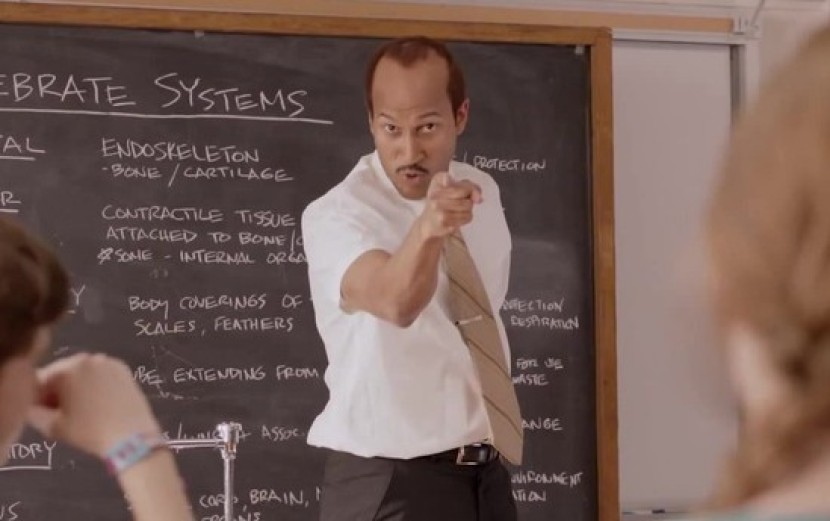
Retizen.
Mengawali tahun 2026, kita sudah dihadapkan pada persoalan yang katanya dapat mengancam kebebasan berdemokrasi kita. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang sebetulnya sudah diketok palu sejak 2023 itu kini berlaku tertanggal 2 Januari 2026 kemarin. Banyak dalih yang menyebabkan kekhawatiran akan suatu reformasi perundang-undangan hukum pidana dan hukum acara pidana, mulai dari pasal-pasal penghinaan kepada lembaga negara, pencemaran nama baik akibat kata umpatan, sampai aturan demonstrasi yang dinilai sebagai pasal karet. Kita tidak akan membahas tentang pasal mana saja yang dimaksud, tetapi ada sisi lain yang perlu kita bahas.
Pertanyaan: mengapa sampai saat ini kritik dianggap sebagai salah satu narasi buruk yang dipahami rakyat? Apakah publik masih belum memahami esensi yang fundamental dari "KRITIK."
Salah Paham Konsep Kritik
Kritik itu sebetulnya bukan apa dan siapa yang perlu disalahkan. Kritik itu berawal dari proses didaktika untuk merespons terhadap perubahan narasi yang mengganggu idealisme kita. Kritik berasal dari kata "clitikos" dalam bahasa Yunani, artinya ciri pembeda. Artinya, bila ada informasi atau pendapat yang berbeda dengan pendapat lain maka perlu adanya sistem untuk menganalisis perbedaan itu sehingga menghasilkan keputusan yang hanya bisa ditransfer lewat dialektika, apakah perlu disetujui atau ditolak. Kritik seharusnya tidak hanya sekadar meresistensikan suatu hal, tetapi berlaku juga pada sesuatu yang lain. Ini sudah sering terjadi dalam keseharian kita, mulai dari kritik di tongkrongan sampai kurasi di pameran. Misal, sebuah karya yang dipamerankan di galeri atau eksibisi bisa dikatakan bernilai jika disertai dengan asesmen, apresiasi, maupun kritik. Seorang kurator berhak menilai apakah karya tersebut layak diasesmen, diapresiasi, ataupun dikritik oleh visitornya. Artinya, semakin banyak nilainya, semakin tinggi pula rating dari karya tersebut. Hasil dari penilaian itulah yang kemudian ditulis dalam bentuk resensi atau ulasan.
Persoalannya adalah kritik yang sebetulnya diproses oleh pikiran secara objektif terkadang direspons kembali dalam bentuk sentimen atau satire, bukan argumen atau konklusi. Kritik selama ini hanya dipahami sebagai cara untuk menyatakan bantahan, kecaman, atau bahkan umpatan buruk kepada individu/pihak lain. Kritik yang seharusnya untuk mengevaluasi dan memperbaiki kesalahan dari individu/pihak lain itu justru diterjemahkan sebagai cara untuk mencederai dan menghantui nurani mereka.
Dalam sirkus politik saat ini, kritik yang paling keras justru dialamatkan oleh komunitas "rakyat" kepada otoritas "pemerintah" secara umum, tanpa disertai dengan analisis dan argumen yang jelas. Alih-alih mengkritik secara objektif, narasi atau clickbait yang dibuat oleh komentator lain justru mengarah pada hinaan atau ujaran kebencian. Bahkan tidak hanya sekadar mengkritik, sebagian rakyat kita justru menolak apapun kebijakan yang diberikan. Pemerintah tidak diberikan solusi apapun karena justru merekalah yang dianggap memberikan solusi atas kritikan dari rakyat. Begitupun dengan pemerintah pun seolah menolak narasi yang antitesis itu dengan berdalih intervensi asing atau kicauan yang menyerang personal.
Sesat Pikir dan Bias Konfirmasi dalam Kritik
Di sisi lain rakyat kita juga sebetulnya antikritik. Bila pemerintah terkesan antikritik dengan demonstrasi, hinaan, ujaran kebencian, ataupun satire kepada lembaga atau pejabat mereka; rakyat pun terkesan antikritik dengan tendensi, tradisi/kebiasaan, ego identitas, ataupun sekadar pendapat dari orang lain. Tidak perlu jauh-jauh, kesan antikritik ini juga sebetulnya familiar dalam keseharian kita.
Dalam mengkritik sebuah kebijakan, komentar, atau benda seringkali ditemukan sesat pikir maupun bias konfirmasi. Sebuah kritik sering ditanggapi dengan: (1) sentimen yang menyerang personal; (2) generalisasi topik secara berlebihan; (3) opsional yang biner/hitam-putih; (4) dalih/pengalihan isu; serta (5) narasi yang emosional. Contoh sederhananya begini:
A: Kamu seharusnya tidak boleh pacaran.
B: (1) kamu sendiri suka merokok; (2) kamu tidak ada gairah; (3) kamu lebih sayang ibu atau teman cewe?; (4) skor pernikahan di Indonesia menurun; (5) berarti tidak sayang cewe?
Begitupun dengan kasus yang lebih besar:
Warga X: Jangan buang sampah sembarangan!
Warga Y: (1) kalian sendiri makan sembarangan; (2) kalian setuju tidak ada sampah; (3) kalian bersihkan sampah ini atau kami lempari?; (4) pemerintah biarkan kayu-kayu hanyut di sungai; (5) memangnya betah rumah kalian bau?
Selain itu, terkadang kritik yang dibangun rakyat disertai dengan bias konfirmasi. Bila ada suatu pendapat dari seseorang, kita cenderung mencari dalil-dalil lain untuk menguatkan pendapat tersebut dan menolak pendapat yang lain. Misal:
Premis: seorang nenek pencuri ayam dijatuhi hukuman 6 bulan penjara.
Pro-rakyat: tidak boleh diadili, nenek itu miskin, jadi terpaksa mencuri ayam.
Kontra-rakyat: hukum positif berlaku bagi siapapun, termasuk si nenek.
Pola-pola semacam inilah yang membingungkan persepsi kita dari esensi kritik yang seharusnya. Oleh karena itu, perlu ada kejelasan dan edukasi kepada semua pihak tentang bagaimana cara mengkritik sesuatu dengan objektif, analitis, dan efektif; bukan justru membangun narasi yang subjektif, apatis, dan intimidatif. Selain itu, perlu membangun cara mengkritik yang baik dengan memberikan solusi atas setiap kesalahan sehingga sasaran yang dikritik bisa menyadari sekaligus memperbaikinya di masa mendatang.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.