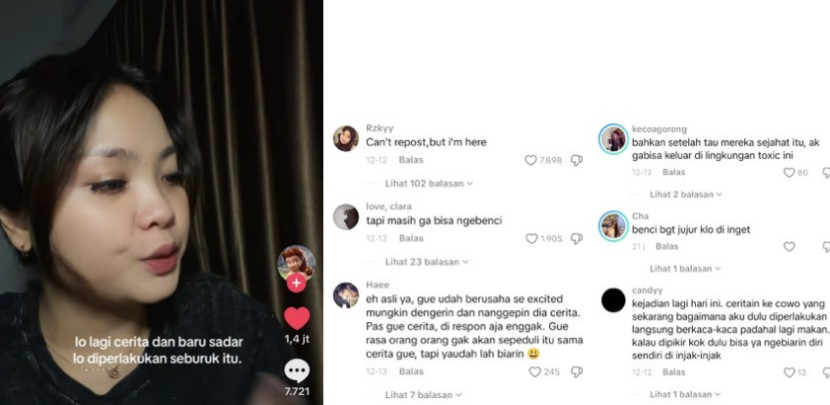Indah Ayudia
Indah Ayudia
Penegakan Etik yang Tidak Pernah Setara
Hukum | 2026-01-02 23:52:36
Ada orang yang langsung dijatuhkan karena satu pelanggaran etik. Namanya diumumkan, jabatannya dicopot, dan publik diminta percaya bahwa keadilan telah bekerja. Tetapi ada pula pelanggaran yang dibiarkan mengendap, dibahas diam-diam, lalu perlahan dilupakan. Bukan karena pelanggarannya ringan, melainkan karena pelakunya terlalu penting untuk dijatuhkan. Di situlah etika mulai kehilangan nyalinya. Bukan karena tidak ditegakkan, tetapi karena tidak pernah benar-benar setara.
Kode etik seharusnya menjadi pagar moral. Ia dirancang untuk memastikan bahwa siapa pun tanpa kecuali tunduk pada standar perilaku yang sama. Dalam rumus ideal, etika tidak mengenal jabatan, kedekatan, atau jasa masa lalu. Namun dalam praktiknya, kode etik kerap berubah fungsi. Ia tidak lagi berdiri sebagai pedoman netral, melainkan menjadi instrumen yang lentur, bisa diperketat atau dilonggarkan sesuai kebutuhan institusi.
Masalahnya bukan pada keberadaan kode etik. Hampir semua lembaga memilikinya, lengkap dengan pasal, mekanisme, dan sanksi. Masalahnya terletak pada siapa yang menafsirkan, siapa yang mengadili, dan kepentingan apa yang sedang dijaga. Dalam banyak kasus, penegakan etik berlangsung tertutup, minim transparansi, dan sarat relasi kuasa. Publik hanya disuguhi hasil akhir, tanpa pernah tahu pertimbangan moral apa yang benar-benar bekerja di balik keputusan tersebut.
Di titik inilah ketidaksetaraan mulai terasa nyata. Pelanggaran yang serupa dapat menghasilkan putusan yang sangat berbeda. Individu dengan posisi lemah sering dijadikan contoh ketegasan institusi, seolah-olah dari merekalah integritas harus dimulai. Sementara mereka yang berada di lingkar kekuasaan justru diperlakukan dengan kehati-hatian berlebihan. Etika menjadi tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas.
Penegakan etik lalu berubah menjadi pertunjukan moral. Sidang digelar, pernyataan resmi dibacakan, sanksi dijatuhkan. Semua tampak rapi dan prosedural. Namun yang sesungguhnya dijaga bukan keadilan, melainkan stabilitas dan citra. Etika tidak lagi berfungsi sebagai alat koreksi kekuasaan, melainkan sebagai tameng untuk melindunginya.
Ironisnya, sanksi etik sering kali lebih mematikan daripada sanksi hukum. Reputasi hancur, karier berhenti, nama tercatat buruk tanpa ruang pembelaan yang seimbang. Tetapi justru karena dibungkus atas nama “moral”, prosesnya jarang dipertanyakan. Seolah-olah segala sesuatu yang mengatasnamakan etika otomatis sah dan tidak boleh digugat. Padahal, etika tanpa akuntabilitas berisiko berubah menjadi bentuk kekuasaan yang paling senyap sekaligus paling keras.
Sebagian orang akan berkilah bahwa setiap kasus memiliki konteks. Bahwa perbedaan putusan adalah hal wajar. Argumen ini terdengar rasional, tetapi sering kali menutupi pola yang berulang. Ketika perbedaan perlakuan selalu menguntungkan pihak yang sama mereka yang memiliki posisi strategis maka persoalannya bukan lagi konteks, melainkan struktur. Ketidaksetaraan itu bukan kebetulan, melainkan hasil dari relasi kuasa yang dibiarkan bekerja tanpa koreksi.
Dampak terbesarnya bukan hanya pada individu yang dijatuhi sanksi, melainkan pada kepercayaan publik. Ketika masyarakat melihat bahwa etika bisa dinegosiasikan, mereka akan berhenti memandangnya sebagai nilai bersama. Etika lalu dipahami bukan sebagai komitmen moral, melainkan sebagai risiko administratif sesuatu yang berbahaya hanya bagi mereka yang tidak cukup kuat untuk dilindungi.
Di sinilah kegagalan etika menjadi lengkap. Kode etik yang seharusnya menjadi standar moral bersama justru melahirkan sinisme. Ia tidak lagi mengajarkan tentang benar dan salah, tetapi tentang siapa yang aman dan siapa yang bisa dikorbankan. Penegakan etik kehilangan ruhnya, tersisa hanya prosedur tanpa keberanian.
Penegakan etik yang tidak setara pada akhirnya bukan sekadar cacat mekanisme, melainkan krisis integritas. Ia menandai momen ketika prinsip dikalahkan oleh kepentingan, dan moral tunduk pada kalkulasi kekuasaan. Selama etika hanya berani menghukum yang lemah dan memilih diam ketika berhadapan dengan yang kuat, keadilan hanyalah slogan yang dipajang untuk konsumsi publik.
Kita boleh terus menggelar sidang etik, merilis pernyataan resmi, dan menjatuhkan sanksi simbolik. Tetapi publik tidak bodoh. Mereka melihat pola. Dan ketika kepercayaan itu runtuh, yang tersisa bukan lagi etika, melainkan kekuasaan yang telanjang tanpa legitimasi moral untuk memerintah, dan tanpa hak etis untuk menghakimi.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.