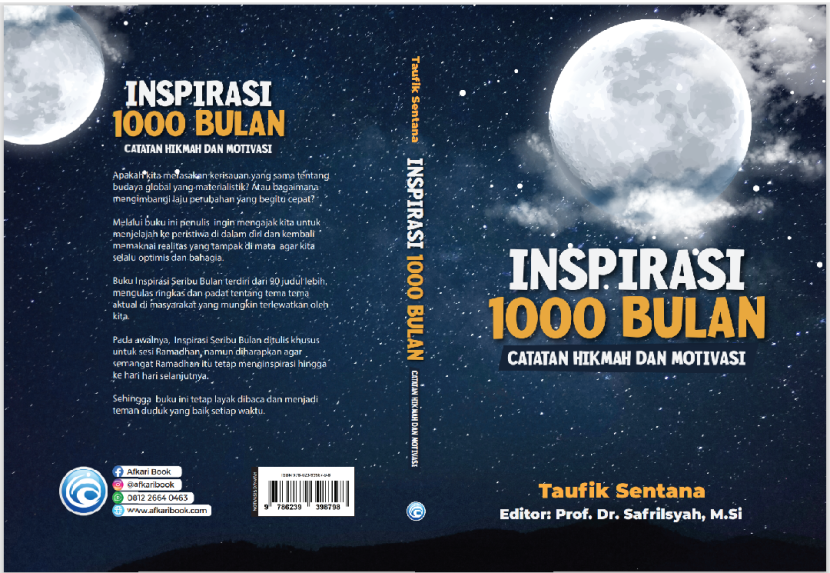Ervita Febriyanti
Ervita Febriyanti
Toxic Positivity? Ketika Afirmasi Positif Justru Menyakitkan
Eduaksi | 2025-12-25 21:37:46
Afirmasi positif adalah salah satu metode psikologis yang sudah sangat awam dikalangan masyarakat luas terutama mahasiswa. Metode ini dilakukan dengan mengulangi pernyataan-pernyataan positif pada diri sendiri (self talk), seperti “aku pasti bisa”, “aku mampu menghadapi tantangan”, “aku pasti bisa lulus tepat waktu”, “ aku bisa dan aku berhak bahagia”, serta “aku pasti bisa mendapat nilai 100 di UTS”. Menurut KBBI sendiri afirmasi positif adalah penetapan yang positif, penegasan, peneguhan, pernyataan atau pengakuan yang sungguh-sungguh (di bawah ancaman hukum) oleh orang yang menolak melakukan sumpah, pengakuan. Tujuan adanya afirmasi positif ini adalah untuk mengubah pola pikir negatif menjadi pola pikir positif yang dapat membangun individu, memperkuat rasa percaya diri, mengurangi stes, serta memotivasi diri untuk menghadapai tantangan hidup. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa afirmasi positif dapat membantu mengubah pola pikir negatif menjadi lebih konstruktif dan mendukung kesehatan mental secara keseluruhan (Critcher & Dunning, 2015). Akan tetapi, penggunaan afirmasi positif yang tidak proporsional atau tanpa mempertimbangkan keadaan emosional mahasiswa yang sebenarnya dapat menimbulkan efek samping yang justru merugikan, salah satunya adalah fenomena yang dikenal sebagai toxic positivity.
Menurut Lukin (2019), toxic positivity adalah ide tentang menjalani hidup dengan positif. Sedangkan, Cherry (2021) mengatakan bahwa toxic positivity adalah keyakinan bahwa, terlepas dari seberapa sulit dan mengerikannya keadaan saat ini, seseorang harus tetap positif. Menurut Quintero & Long (2019), toxic positivity adalah ketika seseorang hanya berfokus pada hal-hal positif dan mengabaikan hal-hal yang dapat menyebabkan emosi negatif. Maka dapat kita ketahui toxic positivity merupakan kondisi di mana individu selalu berpikir positif dan menolak segala bentuk emosi negatif menjadi berlebihan dan tidak sehat. Afirmasi positif yang seharusnya menjadi alat untuk pemberdayaan diri justru berubah menjadi bentuk penekanan terhadap perasaan negatif, sehingga individu merasa harus menutupi atau mengabaikan kesedihan, kemarahan, atau kecemasan yang mereka alami. Lukin (2022) menjelaskan dampak yang bisa terjadi apabila toxic positivity terus-menerus terjadi. Perasaan negatif yang terus-menerus tertanam di hati akan menjadi lebih besar dan meluap, membuat seseorang tidak dapat berpikir dengan jelas karena emosi dan perasaan negatif itu tidak dapat dikendalikan dan diidentifikasi. Perasaan ini membuat seseorang berpikir untuk menghindari emosi negatif dalam diri mereka. Jadi pikiran dan tubuh diprogram untuk bahagia bukan kecewa. Karen (dalam Samha, 2022: 93) mengemukakan bahwa emosi adalah nilai-nilai netral yang dapat menghasilkan kebahagian atau kesedihan dalam diri manusia, sebuah studi dalam Journal of Psychosomatic Research menemukan bahwa orang yang terus-menerus menyembunyikan dan menekan perasaan mereka berisiko lebih tinggi mengalami kematian dini, termasuk kanker, maka dapat diketahui bahwa penekanan emosi negatif yang menghasilkan toxic positivity sangat berbahaya bagi kesehatan fisik dan mental. Selanjutnya, individu yang telah terpengaruh oleh gejala toxic positivity akan memilih untuk menghindari semua masalah dan berfokus pada hal lain untuk menyelesaikan masalahnya. Keyakinan mereka bahwa menghindari masalah akan menyelesaikannya hanya akan membuat masalah menjadi lebih buruk karena setiap masalah harus dihadapi dan diselesaikan daripada dihindari (Geaby & Hendro, 2021). Dengan kata lain, toxic positivity membuat individu sulit membedakan antara menerima perasaan yang sebenarnya dan tetap berpikir positif dengan cara yang sehat.
Gangguan kesehatan mental seperti kecemasan, stres berkepanjangan, bahkan depresi ini disebabkan oleh kebiasaan menekan emosi negatif dan terus berpura-pura baik-baik saja dengan terus memberikan afirmasi positif pada diri senditi dalam situasi yang sebenarnya sulit. individu yang mengalami ini memaksa untuk terus bersikap positif, padahal hatinya sedang terluka. Akibatnya, mereka tidak memiliki ruang yang aman untuk mengekspresikan kesedihan atau kekecewaan, sehingga emosi tersebut menumpuk dan berdampak buruk pada kondisi psikologis . Dampak berikutnya adalah kehilangan kepercayaan terhadap orang lain. Sering kali, ketika individu menceritakan masalahnya, mereka justru mendapatkan tanggapan yang terkesan meremehkan seperti, “Kamu harus tetap bersyukur,” atau “Masalahmu nggak seberat orang lain.” Respon semacam ini membuat individu merasa tidak dimengerti, bahkan diabaikan. Hingga akhirnya diam dan tidak terbuka menjadi pilihan karena ketakutan disalahpahami atau dianggap berlebihan . Kemudian, rasa percaya diri juga bisa menurun akibat toxic positivity. Kata-kata motivasi yang tidak tepat bisa membuat seseorang merasa gagal, terutama ketika ia tidak bisa merasa positif seperti yang diharapkan. Misalnya, saat seseorang merasa sedih namun dipaksa untuk “tersenyum dan tetap semangat”, ia bisa menganggap dirinya lemah karena tidak mampu berpikir positif. Ini menunjukkan bahwa dorongan untuk selalu positif justru bisa mengikis kepercayaan diri individu dalam menghadapi kenyataan. Selain itu, toxic positivity juga menyebabkan perasaan tidak dihargai atau diremehkan. Hal ini terjadi ketika emosi seseorang dianggap tidak valid, seperti saat ia marah atau sedih namun langsung disuruh “jangan lebay” atau “tetap positif aja”. Akibatnya, individu tersebut merasa bahwa emosi yang ia rasakan tidak sah dan tidak boleh terjadi, padahal emosi negatif juga bagian dari reaksi manusia yang sehat. Ketika individu merasa emosinya tidak dihargai, mereka bisa merasa kecewa dan menarik diri dari interaksi sosial . Dampak lain yang tak kalah serius adalah kecenderungan untuk menghindari masalah. Karena terlalu fokus berpikir positif, banyak orang jadi tidak menyelesaikan masalahnya, melainkan justru mengalihkan perhatian ke hal lain. Misalnya, dengan menyibukkan diri secara berlebihan atau menolak membicarakan masalah. Padahal, masalah yang tidak diselesaikan bisa semakin memburuk. Hal ini menunjukkan bahwa toxic positivity membuat seseorang menyangkal kenyataan dan malah memperpanjang beban yang dipikul . Terakhir, toxic positivity juga berdampak pada kesehatan fisik. Emosi negatif yang terus ditekan tanpa diolah bisa memicu gangguan fisik serius seperti tekanan darah tinggi, gangguan pencernaan, bahkan risiko penyakit berat seperti kanker. Studi dalam Journal of Psychosomatic Research bahkan menemukan bahwa orang yang terus menekan emosinya memiliki risiko lebih tinggi mengalami kematian dini. Ini membuktikan bahwa memaksakan diri untuk selalu “bahagia” bisa sangat merusak, baik secara mental maupun fisik. (Geaby & Hendro, 2021) menyatkan faktor-faktor yang dapat memengaruhi toxic positivity dapat terjadi adalah toxic positivity dapat disebabkan oleh motivasi yang tidak sesuai yang diberikan oleh seseorang yang awalnya ingin memberikan dukungan tetapi berakhir tidak sesuai dengan harapan, kedua respon yang menganggap reaksi atau kondisi kita berlebihan yang membuat kita kecewa dan marah, ketiga perasan yang tidak dipahami karena masalah atau kondisi yang dihadapi dianggap remeh, dan keempat mendapatkan kekerasan verbal dari keluarga.
Dari semua dampak toxic positivity tersebut mahasiswa dapat menjadi salah satu elemen yang paling riskan terkena, dimana dinamika perkuliahan yang kompleks dimulai dari tugas, lingkungan belajar, lingkungan pertemanan, hingga tuntutan orang tua dapat menjadi faktor yang memenaruhi toxic positivity terjadi. Toxic positivity merupakan kondisi ketika seseorang memaksakan diri untuk selalu berpikir positif dan menolak keberadaan emosi negatif yang sebenarnya wajar dirasakan. Meskipun afirmasi positif memiliki manfaat dalam membangun pola pikir dan motivasi diri, penggunaannya yang berlebihan atau tidak tepat dapat memicu tekanan emosional yang justru berdampak buruk bagi kesehatan mental maupun fisik. Mahasiswa menjadi bagian yang rentan terhadap toxic positivity karena tekanan akademik, sosial, dan tuntutan eksternal yang kompleks. Untuk itu, penting bagi mereka memiliki ruang yang aman untuk mengenali, menerima, dan mengekspresikan emosinya secara sehat.
“People often need to accept the reality of a situation before moving forward. Not all situations have a silver lining or a positive spin. Some things are just really, really hard, and that’s OK.”― Whitney Goodman
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.