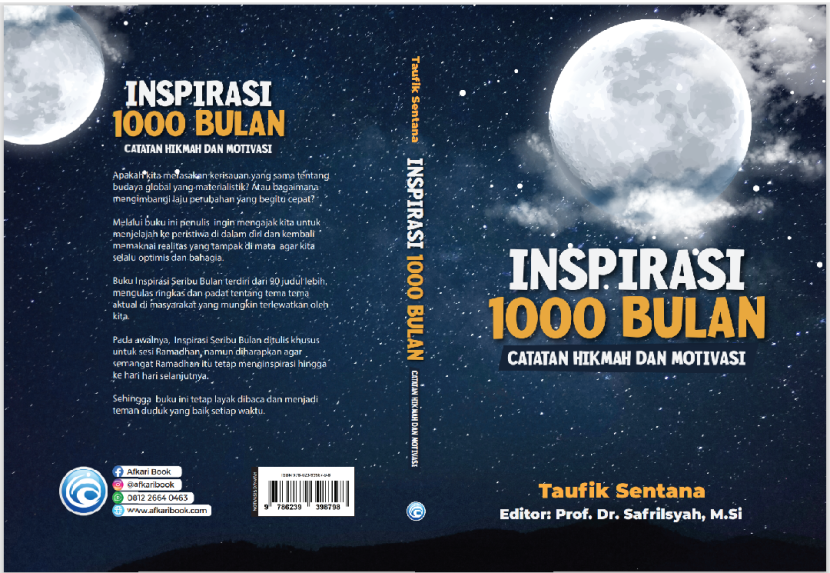Abdullah Abubakar Batarfie
Abdullah Abubakar Batarfie
Ketika Sejarah Diperintahkan untuk Dijaga
Sejarah | 2026-02-11 20:10:58
Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah yang dihadiri seluruh kepala daerah se-Indonesia terdengar tegas dan penuh kesadaran sejarah. Para kepala daerah diminta menjaga nilai-nilai sejarah di wilayah masing-masing, bukan merusak, apalagi menghancurkan.
Namun ironi itu datang nyaris tanpa jeda, dalam hitungan hari, bahkan hampir bersamaan, Presiden kembali menyampaikan pidato berapi-api tentang rencana pembangunan gedung 40 lantai di lokasi paling strategis di jantung Jakarta, di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat. Gedung itu, kata Presiden, akan disiapkan negara sebagai kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat serta pusat perkantoran ormas Islam.
Janji ini disampaikan hanya sehari setelah pertemuan Presiden dengan pimpinan MUI dan ormas Islam di Istana Merdeka, pasca meredanya polemik “Board of Peace”. Yang semula menolak, kini menyatakan dukungan.
Ironisnya, lahan yang akan digunakan sebagaimana dilaporkan Kompas dan sejumlah sumber lain, adalah bekas kantor Kedutaan Besar Inggris, sebuah bangunan yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya. Sebuah bangunan dengan nilai sejarah penting yang semestinya dilindungi, bukan dikorbankan.
Di titik inilah paradoks menjadi telanjang: bagaimana mungkin negara menyerukan pelestarian sejarah, namun di saat yang sama merancang penghapusan jejak sejarahnya sendiri?
Lebih mengusik lagi, Majelis Ulama Indonesia yang semestinya berfungsi sebagai pengawas moral kekuasaan, belum menunjukkan sikap kritis terhadap langkah pemerintah yang berpotensi menghilangkan memori kolektif bangsa. Alih-alih menjaga nilai, justru tampak ikut menikmati hasil pengabaian aturan. Seolah-olah perusakan cagar budaya menjadi wajar, selama dibungkus kepentingan agama dan pembangunan.
Padahal, dalam etika Islam, kekuasaan tidak boleh berjalan tanpa kendali moral, dan hukum tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan, betapapun mulianya label yang disematkan.
Bangunan bersejarah bukan sekadar batu dan tembok. Ia adalah ingatan kolektif, saksi zaman, dan ruang dialog antara masa lalu dan masa depan. Ia memang bisa hilang ditelan masa, namun akan jauh lebih cepat lenyap jika ditelan ambisi ekonomi dan politik pembangunan.
Pembangunan tanpa kesadaran sejarah bukanlah kemajuan, melainkan amputasi ingatan.
Jika negara mulai meruntuhkan cagar budaya di pusat ibu kota demi kepentingan simbolik, maka pesan kepada daerah sangat jelas, sejarah boleh dikorbankan, asal diganti gedung tinggi dan slogan luhur.
Dan jika ulama diam ketika sejarah dihancurkan, siapa lagi yang akan mengingatkan bahwa kekuasaan pun harus tunduk pada etika, hukum, dan memori bangsa?
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.