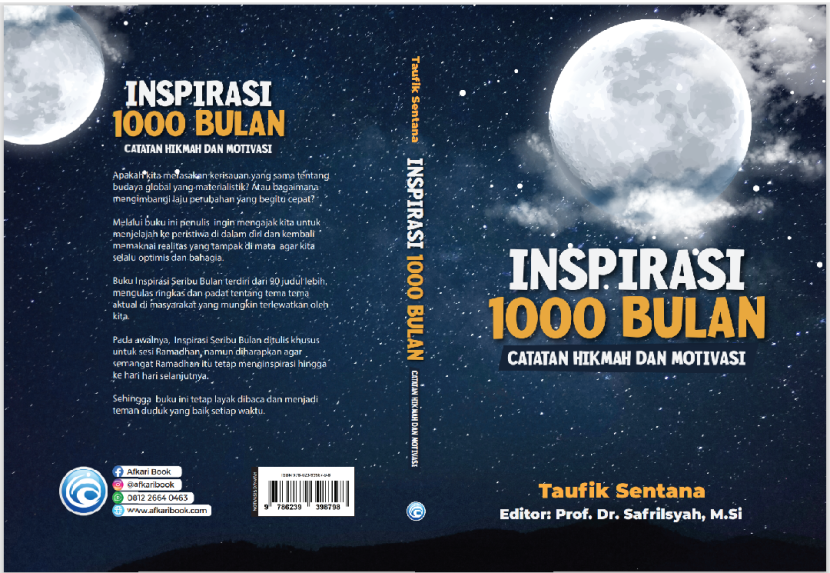Ragil Angga Prastiya, drh., M.Si.
Ragil Angga Prastiya, drh., M.Si.
Tekanan Berlapis dan Rapuhnya Mental Mahasiswa Masa Kini
Edukasi | 2026-02-11 07:57:22Oleh: Ragil Angga Prastiya, drh., M.Si., Dosen Reproduksi Veteriner, Program Studi Kedokteran Hewan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Kedokteran, dan Ilmu Alam (FIKKIA), Universitas Airlangga, Banyuwangi

Kampus selama ini dipersepsikan sebagai ruang tumbuhnya nalar kritis, etika, dan kepemimpinan masa depan. Namun, di balik hiruk-pikuk aktivitas akademik, terdapat realitas sunyi yang kian mengkhawatirkan: kesehatan mental mahasiswa yang terus tergerus oleh tekanan berlapis, kompleks, dan sering kali tidak terlihat. Ini bukan lagi isu individual, melainkan persoalan sistemik yang menuntut kehadiran serius dunia kampus, keluarga, dan negara.
Mahasiswa hari ini menghadapi spektrum stresor yang jauh lebih luas dibanding generasi sebelumnya. Tekanan akademik seperti beban tugas, tuntutan indeks prestasi, dan kecemasan menghadapi tugas akhir (skripsi) masih menjadi faktor dominan. Namun, problem tersebut kini berkelindan dengan persoalan sosial dan ekonomi yang jauh lebih berat: perundungan di lingkungan kampus, keterjeratan judi online dan pinjaman online, kerugian akibat penipuan investasi kripto dan saham, hingga kekurangan biaya kuliah yang membuat sebagian mahasiswa terpaksa bertahan dalam kondisi psikologis yang rapuh.
Tidak sedikit pula mahasiswa yang terjebak dalam relasi personal yang tidak sehat, hubungan pacaran yang mengandung unsur kontrol, manipulasi, hingga pelecehan seksual. Di sisi lain, ruang-ruang pembelajaran di luar kelas seperti magang, PKL, dan KKN yang seharusnya menjadi wahana pendewasaan justru kadang menyisakan trauma akibat pelecehan atau kekerasan berbasis relasi kuasa. Ironisnya, dalam beberapa kasus, pelecehan justru dilakukan oleh tenaga pendidik atau tenaga kependidikan, figur yang semestinya menjadi pelindung dan teladan.
Masalah-masalah ini jarang muncul ke permukaan secara utuh. Salah satu penyebab utamanya adalah minimnya sistem deteksi dini dan asesmen kesehatan mental di kampus. Teman sebaya sering kali tidak memiliki literasi kesehatan mental yang memadai untuk mengenali tanda-tanda stres berat. Dosen pembimbing lebih fokus pada capaian akademik, sementara satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan (PPKK) kerap bekerja secara reaktif, bukan preventif. Di sisi mahasiswa sendiri, budaya “bertahan sendiri” masih kuat; banyak yang memilih diam karena takut distigma, dianggap lemah, atau khawatir berdampak pada studi mereka.
Ketika tekanan terus menumpuk tanpa ruang aman untuk bercerita dan mendapatkan bantuan, gangguan mental pun menjadi keniscayaan. Gejalanya bervariasi, mulai dari kecemasan kronis, gangguan tidur, depresi ringan, hingga kondisi yang lebih berat seperti depresi mayor, ide bunuh diri, dan perilaku menyakiti diri. Pada tahap ini, kampus sering kali baru “tersadar”, namun intervensi sudah terlambat dan berisiko tinggi.
Kondisi ini menjadi semakin kompleks karena mahasiswa saat ini didominasi oleh Generasi Z, dan dalam waktu dekat Generasi Alpha akan memasuki perguruan tinggi. Kedua generasi ini tumbuh dalam ekosistem digital yang sangat intens, cepat, dan penuh distraksi. Mereka lebih terbuka terhadap isu kesehatan mental, namun juga lebih rentan terhadap tekanan sosial, perbandingan diri di media sosial, serta kecemasan eksistensial. Pendekatan otoriter dan birokratis yang selama ini lazim di kampus jelas tidak lagi relevan.
Lantas, apa yang perlu dilakukan?
Pertama, kampus harus menempatkan kesehatan mental sebagai bagian integral dari mutu pendidikan tinggi, bukan sekadar layanan tambahan. Unit layanan konseling perlu diperkuat secara kelembagaan, profesional, dan mudah diakses, dengan pendekatan yang proaktif, bukan menunggu laporan. Asesmen kesehatan mental dasar seharusnya menjadi bagian dari orientasi mahasiswa baru dan pemantauan berkala.
Kedua, dosen dan tenaga kependidikan perlu dibekali pelatihan literasi kesehatan mental dan etika relasi kuasa. Mereka tidak dituntut menjadi psikolog, tetapi mampu mengenali tanda peringatan dini dan tahu ke mana harus merujuk mahasiswa secara aman dan bermartabat.
Ketiga, sistem pelaporan kekerasan dan pelecehan harus benar-benar berpihak pada korban: anonim, aman, cepat, dan bebas konflik kepentingan. Satgas PPKK perlu dievaluasi secara berkala, tidak hanya dari sisi kepatuhan administratif, tetapi juga efektivitas perlindungan psikososial bagi korban.
Keempat, keluarga tidak bisa sepenuhnya menyerahkan tanggung jawab ini kepada kampus. Komunikasi yang sehat, empatik, dan non-judgmental dengan anak yang sedang kuliah menjadi benteng pertama pencegahan gangguan mental. Dukungan emosional sering kali jauh lebih menentukan daripada sekadar dukungan finansial.
Kelima, pemerintah perlu hadir melalui kebijakan yang lebih progresif: penguatan layanan kesehatan mental berbasis kampus, regulasi tegas terhadap judi online dan pinjaman online yang menyasar anak muda, serta skema bantuan pendidikan yang adaptif terhadap krisis psikologis mahasiswa.
Kesehatan mental mahasiswa bukan isu “lembek” atau tanda kegagalan individu. Ia adalah cermin dari ekosistem pendidikan dan sosial yang kita bangun bersama. Jika kampus ingin melahirkan lulusan yang unggul, beretika, dan tangguh, maka menjaga kesehatan mental mahasiswa bukanlah pilihan, melainkan keharusan moral dan strategis. Krisis sunyi ini harus diakhiri, sebelum kita kehilangan lebih banyak generasi masa depan dalam diam.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.