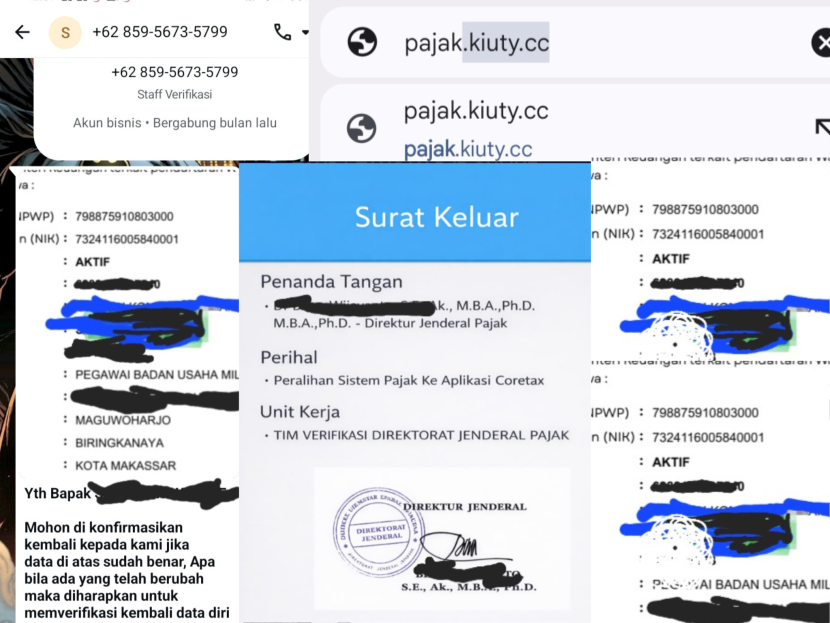Moh. Khamidan Akhdan
Moh. Khamidan Akhdan
Perempuan dalam Dunia Ketidakadilan
Sastra | 2026-01-05 13:52:17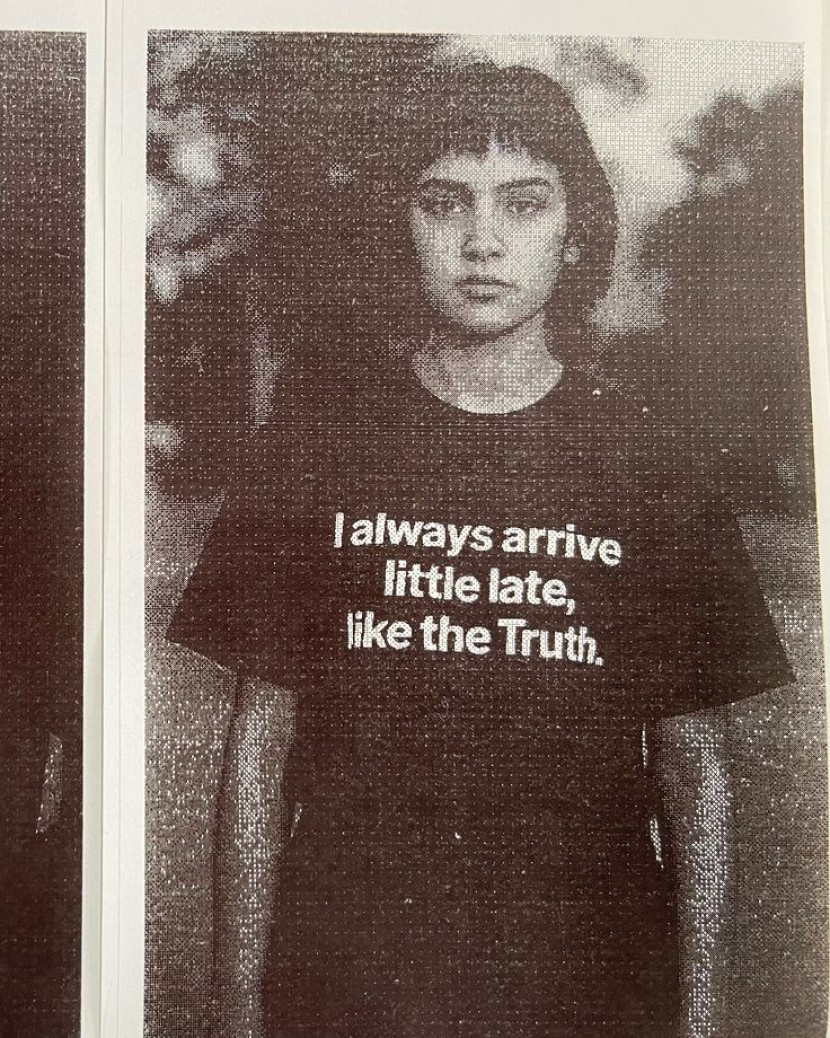
Dalam banyak karya sastra, perempuan sering hadir bukan sebagai pusat dunia, melainkan sebagai akibat dari dunia yang rusak. Ia muncul ketika konflik telah terlanjur kotor, ketika kemiskinan sudah membatu, ketika cinta telah kehilangan keberanian. Begitulah Mirah dalam Bunga Semerah Darah karya W.S. Rendra dan Mira dalam Awal dan Mira karya Utuy Tatang Sontani. Mereka bukan perempuan yang memilih menderita; merekalah yang dipilih oleh penderitaan.
Mirah hidup di dunia yang tak pernah memberinya jeda untuk menjadi manusia utuh. Tubuhnya adalah ruang paling rentan: dipantau, dicurigai, dipukul, dan akhirnya dibiarkan sakit tanpa pengobatan. Ia tidak pernah memiliki otoritas atas hidupnya sendiri. Bahkan ketika ia bertahan, kesetiaannya justru ditafsirkan sebagai kelemahan. Dalam pandangan laki-laki di sekitarnya, Mirah tidak pernah cukup tidak cukup kuat, tidak cukup patuh, tidak cukup bernilai.
Rendra menuliskan penderitaan Mirah dengan suara keras, nyaris kasar. Kekerasan rumah tangga tidak disamarkan, ancaman pengusiran tidak diperhalus, kemiskinan tidak diberi romantisme. Perempuan miskin, dalam dunia ini, adalah tubuh yang selalu bisa ditekan. Ketika Mirah sakit, dunia tidak berhenti. Ketika ia mati, dunia bahkan tidak menoleh. Yang tersisa hanyalah ratapan anak, suara paling jujur yang muncul setelah segalanya terlambat.
Berbeda dengan Mirah, Mira tidak dihancurkan oleh tamparan atau kelaparan. Ia dihancurkan oleh cara dunia menatapnya. Tubuhnya cacat akibat perang, tetapi luka terbesarnya justru muncul setelah perang usai. Mira hidup di ruang antara: antara dicintai dan ditolak, antara dikagumi dan dikasihani. Ia hadir sebagai perempuan yang utuh secara perasaan, tetapi tidak pernah dianggap utuh secara sosial.
Utuy menulis Mira dengan keheningan yang panjang. Penderitaannya tidak meledak, melainkan mengendap. Ia mencintai dengan sungguh-sungguh, sementara laki-laki yang dicintainya terlalu sibuk mencintai kegelisahannya sendiri. Mira memahami, menunggu, dan mengalah bukan karena ia lemah, tetapi karena dunia tidak menyediakan alternatif lain bagi perempuan seperti dirinya. Dalam relasi ini, perempuan dituntut untuk mengerti, sementara laki-laki diberi hak untuk ragu tanpa batas.
Jika Mirah adalah perempuan yang dihancurkan oleh struktur sosial yang kejam, maka Mira adalah perempuan yang dilumpuhkan oleh relasi emosional yang timpang. Keduanya sama-sama tidak diberi ruang untuk marah. Mirah marah berarti melawan kekuasaan; Mira marah berarti dianggap tidak tahu diri. Dalam dua dunia yang berbeda, perempuan tetap ditempatkan sebagai pihak yang harus menanggung beban paling sunyi.
Sastra bandingan memperlihatkan satu benang merah yang menyakitkan: penderitaan perempuan sering kali tidak dianggap tragedi, melainkan konsekuensi. Ketika Mirah mati, kemiskinan dianggap penyebabnya. Ketika Mira terluka batin, cinta dianggap alasannya. Padahal, di balik itu semua, ada sistem yang sama: sistem yang menormalisasi pengorbanan perempuan dan menyebutnya takdir.
Rendra dan Utuy tidak sedang menulis kisah tentang perempuan lemah. Mereka menulis tentang dunia yang gagal merawat perempuan. Mirah dan Mira tidak kekurangan daya hidup; merekalah yang hidup di masyarakat yang miskin empati. Dalam kedua naskah ini, perempuan bukan pusat perlindungan, melainkan pusat penyangkalan selalu diminta memahami, jarang dipahami.
Membaca Mirah dan Mira hari ini terasa menyakitkan karena dunia yang mereka huni belum sepenuhnya berlalu. Kita masih sering menemukan perempuan yang harus memilih antara harga diri dan bertahan hidup, antara cinta dan keutuhan diri. Sastra, dalam hal ini, tidak memberi jawaban. Ia hanya mengajukan satu tuntutan yang paling mendasar: agar kita berhenti menganggap penderitaan perempuan sebagai sesuatu yang wajar.
Dan mungkin, selama tuntutan itu belum benar-benar dipenuhi, kisah Mirah dan Mira akan terus relevan sebagai pengingat bahwa keadilan sering datang terlambat bagi perempuan, atau tidak datang sama sekali.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.