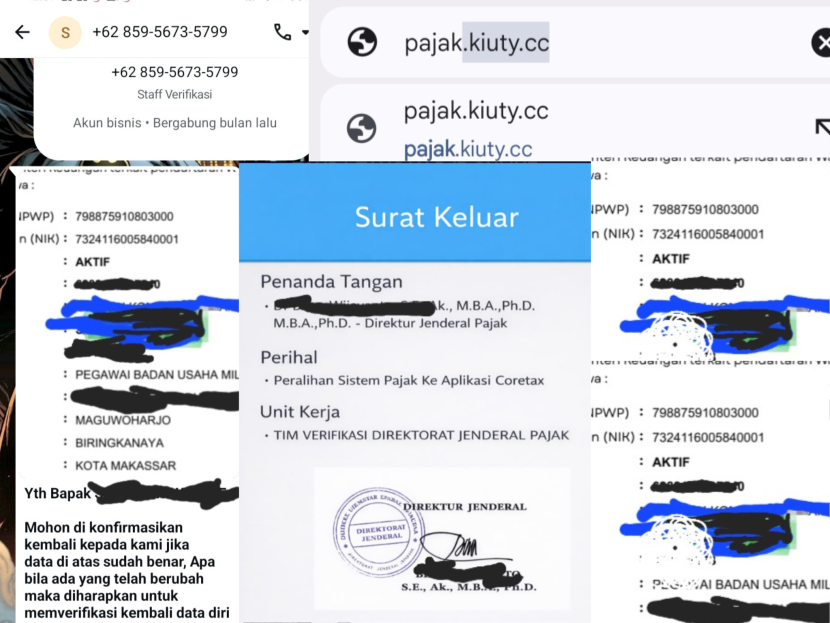Hilya Hafiza Sadi
Hilya Hafiza Sadi
Hukuman sebagai Mekanisme Kekuasaan yang Diwajarkan
Sastra | 2026-01-04 12:27:00
Hukuman tidak hanya hadir dari negara ataupun vonis hakim saja, ada pula hukuman yang berasal dari kepercayaan dan kebiasaan adat istiadat setempat. Contohnya dapat dilihat pada cerpen “Merebut Tanah” karya I Putu Supartika dan “Bagaimana Saya Bertemu Orang yang Telah Saya Eksekusi” karya Era Ari Astanto. Kedua cerpen ini sama-sama menghadirkan individu yang berhadapan dengan sistem kekuasaan melalui mekanisme hukuman yang berbeda.
Michel Foucault dalam bukunya yang berjudul Discipline and Punish: The Birth of the Prison (1975), beranggapan bahwa kekuasaan tidak hanya berfungsi melalui hukum yang tertulis atau lembaga negara saja, akan tetapi kekuasaan juga bekerja melalui praktik sosial, norma, dan sistem yang diterima oleh masyarakat. Kekuasaan hadir dalam kehidupan sehari-hari dan membentuk cara berpikir, bertindak, serta ketaatan individu terhadap aturan yang berlaku.
Dalam hal ini, hukuman tidak hanya hadir untuk mengadili kesalahan, tetapi juga untuk mendisiplinkan. Hukuman di sini digunakan untuk mengontrol dan menundukkan perilaku individu agar sesuai dengan apa yang diinginkan. Sehingga kekerasan atau hukuman bisa dianggap sah jika sudah disetujui oleh sistem, baik itu melalui adat maupun hukum negara. Dalam hal ini, seseorang bisa berada dalam dua posisi, yaitu sebagai korban kekuasaan atau sebagai alat untuk melaksanakan kekuasaan. Namun dalam kedua posisi tersebut, individu tetap berada dalam kendali sistem yang lebih besar.
Kekuasaan tidak selalu datang melalui aturan hukum atau lembaga negara, tetapi juga melalui nilai-nilai sosial yang dianggap wajar dan tidak perlu dipertanyakan. Dalam sastra, praktik kekuasaan semacam ini kerap digambarkan melalui tokoh-tokoh yang berhadapan langsung dengan sistem yang lebih besar dari dirinya. Dua cerpen yang berjudul “Merebut Tanah” karya I Putu Supartika dan “Bagaimana Saya Bertemu Orang yang Telah Saya Eksekusi” karya Era Ari Astanto, menghadirkan gambaran tentang individu yang terjebak dalam mekanisme kekuasaan melalui hukuman. Meski berlatar dan konteks yang berbeda, keduanya memperlihatkan bagaimana hukuman digunakan bukan sekadar untuk memberi keadilan, melainkan untuk menjaga keteraturan sosial.
Dalam cerpen “Merebut Tanah”, kekuasaan muncul melalui adat yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Sudarma, tokoh utama, secara hukum negara berada di pihak yang benar karena memenangkan gugatan atas tanah warisan keluarganya. Namun, kebenaran hukum tersebut justru bertabrakan dengan nilai adat yang telah lama disepakati oleh masyarakat setempat.
“Berani melawan adat, berarti sudah siap melawan kami semua.”
Kutipan di atas memperlihatkan bagaimana adat berfungsi sebagai kekuasaan kolektif yang tidak memberi ruang bagi perbedaan. Ketika Sudarma memilih jalur hukum negara, ia dipandang bukan sekadar sebagai individu yang mempertahankan hak, melainkan sebagai ancaman terhadap tatanan sosial masyarakat setempat. Dalam kondisi seperti ini, kebenaran tidak lagi ditentukan oleh aturan tertulis, tetapi oleh kesepakatan sosial yang telah dinormalisasi.
Hukuman yang diterima Sudarma pun berlangsung secara terbuka dan brutal. Ancaman pembunuhan, penjarahan harta benda, perusakan, hingga pembakaran rumah menjadi bentuk sanksi sosial yang dianggap sah demi menjaga adat. Kekerasan tersebut tidak dipandang sebagai kejahatan, melainkan sebagai kewajiban moral masyarakat. Hukuman berfungsi sebagai peringatan bagi siapa pun yang berniat keluar dari aturan yang telah disepakati bersama.
Berbeda dengan itu, cerpen “Bagaimana Saya Bertemu Orang yang Telah Saya Eksekusi” menampilkan wajah kekuasaan negara yang bekerja melalui sistem hukum dan administrasi. Hukuman mati yang dijalankan oleh tokoh Petugas terhadap para terpidana dilakukan secara rapi, tertutup, dan steril. Negara hadir sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas hidup dan mati warganya.
Tokoh Petugas tidak mempertanyakan benar atau salah dari hukuman yang ia jalankan. Ia memandang dirinya hanya sebagai bagian kecil dari sistem yang harus patuh terhadap perintah. Dalam posisi ini, kekuasaan tidak hanya mengendalikan tubuh orang yang dihukum, tetapi juga membentuk sikap batin pelaksananya agar tunduk, dingin, dan menyingkirkan pertimbangan moral pribadi.
Namun, kepatuhan itu perlahan runtuh ketika Petugas bertemu kembali dengan orang-orang yang telah ia eksekusi. Pertemuan tersebut memunculkan pertanyaan tentang siapa sebenarnya manusia yang ia tembak, dan untuk apa semua itu dilakukan. Dari sinilah muncul krisis batin yang mengguncang kejiwaannya.
“Kadang, kalau malam, saya bermimpi sedang menarik pelatuk, tapi yang jatuh bukan orang-orang, melainkan bayangan saya sendiri.”
Kutipan di atas menunjukkan bahwa hukuman tidak hanya menghancurkan mereka yang menjadi korban langsung, tetapi juga meninggalkan dampak psikologis pada mereka yang terlibat dalam prosesnya.
Kedua cerpen sama-sama menampilkan hukuman sebagai alat untuk menjaga tatanan yang dianggap benar. Adat maupun negara memiliki legitimasi masing-masing dalam menentukan siapa yang patuh dan siapa yang menyimpang. Dalam kedua cerpen, individu kehilangan kendali atas tubuh dan hidupnya ketika berhadapan dengan sistem kekuasaan yang lebih besar.
Perbedaan terletak pada posisi tokoh, Sudarma menjadi korban kekuasaan secara langsung melalui kekerasan fisik yang terbuka. Sementara itu, tokoh Petugas berada di posisi pelaksana hukum sekaligus korban dari sistem yang memaksanya patuh. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kekuasaan tidak hanya menindas dari luar, tetapi juga dapat bekerja dan menindas hingga ke dalam diri manusia.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.