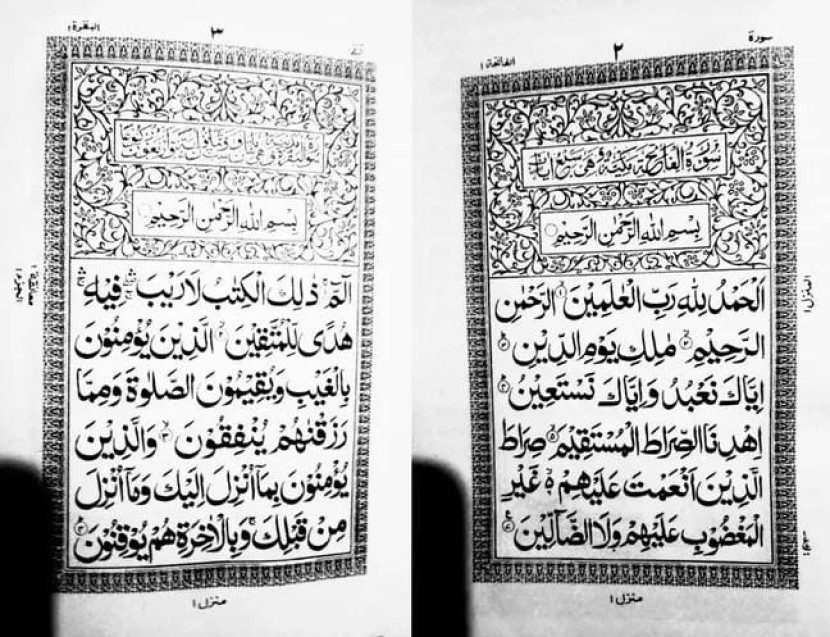Thoriq Panji Perdana
Thoriq Panji Perdana
Hashtag Diplomacy: Ketika Twitter dan TikTok Jadi Arena Politik Luar Negeri
Politik | 2025-10-15 14:35:27Oleh Siti Rianti Safira

Dulu, diplomasi identik dengan ruang rapat tertutup, protokol kaku, dan bahasa yang serba formal. Tapi sekarang? Diplomasi bisa terjadi lewat satu tweet, satu video TikTok, atau satu tagar yang viral. Era baru ini melahirkan fenomena yang disebut Hashtag Diplomacy — di mana hubungan antarnegara, krisis global, dan citra nasional dipertarungkan bukan hanya di meja perundingan, tapi di timeline media sosial.
Media sosial udah jadi panggung global yang terbuka. Setiap negara, pemimpin, bahkan kementerian luar negeri kini punya akun resmi di X (dulu Twitter), TikTok, dan Instagram. Tapi fungsinya nggak cuma buat publikasi kegiatan diplomatik — melainkan untuk membentuk persepsi, mengendalikan narasi, bahkan mempengaruhi kebijakan publik dunia.
Contohnya? Saat perang Rusia–Ukraina meledak, Kementerian Luar Negeri Ukraina aktif banget di Twitter. Mereka bukan cuma melaporkan kejadian, tapi juga memainkan emosi publik global lewat narasi heroik, visual dramatis, dan tagar seperti #StandWithUkraine. Hasilnya? Dukungan publik internasional melonjak, dan banyak negara terdorong memberi bantuan militer dan kemanusiaan. Di sisi lain, Rusia juga nggak tinggal diam — mereka melancarkan disinformation campaign lewat media sosial, berusaha menggiring opini bahwa invasi mereka adalah “langkah pertahanan diri.”
Soft Power dalam Bentuk Tagar
Hashtag diplomacy pada dasarnya adalah evolusi dari soft power — kekuatan untuk memengaruhi tanpa paksaan. Tapi kalau dulu soft power berbasis budaya, film, dan musik, kini bentuknya berubah jadi konten. Negara yang bisa menguasai algoritma dan tren digital punya keunggulan diplomatik baru.
Amerika Serikat misalnya, memanfaatkan platform seperti TikTok dan YouTube untuk menyebarkan nilai-nilai demokrasi dan gaya hidup liberal. Di sisi lain, Tiongkok menggunakan influencer dan media seperti CGTN untuk membangun citra positif lewat narasi “kerja sama damai” dan “kebangkitan Asia.” Bahkan, mereka meluncurkan tagar global seperti #BRI (Belt and Road Initiative) untuk memperkuat brand geopolitiknya.
Fenomena ini juga bisa dilihat dari cara K-pop dan budaya Korea Selatan berperan dalam diplomasi publik. Tagar-tagar seperti #KoreaInspires atau #Hallyu bukan sekadar tren, tapi bagian dari strategi besar nation branding. Ketika BTS bicara soal perubahan iklim di PBB, itu bukan cuma momen budaya — tapi juga diplomasi digital yang cerdas, menggabungkan pop culture dengan politik luar negeri.
Tapi di sisi lain, hashtag diplomacy juga bisa jadi alat tekanan politik. Misalnya, kampanye global seperti #FreePalestine atau #MilkTeaAlliance menunjukkan bagaimana masyarakat sipil lintas negara bisa bersatu lewat media sosial untuk menekan pemerintah atau memperjuangkan nilai tertentu. Dalam kasus ini, diplomasi bukan lagi monopoli negara, tapi juga ruang partisipasi bagi warga dunia.
Tantangan Etika dan Masa Depan Diplomasi Digital
Meski terlihat keren dan progresif, hashtag diplomacy juga punya sisi gelap. Ketika diplomasi berubah jadi permainan algoritma, kecepatan sering kali mengalahkan akurasi. Disinformasi, propaganda, dan manipulasi citra jadi hal yang sulit dihindari. Negara yang punya sumber daya digital besar bisa dengan mudah menguasai narasi global, sementara negara kecil harus berjuang keras biar suaranya nggak tenggelam di antara lautan konten.
Selain itu, muncul pertanyaan soal etika: seberapa jauh diplomat boleh “bermain” di media sosial? Apakah pantas isu serius seperti perang, HAM, atau perubahan iklim disederhanakan jadi konten viral? Banyak ahli hubungan internasional memperingatkan bahwa diplomasi digital yang terlalu performatif bisa menggerus substansi dialog dan menggantinya dengan pencitraan semata.
Namun, terlepas dari semua risikonya, diplomasi digital udah nggak bisa dihindari. Platform seperti X, TikTok, dan Instagram udah jadi arena politik luar negeri yang nyata — tempat negara berinteraksi, berkompetisi, dan kadang saling serang lewat narasi.
Indonesia sendiri mulai sadar akan potensi ini. Melalui public diplomacy digital, Kementerian Luar Negeri RI aktif membangun citra positif Indonesia sebagai negara demokratis, ramah, dan stabil di kawasan. Tapi tantangannya sekarang adalah bagaimana membentuk digital storytelling yang kuat dan konsisten — bukan cuma promosi pariwisata, tapi juga posisi politik luar negeri yang strategis.
Pada akhirnya, diplomasi digital bukan cuma soal siapa yang punya kekuatan, tapi siapa yang bisa mengendalikan cerita. Dunia kini hidup di era di mana sebuah tagar bisa mengguncang sistem, mengubah opini, bahkan mengubah arah kebijakan luar negeri. Dan di era seperti ini, diplomasi bukan lagi hanya seni berbicara — tapi juga seni trending.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.