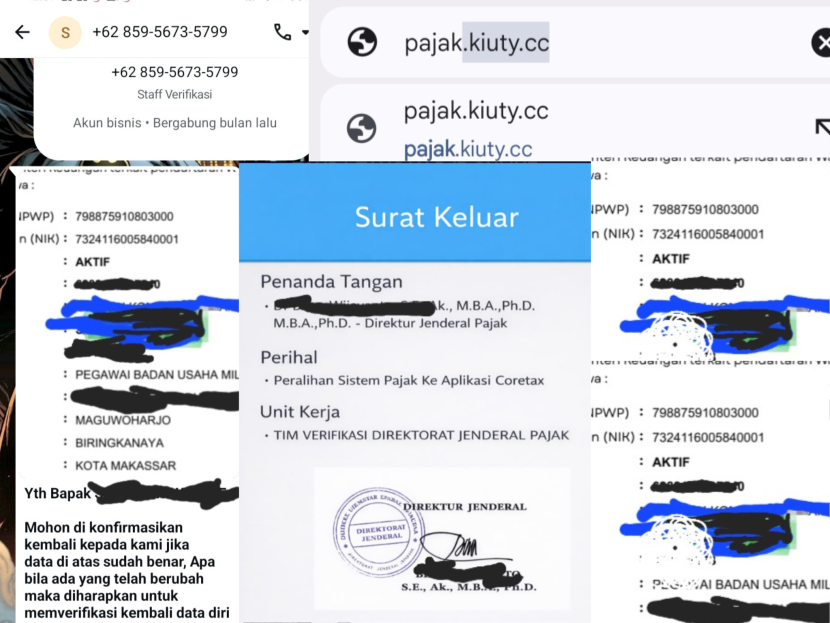aysah aurellia
aysah aurellia
Jujur atau Sekadar Pencitraan?
Eduaksi | 2025-05-07 05:16:37Apa yang terlihat natural di linimasa, bisa jadi hasil strategi pemasaran yang sangat terencana. Influencer hadir sebagai “teman virtual” yang “dipercaya”, sementara berbagai brand membayar mereka untuk mempromosikan produk mereka secara halus atau softselling. Batas antara konten pribadi dan iklan semakin kabur seperti Iklan konvensional (TV, Radio, Baliho, dll) yang sudah jarang terlihat dan di gunakan, mengapa? Atau mungkin pertanyaan dari zaman Gen Alpha adalah dimana? yang mana ya?. Oh.. waw? Apakah iklan konvensional hilang? Oh tidak, biar saya jelaskan. Dan apa yang terlihat natural di linimasa adalah apa yang harus kita khawatirkan, apakah kita sedang disuguhi opini jujur, atau hanya melihat hasil pencitraan yang dikemas dengan rapi?
1. Influencer.
Influencer siapa sih kak ? Influencer adalah seseorang yang memiliki pengaruh terhadap perilaku, opini, atau keputusan audiensnya terutama di media sosial. Secara umum, Influencer memegang 1 niche atau 1 fokus untuk konten kontennya. Contohnya adalah Tasya Farasya yang fokus di bidang kecantikan, jadi rata – rata atau hampir keseluruhan isi konten tasya farasya adalah tentang kecantikan. Laporan We Are Social Digital 2025 menunjukkan bahwa influencer memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. Hampir semua konsumen (86%) melakukan pembelian yang terinspirasi oleh influencer setidaknya sekali dalam setahun. Platform media sosial seperti TikTok dan Instagram menjadi platform utama yang digunakan konsumen untuk riset produk dan pembelian.
2. Media sosial

Media sosial memiliki jutaan pengguna aktif yang terhubung sampai internasional. Maka dari itu, platform seperti instagram, tiktok, dan youtube menjadi ladang atau tempat yang strategis untuk beriklan atau lahan subur untuk iklan terselubung. Konten pribadi dan iklan semakin kabur (sulit dibedakan), seringkali disisipkan dalam format cerita pribadi, review, atau bahkan gaya hidup sehari-hari. Pada awalnya, Iklan Konvensional dan iklan di media sosial adalah rata. Namun, masalah muncul ketika promosi tersebut tidak diungkapkan secara transparan. Hashtag seperti #ad atau #sponsored seringkali disembunyikan, atau bahkan tidak disertakan sama sekali. Ini menciptakan kebingungan bagi audiens yang tidak tahu bahwa mereka sedang dipersuasi secara halus.
Beberapa waktu lalu, beberapa influencer terkenal sempat viral karena mempromosikan produk kecantikan yang ternyata berbahaya atau tidak memiliki izin BPOM. Dalam kasus lain, konten “review jujur” ternyata dibuat berdasarkan script dari brand, tanpa pernah mencoba produknya sendiri.
Dalam etika komunikasi, audiens berhak tahu jika mereka sedang menerima pesan komersial. Di negara-negara maju, seperti Amerika Serikat dan Inggris, aturan ini ditegakkan oleh lembaga seperti FTC atau ASA. Mereka mewajibkan influencer untuk mengungkapkan secara eksplisit jika kontennya adalah iklan berbayar.
Sayangnya, di Indonesia, aturan terkait transparansi iklan digital masih belum kuat. Pedoman dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) maupun Kementerian Kominfo belum secara spesifik menyentuh ranah media sosial pribadi, sehingga banyak influencer maupun brand yang bermain abu-abu demi engagement tinggi.
Kejadian-kejadian ini menunjukkan bahwa kurangnya etika bisa menimbulkan kerugian nyata, tidak hanya bagi konsumen, tetapi juga reputasi influencer itu sendiri.
Lalu? Bagaimana dengan iklan konvensional?
iklan konvensional (TV, radio, koran, baliho, dll) masih ada, tapi memang semakin tersisih dan jumlahnya menurun drastis, terutama di kalangan generasi muda dan pengguna internet aktif. Hal ini terjadi karena perubahan perilaku konsumen yang lebih banyak menghabiskan waktu di media sosial, bahkan lebih memilih untuk menonton streaming dibanding menonton TV. Generasi muda (Gen Z dan milenial) cenderung lebih responsif terhadap konten interaktif dan visual pendek, seperti iklan di TikTok atau Instagram. Mengukur efektivitas iklan juga lebih mudah di media sosial, Iklan digital dapat diukur (click, view, conversion), sedangkan iklan konvensional seperti di TV atau koran sulit diukur secara langsung efektivitasnya. Untuk biaya, Iklan TV dan cetak butuh biaya besar dan waktu produksi lebih lama, sedangkan Iklan digital bisa dibuat cepat, murah, dan bisa langsung diubah jika perlu.
Jadi.. Apakah Iklan Konvensional Benar-Benar Hilang?
Tidak. Iklan konvensional masih relevan untuk:
- Target audiens yang lebih tua atau kurang aktif secara digital.
- Kampanye berskala besar atau nasional (misalnya produk FMCG, kampanye politik).
- Meningkatkan brand awareness melalui kehadiran fisik (contoh: billboard di kota besar).
Jadi, iklan konvensional belum punah, tapi perannya makin kecil dan spesifik. Iklan digital sekarang menjadi "raja", karena fleksibel, murah, dan bisa menjangkau target yang lebih tepat.
3. Tanggung Jawab Moral
Bukan hanya brand yang harus mengedepankan etika, tetapi juga para influencer. Mereka memiliki tanggung jawab moral terhadap audiensnya, terutama karena pengikut mereka sering merasa terhubung secara emosional. Jadilah influencer yang jujur dan transparan, hindari klaim produk yang tidak dapat dibuktikan, tidak mempromosikan produk yang berisiko seperti produk produk meragukan yang belum BPOM, dan harus mengungkapkan sponsorship secara jelas.
4. Menuju Etika Digital yang Lebih Baik
Etika dalam periklanan media sosial bukan sekadar soal aturan, tapi soal kejujuran dan tanggung jawab. Di tengah derasnya konten promosi, penting bagi kita sebagai audiens untuk lebih kritis, dan bagi para pelaku industri untuk lebih sadar akan dampak sosial dari setiap pesan yang mereka sebarkan.
Etika digital tidak harus menunggu diawasi oleh KPI agar menjadi lebih baik, hal ini bisa di mulai dari tiap-tiap individu agar iklan di media sosial lebih etis. Buatlah pedoman untuk diri sendiri layaknya menerapkan EPI (Etika Pariwara Indonesia) atau membaca, memahami EPI; seperti jujur, tidak di lebih – lebihkan saat merekomendasikan produk, menggunakan produk terlebih dahulu sebelum mempromosikannya, dan tidak mempromosikan barang illegal atau belum BPOM, bagikan yang terbaik untuk diri sendiri dan orang lain. Hal ini juga dapat menghindari masalah dari followers tiap - tiap individu, lebih di cintai dan dikenali dengan kejujurannya dapat membangun loyalitas followers, mereka akan selalu kembali untuk melihat konten kejujuranmu selanjutnya. Ingat, Influencer bukan hanya pembawa pesan, mereka pencipta persepsi. Etikanya harus sepadan dengan pengaruhnya.
Pada akhirnya, kepercayaan adalah aset terbesar di dunia digital. Ketika kepercayaan itu rusak karena manipulasi atau kebohongan, dampaknya bisa sangat luas. Jadi, jujurlah.
5. Kita butuh Solusi: Regulasi, Edukasi, dan Kesadaran
Menurut saya, untuk mengatasi persoalan ini, kita perlu langkah kolaboratif:
- Pemerintah perlu menyusun regulasi spesifik untuk konten sponsor di media sosial.
- Platform media sosial harus membuat sistem penanda konten berbayar yang lebih tegas.
- Influencer dan brand harus sadar bahwa kejujuran menciptakan loyalitas jangka panjang.
- Konsumen harus lebih kritis, tidak langsung percaya pada setiap "testimoni".
Etika periklanan di media sosial bukan soal hukum semata, melainkan soal integritas, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Ketika para influencer dan brand mengabaikannya, yang dirugikan bukan hanya konsumen, tetapi juga kepercayaan publik terhadap seluruh ekosistem digital.
Semoga ke depan, konten di media sosial bisa menjadi ruang yang lebih jujur, bukan sekadar panggung pencitraan.
Aysah Aurellia Rosspertiwi,
Universitas Muhammadiyah Jakarta
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.