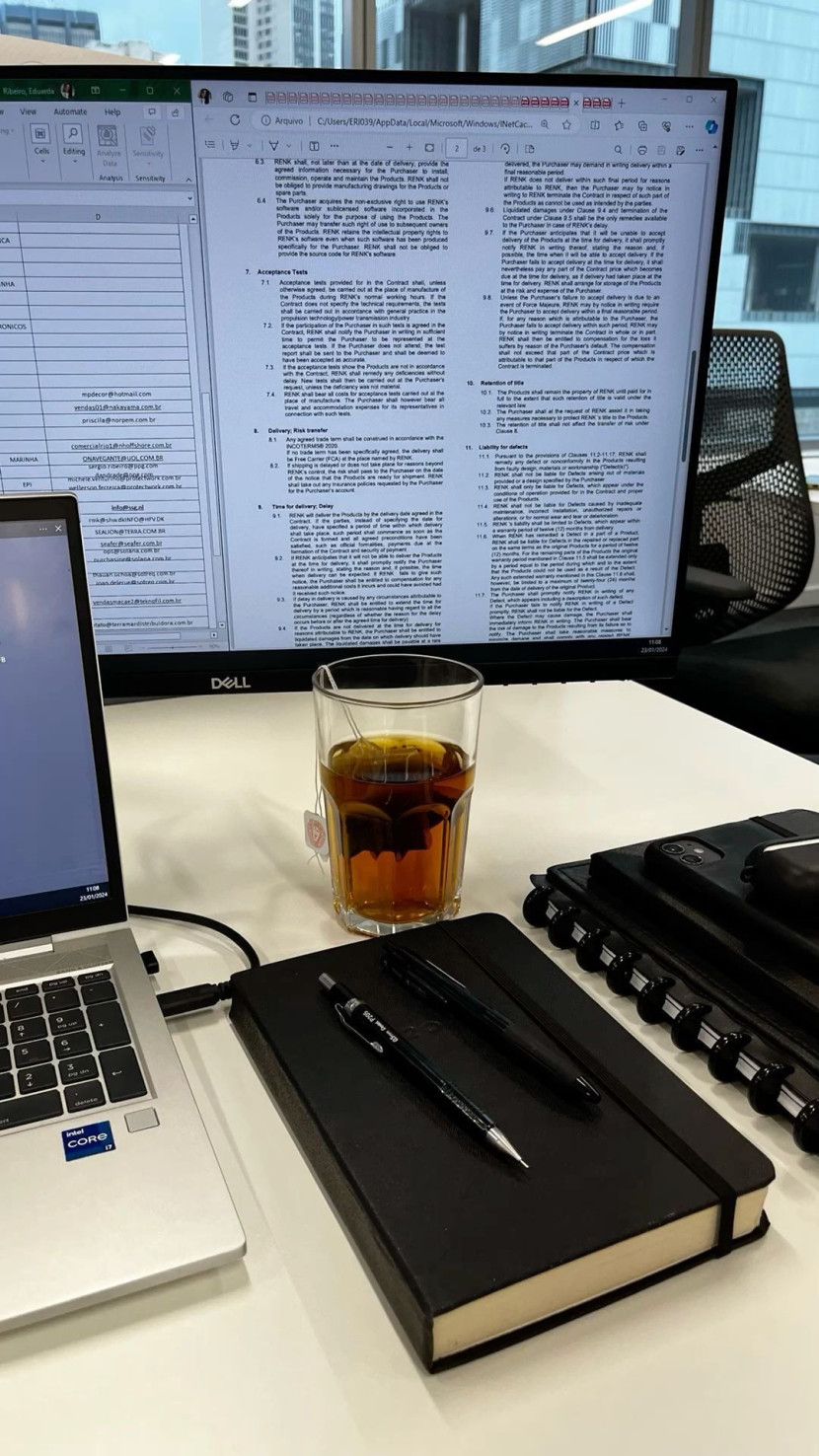Dr. Cand Sukarijanto, SE., MM., CILT., CFS
Dr. Cand Sukarijanto, SE., MM., CILT., CFS
Ketika Kepastian Menjadi Ilusi, Mengapa Kepemimpinan Hibrida Muncul?
Kolom | 2026-02-19 09:41:47Dunia hari ini tidak sedang mengalami perubahan biasa, melainkan perubahan bersifat struktural. Masih memanasnya rivalitas geopolitik Amerika Serikat-Tiongkok, fragmentasi rantai pasok global, percepatan teknologi artificial intelligence (AI) yang sangat eskalatif di berbagai bidang kehidupan, hingga krisis iklim telah mengubah cara negara, perusahaan, dan institusi mengambil keputusan. Stabilitas bukan lagi kondisi normal, ia menjadi pengecualian.
Kondisi inilah yang dikenal sebagai era VUCA, volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Dalam lanskap yang demikian, kepemimpinan tidak lagi dapat bergantung pada model linear berbasis perencanaan jangka panjang yang stabil. Banyak organisasi justru gagal bukan karena kurang strategi, akan tetapi karena implementasi strategi mereka terlalu kaku untuk dunia yang berubah cepat.
Penelitian organisasi menunjukkan bahwa lingkungan VUCA menantang asumsi klasik tentang kepastian strategi dan kontrol manajerial. Studi tentang kesiapan pemimpin di lingkungan VUCA menemukan hasil bahwa metode kepemimpinan lama sering gagal karena perubahan berlangsung terlalu cepat untuk direspon melalui struktur hierarkis tradisional yang lambat mengakomodasi. Padahal, dalam kondisi volatil keputusan harus cepat diambil namun tetap kolaboratif, organisasi membutuhkan stabilitas sekaligus fleksibilitas, pemimpin harus menjadi pengarah sekaligus fasilitator.
Ekonom Institusional Universitas Washington, Douglass North berargumen bahwa sebuah institusi bertahan bukan karena rigiditas, tetapi kemampuan beradaptasi terhadap ketidakpastian. Logika yang sama berlaku pada kepemimpinan, bahwa stabilitas kini berasal dari kemampuan untuk berubah. Dengan kata lain, pemimpin modern tidak lagi hanya “decision maker”, melainkan “sense-maker”, penafsir realitas kompleks.
Di tengah realitas tersebut, konsep kepemimpinan hibrida muncul sebagai jawaban populer: pemimpin yang mampu menggabungkan ketegasan dan empati, hierarki dan kolaborasi, stabilitas dan eksperimen. Namun pertanyaan mendasar perlu diajukan secara lebih kritis, apakah hybrid leadership benar-benar merupakan solusi strategis, atau justru refleksi dari krisis kepemimpinan global yang kehilangan arah?
Ketika Kompetensi Puritan Tidak Lagi Memadai
Sepanjang kurun waktu di abad ke-20, dunia mengenal dua model kepemimpinan dominan. Pertama, model birokratis-hierarkis ala industrialisme Barat yang menekankan kontrol dan efisiensi. Kedua, model strong leadership berbasis sentralisasi keputusan yang banyak muncul dalam negara pembangunan Asia Timur. Keduanya lahir dari dunia yang relatif dapat diprediksi dengan bercirikan, ekonomi tumbuh stabil, teknologi berubah perlahan, dan globalisasi bergerak satu arah. Kini konteks tersebut runtuh. Perang dagang, reshoring industri, serta nasionalisme ekonomi membuat organisasi harus beroperasi dalam banyak logika sekaligus. Perusahaan global harus efisien secara kapitalis namun sensitif secara politik domestik. Negara harus terbuka terhadap investasi tetapi sekaligus protektif terhadap keamanan nasional.
Dalam situasi paradoksal semacam ini, seorang pemimpin tidak lagi cukup menjadi spesialis satu gaya. Mereka dituntut menjadi integrator kontradiksi. Contoh historis paling jelas pada konteks kenegaraan terlihat pada figur Deng Xiaoping. Ia mempertahankan struktur politik komunis sambil membuka mekanisme pasar kapitalistik. Pendekatan ini bukan kompromi ideologis semata, melainkan strategi kepemimpinan hibrida untuk menghadapi ketidakpastian global pasca Perang Dingin.
Dalam konteks organisasi modern, Satya Nadella, CEO Microsoft keturunan India, sukses mengubah budaya kompetitif internal menjadi kolaboratif tanpa kehilangan disiplin kinerja. Ia menggabungkan empati kepemimpinan dengan strategi bisnis agresif, contoh modern hybrid leadership berbasis budaya organisasi. Baik Deng Xiaoping maupun Satya Nadela, menunjukkan pola yang sama, yaitu pola kepemimpinan efektif yang lahir dari kemampuan mengelola paradoks, bukan memilih satu kutub ekstrem.
Fenomena kepemimpinan hibrida juga tidak bisa dilepaskan dari apa yang oleh banyak analis organisasi disebut sebagai krisis kelas manajerial. Selama beberapa dekade, sistem pendidikan manajemen global menghasilkan pemimpin berbasis optimasi, ahli efisiensi, KPI, dan perencanaan rasional. Namun era VUCA menuntut kemampuan yang berbeda, seperti membaca sinyal lemah, mengelola ambiguitas, dan mengambil keputusan tanpa data lengkap.
Henry Mintzberg, seorang profesor bidang manajemen di Universitas McGill, Quebec, Kanada, sejak lama telah mengkritisi adanya fenomena produksi massal lulusan program MBA yang terlalu menekankan analitik dan mengabaikan judgment kontekstual. Krisis pandemi covid-19 memperlihatkan kelemahan tersebut. Banyak organisasi dengan sistem manajemen paling efisien justru paling rapuh menghadapi gangguan ekstrem. Di sinilah hybrid leadership muncul sebagai respons terhadap kegagalan paradigma manajemen lama. Pemimpin kini harus menjadi sekaligus analis data, komunikator empatik, pengambil risiko, dan arsitek budaya organisasi. Akan tetapi masalahnya, tuntutan multidimensi ini menciptakan tekanan baru, yakni tidak semua pemimpin memiliki kapasitas untuk memainkan banyak peran sekaligus. Maka, hybrid leadership juga dapat dibaca sebagai gejala meningkatnya kompleksitas yang melampaui kesiapan elite manajerial global.
Dalam konteks ekonomi modern, keunggulan kompetitif semakin bergeser dari efisiensi menuju adaptabilitas. Joseph Schumpeter menggambarkan kapitalisme sebagai proses”, di mana inovasi terus menggantikan struktur lama. Dalam konteks ini, pemimpin berfungsi sebagai agen transisi, menjaga stabilitas organisasi sambil memungkinkan disrupsi internal. Kepemimpinan hibrida menjadi penting karena organisasi harus melakukan dua hal yang tampak saling bertentangan, yakni mengeksploitasi sistem lama sekaligus mengeksplorasi masa depan. Meskipun demikian, adaptasi tanpa arah juga berbahaya. Fleksibilitas ekstrem dapat menciptakan instabilitas strategis dan meningkatkan biaya koordinasi. Dengan kata lain, hybrid leadership efektif hanya jika memiliki jangkar nilai dan visi jangka panjang.
Mewaspadai Fleksibilitas Tanpa Arah
Meskipun terdengar ideal, hybrid leadership berpotensi memunculkan risiko serius. Pertama, fleksibilitas berlebihan dapat menciptakan kebingungan organisasi. Karyawan membutuhkan konsistensi nilai dan arah strategis. Tanpa itu, adaptasi berubah menjadi ketidakpastian permanen. Kedua, kepemimpinan hibrida mudah disalahartikan sebagai bentuk kompromi politik atau populisme organisasi, seperti pemimpin mencoba menyenangkan semua pihak tanpa keputusan tegas. Ketiga, tuntutan adaptasi konstan meningkatkan risiko burnout pada level eksekutif. Dunia VUCA tidak hanya menciptakan tekanan ekonomi, tetapi juga tekanan psikologis kepemimpinan. Hybrid leadership bukan sekadar soal fleksibilitas, melainkan kemampuan menjaga keseimbangan antara perubahan dan stabilitas.
Bagi negara berkembang seperti Indonesia, diskursus kepemimpinan hibrida memiliki implikasi strategis. Pertama, reformasi birokrasi tidak cukup hanya meningkatkan efisiensi administratif. Aparatur publik perlu dilatih menghadapi ambiguitas kebijakan, koordinasi lintas sektor, dan pengambilan keputusan adaptif. Kedua, sistem pendidikan kepemimpinan nasional—baik di sektor pemerintahan maupun korporasi, perlu bergeser dari model hafalan prosedural menuju pembelajaran berbasis problem kompleks. Ketiga, negara membutuhkan pemimpin yang mampu menjembatani dualitas pembangunan, yaitu stabilitas sosial domestik dan kompetisi ekonomi global.
Kepemimpinan hibrida relevan bukan karena dunia membutuhkan pemimpin yang serba bisa, tetapi karena realitas modern dipenuhi kontradiksi yang tidak dapat diselesaikan secara linear. Era VUCA menuntut pemimpin yang mampu hidup dalam atmosfir ketegangan antara kepastian dan perubahan, antara kontrol dan kepercayaan, antara strategi jangka panjang dan respons cepat. Namun, hybrid leadership bukanlah semacam obat universal. Ia efektif hanya ketika fleksibilitas dipandu oleh nilai yang jelas dan arah strategis yang konsisten.
Pada akhirnya, tantangan terbesar kepemimpinan abad ke-21 bukan lagi bagaimana memimpin dalam kondisi stabil, melainkan bagaimana menciptakan stabilitas di dunia yang secara permanen tidak stabil. Dan mungkin di situlah definisi baru kepemimpinan lahir: bukan pengendali perubahan, melainkan arsitek adaptasi kolektif Dalam konteks geopolitik multipolar, kemampuan hibrida ini menjadi aset strategis. Negara yang terlalu kaku berisiko tertinggal, dan sebaliknya, negara yang terlalu oportunistik kehilangan kredibilitas.

Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.