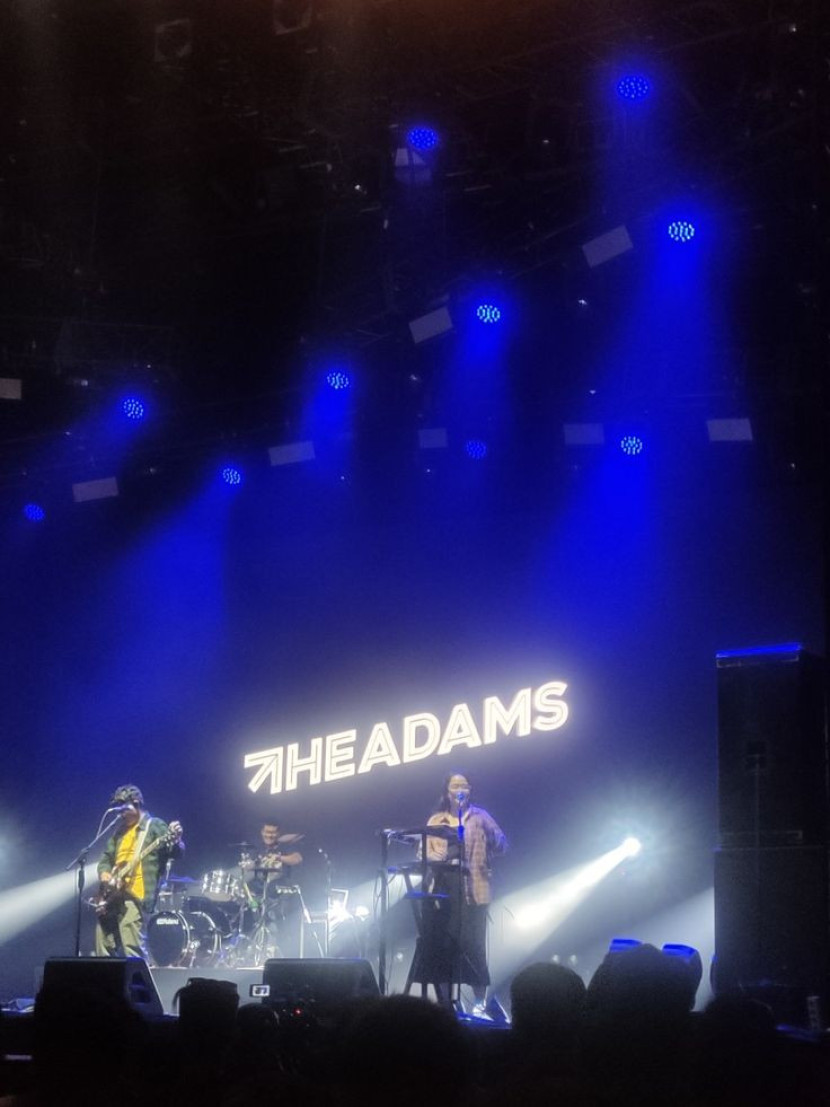Badrut Tamam
Badrut Tamam
Pesantren dan Masa Depan Karakter Bangsa: Sebuah Solusi?
Edukasi | 2026-01-22 09:59:05
Oleh: Muhamad Arifin
(Dosen STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB)
Belum lama ini, kita dikejutkan oleh berita-berita pilu: pengeroyokan siswa terhadap guru, bullying yang berujung luka fisik dan mental, hingga kekerasan verbal yang menjadi “bahasa sehari-hari” di kalangan pelajar. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2023 menunjukkan tingginya angka kekerasan di lingkungan pendidikan, baik secara fisik maupun psikis. Fenomena ini adalah bukti nyata dari degradasi moral yang menggerogoti sendi-sendi karakter anak bangsa.
Situasi ini mengingatkan kita pada peringatan Bung Hatta, “...tidak jujur itu sangat susah diperbaiki.” Kekerasan dan ketidakadilan adalah anak kandung dari ketidakjujuran terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Lembaga pendidikan, yang seharusnya menjadi taman yang menumbuhkan kebajikan, justru kerap menjadi panggung konflik dan penyimpangan. Ini adalah alarm darurat bahwa pendekatan pendidikan kita selama ini terlalu menitikberatkan kecerdasan akademik (kognitif) dan mengabaikan penanaman karakter (afektif) serta pembiasaan perilaku (psikomotorik) secara serius.
Lemahnya Fondasi Karakter dan Kendali Diri
Banyak analisis menyebutkan bahwa lemahnya kontrol diri, rendahnya empati, dan kaburnya nilai hormat kepada guru dan sesama adalah akar masalahnya. Dunia digital yang tanpa batas memperparah kondisi ini, di mana kekerasan verbal dan fisik di dunia nyata seringkali merupakan lanjutan dari permusuhan di dunia maya. Sekolah umum, dengan waktu interaksi yang terbatas dan sistem yang seringkali terjebak pada formalitas kurikulum, kesulitan membangun fondasi karakter yang kokoh. Pendidikan karakter menjadi sekadar mata pelajaran, bukan nafas yang menghidupi seluruh aktivitas sekolah.
Lalu, adakah alternatif ekosistem pendidikan yang mampu membendung krisis ini? Di sinilah pesantren menawarkan model yang relevan. Sebagai sub-kultur pendidikan (Geertz & Wahid), pesantren bukan sekadar sekolah, tetapi sebuah ekosistem kehidupan. Sistem asrama menciptakan lingkungan 24 jam di mana nilai-nilai tidak hanya diajarkan, tetapi “dihidupi” dan “diawasi” secara kolektif.
Kontrol ketat terhadap gadget dan akses internet, seperti diungkapkan Arifin (2024), bukan bentuk pengasingan, melainkan strategi untuk menciptakan ruang aman bagi pembentukan konsentrasi dan karakter. Dalam ekosistem ini, hubungan antara santri, ustadz, dan kiai dibangun dengan pondasi rasa hormat (ta'dzim) yang mendalam. Kekerasan fisik atau verbal terhadap guru adalah hal yang hampir tak terbayangkan karena nilai adab kepada pengajar adalah fondasi pertama yang ditanamkan.

Akhlak: Lebih Dari Sekedar Teori
Yang membedakan pesantren adalah kemampuannya menerjemahkan pendidikan akhlak menjadi tindakan nyata. Bukan hanya tahu bahwa bullying itu salah, tetapi santri hidup dalam lingkungan yang secara aktif mencegahnya melalui pengawasan peer group dan figur otoritas (kiai/ustadz) yang selalu hadir. Konsep “otot-otot akhlak” yang perlu terus dilatih (Indonesian Heritage Foundation, dalam Arifin, 2024) menemukan medan latihannya yang sempurna di pesantren.
Nilai-nilai inti seperti “hormat” (al-adab), “kasih saying” (ar-rahmah), “tanggung jawab” (al-mas'uliyyah), dan “cinta damai” (as-silm) dikembangkan bukan melalui seminar, tetapi melalui interaksi harian: mengantri mandi, menghormati teman yang sedang menghafal, menyelesaikan konflik dengan mediasi, hingga kerja bakti membersihkan lingkungan. Inilah pendidikan karakter yang aplikatif, yang langsung menyentuh ranah perilaku.
Kontribusi Pesantren untuk Pendidikan Nasional
Maraknya kekerasan di lembaga pendidikan adalah cermin kegagalan kita membangun ekosistem karakter yang integral. Pesantren, dengan segala keunikannya, menunjukkan bahwa pembentukan karakter memerlukan:
1. Waktu yang cukup: Tidak bisa dicicil 2 jam pelajaran per minggu.
2. Keterlibatan komunitas penuh: Guru, pengasuh, dan senior semua adalah pendidik.
3. Keteladanan yang konsisten: Figur otoritas (kiai/ustadz) hidup di tengah dan menjadi contoh utama.
4. Sistem yang mendukung: Aturan, rutinitas, dan pengawasan yang jelas untuk membentuk kebiasaan.
Pemerintah dan pelaku pendidikan formal perlu melihat pesantren bukan sebagai lembaga eksklusif, tetapi sebagai laboratorium hidup pendidikan karakter. Kolaborasi bisa dibangun, misalnya dengan program pertukaran pengalaman, integrasi model mentoring asrama ke sekolah tertentu, atau pelatihan guru yang menekankan pada keteladanan dan pendekatan holistik.
Seperti pepatah Arab yang dikutip penulis, “Syubbānul yaum rijālul ghad”: Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Jika kita ingin masa depan dengan pemimpin yang berintegritas, empatik, dan menjunjung tinggi perdamaian, maka kita harus memperbaiki ekosistem pendidikan yang membentuk mereka hari ini. Pesantren, dengan warisan panjangnya, menawarkan secercah solusi yang patut dipertimbangkan dan diadaptasi dengan konteks kekinian. Krisis kekerasan di sekolah adalah panggilan mendesak untuk tidak lagi memandang pendidikan karakter sebagai pelengkap, tetapi sebagai inti dari proses pembelajaran.
Referensi:
Arifin, M. (2024). *Pendidikan Pesantren: Solusi atas Moralitas Anak Bangsa?* (Artikel orisinal yang dikembangkan).
Wahid, A. & Geertz, C. (Konsep pesantren sebagai sub-kultur).
Indonesian Heritage Foundation. (Konsep 9 Pilar Karakter dalam Arifin, 2024).
Data dan Laporan KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) mengenai kekerasan di lingkungan pendidikan.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.