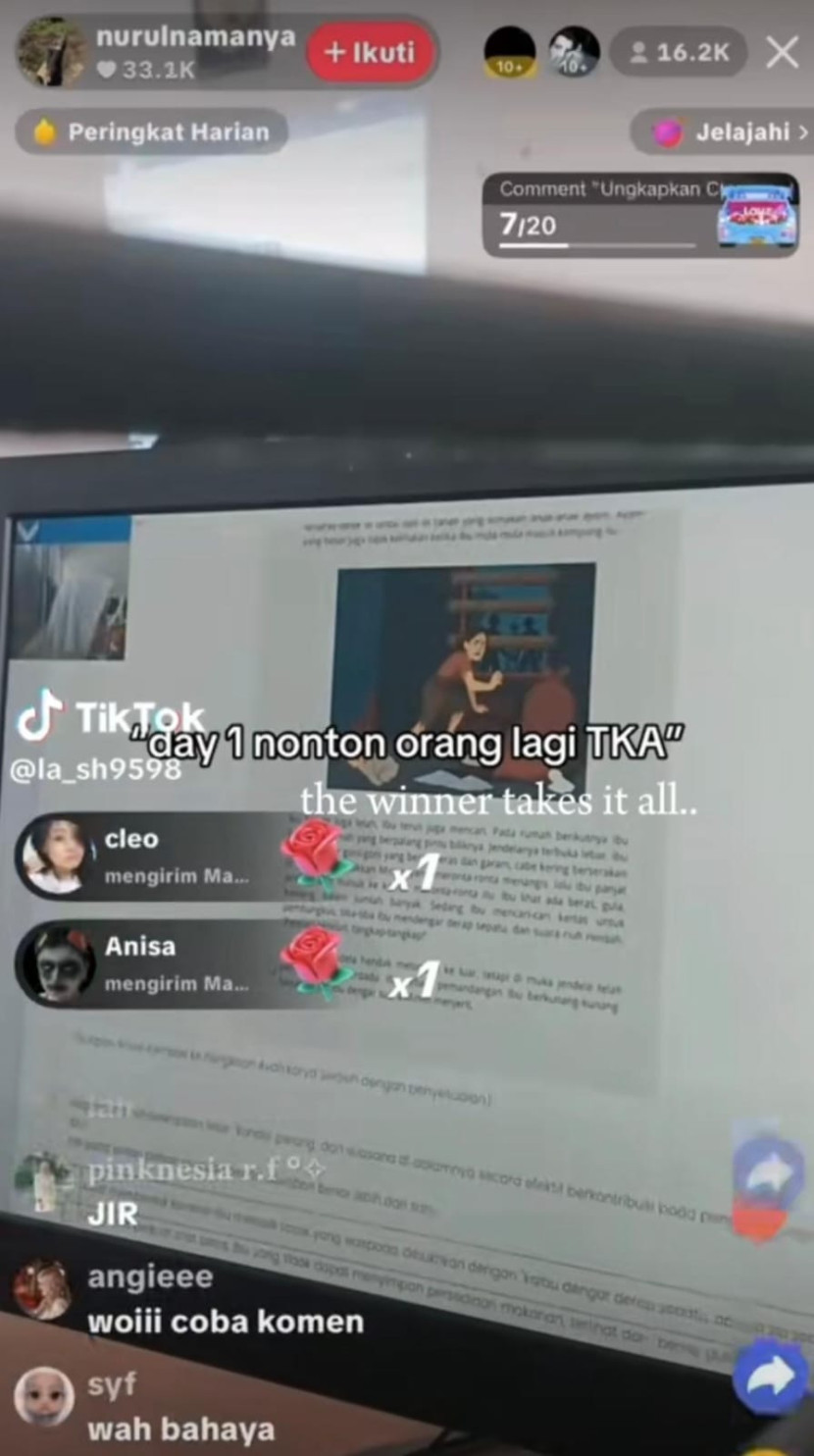Humas UMKT
Humas UMKT
Perlu Reformasi Sistemik, Bukan Sekadar Menyalahkan Guru!
Edukasi | 2025-12-30 14:16:42
Abdul Halim, Ph.D. Wakil Rektor I UMKT
umkt.ac.id - Rilis terbaru tentang rendahnya hasil TKA Bahasa Inggris SMA tahun 2025 dengan rerata nasional hanya sekitar 25 dari 100 adalah sebuah alarm keras yang seharusnya mengguncang kesadaran kita. Namun, kesalahan terbesar yang terus berulang adalah kecenderungan menyalahkan guru sebagai biang keladi tunggal. Cara pandang ini bukan hanya tidak adil, melainkan juga menyesatkan, karena menutup mata terhadap kompleksitas persoalan yang jauh lebih luas. Guru memang berperan penting, tetapi mereka bekerja dalam ekosistem yang sempit, dengan paparan bahasa yang minim, kurikulum yang kaku, serta kebijakan yang sering kali tidak berpihak pada pembelajaran komunikatif. Jika kita ingin keluar dari krisis ini, maka solusi tidak bisa berhenti pada pelatihan guru, melainkan harus berupa reformasi sistemik yang menyentuh akar persoalan.
Langkah pertama yang mendesak adalah reformasi asesmen. Selama ini, ujian Bahasa Inggris di Indonesia masih terjebak dalam paradigma lama yang menilai grammar, vocabulary, dan reading comprehension secara terpisah. Padahal, bahasa bukan sekadar kumpulan aturan, melainkan alat komunikasi. Ironisnya, siswa yang mampu menjawab soal grammar sering kali gagap ketika harus berbicara dengan penutur asing. Tes berbasis performa seperti speaking test, listening comprehension dalam konteks autentik, atau simulasi percakapan harus menjadi bagian integral dari evaluasi. Jika asesmen tetap berorientasi pada hafalan, maka guru dan siswa akan terus terjebak dalam lingkaran setan: belajar untuk tes, bukan belajar untuk berkomunikasi. Reformasi asesmen adalah pintu masuk utama untuk mengubah orientasi pembelajaran dari sekadar hafalan menuju kemampuan komunikasi nyata.
Selain asesmen, paparan bahasa adalah kunci pemerolehan bahasa. Di Indonesia, paparan Bahasa Inggris sangat terbatas. Di luar kelas, hampir tidak ada ruang publik yang menggunakan Bahasa Inggris. Di dalam kelas, waktu belajar singkat dan interaksi minim. Di era digital, keterbatasan paparan seharusnya bisa diatasi. Integrasi teknologi dan media digital harus menjadi strategi utama. Platform seperti YouTube, podcast, film berbahasa Inggris, aplikasi belajar interaktif, hingga game online dapat menjadi sumber paparan yang kaya. Namun, integrasi ini tidak boleh sekadar formalitas. Sekolah harus berani memasukkan media digital ke dalam kurikulum, bukan hanya sebagai tambahan tetapi sebagai bagian inti pembelajaran. Bayangkan jika siswa diwajibkan membuat vlog berbahasa Inggris, berdiskusi melalui forum daring internasional, atau mengerjakan proyek kolaboratif dengan sekolah luar negeri melalui platform digital. Paparan semacam ini tidak hanya meningkatkan kompetensi bahasa, tetapi juga membangun kepercayaan diri dan motivasi. Mengabaikan teknologi dalam pembelajaran bahasa sama saja dengan menutup mata terhadap kenyataan bahwa generasi muda kita hidup di dunia digital.

Langkah berikutnya adalah keberanian untuk menerapkan program bilingual di sekolah tertentu. Indonesia sering kali terjebak dalam kebijakan seragam: semua sekolah diperlakukan sama, padahal kondisi dan kebutuhan berbeda. Program bilingual bukan berarti mengganti Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar utama, melainkan memberikan ruang bagi Bahasa Inggris untuk digunakan lintas mata pelajaran. Misalnya, mata pelajaran sains atau teknologi diajarkan sebagian dalam Bahasa Inggris. Dengan demikian, siswa tidak hanya belajar bahasa sebagai mata pelajaran, tetapi juga menggunakannya sebagai alat berpikir dan komunikasi. Filipina dan Singapura berhasil karena Bahasa Inggris hadir dalam berbagai konteks akademik dan sosial. Indonesia bisa meniru dengan cara yang disesuaikan: tidak semua sekolah harus bilingual, tetapi sekolah-sekolah tertentu bisa dijadikan pusat unggulan. Dari sini, praktik baik bisa menyebar ke sekolah lain. Menolak program bilingual dengan alasan tidak realistis adalah bentuk pesimisme yang berbahaya. Justru dengan keberanian mencoba, kita bisa menemukan model pembelajaran bahasa yang lebih efektif.
Namun, semua langkah tersebut akan sia-sia jika kebijakan tidak memperhatikan kesenjangan wilayah. Siswa di kota besar memiliki akses ke guru berkualitas, kursus, internet, dan media digital. Sementara itu, siswa di daerah terpencil sering kali belajar dengan fasilitas minim, guru terbatas, dan akses internet yang buruk. Jika kebijakan bahasa tidak memperhatikan kesenjangan ini, maka reformasi hanya akan memperkuat ketimpangan. Kebijakan afirmatif harus diterapkan: daerah tertinggal mendapat dukungan lebih besar, baik berupa fasilitas digital, pelatihan guru, maupun program khusus untuk memperluas paparan bahasa. Pemerintah bisa menyediakan learning hub berbasis komunitas di daerah terpencil, lengkap dengan akses internet dan materi digital berbahasa Inggris. Guru di daerah tersebut harus mendapat insentif lebih besar agar termotivasi. Tanpa kebijakan afirmatif, kita hanya akan menciptakan Indonesia dua wajah: satu kelompok siswa yang siap bersaing global, dan kelompok lain yang terus tertinggal.
Selain itu, kita tidak boleh melupakan peran keluarga dan komunitas belajar informal. Sekolah bukan satu-satunya ruang belajar. Dukungan keluarga dan komunitas belajar informal adalah faktor yang sering diabaikan. Padahal, motivasi dan paparan bahasa sering kali lebih kuat di luar kelas. Keluarga bisa berperan dengan cara sederhana: menyediakan buku cerita berbahasa Inggris, menonton film bersama, atau mendukung anak mengikuti kursus daring. Komunitas belajar informal seperti English club, kelompok diskusi, atau bahkan komunitas gamer online bisa menjadi ruang paparan bahasa yang otentik. Sayangnya, kebijakan pendidikan jarang melibatkan keluarga dan komunitas. Padahal, tanpa dukungan mereka, pembelajaran bahasa akan berhenti di ruang kelas yang terbatas. Pemerintah harus mendorong program yang melibatkan keluarga, misalnya kampanye nasional “English at Home” atau dukungan bagi komunitas belajar bahasa di tingkat lokal. Mengabaikan peran keluarga dan komunitas sama saja dengan mengabaikan kenyataan bahwa bahasa adalah praktik sosial, bukan sekadar mata pelajaran.
Kesimpulannya, rendahnya hasil TKA Bahasa Inggris SMA 2025 bukanlah sekadar masalah guru. Guru memang penting, tetapi mereka bekerja dalam ekosistem yang sempit. Tanpa reformasi asesmen, integrasi teknologi, program bilingual, kebijakan afirmatif untuk daerah tertinggal, serta dukungan keluarga dan komunitas, kompetensi Bahasa Inggris siswa Indonesia tidak akan pernah meningkat signifikan. Kita harus berani mengubah paradigma: dari pendekatan individual ke pendekatan sistemik. Reformasi ini bukan pilihan, melainkan keharusan. Jika tidak, kita akan terus mengulang siklus lama: guru dilatih, siswa diuji, hasil rendah, lalu guru kembali disalahkan. Bahasa Inggris bukan sekadar mata pelajaran, melainkan alat komunikasi global. Jika Indonesia ingin bersaing di dunia internasional, maka pembelajaran Bahasa Inggris harus diperlakukan sebagai investasi strategis. Reformasi sistemik adalah satu-satunya jalan keluar dari krisis ini.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.