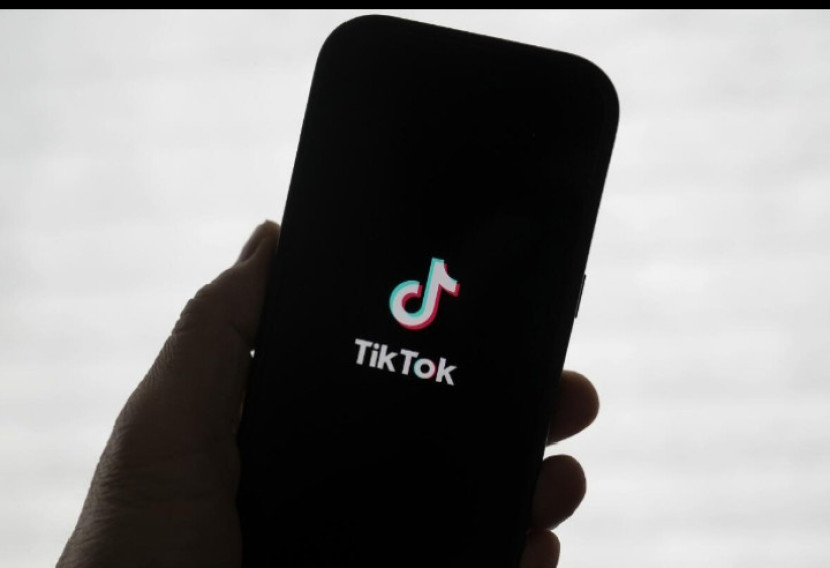Syakira Amalia Putri Prayogo
Syakira Amalia Putri Prayogo
Hedonisme Digital: Ketika FOMO Mengatur Kebahagiaan Kita
Rubrik | 2025-11-25 08:14:42Dalam beberapa tahun terakhir, kebahagiaan masyarakat semakin dipengaruhi oleh dinamika ruang digital. Media sosial, yang semula diposisikan hanya sebagai sarana hiburan atau komunikasi, kini berkembang menjadi arena pembandingan sosial yang intens. Pada titik tertentu, muncul fenomena yang kian menonjol: ketakutan tertinggal dari arus tren atau Fear of Missing Out (FOMO). Fenomena ini tidak hanya memengaruhi preferensi hiburan atau konsumsi, tetapi juga cara masyarakat mendefinisikan kebahagiaan.

Bersumber dari laporan We Are Social pada awal tahun 2025, rata-rata pengguna internet di Indonesia menghabiskan waktu sekitar 3 jam 8 menit atau setara dengan 188 menit per hari untuk mengakses media sosial, menempatkan Indonesia pada posisi ke-9 dalam daftar negara dengan durasi penggunaan media sosial terlama di dunia. Sementara itu, merujuk pada laporan Digital 2025: Indonesia yang dirilis oleh DataReportal menunjukkan bahwa terdapat sekitar 143 juta identitas pengguna media sosial pada Januari 2025, atau setara dengan 50,2% dari total populasi. Angka-angka tersebut mengindikasikan bahwa interaksi digital bukan lagi selingan, tetapi bagian penting dari rutinitas harian yang membentuk persepsi diri dan relasi sosial.
Masalah utama bukan terletak pada platformnya, melainkan pada cara validasi yang tumbuh di dalamnya. Unggahan yang memperoleh banyak respons positif sering dianggap sebagai cerminan nilai diri. Riset “The Role of Likes: How Online Feedback Impacts Users' Mental Health” (2024) menunjukkan bahwa reaksi online dapat berdampak besar terhadap harga diri, rasa keterhubungan sosial, hingga tingkat stres pengguna. Dalam lingkungan seperti ini, keputusan personal kerap bergeser menjadi keputusan yang berdasar pada ekspektasi orang banyak: apakah suatu pilihan akan dianggap relevan oleh publik.
Ungkapan sederhana seperti “kamu belum coba” atau “ini lagi viral” menjadi sentilan yang menyadarkan seseorang bahwa posisinya dalam pergaulan dunia maya sangat bergantung pada seberapa cepat ia mengikuti tren. Tekanan ini bekerja pelan dan nyaris tak terasa, tetapi dampaknya nyata. Banyak orang akhirnya menjalani hidup dengan ritme yang bukan berasal dari keinginan sendiri, melainkan karena tuntutan di media sosial.
Konsekuensi psikologisnya sering kali diremehkan. Banyak anak muda mengalami kelelahan sosial karena merasa harus tampil menarik setiap hari. Ada dorongan terus-menerus untuk memperbarui diri, memastikan bahwa hidup mereka terlihat dinamis meski kenyataannya tidak selalu demikian. Mereka mengejar sesuatu yang tidak pernah selesai: perhatian publik. Kondisi ini melahirkan kekosongan emosional yang tidak mudah dikenali, karena tertutup oleh aktivitas yang tampak menyenangkan. Di tengah gemuruh konten, justru banyak orang merasa semakin jauh dari dirinya sendiri.
Fenomena ini juga menyisipkan pola konsumsi tanpa pikir panjang. Ketika konten menunjukkan gaya hidup tertentu sebagai standar, banyak orang tergiur membeli sesuatu yang tidak mereka butuhkan. Yang mereka beli bukan sekadar bendanya, melainkan pengakuan sosial. Belanja tidak lagi memenuhi kebutuhan, tetapi menjadi cara untuk menjaga citra diri di ruang digital. Konsumsi berubah dari aktivitas rasional menjadi respons emosional terhadap tekanan sosial.
Meski demikian, penting diakui bahwa tren digital tidak selalu berdampak negatif. Banyak kampanye mengenai kesehatan, olahraga, literasi finansial, edukasi seksualitas, hingga gerakan solidaritas sosial. Di banyak kesempatan, tren dapat menjadi pintu masuk bagi perubahan yang lebih baik. Yang menjadi masalah ialah ketika tren menjadi kewajiban tak tertulis. Tekanan sosial yang memaksa setiap orang merasa wajib mengikuti tren, meski bertentangan dengan kebutuhan pribadinya, menghilangkan ruang kebebasan dan refleksi. Ketika pilihan diambil bukan karena kehendak, tetapi karena kecemasan, hidup menjadi sekadar respons otomatis terhadap desakan dari luar
Fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari struktur ekonomi digital. Platform media sosial dirancang untuk mempertahankan perhatian pengguna selama mungkin. Algoritma mengedepankan konten yang memicu keterlibatan tinggi, termasuk konten yang menimbulkan perbandingan sosial. Kompetisi antarteknologi dalam merebut waktu pengguna, sebagaimana dalam “Tech titans clash over scraps of limited time” yang diberitakan oleh Reuters pada tahun 2025, memperjelas bahwa perhatian manusia saat ini adalah sumber daya yang sangat diperebutkan. Karena itu, persoalan hedonisme digital tidak cukup disikapi melalui imbauan moral individual, tetapi membutuhkan diskusi lebih luas mengenai literasi digital dan desain teknologi yang lebih etis.
Pada akhirnya, kita perlu mengambil kembali kendali atas hidup kita. Pertanyaannya sederhana tetapi mendasar: apakah keputusan kita hari ini lahir dari keinginan atau dari ketakutan? Dunia digital akan terus menciptakan tren baru dalam hitungan jam. Algoritma tidak berhenti bekerja. Selalu ada suguhan baru yang dianggap perlu dicoba. Namun di tengah derasnya arus ini, manusia tetap memiliki ruang untuk memilih. Kebahagiaan tidak seharusnya menjadi proyek publik yang diukur dari respons di media sosial, melainkan keputusan pribadi yang selaras dengan nilai masing masing.
Pemulihan kendali ini memerlukan kesadaran individu sekaligus perubahan cara kita memandang relevansi sosial. Tidak semua tren perlu diikuti. Tidak setiap hal viral memiliki nilai untuk kehidupan pribadi. Terdapat kekuatan dalam kemampuan mengatakan “tidak perlu” kepada sesuatu yang tampak menarik. Tindakan kecil itu menjadi bentuk perlawanan terhadap tekanan sosial yang mengatur cara berpikir dan bertindak.
Selain itu, masyarakat perlu memahami bahwa apa yang terlihat di layar bukan seluruh kisah. Banyak yang tampak mudah adalah hasil kerja panjang yang tidak ditampilkan. Banyak yang terlihat mewah sebenarnya dilandasi tuntutan ekonomi, bukan kenyamanan. Kesadaran ini dapat meredakan tekanan untuk terus membandingkan diri dengan orang lain.
Jika masyarakat tidak belajar mengendalikan ritme ini, hedonisme digital akan terus membentuk generasi yang rentan terhadap tekanan sosial. Individu yang selalu merasa tertinggal, selalu merasa perlu memperbarui diri, dan selalu merasa kurang. Tantangannya bukan menghentikan tren, tetapi memastikan individu tetap memiliki kendali atas hidupnya. Dunia digital mungkin menawarkan panggung, tetapi kita tetap memiliki hak penuh atas naskah yang ingin kita mainkan.
Pada akhirnya, kebebasan tidak ditentukan oleh kemampuan mengikuti arus, melainkan oleh keberanian untuk menentukan arah. Di tengah derasnya hedonisme digital, kemampuan menjaga kedalaman diri menjadi bentuk perlawanan paling penting. Jika kita berhasil mempertahankan ruang itu, maka kebahagiaan tidak akan lagi ditentukan oleh sorakan semu di media sosial, tetapi oleh suara hati yang jujur dari dalam diri.
Referensi:
Saba, J. (2025). Tech titans clash over scraps of limited time. https://www.reuters.com/breakingviews/tech-titans-clash-over-scraps-limited-time-2025-05-27/
Voggenreiter, A., Brandt, S., Putterer, F., Frings, A., & Pfeffer, J. (2024). The Role of Likes: How Online Feedback Impacts Users’ Mental Health. Proceedings of the 16th ACM Web Science Conference, WebSci 2024, 302–310. https://doi.org/10.1145/3614419.3643995
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.