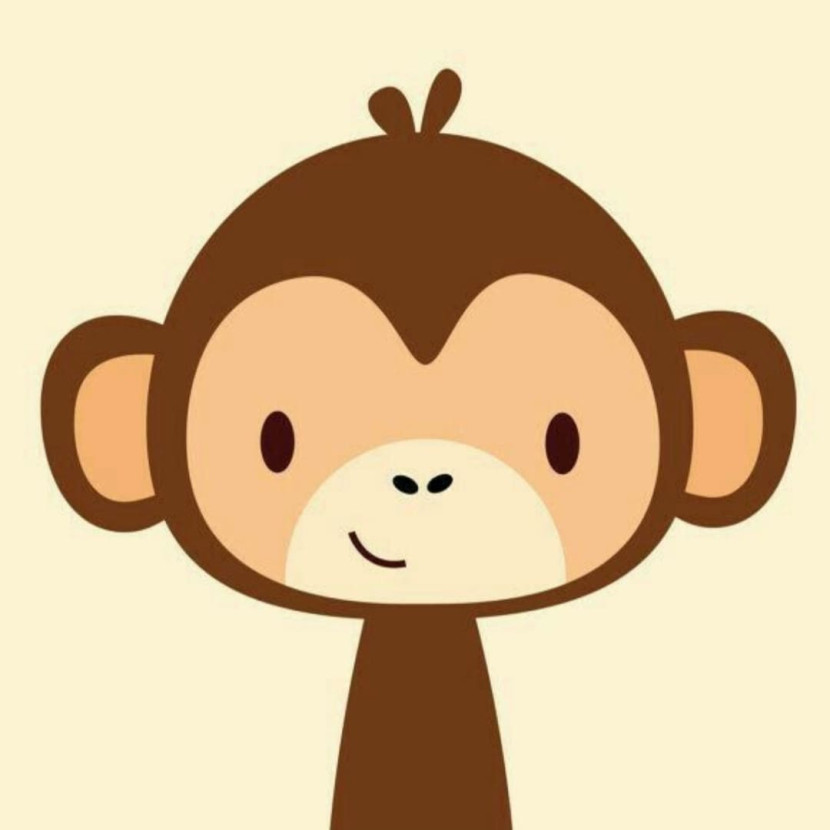Ana Fras
Ana Fras
Al-Fashir dan Cermin Runtuhnya Perisai Umat
Politik | 2025-10-31 19:27:50
Kota Al-Fashir, ibu kota Darfur Utara, kini menjadi saksi bisu kehancuran kemanusiaan di tengah dunia Islam.Sejak April 2023, perang antara militer Sudan (Sudan Armed Forces/SAF) dan pasukan paramiliter Rapid Support Forces (RSF) menjerat kota ini dalam pengepungan panjang. Menurut data ACLED (Armed Conflict Location & Event Data Project), hingga Agustus 2025 tercatat lebih dari 400 insiden kekerasan terhadap warga sipil di wilayah Al-Fashir dan sekitarnya dengan lebih dari 1.400 korban jiwa. Laporan AP News pada 31 Oktober 2025 menambahkan, sedikitnya 91 orang tewas hanya dalam sebulan terakhir, sementara 23 orang meninggal akibat kelaparan dalam bulan yang sama.
UNICEF, dalam pernyataannya pada Agustus 2025, menggambarkan penderitaan anak-anak di Al-Fashir setelah lebih dari 500 hari pengepungan: kelaparan massal, penyakit yang tak tertangani, dan fasilitas kesehatan yang lumpuh.Badan Kesehatan Dunia (WHO) bahkan mengutuk serangan berulang terhadap Saudi Maternity Hospital — satu-satunya rumah sakit bersalin yang tersisa — yang menewaskan tenaga medis dan lebih dari 460 pasien serta pengungsi. Sementara laporan EUAA (European Union Agency for Asylum) menegaskan RSF menutup seluruh jalur logistik ke kota, memutus suplai makanan, air, dan obat-obatan. Citra satelit yang dianalisis Yale Humanitarian Research Lab dan dipublikasikan The Washington Post menunjukkan dinding dan parit sepanjang tiga puluh kilometer yang mengelilingi kota itu — menciptakan apa yang disebut analis sebagai “kill box”.
Di tengah kehancuran ini, azan masih berkumandang. Namun suara takbir bercampur dengan dentuman senjata yang ditembakkan oleh tangan-tangan sesama Muslim. Hampir seluruh penduduk Al-Fashir beragama Islam, tetapi keislaman itu tidak lagi cukup untuk menghentikan darah yang tumpah. Inilah tragedi paling telanjang dari lemahnya perisai umat.
Dari lensa ideologis Islam sebagaimana digariskan Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, tragedi Al-Fashir bukan semata konflik etnis atau politik. Ia adalah simptom ideologis — tanda sakit kronis yang menimpa dunia Islam sejak runtuhnya Khilafah Islamiyyah pada 1924.
Menurut an-Nabhani, ketika kepemimpinan Islam hilang, umat kehilangan “perisainya” yaitu sistem politik yang menerapkan hukum Allah dan melindungi darah kaum Muslimin. Negeri-negeri Islam pun terpecah menjadi negara-negara sekuler buatan penjajah, di mana kekuasaan dipegang oleh elit militer dan politik yang loyal kepada sistem kapitalis, bukan kepada Islam.
Sudan adalah contoh nyata warisan kolonial itu. Meski 99 persen penduduknya Muslim, konstitusi dan sistem hukumnya sekuler. Militer nasional (SAF) dan RSF sama-sama bersumpah atas nama Islam, namun keduanya berperang untuk kekuasaan dan harta, bukan untuk menegakkan syariat. Dalam kacamata an-Nabhani, pertikaian semacam ini bukan jihad, melainkan perang antar-alat penjajahan yang berbeda seragam namun tunduk pada sistem kufur yang sama.
Barat tidak lagi perlu menaklukkan umat dengan pasukan. Cukup menanamkan sistemnya, memelihara rezim-rezim yang bergantung padanya, dan membiarkan umat Islam saling menghabisi diri. Dalam konteks Sudan, kepentingan asing terlihat jelas: Uni Emirat Arab disebut sebagai penyokong dana dan senjata bagi RSF demi keuntungan tambang emas; Mesir mendukung militer SAF untuk menjaga stabilitas politik yang sejalan dengan blok Barat; sementara Rusia, Turki, dan Cina ikut memburu keuntungan dari perdagangan senjata dan sumber daya Darfur. Semua pihak bermain di atas penderitaan umat Islam.
An-Nabhani sejak lama memperingatkan bahwa nasionalisme dan sekularisme adalah racun yang menghancurkan ukhuwah. Ia memecah umat menjadi bangsa-bangsa kecil yang saling curiga, hingga mereka rela menumpahkan darah saudara seimannya. Apa yang terjadi di Al-Fashir adalah bukti nyata tesis itu: kaum Muslim saling membunuh atas nama etnis dan bendera, bukan karena perbedaan aqidah.
Dari sisi spiritual, tragedi ini adalah fitnah bagi umat yang meninggalkan hukum Allah namun tetap mengaku Muslim. Ketika syariat diganti dengan undang-undang Barat, lahirlah tirani; ketika jihad diubah menjadi ambisi pribadi, darah menjadi murah; dan ketika umat membisu, kehinaan turun atas mereka semua. Dalam pandangan an-Nabhani, kehinaan itu tidak akan berakhir melalui konferensi damai atau perjanjian politik, karena akar masalahnya bukan pertempuran, melainkan sistem yang melahirkannya.
Solusi sejati, bagi beliau, adalah kebangkitan ideologis Islam. Umat harus kembali memahami dirinya sebagai satu ummah, menolak seluruh sistem kufur — kapitalisme, nasionalisme, dan demokrasi — dan menegakkan kembali Khilafah ‘ala minhaj an-nubuwwah yang menjadi perisai tunggal umat. Hanya dengan itu hukum Allah dapat ditegakkan, darah Muslim dilindungi, dan kehormatan umat dikembalikan.
Al-Fashir bukan sekadar tragedi Afrika, sebagaimana Gaza bukan sekadar konflik Timur Tengah. Keduanya adalah dua luka dari satu tubuh: Gaza mencerminkan penindasan dari luar, Al-Fashir menggambarkan kehancuran dari dalam. Keduanya bersumber dari sebab yang sama — hilangnya kepemimpinan Islam yang adil.
Selama dunia Islam tetap berada di bawah sistem sekuler dan tatanan global kapitalis, tragedi seperti Al-Fashir akan terus berulang dengan nama dan tempat yang berbeda. Dan selama umat ini belum menegakkan kembali perisainya, darahnya akan tetap tumpah di bumi yang mereka sucikan sendiri.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.