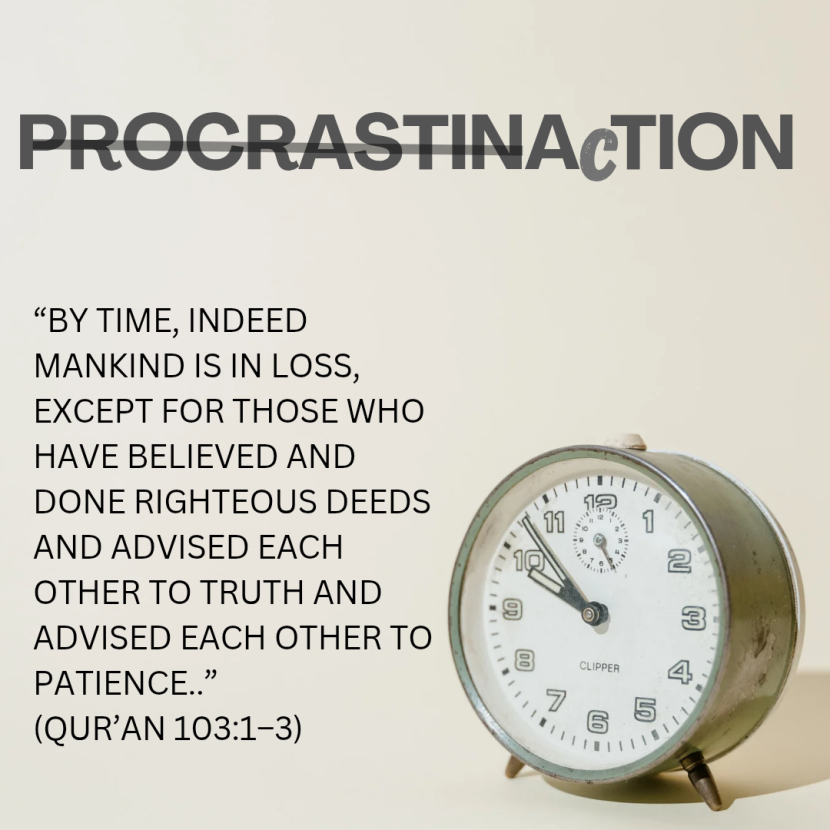Ghulam Mujadid
Ghulam Mujadid
Islam dan Politik : Interpertasi Wacana Kenegaraan
Agama | 2025-01-06 16:12:19Islam dan politik memiliki hubungan yang erat dan kompleks serta Islam juga dalam kaitannya dengan politik telah mewarnai kajian sosiohistoris, di mana keduanya sering kali dipengaruhi oleh interpretasi terhadap ajaran agama dan konteks sosial-politik yang berkembang serta kancah yang mewarnai kajian dimana Islam pernah menjadi sejarah daulah dan khilafah yang besar dan berpengaruh hingga membentuk suatu dinamika pemahaman dan pemikiran yang menarik, apakah esensialnya Islam itu suatu sistim yang wajib ataukah terpisah namun tetap memandang perlu adanya nilai pemikiran didalamnya.
Wacana kenegaraan dalam Islam tidak hanya mencakup aspek teologis, tetapi juga aspek praktis yang terkait dengan pemerintahan dan organisasi sosial. Dalam konteks ini, artikel ini bertujuan untuk menggali bagaimana berbagai interpretasi terhadap teks-teks Islam—terutama Al-Qur’an dan Hadis—mempengaruhi pemahaman dan praktik politik dalam dunia Islam. Diskursus politik Islam mencakup berbagai pendekatan, mulai dari penerapan syariat secara ketat hingga pemisahan antara agama dan negara.
Penelitian ini mengkaji peran ulama, intelektual Muslim, dan pemimpin politik dalam membentuk pemikiran kenegaraan Islam. Selain itu, artikel ini juga mengkritisi relevansi prinsip-prinsip politik Islam di dunia modern, di tengah tantangan globalisasi, pluralisme, dan perkembangan demokrasi. Kesimpulannya, meskipun terdapat perbedaan signifikan dalam interpretasi dan implementasi politik Islam, pemahaman yang holistik terhadap teks-teks agama dan konteks sejarah sosial-politik merupakan kunci untuk menciptakan model kenegaraan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

“ Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridhai Islam sebagai agamamu ” (QS. Al-Maa’idah [5]; 3)
Dalam paradigma sebagian cendekiawan muslim kontenporer, agama Islam dalam konteks ayat-ayat tersebut mencakup dua kategori makna, yaitu agama sebagai persoalan pribadi dan tindakan eksistensial setiap orang yang mempercayai agama, dan dalam pengertian yang umum, yaitu suatu agama yang dikenal oleh masyarakat yang meliputi suatu kepercayaan dan praktik ritual yang dilakukan oleh umat Islam. Islam dalam kategori pertama ialah Islam subtansial yang bersifat trans-historis. Sementara, Islam dalam kategori kedua ialah Islam komunal yang bersifat historis-sosiologis.[1]
Ada suatu memori kolektif yang kuat sekali di kalangan umat Islam, yaitu terdapat semacam doktrin yang berbunyi,”Al-Islam huwa al-din wa al-dawlah, Islam adalah agama dan sekaligus kekuasaan.”[2] Sehingga, implikasi hubungan antara agama dan Negara, antara aspek ritual dan politik, sangat erat kaitannya, bahkan tidak dapat dipisahkan. Aspek hokum menyentuh ke semua aspek sosial-politik. Sejak Nabi Muhammad sampai sekarang, kenangan tentang Madinah-tempat dimana Nabi mulai memetik kesuksesan dalam dakwah dan membangun masyarakatnya-sangatlah kuat.[3]
Pembicaraan Islam dalam hal politik mempunyai akar sejarah yang panjang dan tentu banyak doktrin-doktrin mengenai hal itu. Dimulai dari beragam interperasi mengenai corak pemikiran tentang Islam itu sendiri sebagai wacana dalam pandangan ulama, cendekiawan muslim, tokoh pemikiran dan pergerakan dsb. Orang Islam percaya terhadap sifat Islam yang holistik. Sebagai suatu alat untuk memahami kehidupan, Islam sering dianggap sebagai sesuatu yang lebih daripada sekedar sebuah agama. Ada yang menggap sebagai suatu “masyarakat sipil”. Ada jug yang menilainya sebagai suatu sistem “peradaban yang menyeluruh”. Bahkan, ada pula yang mempercayainya sebagai “agama dan Negara”. Lebih spesifik lagi, Islam tidak mengenal dinding pemisah antara yang bersifat spiritual dan temporal. Sebaliknya, Islam memberi panduan etis bagi setiap aspek kehidupan.[4]
Namun sebelum membahas terkait Islam sebagai Politik Kenegaraan, perlu kiranya kita menilik beberapa konsesus pengertian Islam dan Politik serta pemikiran dari abad klasik, pertengahan hingga modern, dan beberapa pengertian tentang konteks Islam itu sendiri dalam melihat kemasyarakatan atau ummah yang terbentuk dari suatu dinamika wacana Politik Islam.
A. Pengertian
Kata Islam secara semantik berasal dari akar kata salima yang berarti menyerah, tundukdan selamat. Kata Islam juga berasaldari fi’il madhi: aslama-yuslimu-islaaman, yang berarti tunduk, patuh, berserah kepada Allah.[5] Islam yang secara harfiah adalah tunduk,patuh dan pasrah kepada Allah SWT dan untuk memperoleh daripadanya keselamatan. Sedangkan Politik kalau dalam bahasa Arab ialah Siyasah yang mempunyai arti sebagai kepemimpinan. Secara literal, Politik di dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah siyasah. Oleh karena itu di dalam buku-buku ulama salaf atau ulama klasik dikenal dengan istilah siyasah syar’iyyah. Dalam kitab Al Muhith dijelaskan bahwa, siyasah berakar dari kata sâsa – yasûsu. Dalam kalimat Sasa addawaba yasusuha siyasatan berarti Qama ‘alaiha wa radlaha wa adabbaha yang mempunyai arti mengurusinya, melatihnya, mengasuhnya, dan mendidiknya. Bila dikatakan sasa al amra itu sama artinya dengan dabbarahu (mengurusi atau mengatur perkara).[6]
Sedangkan Politik dari bahasa Yunani yang berarti Kota atau Negara yang berasal dari kata polis. Kalau misalnya kita gabungkan dan jabarkan ialah suatu bentuk kota atau Negara dengan kepemimpinan yang tunduk dan patuh pada aturan atau perkara hukum Allah SWT dalam mengurusi dan mengatur rakyat dengan hukum Islam yang selamat.
Sedangkan kita bisa melihat suatu perwujudan kota atau Negara didalam komunitasnya terdapat kehidupan masyarakat, kata "masyarakat" berasal dari kata bahasa Arab syaraka yang berarti ikut serta atau berpartisipasi. Dan bandingkan dengan konteks ummah dalam bahasa Arab yang terambil dari akar kata[7] amma-ya’ummu-amman, yang mempunyai arti “menuju”,”menjadi”,”ikutan”, dan “gerakan”.
Dalam sketsa pengertian diatas sebelumnya, yang dicakup dari pengertian-pengertian tersebut dapat diambil simpulan bahwa suatu bentuk Negara ataupun Politik Islam pasti didalamnya ada suatu bentuk partisipasi dari society (masyarakat/warga) yang mempunyai arah tujuan dan menjadikan dalam lingkup gerak masyarakatnya menjadi suatu dinamika gagasan Negara Islam ataupun Politik Islam sebagai nilai dari kehidupan bernegara yang dimaksudkan bahwa suatu masyarakat mempunyai peran dari tujuan bernegara itu sendiri.
Namun secara praksis-oprasional subtansi politik Islam juga sering membuat Islam berhadap-hadapan kekuasaan dan Negara yang menjadi dasar lahirnya sikap dan prilaku politik (political behavior) serata budaya politik (political culture) yang berorientasi pada nilai-nilai Islam. Sikap prilaku serta budaya politik yang memakai kata sifat Islam, menurut Dr. Taufik Abdullah, bermula dari suatu keprihatinan moral dan doktrinal terhadap keutuhan komunitas spiritual Islam.[8]
Tapi sebelum itu mari kita kaji terlebih dahulu apa yang menjadi suatu subtansi dari bentuk nilai-nilai dalam bernegara atau suatu politik itu sendiri berdasarkan pemikiran dan pendapat menurut tokoh, karena Islam diyakini mempunyai pedoman bagi segala aspek kehidupan, khususnya ketatanegaraan atau politik, ternyata hubungan antara agama dan Negara dalam Islam sangat poly interpretable, kaya penafsiran. Maka dari hal tersebut:
1) Al-Farabi Mengenai Pemahaman Filsafatnya
Mungkin tokoh yang satu ini sangat terkenal dengan kajian dalam teori sosialnya, dimana ia menggabungkan wawasan khasanah pemikiran tokoh Yunani yaitu Plato, dengan prasyaratan Islam. Dalam utopianya,[9] yang diuraikan dalam Ara’ Ahl Al-Fadhilah, penguasa adalah filosofis sekaligus nabi, yang menggabungkan hakistimewa dan kebajikan keduanya. Al-Farabi merasa bahwa persaudaraan Islam menghendaki agar warga menjadi seperti anggota tubuh organik, agar pekerjaan sesuai dengan kecakapan sedangkan imbalan sesuai dengan prestasi.
Pemikiran Politik Al-Farabi tentang Kota Utama, dalam Al-Madinah Al-Fadhilah (Kota Utama) dijelaskan: Kota Utama adalah kota yang –melalui perkumpulan yang ada didalamnya- bertujuan untuk bekerja sama dalam mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya.[10]
2) Paradigma Formalistik
Paradigma formalistic memandang agama Islam sebagai suatu agama yang sempurna dan sangat lengkap, yang meliputi tidak saja tuntunan moral dan peribadatan, melainkan juga petunjuk-petunjuk mengenai cara mengatur segala aspek kehidupan politik, ekonomi, dan sosial. Oleh karenanya, untuk pemulihan kejayaan dan kemakmuran, umat islam harus kempali kepada agamanya yang sempurna dan komperehensif, kembali kepada kitab sucinya, al-Qur’an dan sunnah Nabi SAW., mencontoh pola hidup Rasul SAW dan umat Islam generasi pertama, serta tidak perlu atau bahkan jangan meniru pola atau sistem politik, ekonomi, dan sosial Barat.[11]
Seperti halnya argumentasi yang mendukung dari para orientalis, Orientalis yang mengakui kenyataan sebagaimana tersebut di atas antara lain C.A. Nolino yang berkata ,”Muhammad telah meletakkan dasar agama dan dasar Negara pada waktu yang sama.” Mac Donald mengatakan,”Di sana di Madinah, telah terbentuk Negara Islam yang pertama, diletakkan pula prinsip-prinsip yang asasi di dalam aturan-aturan Islam.” Dan H. R. Gibb, menyatakan “Pada waktu itu menjadi jelas bahwa Islam bukanlah semata akidah agama yang individual sifatnya, tetapi juga mewajibkan mendirikan masyarakat yang mempunyai uslub-uslub tertentu didalam pemerintahan dan mempunyai undang-undang dan aturan-aturan yang khusus.”[12]
Dikalangan ulama-ulama besar Islam yang berbicara tentang hubungan antara agama dan Negara ini antara lain diungkap oleh Syekh Mahmud Syaltout sebagai berikut,”Tidak Mungkin tergambarkan agama Islam tanpa adanya pengetahuaan dari masyarakat dan politik Negara, kareana apabila demikian Negara itu tidak bersifat Islami.”[13]
3) Paradigma Substansialistik (Simbiotik)[14]
Dalam Paradigma substansialistik, Agama Islam mempunyai seperangkat prinsip dan nilai-nilai tentang kehidupan bermasyrakat, termasuk sistim pemerintahan. Dalam perspektif Muhammad Abduh, hakikat pemerintahan Islam tidak bersifat keagamaan, melainkan bersifat keduniawiaan. Abduh menyatakan bahwa kekuasaan politik harus didasarkan pada kedaulatan rakyat atau kehendak publik. Kedaulatan rakyat ini, menurut Abduh, harus dibangun atas dasar prinsip-prinsip kebebasan (hurriyah), demokrasi (syura), dan konstitusi (qanun) yang berfungsi sebagai landasan sistem politik dan kekuasaan tersebut.
Konsepsi Abduh tentang kebebasan meliputi kebebasan sosial dan politik, termasuk didalamnya kebebasan berpendapat, kebebasan berbicara, kebebasan memilih, bahkan kebebabasan bagi kaum perempuan dalam memperoleh hak-hak mereka. Jika nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan politik, maka hubungan antara yang berkuasa dan yang dikuasai akan berlangsung dalam interaksi yang positif dan konstruktif.
Menurut Abduh, Islam tidak mengenal adanya kekuasaan agama, dalam arti: (1) Islam tidak memberikan kekuasaan kepada seseorang atau sekelompok orang untuk menindak orang lain atas nama agama atau berdasarkan dari mandat agama; (2) Islam tidak membenarkan campur tangan seseorang, penguasa sekalipun, dalam kehidupan dan urusan keagamaan orang lain; dan (3) Islam tidak mengakui hak hak seseorang untuk memaksakan pengertian, pendapat, dan penafsirannya tentang agama atas orang lain.
4) Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah[15]
Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa mengatur urusan umat memang merupakan bagian dari kewajiban agama yang terpenting, tetapi hal ini tidak berarti pula bahwa agama tidak dapat hidup tanpa negara. Karenanya, Ibnu Taimiyah menolak ijma’ sebagai landasan kewajiban tersebut. Berbeda dengan al-Mawardi, Ibnu Taimiyah menggunakan pendekatan sosiologis. Menururtnya, kesejahteraan manusia tidak dapat tercipta kecuali hanya dalam satu tatanan sosial di mana setiap orang saling bergantung pada yang lainnya. Oleh sebab itu, dibutuhkan seseorang pemimpin yang akan mengatur kehidupan sosial tersebut.
Jadi, bagi Ibnu Taimiyah, penegakan imamah bukanlah merupakan salah satu asas atau dasar agama, melainkan hanya kebutuhan praktis saja. Namun demikian, Ibnu Taimiyah juga menekankan fungsi Negara untuk membantu agama. berdasarkan pandangannya, Ibnu Taimiyah menolak kekuasaan bani Umaiyah dan bani Abbas sebagai dasar filsafat politik Islam. Ia tidak membenarkan khalifah-khalifah bani Abbas yang hanya dijadikan boneka oleh sekelompok elite. Selain itu, berbeda dengan al-Mawardi yang selalu menggunakan term “imâmah” atau pemikiran sunni lainnya yang menggunakan kata “khilafah” untuk kenegaraan ini, Ibnu Taimiyah menggunakan kata “imârah”.
Berbeda dengan al-Mawardi, prosedur pemilihan kepala Negara tidak terlalu menyita perhatian Ibnu Taimiyah. Ini wajar, karena Ibnu Taimiyah menolak teori khilafah Sunni tentang pengangkatan kepala Negara oleh ahl al-hall wa al ‘aqd, seperti dielaborasi oleh al-Mawardi, dan konsep bay’ah oleh segelintir ulama.
Sebagai alternatif, Ibnu Taimiyah membangun konsp al-syakwah dalam terori politiknya. Menurutnya, ahl al-syakwah adalah orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan kedudukan yang dihormati dan ditaati oleh masyarakat. Ahl al-Syakwah inilah yang memilih kepala Negara dan melakukan sumpah setia (bay’ah) untuk kemudian diikuti oleh rakyat. Seseorang tidak dapat menjadi kepala Negara tanpa didukung oleh ahl al-syakwah.
5) Panradigma Sekuralistik
Bagi Abdar-Raziq, Tuhan telah menyerahkan sepenuhnya wilayah pemerintahan sipil dan kepentingan duniawi untuk menjadi persoalan nalar manusia. Islam tidak memperkenalkan suatu sistim tertentu atau menolaknya, tidak memerintahkan atau melarangnya. Agama Islam menyerahkan semua urusan tersebut kepada manusia untuk dikembalikan kepada standar-standar logika, pengalaman umat-umat lain, serta kaidah-kaidah politik. Seperti halnya pengelolaan tentara Islam, membangun kota, jalan-jalan dan pelabuhan, sistem departemen, tidak ada hubungannya dengan agama tetapi kembali kepada akal dan pengalaman atau kepada kaidah-kaidah kemiliteran, insiyur pembangunan, atau pendapat para ahli. Islam tidak melarang berlomba-lomba dengan umat lain dalam bidang sosial dan politik, merobohkan sistem lapuk yang merendahkan martabat manusia, untuk kemudian membangun kaidah-kaidah kekuasaan dan sistem pemerintah yang sesuai dengan penemuan dan pengalaman mukhtahir, yang telah teruji ketangguhannya bahwa itu merupakan dasar-dasar pemerintahan yang baik.[16]
Dari sini mungkin ada suatu hal dimana para tokoh memperlihatkan pada kita subtansi dari apa yang bisa mereka gambarakan sebagai suatu penafsiran dan pemahaman. Namun, pada dasarnya melihat beragam corak tersebut dari pemaparan diatas menggabarkan interpertasi sedemikian hal yang menunjukan bagaimana suatu hal itu dikaji dan diterima sebagai bentuk suatu apa yang dimaksud dengan banyaknya bergam perbedaan serta latar belakang dasar apa yang meliputi suatu corak pemikiran, intelektual, sosiologis budaya dan lai-lain.
Dan, Mengakui syariah sebagai suatu sistem kehidupan yang menyeluruh merupakan suatu hal, sementara memahaminya secara benar adalah hal yang lain. Bahkan, dalam konteks “bagaimana syariah harus dipahami” inilah, sebagaimana dilihat oleh Fazlur Rahman, terletak persoalan yang sebenarnya. Ada sejumlah faktor yang mempengaruhi dan membentuk hasil pemahaman kaum muslim terhadap syariah. Situasi sosiologis, cultural, dan intelektual, atau yang disebut Arkoun sebagai “estetika penerimaan” (asthetic of reception), sangat berpengaruh dalam menentukan bentuk dan isi pemahaman.[17]
[1] Dr. Zaprulkhan, S.Sos.I.,M.S.I., Pengantar Filsafat Islam: Klasik, Moderen, dan Kontemporer, IRCiSoD, (Yogyakarta: November 2019), Cetakan Pertama, Hal 150
[2] Dr. Zaprulkhan, S.Sos.I.,M.S.I., Pengantar Filsafat Islam: Klasik, Moderen, dan Kontemporer, IRCiSoD, (Yogyakarta: November 2019), Cetakan Pertama, Hal 233
[3] Dr. Zaprulkhan, S.Sos.I.,M.S.I., Pengantar Filsafat Islam: Klasik, Moderen, dan Kontemporer, IRCiSoD, (Yogyakarta: November 2019), Cetakan Pertama, Hal 233
[4] Dr. Zaprulkhan, S.Sos.I.,M.S.I., Pengantar Filsafat Islam: Klasik, Moderen, dan Kontemporer, IRCiSoD, (Yogyakarta: November 2019), Cetakan Pertama, Hal 233-234
[5] Dr. Zaprulkhan, S.Sos.I.,M.S.I., Pengantar Filsafat Islam: Klasik, Moderen, dan Kontemporer, IRCiSoD, (Yogyakarta: November 2019), Cetakan Pertama, Hal 19
[6] Dr. H. Abd. Halim, M.Ag., Relasi Islam Politik dan Kekuasaan, LKiS Yogyakarta, (Yogyakarta: 2013), Cetakan Pertama, Hal 23
[7] Akhmad Satori dkk, Sketsa Pemikiran Politik Islam, deepublish, (Yogyakarta: September 2016), Cetakan Pertama, Hal 6
[8] Dr. H. Abd. Halim, M.Ag., Relasi Islam Politik dan Kekuasaan, LKiS Yogyakarta, (Yogyakarta: 2013), Cetakan Pertama, Hal 24
[9] Akhmad Satori dkk, Sketsa Pemikiran Politik Islam, deepublish, (Yogyakarta: September 2016), Cetakan Pertama, Hal 57-58
[10] Akhmad Satori dkk, Sketsa Pemikiran Politik Islam, deepublish, (Yogyakarta: September 2016), Cetakan Pertama, Hal 60-61
[11] Dr. Zaprulkhan, S.Sos.I.,M.S.I., Pengantar Filsafat Islam: Klasik, Moderen, dan Kontemporer, IRCiSoD, (Yogyakarta: November 2019), Cetakan Pertama, Hal 243
[12] Prof. H. A. Djazuli, Fiqh Siyâsah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu syariah, Kencana, (Jakarta: September 2003), Cetakan ke 2, Hal 80
[13] Prof. H. A. Djazuli, Fiqh Siyâsah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu syariah, Kencana, (Jakarta: September 2003), Cetakan ke 2, Hal 80-81
[14] Dr. Zaprulkhan, S.Sos.I.,M.S.I., Pengantar Filsafat Islam: Klasik, Moderen, dan Kontemporer, IRCiSoD, (Yogyakarta: November 2019), Cetakan Pertama, Hal 251
[15] Dr. Muhammad Iqbal M.Ag. dan Drs. H. Amin Husein Nasution M.A., Pemikiran Politik Islam; dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer, Kencana, (Jakarta: Januari 2017), Cetakan ke-4, Hal 33-34
[16] Dr. Zaprulkhan, S.Sos.I.,M.S.I., Pengantar Filsafat Islam: Klasik, Moderen, dan Kontemporer, IRCiSoD, (Yogyakarta: November 2019), Cetakan Pertama, Hal 240-241
[17] Dr. Zaprulkhan, S.Sos.I.,M.S.I., Pengantar Filsafat Islam: Klasik, Moderen, dan Kontemporer, IRCiSoD, (Yogyakarta: November 2019), Cetakan Pertama, Hal 261
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.