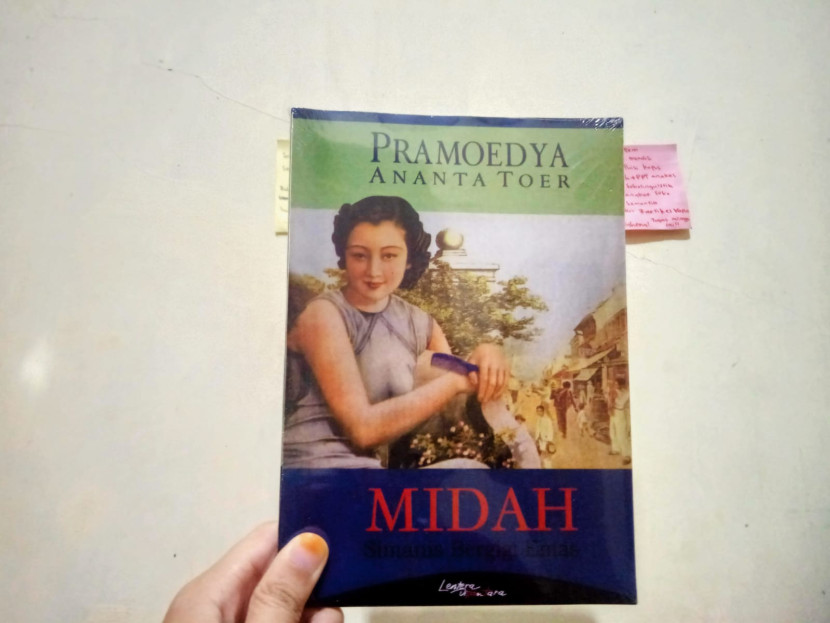Ghofiruddin Alfian
Ghofiruddin Alfian
Warung Kopi dan Orang Gila
Sastra | 2021-12-09 08:42:20
Himpunan manusia telah berkumpul di warung dan dengan wajah yang dibikin begitu tenang mereka menyerap bau apek yang mereka endusi dengan begitu santai. Tentu saja mereka sudah mandi atau paling tidak sudah membasuh muka sebelum berangkat beraktivitas. Namun aktifitas pagi untuk mengais rejeki sebelum matahari terbit dan meninggi itu memaksa sebuah kehangatan untuk memancar. Energi panas berikutnya telah membakar lemak-lemak jahat di dalam tubuh dan metabolisme di dalam tubuh mengeluarkannya dalam bentuk cairan yang disebut dengan keringat.
Keringat inilah (meskipun masih ada keraguan di dalamnya) yang menguarkan bau apek itu terutama keringat-keringat yang mengucur dari balik lekitan-lekitan tubuh yang berhawa lembab. Bau apek di sana adalah yang tidak tertandingi, mungkin juga karena kuman-kuman dan bakteri-bakteri telah terakumulasi sedemikian rupa di bagian yang sulit dijangkau oleh tangan-tangan yang hendak membersihkan diri. Mungkin membutuhkan tangan yang lain sebagai bantuan tambahan.
Sambil tetap mengendusi bau apek mereka, sambil menghisap cerutu dan menyantap aneka hidangan yang disajikan oleh sang penjual kopi (biasanya berupa jajanan khas pedesaan), mereka memperbincangkan apa saja yang bisa dibicarakan, mengolok-olok apa yang bisa diolok-olok, atau istilah ngetrennya jagongan atau gegojegan yang berarti juga bermesraan.
Mungkin di saat seperti ini dan di tempat yang seperti warung ini, alangkah baiknya jika seorang pamong ikut nimbrung, baik itu pamong dari tingkat RT, maupun hingga pamong tingkat nasional dan bahkan juga internasional. Tidak usah terlalu muluk-muluk dengan ikut dalam pembicaraan, cukup dengan menyamar duduk santai di pojokan sambil menikmati sesuatu yang dihidangkan di sana, menikmati obrolan santai para rakyat yang bahkan dalam keadaan tertekan sekalipun masih sanggup menggelontorkan beraneka candaan yang setara dengan yang disajikan oleh para komedian di layar kaca.
Ini penting bagi seorang pejabat yang benar-benar memiliki jiwa kepemimpinan dan rasa kepamongan di dalam dirinya, atau seorang pejabat yang masih merasa dirinya adalah juga seorang rakyat, seorang manusia biasa, bukannya seorang dewa yang meminta disembah dan dipuja sedemikian rupa.
Namun, warung ya tetaplah warung. Seseorang yang bersemayam di dalam jiwanya rasa elit pasti kemudian akan muncul rasa pelit. Rasa pelit ini adalah sebuah perasaan gengsi, di mana mereka nimbrung bukan hendak nyawiji atau manunggal dengan para kawulanya gusti. Orang-orang pelit ini hendak berspekulasi apakah ada suatu keuntungan yang bisa didapatkan di masa yang akan datang dari setiap interaksi dengan orang-orang. Kalau ada keuntungan, yang seperti apa. Apakah cukup sebuah keuntungan psikologis dan sosial?
Namun sayangnya keuntungan sekarang telah diperhitungkan dan diberikan batasan jika telah bersangkut paut dengan yang namanya finansial, dengan harta benda, dengan hitungan uang dalam angka-angka yang pasti. Keuntungan dan kepuasan karena ide-ide para elit yang pelit ini telah menjadi terlalu kuantitatif, dan sebuah renungan kontemplatif yang bersifat kualitatif jauh telah terpinggirkan hanya untuk dimiliki oleh orang-orang kuno yang mungkin sudah tidak ada lagi. Mereka terlalu lama bertapa di gunung-gunung atau goa-goa sunyi.
Orang-orang ini adalah orang-orang yang terpinggirkan karena memang sengaja meminggirkan diri untuk menemukan sebuah ruang kontemplasi yang paling otentik. Bahkan yang paling radikal dari mereka akan berusaha untuk menemukan dan menciptakan sesuatu yang orisinal, yang benar-benar lahir dari rahim kesunyian dan kesendiriannya, tanpa dikenai oleh campuran-campuran inovasi dari benda-benda atau temuan-temuan yang ada sebelumnya.
Akhirnya kebanyakan orang-orang kualitatif ini banyak mengurung diri, memikirkan sesuatu kemustahilan serta berusaha untuk menemukan cara untuk menciptakan sesuatu yang paling mustahil, sesuatu yang tidak bisa diciptakan. Dan karena sesuatu yang mereka idamkan atau ingin ciptakan itu adalah sesuatu yang mustahil, mereka hanya bisa berharap dan dengan tenang menunggu kematian, berharap setelah kematian itu segala kemustahilan, hal yang mustahil dari yang paling mustahil akan tersingkap.
Saat mereka mulai pasrah tentang kemustahilan yang tidak kunjung digenggam itu, maka saat itulah mereka akan benar-benar bahagia. Di saat itu pula, mereka memutuskan keluar untuk menyapa para penghuni warung yang sederhana. Sepiring nasi pecel dengan lauk rempeyek kacang atau terkadang kripik akan mereka pesan. Juga secangkir kopi yang gagangnya patah.
Mereka akan mengambil tempat yang paling luang, biasanya di tempat yang paling pojok sehingga wajahnya yang sudah terlalu usang bisa tersembunyi dari pandangan orang-orang yang berdikari. Mereka mengecap setiap pembicaraan yang ada di warung itu hanya dengan berdiam diri dan lebih banyak mendengarkan. Sudah tidak ada yang aneh lagi bagi mereka, dan setiap berita, entah itu fakta atau hoax, baik itu yang sedih, yang marah, yang gembira, yang membingungkan, segalanya hanya membuat mereka tersenyum.
Dan, senyuman itu semakin hari semakin aneh, terutama jika dilihat dari sudut pandang orang-orang yang merasa paling tidak aneh. Lama kelamaan mereka mendapat label orang gila, orang yang telah bebas dari segala kekangan norma, dan oleh sebab itu mereka berada di suatu tempat netral di antara surga dan neraka.
Orang gila sudah tidak lagi memandang ke atas surga sebagai suatu puncak anugerah untuk segala kebajikan yang telah diperjuangkan. Juga neraka menjadi tempat yang sangat biasa-biasa saja, dan tidak lagi ada suatu perasaan fenomenal tentang deraan-deraan penderitaan sebagai balasan atas segala nafsu berlebih yang tidak bisa terkekang. Orang gila adalah orang-orang yang mencapai tingkat kebijaksanaan yang kebablasan.
Mereka bukan orang yang tidak mampu menerima kegagalan. Mereka hanyalah orang-orang yang terlalu dini menerima segala kenyataan, membuat sebuah garis abstraksi di dalam pikiran bahwa segala konsekuensi yang paling tinggi dari kehidupan hanyalah kematian.
Mereka sudah tidak terlalu memikirkan sebuah pertanyaan tentang siapakah aku? Apa yang harus kulakukan di dalam kehidupan? Apakah asal-usul dari segala sesuatu yang berada? Atau yang paling membosankan apakah ini benar dan itu salah, dan apakah ini baik atau buruk, serta kemudian mencoba berdalih untuk menemukan bermacam-macam alasan.
Inti di dalam mereka bukan lagi tentang masalah eksistensi dunia, namun adalah insistensi, sesuatu yang sering dilupakan karena ia meluruhkan diri di dalam segala kenyataan.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.