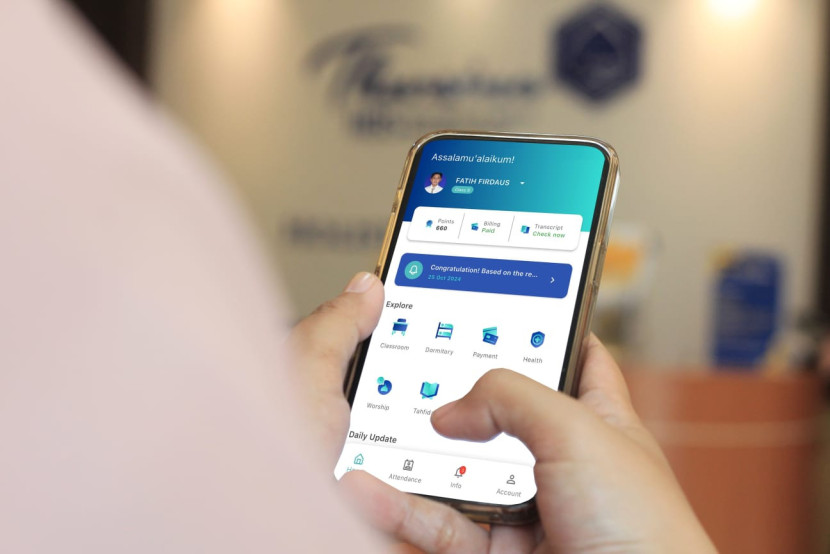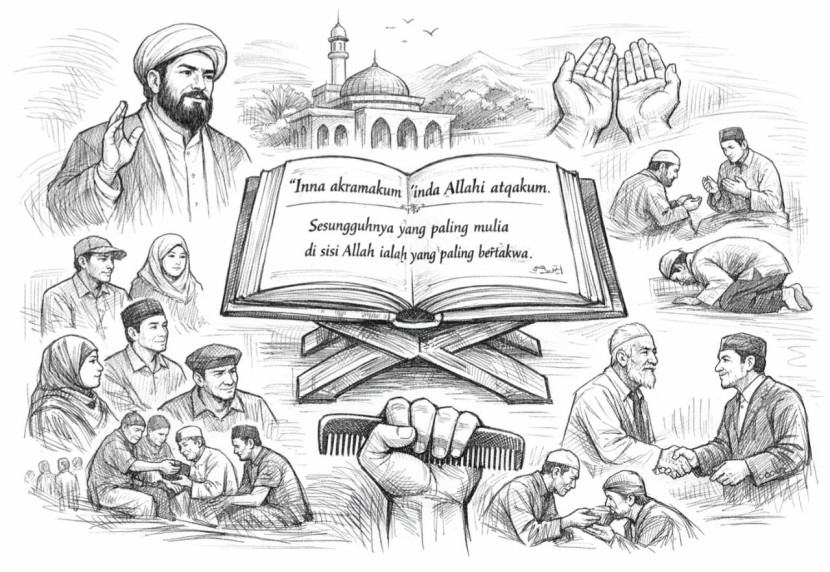IMELDA AGNESIA
IMELDA AGNESIA
Viralitas Empati: Ketika Layar Menjadi Arena Tanggung Jawab
Gaya Hidup | 2026-01-11 17:54:48Di era di mana satu detik bisa membuat sebuah video menjadi perhatian nasional, muncul fenomena baru yang layak dicermati: viralitas empati. Fenomena ini bukan sekadar soal banyaknya like atau komentar, melainkan tentang bagaimana rasa iba dan respons kolektif diproduksi, didistribusikan, dan akhirnya mempengaruhi persepsi publik terhadap peristiwa terutama bencana. Ketika gambar penderitaan berputar tanpa henti di layar, ada pertanyaan penting: siapa yang mendapatkan sorotan, dan siapa yang bekerja di balik layar?
Salah satu mekanisme yang mempercepat viralitas empati adalah framing media. Media memilih aspek tertentu dari peristiwa misalnya wajah korban, rumah yang roboh, atau aksi dramatis seorang relawan dan menjadikannya pusat perhatian. Framing ini efektif membentuk emosi publik, menetapkan siapa yang berhak mendapatkan simpati, dan sekaligus mengaburkan konteks yang lebih luas. Dalam kondisi post-truth yang makin mengakar, emosi sering mendahului fakta, sehingga narasi emosional lebih cepat dipercaya dan dibagikan ketimbang laporan yang berisi data dan proses birokratis yang kompleks.
Media sosial bertindak sebagai amplifier. Algoritma yang mendahulukan engagement cenderung memilih konten yang memicu reaksi emosional marah, sedih, atau empati sehingga cerita manusiawi dengan visual kuat mendapatkan ruang lebih luas. Di sisi lain, kerja institusional yang dilakukan melalui prosedur, rapat koordinasi, hingga distribusi logistik yang tepat waktu, tidak mudah tampil sebagai konten viral. Padahal, tanpa kerja panjang yang tidak tampak itu, membantu korban secara berkelanjutan hampir mustahil.
Fenomena ini juga membuka ruang baru bagi figur publik non-institusional: influencer kemanusiaan. Mereka sering tampil di lokasi bencana, menunjukkan aksi nyata, menggalang donasi, dan menyiarkan secara langsung. Tindakan mereka dapat memberi manfaat cepat: mobilisasi bantuan, penggalangan dana, dan peningkatan perhatian publik. Namun, ada juga risiko—ketergantungan pada figur-figur ini bisa menggeser tanggung jawab publik kepada reputasi personal, memunculkan kompetisi simpati, dan kadang menimbulkan praktik yang lebih menonjolkan tampilan daripada dampak jangka panjang.
Di sisi lain, ketidaksinkronan antara tampilan publik dan kerja struktural bisa memicu krisis kepercayaan terhadap negara. Ketika publik melihat banyak ekspresi empati individu namun sedikit informasi terstruktur dari institusi, pertanyaan tentang 'sense of urgency' negara menjadi wajar. Kritik semacam ini penting sebagai kontrol sosial, tetapi harus dibaca secara proporsional: absennya narasi institusional di media tidak selalu berarti absennya aksi di lapangan. Seringkali koordinasi lintas lembaga memerlukan waktu sebelum dapat dikomunikasikan secara efektif kepada publik.
Lalu, bagaimana kita membaca fenomena viralitas empati secara lebih konstruktif? Pertama, perlu ada kesadaran media: jurnalisme tidak hanya memerlukan kecepatan, tetapi juga konteks. Reporter dan platform harus berupaya menyeimbangkan narasi human interest dengan penjelasan tentang langkah-langkah institusional yang sedang berjalan. Kedua, institusi publik harus meningkatkan kapasitas komunikasi krisis: membuka saluran informasi yang transparan, rutin, dan mudah diakses sehingga publik dapat memahami proses yang sedang berlangsung mulai dari identifikasi korban hingga mekanisme distribusi bantuan.
Selain itu, pendidikan literasi media menjadi kunci. Masyarakat perlu dilatih mengenali perbedaan antara cerita emosional yang menggugah dan informasi komprehensif yang menjelaskan konteks. Literasi ini akan membantu publik membuat penilaian yang lebih matang tentang siapa yang bekerja dan apa yang sebenarnya dibutuhkan di lapangan. Tanpa kemampuan ini, kita mudah terseret pada narasi yang kuat secara emosional tetapi miskin solusi sistemik.
Fenomena viralitas empati juga menuntut pertimbangan etis. Momen bencana sering kali memunculkan eksposur mendalam terhadap penderitaan individu. Siapa berhak menyebarluaskan gambar-gambar itu? Bagaimana menjaga martabat korban sekaligus mendorong respons publik? Ada garis tipis antara dokumentasi dan eksploitasi; penting untuk menegakkan prinsip-prinsip etika dalam pelaporan dan berbagi informasi, termasuk persetujuan, anonymisasi jika perlu, dan fokus pada solusi bukan hanya sensasi.
Akhirnya, viralitas empati hendaknya menjadi pemicu perubahan positif, bukan sekadar tontonan sesaat. Jika kekuatan digital dapat mempersatukan perhatian dan sumber daya, mengapa tidak diarahkan untuk memperkuat kapasitas lokal, memperbaiki sistem peringatan dini, dan membangun infrastruktur yang tahan bencana? Ketika perhatian publik memudar setelah trending topic berlalu, tantangannya adalah memastikan bantuan tetap mengalir dan kebijakan diperbaiki. Nilai empati sejati terlihat ketika solidaritas itu bertransformasi menjadi tindakan kolektif yang berkelanjutan.
Fenomena viralitas empati menawarkan pelajaran ganda: ia menunjukkan potensi luar biasa jejaring digital dalam memobilisasi perhatian dan sumber daya, sekaligus menyingkap kelemahan dalam cara kita memahami dan menilai respons terhadap krisis. Menyikapi fenomena ini membutuhkan sinergi antara media yang bertanggung jawab, institusi yang komunikatif, figur publik yang akuntabel, dan publik yang kritis. Hanya dengan demikian layar tidak lagi menjadi arena tunggal bagi drama penderitaan, tetapi berubah menjadi medium solidaritas yang efektif dan berkelanjutan.
Viralitas empati memadukan dua kekuatan zaman digital: visual yang cepat menyentuh emosi dan jejaring sosial yang memperkuat narasi tertentu. Dalam banyak peristiwa bencana, publik lebih mudah mengenali figur yang muncul secara visual relawan, korban yang menjerit, atau influencer yang melakukan live streaming dibandingkan dengan institusi yang bekerja berjenjang seperti pemerintah, TNI, atau lembaga penanggulangan bencana. Akibatnya, penilaian terhadap respons kemanusiaan seringkali terfragmentasi: yang tampak jadi center of attention, sementara kerja struktural yang panjang dan prosedural menjadi sama.

Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.