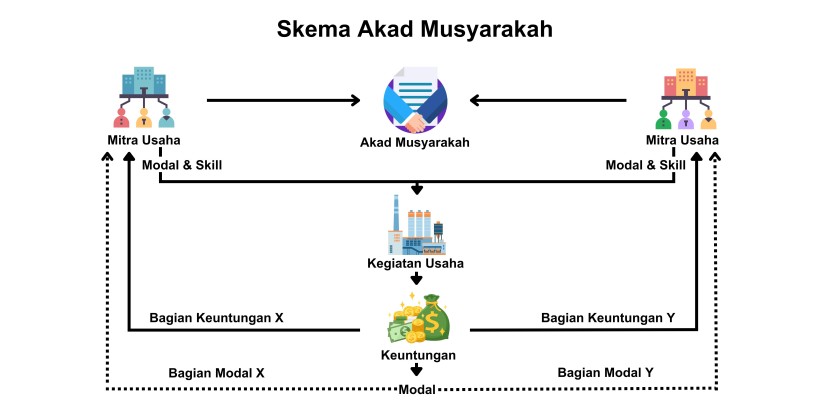Nadia Jamiatunnisa
Nadia Jamiatunnisa
Doa di Antara Mimbar dan Jalanan: Ketika Ritual Menjadi Bahasa Publik
Agama | 2026-01-08 23:02:24
Di Indonesia, doa tidak pernah benar-benar berhenti di rumah ibadah. Ia kerap hadir di ruang publik, di panggung politik, di tengah aksi massa, hingga menjadi pembuka berbagai acara resmi. Lama-kelamaan, doa terasa seperti bagian wajar dari kehidupan sosial kita.
Namun, jika diperhatikan lebih jauh, doa di ruang publik memiliki nuansa yang berbeda dengan doa personal. Ucapan “amin” yang dipanjatkan sendirian tentu tidak sama maknanya dengan “amin” yang diucapkan bersama ribuan orang. Di titik ini, doa tidak lagi hanya menjadi praktik spiritual, tetapi juga berfungsi sebagai bahasa bersama yang membangun makna sosial.
Di sinilah doa mulai bekerja sebagai alat komunikasi. Dalam kajian komunikasi, ada pandangan yang melihat doa sebagai bentuk retorika. Salah satunya dikemukakan oleh William Fitzgerald melalui teori Prayer as Rhetoric. Gagasannya sederhana, doa bukan hanya ditujukan kepada Tuhan, tetapi juga kepada manusia yang mendengarkannya.
Ketika doa diucapkan di ruang publik, ia selalu memiliki audiens. Pilihan kata dalam doa tersebut tidak netral. Doa tentang “keadilan”, misalnya, secara tidak langsung mengajak pendengar untuk menyadari adanya ketimpangan. Doa tentang “ketertiban” dapat membingkai situasi seolah stabilitas adalah nilai yang paling penting. Tanpa disadari, doa membentuk cara orang memahami realitas.
Doa memiliki kekuatan karena bekerja di beberapa lapisan sekaligus. Pertama, ia membangun otoritas moral. Orang yang memimpin doa sering dipersepsikan sebagai pihak yang tulus dan berpihak pada nilai-nilai luhur. Kedua, doa menyentuh emosi. Ia langsung bekerja di ranah perasaan, menciptakan rasa kebersamaan dan keterhubungan.
Ketiga, doa membingkai makna. Melalui kata-katanya, doa secara halus menentukan mana yang dianggap baik, mana yang dianggap masalah, dan apa yang layak diperjuangkan. Semua ini terjadi tanpa perlu argumentasi panjang, karena doa dibungkus dalam bahasa religius yang dianggap suci. Akibatnya, doa di ruang publik sering kali sulit dikritik. Menyanggah doa terasa tidak pantas, meskipun dampaknya bisa sangat politis.
Dalam konteks politik, doa sering hadir sebagai simbol moral. Ia memberikan legitimasi emosional dan membantu membangun kepercayaan publik tanpa perlu penjelasan teknis yang rumit. Dalam konflik sosial, doa kerap tampil sebagai ekspresi damai yang kuat, menyatukan orang-orang dalam satu tujuan bersama. Sementara itu, dalam aksi kemanusiaan, doa berfungsi sebagai pemersatu lintas perbedaan. Ia menjadi bahasa yang dapat diterima oleh banyak pihak, bahkan ketika pandangan politik atau latar belakang sosial mereka berbeda.
Namun, penggunaan doa yang terlalu sering dan berulang juga membawa risiko. Fitzgerald mengingatkan bahwa kekuatan doa sebagai retorika sangat bergantung pada persepsi ketulusan. Jika doa hanya dijadikan pelengkap acara atau strategi komunikasi, maknanya bisa menipis. Pada titik tertentu, doa dapat terasa seperti formalitas. Diucapkan, diaminkan, lalu dilupakan. Ketika publik mulai membaca doa sebagai bagian dari skenario, bukan sebagai ungkapan batin, kepercayaan pun perlahan runtuh.
Doa di ruang publik Indonesia hari ini bersifat dinamis. Ia bisa menjadi jembatan harapan, alat pemersatu, sekaligus sarana membangun makna sosial. Karena itu, penting bagi kita untuk lebih peka membaca konteks di balik setiap doa yang terdengar di ruang publik.
Bukan untuk mencurigai doa, tetapi untuk memahami bahwa di masyarakat yang religius, doa bukan hanya soal hubungan manusia dengan Tuhan, melainkan juga tentang bagaimana makna, emosi, dan kebersamaan dibangun di ruang sosial.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.