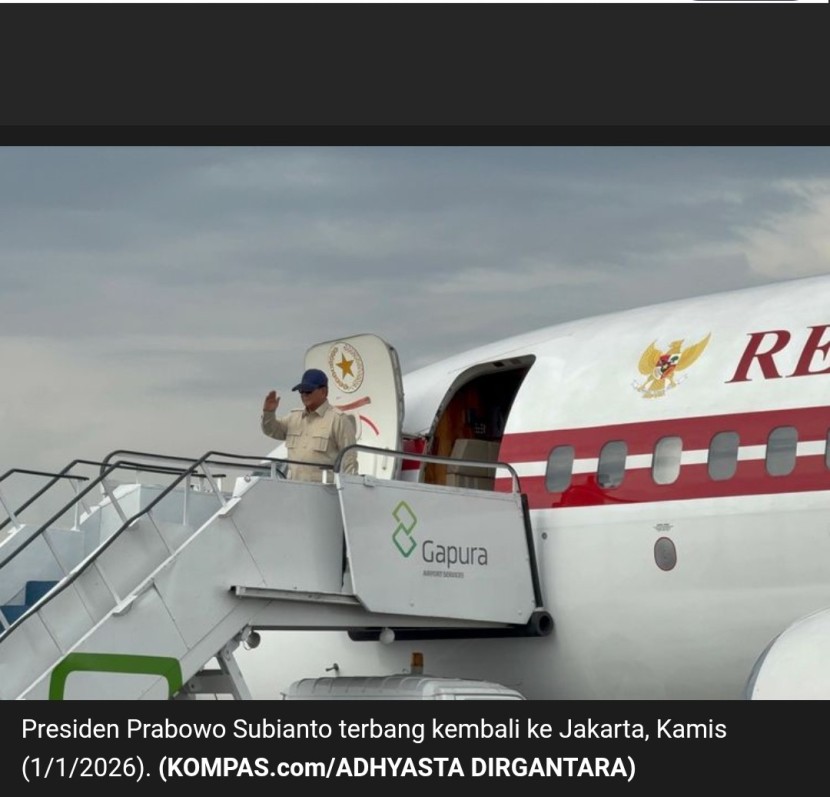KHAIRUL AMIN
KHAIRUL AMIN
Anthropocene, Bencana, dan Muhasabah Kebijakan Publik
Politik | 2026-01-07 11:15:06
Negara Rawan Bencana
Semua sudah mafhum, Indonesia adalah salah satu negara paling rawan bencana di muka bumi. Data INARISK (Indeks Risiko Bencana Indonesia) yang rutin dirilis oleh BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) sejak 2015, sudah lebih dari cukup untuk menggambarkannya. Secara statistik, baik bencana geologis maupun hidrometeorologis adalah ‘tamu’ reguler di negeri kita.
Pada tahun 2024 saja, laporan BNPB mencatat sekitar 3.472 bencana terjadi dengan jumlah korban jiwa mencapai 504 orang, 11 ribu lebih luka-luka, sekitar 8 juta orang lebih menderita dan mengungsi dengan total kerusakan bangunan mencapai 80 ribu lebih. Jika berkaca pada tren beberapa tahun terakhir, potensi dan risiko terus meningkat.
Namun, jika kita mencermati kebijakan alokasi anggaran kebencanaan, justru ditemukan anomali. Alih-alih diperkuat, pagu anggaran justru BNPB dipangkas. Hal ini menyisakan pertanyaan besar. Terbaru, dalam RAPBN 2026, alokasi dana untuk BNPB hanya mencapai 491 miliar-terendah dalam 15 tahun terakhir-setelah pada tahun-tahun sebelumnya selalu berada di atas 1 triliun.
Benar, bahwa pemerintah menyiapkan dana on-call (siap pakai) 60 triliun, juga anggaran perlindungan sosial yang mencapai 508,2 triliun. Namun, justru di situlah letak persoalannya. Secara paradigmatik, alokasi tersebut menunjukkan turunnya fokus pemerintah terhadap aspek mitigasi. Padahal, proyeksi terhadap penanggulangan krisis yang baik, selalu memaksimalkan aspek mitigasi. Kita semua tahu peribahasa: lebih baik mencegah daripada mengobati, tetapi sepertinya kita ‘lebih suka’ mengobati daripada mencegah.
Anthropocene dan Percepatan Krisis
Gaia Vince dalam Adventures in The Anthropocene (2014), menyatakan bahwa kemunculan manusia di panggung sejarah ribuan tahun silam, telah mengubah lanskap kehidupan bumi yang telah berlangsung sekitar 4,6 miliar secara signifikan. Perubahan iklim dan kerusakan ekosistem menjadi bukti kuat yang begitu.
Bagi manusia modern, bumi bukan lagi sekedar tempat menumpang hidup, tetapi gudang sumber daya bebas akses yang dapat dieksploitasi berdasarkan legalitas kertas-kertas dokumen. Situasi pasca revolusi industri utamanya, merupakan arena vis-a-vis antara hasrat dan determinasi manusia modern dengan tata sistem alam (sunnatullah). Tidak jarang hasilnya adalah ‘penaklukan paksa’ oleh manusia, alih-alih mencari harmoni. Tidak heran, Vince menyebut era ini sebagai Anthropocene- istilah geologis yang merujuk pada determinasi dan dominasi aktivitas manusia dalam menentukan dan membentuk situasi iklim, ekosistem, dan lanskap bumi.
Dalam konteks anthropocene, seringkali manusia berhadapan dengan krisis yang lahir dari perbuatannya sendiri. Jika krisis diartikan sebagai periode sulit, keadaan berbahaya atau genting, serta situasi tidak terduga yang memerlukan respon cepat, maka krisis dapat diturunkan ke dalam berbagai dimensi, mulai dari krisis politik, ekonomi, sosial-budaya hingga ekologi. Namun, hampir dipastikan semua krisis memiliki kaitan erat dengan relasi manusia dengan alam (Man-Nature Relation). Krisis politik misalnya, bukan hanya bicara soal kekuasaan (power), tetapi pasti juga sumber daya alam (natural resources). Begitu juga dengan krisis lainnya, hampir dipastikan bersangkut paut dan bermuara pada relasi yang tidak seimbang antara manusia dan alam.
Seperti ditunjukkan oleh S.H. Nasr dalam Man and Modern Nature (1968) telah lama mengingatkan bahwa krisis metafisik dan spiritual masyarakat modern yang materialistik menyebabkan alam dipandang semata sebagai objek yang layak dieksploitasi, tanpa mempertimbangkannya sebagai subjek hidup yang setara. Lebih jauh, bahkan karena memperturutkan hasratnya, manusia kerap alpa dalam melihat potensi krisis yang akan dihadapinya dikemudian hari.
Kebutuhan manusia terhadap sumber daya alam memang bersifat mutlak, namun tidak berarti manusia memiliki hak untuk mengeksploitasinya secara ugal-ugalan tanpa memikirkan keberlanjutannya. Kita tidak boleh lagi terjebak dalam the growth illusion – meminjam istilah Richard Douthwaite dalam The Growth Illusion: How Economic Growth has enriched the Few, Impoverished the Many, and Endangered the Planet (1992). Sebab bagaimanapun juga, slogan pertumbuhan seringkali bersifat terbatas, eksklusif, dan justru mengarah kepada akselerasi krisis ekologis. Jika tidak percaya, kita dapat membuka data peningkatan PDB negara kita dari tahun ke tahun bersisian dengan data kesenjangan sosialnya lewat gini ratio. Kita juga dapat cek data deforestasi ataupun data pertambangan dan kemudian bertanya: bagaimana kabar masyarakat sekitar kawasan, apakah bertambah sejahtera atau makin sengsara?
Muhasabah Paradigma Kebijakan Publik
Jared Diamond dalam Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed (2011) menyebutkan lima faktor yang menentukan keruntuhan suatu masyarakat, yaitu [1] kerusakan lingkungan,[2] perubahan iklim, [3] tetangga yang bermusuhan, [4] hilangnya mitra dagang/bantuan, [5] respon masyarakat terhadap masalah. Menariknya, empat faktor pertama sangat bergantung pada faktor kelima. Artinya, respon masyarakat adalah faktor kunci dan menjadi konsekuensi logis dari Anthropocene. Saat kita berbicara soal respon, kita juga mesti bicara soal proyeksi. Respon tanpa back-up proyeksi yang akurat hasilnya adalah kegugupan, kegagapan, kebingungan, bahkan kepanikan. Dalam konteks inilah, negara sebagai entitas masyarakat modern ‘terkuat’, yang diwakili oleh pemerintah dengan alat kelengkapannya, dituntut untuk memiliki proyeksi potensi krisis masa depan yang akurat dan menjadikannya sebagai dasar kebijakan publik.
Sebagai pengingat, Diamond juga menjelaskan soal bentuk kegagalan masyarakat dalam merespon permasalahan sehingga berujung pada keruntuhan (collapsed). Pertama, masyarakat yang gagal mengantisipasi masalah sebelum tiba. Kedua, masyarakat yang gagal memahami masalah ketika tiba. Ketiga, masyarakat yang dapat memahami masalah tetapi tidak menemukan solusinya. Keempat, masyarakat yang dapat memahami masalah, menemukan solusinya, tetapi tidak berhasil mengeksekusinya dengan baik. Kesemuanya berkaitan erat dengan kemampuan proyeksi, utamanya dalam tiga respon pertama.
Idealnya, negara dengan dukungan fiskal, teknologi, serta sumber daya manusia dan pengetahuan yang memadai, tidak akan terjerembab ke dalam empat situasi di atas. Namun, kehadiran banjir Sumatera di akhir tahun ini, mengisyaratkan sebaliknya. Kita tidak dapat menutup mata. Bencana tersebut bukan sekedar alarm biasa, tetapi akumulasi peringatan puluhan tahun yang kurang didengar, yang pada akhirnya berbunyi demikian keras untuk menyentak kita dari lamunan. Harus diakui, bahwa paradigma kebijakan publik kita perlu ditinjau ulang secara holistik, termasuk soal tata kelola hutan seperti kebijakan pemulihan kawasan ex-illegal logging misalnya.
Pemerintah sangat membutuhkan partisipasi masyarakat soal ini, sebab hutan adalah ruang hidup bersama. Kritik masyarakat terkadang bernada sinis, ketus, skeptis, dan juga dramatis. Namun, sejatinya masyarakat adalah indera keenam negara. Detail-detail yang tidak terlihat oleh negara, kadang nampak begitu jelas di pelupuk mata warga. Sudah saatnya untuk lebih sering duduk bersama.
Proyeksi mitigasi lintas sektor adalah kunci. Tanpanya, bencana hanya akan dianggap sebagai fenomena alam, bukan dampak logis dari rangkaian pengambilan kebijakan. Sebagai penutup, B. Christian pernah berkata: you don't measure what you think you measure. Dalam konteks bencana Sumatera, seakan-akan ia berkata: kami yakin hujan menurunkan air, tetapi faktanya kayu gelondongan juga ikut bersamanya.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.