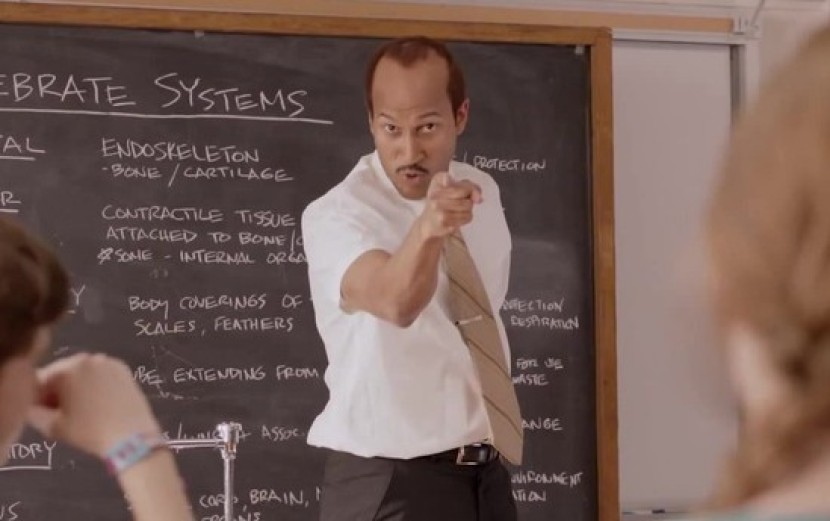AchSin
AchSin
Ironi Rakyat Indonesia
Agama | 2026-01-02 09:37:29
Oleh: Nano Hendi Hartono, Wartawan Senior
Indonesia adalah negeri yang sejak lama dipuji karena kekayaan alamnya. Tanahnya subur, lautnya luas, perut buminya menyimpan emas, nikel, batubara, minyak, gas, hingga aneka hasil hutan dan laut. Kekayaan itu bukan sekadar data statistik, melainkan juga pernah hidup dalam imajinasi kolektif bangsa. Group band legendaris Koes Plus merangkumnya secara puitis dalam lagu Kolam Susu:
Bukan lautan hanya kolam susu
Kail dan jala cukup menghidupimu
Tiada badai tiada topan kau temui
Ikan dan udang menghampiri dirimu
Lagu itu bukan sekadar romantisme, melainkan harapan. Harapan bahwa di negeri ini, hidup seharusnya tidak sulit. Bahwa bekerja keras semestinya berbanding lurus dengan kesejahteraan. Bahwa rakyat kecil tidak perlu menjadi korban sistem. Namun, realitas hari ini justru berbanding terbalik dengan lirik tersebut. Yang ditemui rakyat bukan “kolam susu”, melainkan kolam kesenjangan. Bukan ikan yang menghampiri, tetapi kemiskinan yang diwariskan lintas generasi.
Kemiskinan di Indonesia bukanlah semata-mata akibat kemalasan atau kurangnya sumber daya manusia. Ia adalah kemiskinan struktural—kemiskinan yang lahir dari kebijakan, sistem ekonomi-politik, dan relasi kuasa yang timpang. Dalam sistem seperti ini, kekayaan alam tidak mengalir ke rakyat, melainkan tersedot ke segelintir elite ekonomi dan politik.
Data kemiskinan sering dipoles dengan angka persentase yang menurun. Namun di lapangan, rakyat tetap bergulat dengan harga pangan yang naik, biaya pendidikan yang mahal, akses kesehatan yang terbatas, dan lapangan kerja yang semakin sempit. Banyak orang “tidak miskin” secara statistik, tetapi hidup dalam kondisi rentan—sedikit saja guncangan ekonomi, mereka terperosok ke jurang kemiskinan.
Ironi terbesar negeri ini adalah ketika kekayaan alam justru menjadi sumber konflik dan penderitaan rakyat. Tambang dibuka, hutan dibabat, laut dieksploitasi, namun masyarakat sekitar tetap miskin. Bahkan, sering kali mereka justru tersingkir dari tanah leluhurnya sendiri.
Atas nama investasi dan pertumbuhan ekonomi, negara memberi karpet merah kepada korporasi besar. Izin konsesi dikeluarkan dengan mudah, sementara suara rakyat dianggap penghambat pembangunan. Ketika lingkungan rusak, banjir dan longsor datang, rakyat disalahkan karena dianggap tidak adaptif. Ketika nelayan kehilangan ruang tangkap dan petani kehilangan lahan, mereka diminta bersabar demi “kepentingan nasional”.
Pertanyaannya: kepentingan nasional versi siapa?
Negara seharusnya hadir sebagai pelindung rakyat, bukan sekadar fasilitator modal. Namun yang terlihat justru sebaliknya. Regulasi sering kali lebih berpihak pada investor ketimbang masyarakat. Pajak dan royalti sumber daya alam minim, pengawasan longgar, dan penegakan hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah.
Ketika rakyat kecil memprotes, mereka berhadapan dengan aparat. Ketika elite melanggar, penyelesaiannya sering berakhir di meja kompromi. Hukum kehilangan wibawa, keadilan menjadi barang mahal, dan demokrasi menyempit menjadi sekadar prosedur lima tahunan.
Kemiskinan struktural tidak berhenti pada satu generasi. Anak dari keluarga miskin berangkat dari garis start yang timpang: gizi buruk, pendidikan seadanya, lingkungan yang tidak mendukung. Di sisi lain, anak elite menikmati akses terbaik sejak lahir. Dalam kondisi seperti ini, mobilitas sosial menjadi mitos.
Maka jangan heran jika kesenjangan terus melebar. Jangan heran jika rasa keadilan sosial semakin menipis. Yang berbahaya, kondisi ini melahirkan apatisme dan kemarahan sosial yang terpendam—bom waktu bagi stabilitas bangsa.
Sudah saatnya bangsa ini bertanya secara jujur: untuk siapa pembangunan dilakukan? Apakah pertumbuhan ekonomi semata sudah cukup, jika tidak diiringi pemerataan? Apakah kekayaan alam hanya akan menjadi kutukan (resource curse) yang menguntungkan segelintir orang?
Pembangunan seharusnya berpijak pada keadilan sosial sebagaimana amanat konstitusi. Pasal 33 UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat—bukan kemakmuran elite.
Ironi rakyat Indonesia bukan takdir. Ia adalah hasil pilihan-pilihan politik. Karena itu, solusinya pun bersifat politis dan moral. Negara harus berani membalik orientasi: dari pro-elite menjadi pro-rakyat. Dari eksploitasi menjadi keberlanjutan. Dari statistik menuju realitas.
Jika tidak, lagu Kolam Susu akan tinggal nostalgia. Sebuah ironi pahit di negeri yang kaya, tetapi rakyatnya terus diminta bersabar. Padahal, yang mereka tuntut bukan kemewahan—melainkan keadilan.
Dan keadilan, sejatinya, adalah kekayaan paling mahal yang belum sungguh-sungguh dimiliki Indonesia.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.