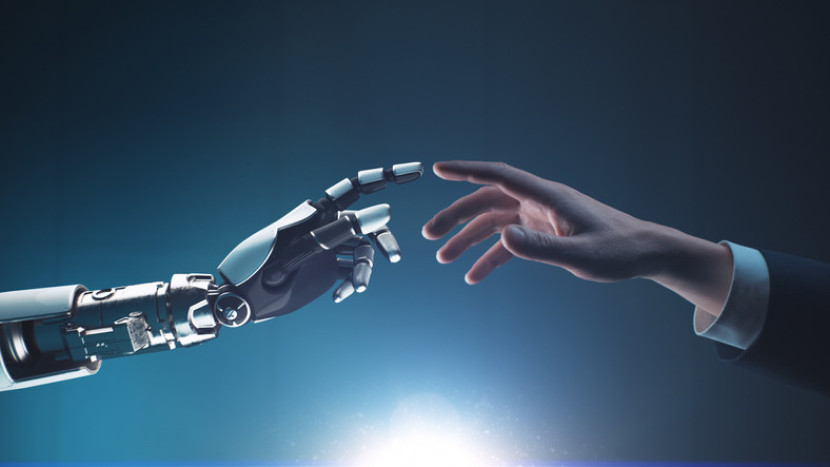Fatimah Azzahra Jamil
Fatimah Azzahra Jamil
Toxic Positivity: Ketika Harus Kuat Justru Melukai Kesehatan Mental
Gaya Hidup | 2025-12-24 18:29:46Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering diajarkan untuk selalu kuat. Sejak kecil, kalimat seperti “jangan cengeng”, “harus ikhlas”, atau “tetap bersyukur” terdengar sebagai nasehat yang baik. Tanpa disadari, pesan-pesan ini membentuk cara kita memandang emosi bahwa sedih, marah, atau kecewa adalah perasaan yang sebaiknya disembunyikan.
Didalamnya toxic positivity mulai bekerja secara halus. Ia bukan tentang optimisme, melainkan tentang paksaan untuk selalu terlihat positif hingga meniadakan emosi negatif yang sebenarnya wajar dan manusiawi.

Apa Itu Toxic Positivity?
Toxic positivity adalah kondisi ketika emosi negatif dianggap salah dan harus segera ditutup dengan sikap “positif”. Misalnya, saat seseorang stres lalu mendapat respon seperti “jangan sedih” atau “harusnya bersyukur”.
Padahal, dalam psikologi, emosi negatif memiliki fungsi penting. Emosi ini membantu seseorang mengenali batas dirinya, memahami luka batin, dan menyadari kebutuhan emosionalnya. Menekan emosi justru membuat masalah tersimpan lebih lama.
Pola ini terbentuk sejak lama. Di rumah, anak sering diminta diam saat sedih. Di sekolah dan tempat kerja, mereka terlihat kuat dan jarang mengeluh lebih dihargai. Media sosial kemudian memperkuatnya lewat narasi self-love, healing, good vibes only dan keharusan untuk selalu tampak bahagia.
Mengapa Fenomena Ini Mudah Diterima?
Budaya sosial di Indonesia menjunjung tinggi ketabahan dan kesabaran. Di satu sisi, nilai ini positif. Namun di sisi lain, muncul tekanan tidak tertulis bahwa menunjukkan kesedihan berarti lemah.
Akibatnya, banyak orang merasa bersalah saat sedang tidak baik-baik saja, seolah-olah emosi negatif adalah kegagalan pribadi.

Dampak Toxic Positivity yang Sering Tidak Disadari
Menekan emosi terus-menerus tidak membuat seseorang menjadi lebih kuat, namun justru melelahkan secara mental. Orang yang terjebak toxic positivity sering kesulitan mengekspresikan perasaannya karena menganggap sedih sebagai sesuatu yang salah.
Lama-kelamaan, mereka menjadi bingung mengenali emosinya sendiri. Sedih dianggap lemah, lelah dianggap kurang bersyukur. Kondisi ini memicu kelelahan emosional, kesulitan meminta bantuan, dan perasaan kesepian meski berada di tengah banyak orang.
Jika dibiarkan, pola ini dapat memicu stres dan kecemasan, terutama pada generasi muda yang tumbuh di tengah tuntutan untuk selalu terlihat positif.

Toxic positivity mengajarkan bahwa emosi negatif harus disingkirkan. Padahal, emosi tersebut justru membantu kita mengenali batas, kebutuhan, dan kondisi diri. Di tengah kehidupan yang penuh tekanan, menjadi manusia seutuhnya jauh lebih penting daripada yang selalu terlihat kuat.
Tidak semua hal harus ditutupi dengan senyuman. Memberikan ruang bagi seluruh emosi baik yang menyenangkan maupun tidak adalah bentuk kepedulian terhadap kesehatan mental. Karena pada akhirnya, tidak apa-apa untuk tidak selalu baik-baik saja.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.