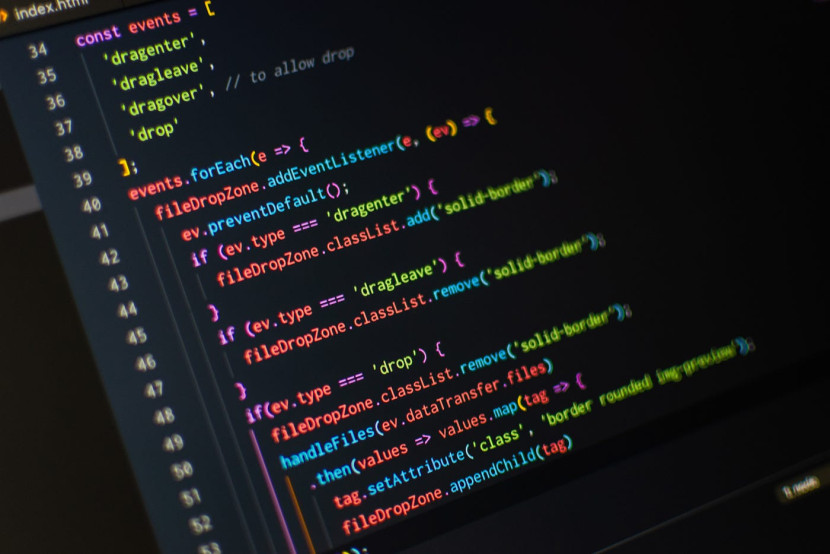Wuri Syaputri
Wuri Syaputri
Kenapa Masakan Ibu Selalu Terasa Lebih Enak?
Kuliner | 2025-12-18 21:36:07Oleh: Wuri Syaputri
Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas

Gambar ilustrasi dibuat oleh AI
Ada jenis makanan yang rasanya sulit dijelaskan secara teknis. Ia tidak selalu paling gurih, tidak selalu paling pedas, dan sering kali justru sederhana. Namun, kita menyebutnya dengan satu istilah yang terasa sangat kuat: masakan ibu, masakan rumah, atau belakangan, comfort food. Kata-kata itu terdengar akrab, hangat, dan menenangkan, bahkan sebelum makanan itu benar-benar disantap.
Fenomena ini menarik, karena menunjukkan bahwa rasa makanan tidak hanya dibentuk oleh bahan dan bumbu, tetapi juga oleh bahasa. Cara kita menamai makanan ikut menentukan bagaimana kita merasakannya. Dalam konteks ini, kuliner bukan sekadar praktik memasak, melainkan praktik linguistik dan kultural.
Dalam kajian semiotika, Roland Barthes (1961) menyebut makanan sebagai sistem tanda. Makanan tidak hanya dimakan, tetapi juga “dibaca”. Ia membawa makna sosial, emosi, dan identitas. Ketika kita menyebut sebuah hidangan sebagai “masakan ibu”, kita tidak sedang mendeskripsikan resep, melainkan memanggil serangkaian makna: rumah, kepedulian, masa kecil, dan rasa aman.
Istilah comfort food sendiri mulai banyak dibahas dalam kajian budaya dan psikologi. Locher et al. (2005) menunjukkan bahwa comfort food sering dikaitkan dengan nostalgia dan kebutuhan emosional, bukan semata kebutuhan biologis. Menariknya, jenis makanan yang dianggap “comfort” berbeda-beda antarbudaya, tetapi bahasa yang digunakan untuk menggambarkannya hampir selalu bernuansa kehangatan dan kedekatan.
Dalam linguistik kognitif, George Lakoff dan Mark Johnson (1980) menjelaskan bahwa manusia memahami pengalaman abstrak melalui metafora konseptual. Rasa aman, misalnya, sering dipahami melalui metafora fisik seperti “hangat”, “dekat”, atau “rumah”. Tidak mengherankan jika makanan yang diasosiasikan dengan kenyamanan diberi label linguistik yang merujuk pada ruang domestik dan relasi personal.
Di Indonesia, bahasa kuliner semacam ini sangat kuat. Kita jarang mengatakan “ini masakan tradisional keluarga inti dengan teknik sederhana”. Kita mengatakan “ini masakan ibu”. Satu frasa, tetapi maknanya luas dan dalam. Secara linguistik, ini adalah bentuk metonymy yaitu satu elemen (ibu) mewakili keseluruhan pengalaman (rumah, perhatian, perawatan).
Menariknya, bahasa ini juga bekerja dalam konteks komersial. Banyak rumah makan menggunakan label “masakan rumahan” atau “rasa rumah” sebagai strategi komunikasi. Kata “rumahan” bukan kategori rasa objektif, melainkan kategori emosional. Ia menjanjikan pengalaman yang familiar dan tidak mengancam. Dalam konteks ini, bahasa menjadi jembatan antara memori personal dan konsumsi publik.
Ahli linguistik Dan Jurafsky (2014), dalam bukunya The Language of Food, menunjukkan bahwa pilihan kata dalam menu dan deskripsi makanan sangat berkaitan dengan kelas sosial, identitas, dan nilai budaya. Kata-kata tertentu, seperti “homestyle”, “traditional”, atau “grandma’s recipe” secara konsisten memicu asosiasi kehangatan dan keaslian, meskipun tidak selalu mencerminkan proses memasak yang sesungguhnya.
Fenomena ini memperlihatkan bahwa bahasa kuliner bukan sekadar penjelasan, melainkan juga persuasi. Kita tidak hanya diyakinkan bahwa makanan itu enak, tetapi juga bahwa makanan itu “baik” bagi perasaan kita. Dalam hal ini, bahasa bekerja di ranah afektif.
Charles Spence (2015), melalui kajian gastrophysics, menunjukkan bahwa persepsi rasa dipengaruhi oleh ekspektasi yang dibangun sebelum makan. Kata-kata, label, dan cerita yang menyertai makanan membentuk ekspektasi tersebut. Ketika sebuah hidangan disebut “comfort food”, kita cenderung merasakannya sebagai lebih menenangkan bahkan jika secara objektif rasanya biasa saja.
Namun, ada sisi lain yang perlu dicermati. Ketika bahasa kehangatan ini digunakan secara berlebihan, ia berisiko kehilangan makna. Jika semua makanan disebut “rumahan” dan “comfort”, maka kategori itu menjadi kabur. Bahasa yang terlalu sering dipakai tanpa refleksi akan kehilangan daya afektifnya.
Selain itu, bahasa “masakan ibu” juga memuat dimensi gender yang jarang dibahas. Ia mengasumsikan peran domestik tertentu dan menempatkan kerja memasak dalam ranah afeksi, bukan kerja nyata. Dalam kajian sosiolinguistik dan gender, hal ini penting dicermati agar kehangatan bahasa tidak sekaligus menutupi beban sosial yang menyertainya.
Meski demikian, sulit menyangkal bahwa bahasa semacam ini memiliki kekuatan simbolik yang besar. Ia menghubungkan makanan dengan pengalaman hidup, bukan sekadar selera. Dalam dunia yang serba cepat dan penuh tekanan, kata-kata yang menenangkan menjadi semakin penting. Kita tidak hanya mencari rasa yang enak, tetapi juga rasa yang membuat kita pulang—meski hanya lewat sepiring nasi.
Mungkin, di sinilah peran bahasa kuliner yang paling mendasar: bukan untuk menjelaskan rasa secara ilmiah, melainkan untuk memberi makna pada pengalaman makan. Bahasa membantu kita mengingat, merasakan, dan menempatkan makanan dalam cerita hidup kita. Karena pada akhirnya, makanan memang mengenyangkan perut. Tetapi kata-kata tentang makananlah yang sering kali mengenyangkan perasaan.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.