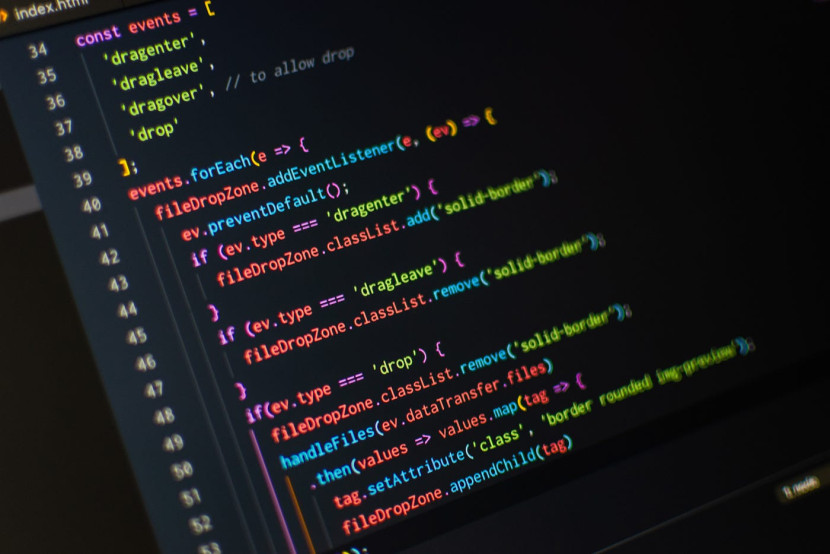Afif Sholahudin, SH, MH.
Afif Sholahudin, SH, MH.
Korupsi Haji dan Demokrasi yang Gagal Mengoreksi Diri
Politik | 2026-01-13 06:35:59
Penetapan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Ia hadir dalam sebuah rangkaian panjang persoalan tata kelola kekuasaan, khususnya pada sektor pelayanan publik yang paling sensitif: urusan keagamaan.
Kasus ini menyentak bukan hanya karena menyangkut uang negara, tetapi karena menyentuh harapan jutaan warga yang menunggu giliran menunaikan ibadah haji dengan penuh kesabaran dan kepatuhan. Ketika urusan sakral dikelola dengan logika kekuasaan dan transaksi, yang rusak bukan hanya hukum, tetapi juga kepercayaan sosial. Namun persoalan sesungguhnya jauh lebih dalam daripada sekadar satu nama atau satu periode jabatan.
Sejarah mencatat, lebih dari satu mantan Menteri Agama pernah terjerat kasus korupsi. Fakta ini penting ditekankan, karena ia menyingkap satu hal mendasar: masalahnya bukan semata individu, melainkan sistem.
Dalam analisis sosial-hukum, pengulangan kejahatan pada jabatan yang sama merupakan tanda klasik systemic failure. Artinya, sistem tidak hanya gagal mencegah penyimpangan, tetapi justru menyediakan ruang yang memungkinkan penyimpangan itu terus terjadi.
Jika satu kementerian, dengan fungsi moral dan religius yang sangat kuat, berulang kali menjadi ladang korupsi, maka narasi “oknum” sudah tidak lagi memadai. Kita berhadapan dengan kegagalan struktural dalam tata kelola demokrasi dan birokrasi.
Secara teoritis, demokrasi dipuji sebagai sistem yang mampu memperbaiki dirinya sendiri. Ketika kekuasaan menyimpang, ada mekanisme kontrol: parlemen, penegak hukum, pers, dan partisipasi publik. Namun kasus-kasus semacam ini justru menunjukkan sisi gelap demokrasi prosedural: pemilihan berjalan, jabatan berganti, pidato antikorupsi diulang, tetapi watak kekuasaan tetap sama.
Rekrutmen politik yang berbasis kompromi elite, pengawasan yang bersifat reaktif, serta partai politik yang lebih sibuk menjaga stabilitas kekuasaan ketimbang integritas kader, membuat demokrasi kehilangan fungsi korektifnya. Ia berjalan, tetapi pincang. Hidup, tetapi sakit dari dalam.
Dalam kondisi seperti ini, korupsi bukan lagi anomali, melainkan produk logis dari sistem yang rusak secara internal.
Penegakan hukum memang penting, tetapi ia sering datang setelah kerusakan terjadi. Ribuan calon jemaah telah dirugikan, keadilan sosial telah dilanggar, dan kepercayaan publik terlanjur runtuh.
Hukum pidana tidak dirancang untuk memperbaiki sistem politik. Ia hanya menghukum pelaku. Tanpa pembenahan struktural—mulai dari rekrutmen pejabat, transparansi kebijakan, hingga pengawasan preventif—kasus serupa hanya menunggu waktu untuk terulang.
Yang paling mengkhawatirkan adalah respons publik yang mulai datar. Berita “menteri jadi tersangka” tak lagi mengejutkan. Ketika korupsi di level tertinggi menjadi hal biasa, maka yang rusak bukan hanya negara, tetapi juga kesadaran moral masyarakat. Demokrasi yang gagal menjaga integritas pejabat publik akan melahirkan sinisme massal: rakyat patuh aturan, sementara elite mempermainkannya.
Jika demokrasi terus melahirkan pejabat publik yang gagal menjaga amanah, maka pertanyaannya bukan lagi siapa yang salah, melainkan sistem apa yang sedang kita pertahankan.
Demokrasi tanpa pembaruan moral dan struktural hanya akan menjadi mesin produksi skandal, bukan alat keadilan.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.