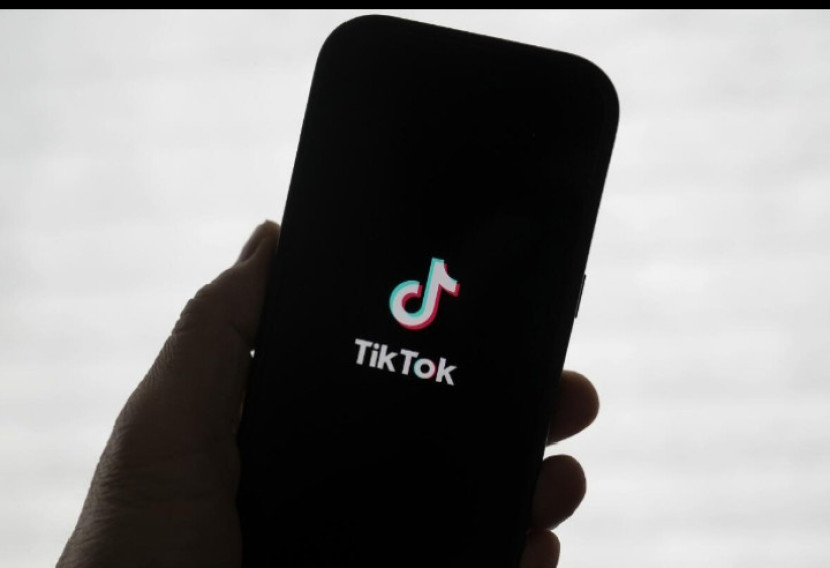Foxwblue
Foxwblue
Mental Health, Trend atau Tanda Bahaya?
Gaya Hidup | 2025-12-17 09:38:53
Oleh Naurah Bivita Wahyuningrum
Beberapa tahun terakhir, media sosial terasa ramai dengan obrolan tentang kesehatan
mental. Timeline dipenuhi curhatan soal kecemasan, burnout, hingga overthinking. Banyak
orang saling mengirimkan quotes penyemangat, sementara konten edukasi psikologi makin
mudah ditemukan. Sekilas, kita patut senang karena stigma mulai berkurang. Tetapi satu
pertanyaan muncul: apakah meningkatnya perhatian ini benar-benar menandakan
kesadaran, atau justru berubah menjadi tren mengikuti arus?
Menurut data Riskesdas Kemenkes (2018), sekitar 9,8% penduduk Indonesia mengalami
gangguan mental emosional. Persentase itu bukan angka kecil. Tetapi di luar sisi seriusnya,
media sosial memiliki cara unik “mengemas” isu ini. Emosi yang rumit sering
disederhanakan menjadi teks estetis atau meme lucu. American Psychological Association
(2020) menyebut ekspresi seperti ini memang membantu orang lebih berani bercerita.
Namun, ada dampak lain yang jarang disadari: maraknya self-diagnosis.
Di lingkungan sekitar, fenomena ini mulai terasa. Ada teman yang langsung menyebut
dirinya depresi hanya karena tugas menumpuk, atau merasa memiliki anxiety ketika gugup
presentasi. Padahal, stres dan grogi adalah reaksi manusia yang normal. Contoh lain,
beberapa orang menyebut diri “overthinker” hanya karena sulit tidur sebelum ujian besok.
Tanpa disadari, label-label seperti ini menempel dan membentuk cara seseorang melihat
dirinya. Situasi ini sejalan dengan penelitian Cahyaningsih et al. (2019) yang menemukan
bahwa penggunaan gawai berlebihan dapat memicu stres dan kebingungan dalam
mengelola emosi.
Media sosial memperkuat persepsi ini melalui algoritma. Setelah kita menyukai satu konten
mental health, sistem akan terus menampilkan hal serupa. Sunstein (2018) menyebut
kondisi ini sebagai “echo chamber”, ruang gema digital yang membuat kita merasa berada
dalam kelompok besar dengan masalah yang sama. Akibatnya, istilah psikologi menjadi
tren identitas: “aku overthinker”, “introvert parah”. Jika dibiarkan, label ini justru bisa
membatasi potensi diri.
Lebih jauh lagi, drama dan musik terkadang menggambarkan gangguan mental dengan cara
puitis. Visual sedih dibuat estetis, luka batin dikemas cantik. Dampaknya? Depresi terlihat
“romantis”. Padahal, bagi penderita sebenarnya, bangun pagi saja bisa menjadi perjuangan
panjang.
Psikiater dr. Tjhin Wiguna (FKUI, 2021) menegaskan bahwa diagnosis gangguan mental
tidak dapat dilakukan hanya dengan membaca daftar gejala di internet. Dibutuhkan
wawancara klinis, observasi, dan asesmen profesional. Sedih, cemas, takut, lelah—itu
emosi yang manusiawi. Tidak semua harus diberi label medis.
Kesadaran kesehatan mental tetap penting, tetapi keseimbangan lebih penting lagi. Kita
perlu belajar mendengarkan diri sendiri tanpa terburu-buru menyimpulkan. Mencari
bantuan tidak membuat kita lemah; mengabaikan diri sendiri justru membuat kita rentan.
Pada akhirnya, kesehatan mental bukan tren yang hilang ketika topik lain viral. Ia adalah
bagian dari kualitas hidup. Mari berhenti memberi label sembarang, berhenti
meromantisasi, dan mulai memahami dengan empati. Mungkin, langkah kecil seperti tidur
cukup, berbagi cerita dengan teman, atau mencari bantuan profesional bisa menjadi awal
yang baik.
Karena pada dasarnya, yang kita butuhkan bukan label, tetapi ruang aman untuk pulih,
berkembang, dan menjadi manusia seutuhnya.
Daftar Sumber
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas)
2018: Hasil utama.
Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan. (2022, Agustus 3). Minimnya Kesadaran
Masyarakat terhadap Mental Health.
Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan. (2025, Januari 10). Kesehatan Mental Penyitas
COVID-19.
CIMSA FK UNS. (2023, Mei 8). How Does Mental Health Affect Adolescents?
Sukesi, T. W., Sulistyawati, S., Khair, U., Asti M., Tentama, F., Ghazali, F. A., Yuliansyah,
H., & Nafiyati, L. (2023). Hubungan antara Kesehatan Lingkungan dengan
Gangguan Emosional. Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.