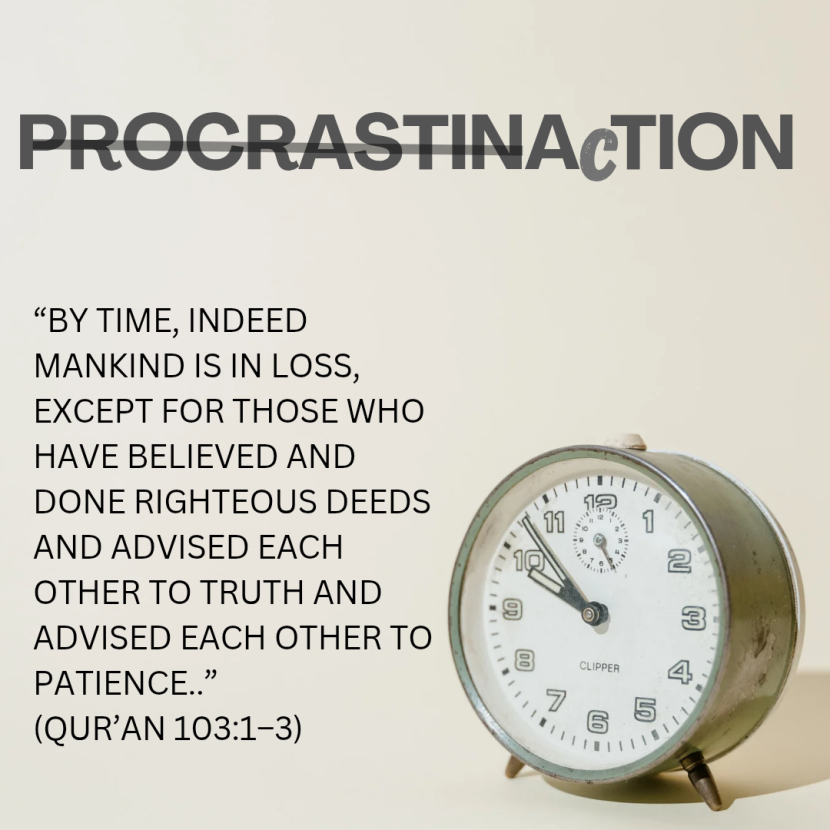Ana Fras
Ana Fras
Ketika Suara yang Diabaikan Terbukti Benar: Tragedi Ekologis Sumatera dan Peringatan Ormas Islam
Edukasi | 2025-12-07 10:26:08
Pernyataan Mahfud MD yang kembali menyinggung gugatan Undang-Undang Migas No. 22/2001 ke Mahkamah Konstitusi membuka satu bab sejarah yang lama terlupakan. Di tengah riuh bencana ekologis yang kini melanda Sumatera, publik mendadak dipaksa mengingat bahwa kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang keliru sebenarnya sudah diperingatkan sejak lebih dari satu dekade lalu. Ironisnya, suara-suara yang dulu mengangkat peringatan itu justru menjadi pihak yang distigma seiring perubahan politik negara.
Padahal, jejak itu tercatat jelas dalam Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012. Gugatan tersebut diajukan oleh 42 pemohon yang mewakili sejumlah tokoh dan organisasi Islam. Pemohon pertama adalah Pimpinan Pusat Muhammadiyah, disusul Syarikat Islam, Persatuan Umat Islam, tokoh-tokoh NU secara personal, dan beberapa organisasi lainnya termasuk Hizbut Tahrir Indonesia (pada masa ketika ia masih berstatus badan hukum). Di antara nama mereka, terselip pula figur-figur publik seperti A.M. Fatwa, Hendri Yosodiningrat, Ali Mochtar Ngabalin, dan Eggi Sudjana.
Mereka mengajukan kritik yang sama: UU Migas membuka jalan bagi privatisasi hajat hidup orang banyak. MK mencatat argumen itu dengan terang:
“Undang-Undang a quo membuka ruang privatisasi atas migas yang merupakan cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak sehingga bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945.”
Dan lebih penting lagi, MK menegaskan:“Penguasaan negara tidak dapat dimaknai sempit, melainkan mencakup kewajiban negara mengelola dan tidak menyerahkannya kepada mekanisme pasar.”
Dua kalimat itu seharusnya cukup untuk menjadi landasan moral dan politik dalam mengelola sumber daya alam Indonesia. Namun yang terjadi justru sebaliknya: kritik substantif itu tenggelam di tengah arus stigma terhadap sebagian pemohonnya, dan negara melanjutkan tata kelola yang semakin memberi ruang bagi korporasi besar.
Kini, ketika Sumatera tenggelam dalam rentetan bencana ekologis, publik baru menyadari bahwa apa yang dulu dipersoalkan bukan sekadar perbedaan ideologis. Itu adalah peringatan dini atas konsekuensi sebuah model ekonomi yang menempatkan kekayaan alam sebagai komoditas, bukan amanah.
Kerusakan berlangsung sistematis. Di banyak daerah di Sumatera, hutan alam diganti dengan deretan kelapa sawit dan tambang minerba yang agresif. Daerah aliran sungai rusak, tutupan hutan menghilang, sementara izin tambang dan konsesi hutan ditandatangani jauh lebih cepat dibanding kemampuan aparat lingkungan untuk mengawasinya.
Akibatnya jelas terlihat. Banjir bandang di Sumatera Barat menyapu permukiman. Longsor memutus jalur transportasi dan merobohkan lereng bukit yang dulu hijau. Sungai-sungai yang menjadi sumber air bersih berubah menjadi saluran keruh penuh sedimen. Dan masyarakat yang tinggal di sekitar konsesi tambang merasakan langsung bagaimana tanah yang dulu memberi hidup kini menjadi ancaman.
Dalam setiap narasi pemerintah seusai bencana, selalu ada frasa yang diulang: curah hujan ekstrem, faktor alam, variabilitas iklim. Namun yang jarang disebut adalah bagaimana ekspansi tambang dan hutan industri telah menghilangkan kemampuan alam untuk meredam bencana. Padahal, data deforestasi menunjukkan bahwa laju kehilangan hutan Sumatera tidak pernah benar-benar berhenti.
Tak sulit melihat kesambungannya: ketika negara membuka ruang dominan bagi korporasi, ketika mekanisme pasar mengatur hajat hidup orang banyak, dan ketika suara kritis diabaikan, bencana ekologis menjadi konsekuensi yang hampir pasti.
Pertanyaannya kemudian: mengapa peringatan itu tidak pernah menjadi arus utama kebijakan?
Jawabannya, meski tidak nyaman, tampaknya sederhana: karena politik lebih mudah membangun stigma terhadap pengkritik daripada memperbaiki kesalahan struktural yang mereka suarakan. Ketika sebagian pemohon dalam gugatan MK itu kemudian diberi label negatif di ruang publik, kritik substantif mereka secara otomatis ikut didelegitimasi. Masyarakat diarahkan untuk fokus pada identitas organisasi, bukan pada isi kritiknya.
Kita melupakan bahwa gugatan tersebut diwarnai nama-nama dan ormas yang memiliki kredibilitas panjang dalam advokasi publik—Muhammadiyah, Syarikat Islam, PUI, tokoh-tokoh pesantren. Kita juga melupakan bahwa dokumen MK adalah dokumen negara, bukan selebaran propaganda. Ia memuat kritik yang sah, argumentatif, dan konsisten dengan mandat konstitusi.
Dan kini, ketika bencana menumpuk, tiba-tiba suara-suara lama itu terdengar kembali gema kebenarannya.
Sumatera hari ini adalah halaman terbuka dari buku besar kesalahan tata kelola. Ia menunjukkan bagaimana kita lebih takut pada kritik daripada pada kerusakan. Bagaimana pemerintah lebih gesit menanggapi isu politik ketimbang memperbaiki kerentanan ekologis. Bagaimana masyarakat dipaksa mencurigai kelompok yang bersuara lantang, tetapi tidak didorong mencurigai kebijakan yang membuat sungai meluap dan tanah longsor.
Padahal, jika kritik itu diikuti sejak awal, jika pengelolaan SDA tidak diserahkan pada mekanisme pasar, jika negara memegang kendali dan memastikan keberlanjutan, mungkin kita tidak sedang menyaksikan Sumatera luluh lantak.
Ada saatnya bangsa harus menatap cermin dan mengakui bahwa ia salah membaca siapa kawan, siapa peringatan, dan siapa ancaman. Suara-suara yang dulu dianggap mengganggu stabilitas politik ternyata adalah suara yang paling peduli pada keberlanjutan hidup rakyat.
Kini, ketika banjir merendam kampung dan longsor merobek tebing, tidak ada lagi tempat untuk menyangkal. Peringatan itu benar. Dan bencana hari ini bukan semata takdir alam, melainkan buah dari keputusan-keputusan yang memilih untuk tidak mendengarkan.
Yang tersisa bagi kita hanyalah satu pertanyaan:berapa banyak lagi tragedi ekologis yang harus terjadi sebelum negara kembali kepada amanat konstitusi—dan kepada akal sehat?
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.