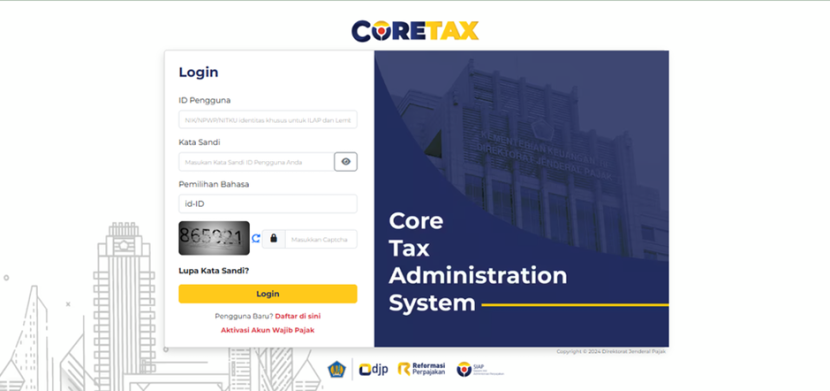Firdaus Abstrak
Firdaus Abstrak
Paradoks Dilematik: Antara Transisi Energi dan Konflik Agraria
Hukum | 2025-10-25 05:39:09Sudah sejak lama sekali Indonesia dikenal sebagai wilayah yang memiliki banyak sekali gunung berapi, jumlahnya pun mencapai ribuan. Tanah yang terhampar dari ujung ke ujung negara kepulauan inipun kaya akan energi, salah satunya adalah panas bumi atau geothermal. Energi panas bumi memiliki beberapa fungsi atau manfaat bagi kehidupan manusia, misalnya sebagai pembangkit listrik, pemanasan dan pendinginan bangunan, serta pemanfaatan langsung untuk keperluan industri dan rumah tangga. Namun, walaupun potensi panas bumi di indonesia mencapai lebih dari 23 ribu megawatt atau sekitar 40% dari total potensi global, indonesia baru bisa memanfaatkannya sekitar 10-11% saja.

Energi panas bumi yang dimiliki indonesia digadang-gadang sebagai masa depan transisi energi, bahkan diyakini juga sebagai solusi yang bersih di tengah ancaman krisis iklim dan ketergantungan lebih pada batu bara. Tapi ambisi besar transisi energi tidak dapat dengan mudah tercapai, sebab ada banyak sekali permasalahan kompleks yang amat nyata dibalik rencana realisasi transisi energi. Bisa kita lihat pada beberapa tahun terakhir, proyek-proyek geothermal di berbagai daerah justru menimbulkan konflik agraria, penolakan-penolakan keras dari masyarakat, dan dugaan-dugaan adanya ketidakpatuhan pada hukum lingkungan.
Bisa kita akui bahwasannya energi bersih merupakan sesuatu yang terdengar menjanjikan, tidak heran jika pemerintah menempatkan energi panas bumi sebagai pilar utama transisi energi nasional. Tapi di sisi lain, proyek-proyek geothermal justru mendapatkan penolakan keras dari masyarakat, misalnya proyek geothermal Cibodas di Jawa Barat, Bedugul di Bali, Dieng di Jawa Tengah, hingga Sorik Marapi di Sumatera Utara. Bukan tanpa sebab, dan bukan pula masyarakat alergi kemajuan, tetapi seringkali pada praktiknya, proyek geothermal direalisasikan secara terburu-buru dan tidak “sehat”. Energi yang sepatutnya menjadi simbol kemajuan justru melahirkan paradoks: di atas kertas terlihat bersih, tetapi di lapangan terlihat kotor.
Jika kita membaca kembali Undang-Undang Pokok Agraria, jelas kita akan menemukan kalimat tegas yang menyebutkan bahwa setiap pemanfaatan tanah harus memperhatikan fungsi sosialnya. Itu artinya, tanah bukanlah sekadar komoditas ekonomi, melainkan ruang hidup sekaligus identitas bagi masyarakat. Sayangnya, prinsip tersebut seringkali diabaikan oleh proyek-proyek geothermal. Di berbagai daerah yang menjadi lokasi proyek geothermal, banyak warga yang kehilangan aksesnya terhadap lahan pertanian, kehilangan atau tercemar sumber airnya, dan terampas wilayah adatnya. Selain itu, seringkali warga baru mengetahui adanya proyek geothermal setelah izin eksplorasi atau produksi dikeluarkan oleh pemerintah. Ini artinya, warga sekitar wilayah proyek tersebut tidak diberikan setidak-tidaknya sosialisasi terlebih dahulu. Sebetulnya adapula yang memberikan sosialisasi terlebih dahulu, namun konsultasi publik yang dilakukan seringkali hanya sekadar formalitas administratif. Prinsip persetujuan bebas dan diinformasikan (Free, Prior, and Informed Consent) sebelumnya tidak dilakukan secara utuh. Lebih jauh lagi, masyarakat seringkali tidak diberi ruang untuk menolak atau mengajukan alternatif solusi dan hal ini lah yang menyebabkan proyek kehilangan legitimasi sosialnya. Penolakan keras yang bermunculan pun berujung pada konflik antara perusahaan, aparat, dan masyarakat.
Jika kita lihat dari perspektif hukum, pembangunan panas bumi diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi. Aturan tersebutlah yang menyodorkan peluang pengusahaan panas bumi di kawasan hutan selagi tidak mengubah fungsi utama kawasan tersebut. Patut disayangkan, fakta memperlihatkan pelaksanaannya di lapangan seringkali jauh dari ideal. Banyak proyek-proyek yang dilakukan di area-area yang dilindungi seperti taman nasional yang tentunya memiliki nilai ekologis penting. Dengan proses yang cukup rumit, mulai dari pembangunan akses jalan, pengeboran sumur, sampai pendirian fasilitas pendukung kerap menyebabkan perubahan bentang alam dan menimbulkan kerusakan vegetasi di sekitar wilayah pembangunan proyek tersebut.
Di Bedugul, kita bisa melihat jelas risiko benturan antara pembangunan dan nilai-nilai budaya yang sudah lama sekali hidup dalam masyarakat. Masyarakat adat melakukan penolakan karena proyek geothermal dianggap dapat mengancam kesucian kawasan serta sumber air yang menopang kehidupan mereka. Lain lagi di Sorik Marapi, aktivitas pengeboran menyebabkan kebocoran gas hingga menelan korban jiwa. Dua peristiwa tersebut menunjukkan bahwa energi yang diklaim ramah lingkungan pun memiliki risiko yang besar jika pada implementasinya tidak disertai pengawasan yang ketat dan akuntabel serta mengabaikan partisipasi publik.
Dari banyak proyek yang ada, tidak jarang masyarakat hanya dianggap sebagai objek penerima dampak, bukan subjek yang memiliki hak untuk menentukan arah pembangunan di tanah mereka sendiri. Padahal sudah sangat jelas diterangkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 bahwasannya bumi, air, dan kekayaan alam harus digunakan untuk kemakmuran rakyat. Jika masyarakat lokal justru terpinggirkan, maka cacatlah makna dari semangat konstitusi tersebut.
Dengan alasan untuk mencapai target transisi energi nasional pemerintah melakukan percepatan proyek panas bumi, tapi pembangunan yang tidak memperdulikan hak masyarakat justru akan menjadi bumerang. Jelas itu akan sangat merugikan. Sebab, konflik agraria yang terjadi membuat proyek tertunda dan pasti menimbulkan kerugian ekonomi hingga sosial.
Dengan melihat permasalahan-permasalahan iklim dan terbatasnya energi dari bahan bakar fosil, transisi menuju energi yang terbarukan seperti geothermal sebetulnya memang sangat penting. Namun di sisi lain, banyak sekali faktor yang menunjukan bahwa pemerintah dan pihak-pihak yang melaksanakan proyek panas bumi belum siap untuk dapat menjamin keadilan sosial, keterbukaan informasi, akuntabilitas hukum, dan memberikan seluruh hak-hak yang sepatutnya dimiliki oleh masyarakat. Hal inilah yang akhirnya menjadikan ambisi transisi energi menjadi sebuah paradoks yang memojokkan pemerintah pada posisi yang dilematis.
Oleh karena itu, setiap proyek haruslah diawali dengan audit hukum tanah yang jelas dan tidak gagap, harus bebas dari sengketa. Juga kajian dampak lingkungan wajib dilakukan dengan ketelitian tinggi dan melibatkan pakar independen. Lalu proses konsultasinya harus ruang yang nyata bagi masyarakat untuk mendapatkan haknya dalam menyampaikan aspirasi, bukan sekadar basa-basi administratif.
Indonesia, jelaslah suatu negara yang kaya akan sumber panas bumi, namun sering kali masih sangat kurang dalam hal kehati-hatian. Di tengah dorongan global menuju energi hijau, pemerintah perlu memastikan bahwa pembangunan energi terbarukan tidak berubah menjadi sumber baru ketimpangan. Kita perlu benar-benar paham tentang tanah, tanah tidak hanya menyimpan potensi energi panas bumi, tapi juga menyimpan kehidupan bagi masyarakat di sekitarnya. Transisi energi hanya akan bermakna jika pada prosesnya dibarengi dengan menghormati hak rakyat dan menjaga bumi yang menjadi pijakannya.
Bogor, 25 Oktober 2025
Mohammad Ikhsan Firdaus, Mahasiswa Ilmu Hukum di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.
Teks ini sepenuhnya merupakan pendapat pribadi.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.