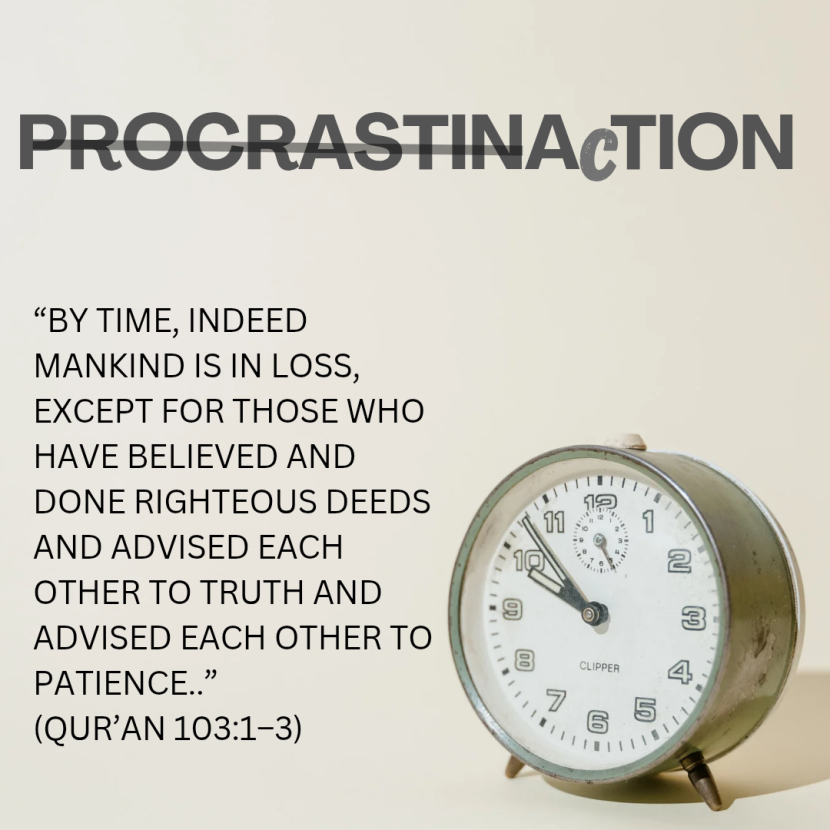Ana Fras
Ana Fras
Krisis Iklim: Ketika Kapitalisme Mengubah Alam Menjadi Komoditas
Humaniora | 2025-10-14 08:26:42
Kita sering diberi tahu bahwa bumi sedang sakit karena emisi, padahal racunnya jauh lebih dalam. Ia bersumber dari cara pandang yang mengajarkan manusia menukar makna hidup dengan angka, dan mengira laba adalah ukuran kemajuan. Krisis iklim bukan hanya tentang panasnya bumi, tetapi tentang hati manusia yang perlahan kehilangan keseimbangannya.
Dalam narasi arus utama, perubahan iklim kerap disebut sebagai akibat dari polusi, konsumsi energi, dan deforestasi. Maka solusi yang ditawarkan pun bersifat teknis, seperti pajak karbon, inovasi hijau, atau energi terbarukan. Namun semua itu hanya menyentuh gejala, bukan akar. Akar persoalan sebenarnya terletak pada paradigma yang menempatkan alam sebagai alat untuk diperas, bukan sebagai amanah yang harus dijaga. Paradigma itu bernama kapitalisme.
Kapitalisme lahir dari keyakinan bahwa alam adalah sumber daya tak terbatas yang boleh dieksploitasi untuk pertumbuhan tanpa akhir. Dalam logika ini, nilai alam diukur dari berapa besar ia bisa diubah menjadi uang. Gunung dianggap tambang, hutan dianggap lahan produksi, sungai dianggap saluran industri. Manusia pun menjadi sekadar roda penggerak dalam mesin ekonomi yang tak mengenal cukup. Kapitalisme bukan hanya sistem ekonomi, tetapi cara pandang terhadap kehidupan.
Dalam sistem ini, kerusakan lingkungan disebut eksternalitas, seolah hanya efek samping yang bisa diabaikan. Ketika pabrik mencemari sungai, biaya kesehatannya ditanggung masyarakat, bukan perusahaan. Ketika tambang merusak hutan, yang dihitung tetaplah keuntungan, bukan kehilangan. Pasar menghitung laba, tapi tidak menghitung luka. Dari sinilah lahir dunia yang tampak makmur di permukaan, namun sesungguhnya rapuh di dalam.
Lebih jauh, kapitalisme hidup dari mitos pertumbuhan tanpa batas. Setiap tahun manusia mengambil lebih banyak dari apa yang dapat dipulihkan bumi, dan tetap menyebutnya kemajuan. Padahal tidak ada pertumbuhan abadi di dunia yang terbatas. Namun kita terus meyakini bahwa teknologi dan uang mampu menaklukkan hukum alam. Ketika grafik ekonomi naik, daya dukung bumi menurun, dan kita berpura-pura tidak melihat hubungan itu.
Dari paradigma yang keliru ini lahir kebijakan yang mempercepat kerusakan. Negara-negara masih memberi subsidi besar untuk industri bahan bakar fosil, seolah bumi sendiri yang membayar ongkos kehancurannya. Sementara itu, energi terbarukan harus berjuang melawan birokrasi dan kepentingan korporasi yang sudah berakar dalam sistem. Bahkan perdagangan karbon yang sering disebut solusi pasar, pada kenyataannya hanyalah cara baru menjual izin untuk mencemari. Polusi dijadikan komoditas, dosa ekologis ditebus dengan uang.
Deforestasi yang merajalela juga merupakan buah dari logika yang sama. Hutan dibabat untuk sawit, tambang, atau peternakan, demi menambah angka pertumbuhan ekonomi. Dalam sistem ini, satu hektar hutan yang tegak dianggap kurang berharga dibanding satu hektar lahan yang bisa dijual. Padahal hutan yang berdiri adalah nafas kehidupan, bukan sekadar aset. Alam kehilangan keseimbangannya karena manusia kehilangan rasa hormat.
Krisis iklim juga memperlihatkan ketimpangan global yang nyata. Negara-negara kaya di belahan bumi utara telah menikmati kemakmuran dari pembakaran bahan bakar fosil selama lebih dari satu abad. Kini mereka menasihati dunia tentang transisi energi, sementara negara-negara miskin di selatan menanggung banjir, kekeringan, dan krisis pangan. Keadilan iklim menjadi slogan yang indah, tapi kosong makna, sebab mereka yang paling sedikit bersalah justru paling menderita.
Islam memandang alam bukan sebagai objek kepemilikan mutlak, melainkan sebagai titipan. Manusia bukan penguasa, melainkan khalifah, yang bertugas menjaga keseimbangan dan menegakkan keadilan. Dalam pandangan ini, keseimbangan bukan kelemahan, tapi tanda kebijaksanaan. Kesederhanaan bukan kemunduran, tapi bentuk kesadaran. Keadilan bukan pilihan moral, tapi syarat kelestarian. Ketika keseimbangan hilang, bukan hanya ekosistem yang runtuh, tetapi juga tatanan nilai kehidupan.
Krisis iklim sesungguhnya adalah cermin dari krisis moral peradaban modern. Dunia berlari mengejar pertumbuhan, tapi kehilangan arah. Kita membangun kota, tapi menghancurkan kehidupan di sekitarnya. Kita menciptakan kemakmuran, tapi menambah ketimpangan. Semua karena paradigma yang menuhankan keuntungan dan menyingkirkan hikmah. Padahal, solusi sejati tidak akan datang dari mesin atau kebijakan, melainkan dari kesadaran yang menempatkan kehidupan di atas laba.
Sudah waktunya kita mengganti cara pandang terhadap dunia. Alam bukan alat produksi, melainkan amanah yang harus dijaga. Pembangunan sejati bukan tentang menambah angka, tetapi menjaga keseimbangan. Kemajuan sejati bukan tentang menguasai bumi, tetapi hidup selaras dengannya. Jika kapitalisme menjadikan alam sebagai komoditas, maka tugas manusia beriman adalah mengembalikannya menjadi karunia.
Krisis iklim tidak datang dari langit, ia lahir dari sistem yang menolak keseimbangan. Selama cara berpikir kita masih tunduk pada logika laba, bumi akan terus membayar harga bagi keserakahan yang tak pernah cukup. Maka jangan salahkan emisi, jangan salahkan teknologi. Salahkan paradigma yang membuat manusia lupa siapa dirinya di hadapan alam dan di hadapan Sang Pencipta.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.