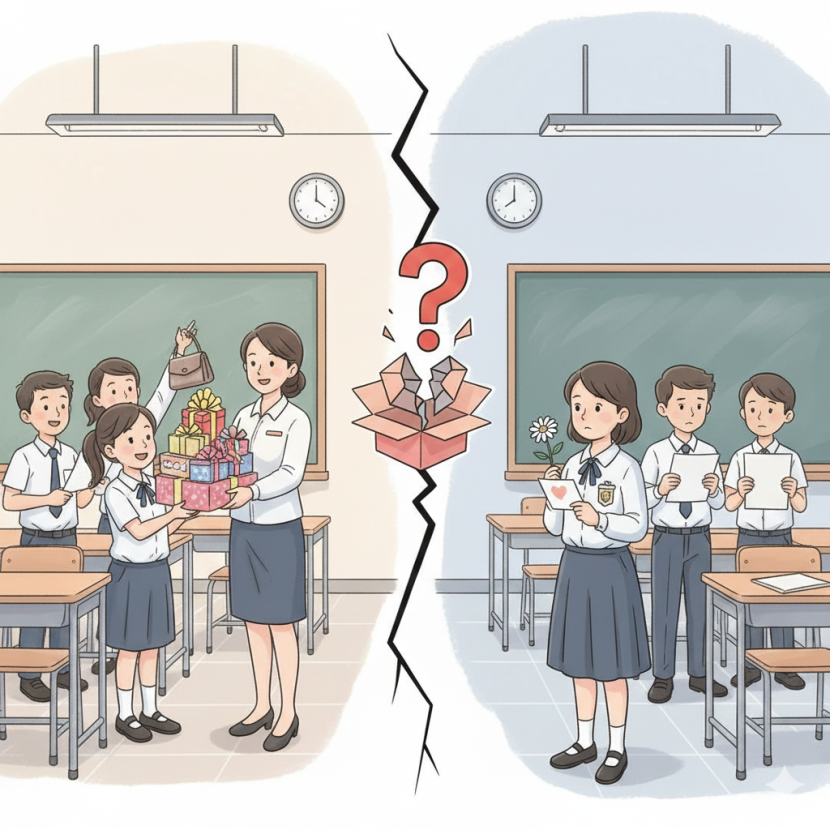Ari J. Palawi
Ari J. Palawi
Melihat Bukan Sekadar Menatap: Kritik, Apresiasi, dan Kemanusiaan di Era Cepat
Pendidikan dan Literasi | 2025-10-14 00:33:42
Sore itu ruang kelas terasa lengang. Beberapa mahasiswa duduk bersandar, sebagian menatap layar ponsel, sebagian lagi hanya menunggu waktu berlalu. Di papan tulis, saya menulis satu kalimat pendek: “Melihat bukan sekadar melihat.” Mereka membaca cepat, lalu diam. Tak satu pun bertanya, tapi keheningan itu cukup bagi saya. Saya tahu, kalimat itu sedang bekerja di kepala mereka, mungkin juga di hati mereka.
Begitulah zaman kita hari ini — serba cepat, serba tampil, dan serba menatap. Kita melihat terlalu banyak hal, tetapi jarang sungguh-sungguh memandang sesuatu dengan kesadaran utuh. Layar-layar di genggaman membuat kita seolah selalu hadir di mana-mana, padahal di dalam diri kita, kelelahan sudah lama menumpuk. Kita kehilangan kemampuan paling sederhana sekaligus paling manusiawi: kemampuan untuk hadir, untuk diam, dan untuk benar-benar melihat.
Dalam ruang kecil itu, saya mencoba mengajak mereka belajar tentang kritik dan apresiasi seni — bukan sebagai teori, melainkan sebagai latihan menjadi manusia yang lebih peka. Saya tidak memulai dengan menjelaskan istilah estetika atau prinsip penilaian karya. Saya mulai dengan keheningan. Lima menit tanpa bicara, hanya menatap satu karya: lukisan, foto, atau potongan video. Lima menit yang terasa panjang bagi generasi yang biasa menggulir layar setiap sepuluh detik.
Setelah diam, baru mereka bicara. “Rasanya lukisan itu menatap balik,” kata seorang mahasiswa. Yang lain menulis, “Saya tidak tahu harus menilai apa, tapi saya merasa sedang dilihat.”
Saat itu saya tahu: mereka mulai belajar melihat. Bukan hanya objek di depan mata, tapi juga diri mereka sendiri. Itulah inti dari apresiasi seni — memperlambat pandangan agar hati sempat ikut bekerja.
Melihat karya seni seharusnya seperti melihat kehidupan: tidak tergesa, tidak hanya menilai permukaan. Setiap warna, garis, atau bunyi adalah bahasa yang membawa pengalaman hidup pembuatnya. Di balik bentuk selalu ada kisah; di balik kisah selalu ada manusia. Dan manusia, betapapun berbeda, selalu punya titik temu dalam rasa. Maka kritik yang sejati bukanlah tentang benar atau salah, melainkan tentang seberapa dalam kita mau mendengar.
Saya sering mengatakan kepada mahasiswa: menilai karya seni adalah menilai kejujuran diri sendiri. Kritik yang tajam tanpa empati hanyalah kebisingan baru. Karena itu, dalam kelas ini, menulis kritik bukan berarti menentukan siapa yang bagus atau gagal. Menulis adalah cara untuk memahami — sekaligus bentuk penghormatan terhadap proses kreatif orang lain. Kita menulis dengan kepala yang jernih dan hati yang penuh tenggang rasa.
Seni, pada hakikatnya, adalah latihan moral. Ia mengajarkan keseimbangan antara berpikir dan berperasaan. Di dunia yang gemar bicara keras, seni mengingatkan kita bahwa ada keindahan dalam kelembutan, dan ada kebenaran dalam keheningan. Mungkin karena itu pula, di tengah gempuran teknologi dan kecepatan, seni masih bertahan — karena ia satu-satunya ruang di mana manusia bisa jujur kepada dirinya sendiri.
Di Aceh, saya sering menemukan kejujuran itu dalam bentuk-bentuk sederhana: suara rapa’i yang memanggil, motif songket yang bercerita, irama pantun yang menuntun hati. Seni di sini bukan urusan ego, melainkan urusan hidup bersama. Tidak ada pemain yang ingin menonjol, karena harmoni lahir dari kebersamaan. Itulah estetika gotong royong — di mana keindahan bukan milik satu orang, tetapi buah dari kesadaran kolektif.
Namun nilai seperti itu perlahan terkikis oleh ritme zaman. Dunia digital memberi ruang bagi setiap orang untuk menjadi pencipta, tapi tidak semua siap menjadi penjaga makna. Kita terbiasa mengunggah, menilai, berkomentar, bahkan menghakimi dengan cepat. Tapi siapa di antara kita yang masih berhenti sejenak dan bertanya: apakah yang kubagikan hari ini menambah kebaikan bagi kehidupan?
Kritik dan apresiasi seni, bagi saya, adalah latihan etis untuk zaman seperti ini. Ia melatih kita membedakan antara ekspresi dan ekses, antara kebebasan dan tanggung jawab. Ia membantu kita menjaga makna di tengah kebisingan algoritma. Sebab tugas manusia bukan hanya mencipta keindahan, tetapi juga memeliharanya agar tidak kehilangan nilai kemanusiaan.
Saya percaya, seni adalah cara paling lembut untuk memperbaiki manusia. Ia tidak memerintah, tidak memaksa — hanya mengajak. Dalam setiap karya yang lahir, tersimpan harapan agar manusia kembali mengingat dirinya sendiri: bahwa hidup bukan sekadar menatap layar, melainkan menatap sesama dengan hati.
Ketika kelas berakhir, saya menatap mereka yang masih diam. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada tanya-jawab panjang. Namun saya tahu, sesuatu sedang tumbuh di dalam mereka. Mungkin kesadaran, mungkin rasa tenang, atau sekadar kerinduan untuk hadir sepenuhnya. Tapi dari sanalah semua dimulai — dari kemampuan untuk melihat sebelum menilai, dan memahami sebelum berbicara.
Sebab pada akhirnya, kritik dan apresiasi seni bukan tentang karya orang lain. Ia adalah cara kita menatap cermin, melihat ke dalam, dan bertanya: Apakah aku masih bisa melihat dengan hati?
Seni mengajarkan kita memperlambat agar bisa memahami, dan memahami agar tetap manusia di tengah dunia yang cepat. — Ari Palawi
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.