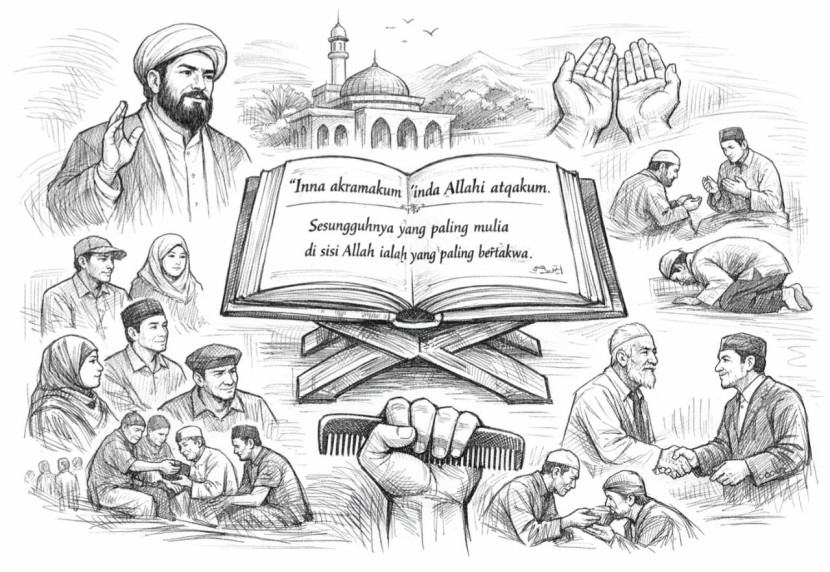Ari J. Palawi
Ari J. Palawi
Energi sebagai Titipan Allah: Menuju Migas Berkah di Tanah Serambi Mekkah
Humaniora | 2025-09-08 19:43:58
Aceh kembali berada di persimpangan sejarahnya. Setelah kejayaan kilang Arun meredup dan meninggalkan jejak infrastruktur yang membisu, kini cadangan gas raksasa di Andaman kembali menyalakan harapan. Mubadala Energy pada akhir 2023 mengumumkan temuan besar di sumur Layaran-1 dengan potensi hingga enam triliun kaki kubik gas, jumlah yang menempatkan Aceh dalam peta energi dunia. Namun pengalaman masa lalu mengajarkan bahwa kelimpahan sumber daya tidak serta-merta menjelma kesejahteraan. Pada masa kejayaan Arun, sebagian besar masyarakat tetap hidup dalam pinggiran, infrastruktur hadir namun tak terkelola, dan generasi muda banyak yang pergi merantau karena tak menemukan ruang untuk berkembang. Pertanyaan besar kini muncul: apakah Aceh akan mengulang pola lama atau memilih jalan baru yang lebih arif?
Dalam perspektif Islam yang mengakar di bumi Serambi Mekkah, sumber daya adalah amanah, titipan yang harus dikelola dengan adil dan membawa maslahat. Itulah mengapa setiap kebijakan migas tidak cukup hanya diukur dengan kalkulasi kontrak atau nilai investasi, melainkan juga harus ditimbang dengan prinsip syariah, dengan keadilan sosial sebagai tolok ukur, dan dengan keberlanjutan lingkungan sebagai penjaga masa depan. Muhammad Dahlan, seorang praktisi migas yang tampil dalam talkshow SagoeTV pada 11 Maret 2025, mengingatkan bahwa momentum Andaman tidak boleh dibiarkan lewat begitu saja. Baginya, penentuan lokasi shore base akan menjadi titik krusial. “Cadangan gas ini adalah momentum Aceh. Shore base harus tetap di Lhokseumawe,” tegasnya. Alasan itu bukan sekadar sentimen, melainkan kalkulasi logis: infrastruktur eks-Arun seperti pelabuhan, bandara Malikussaleh, jaringan pipa, dan kawasan industri telah tersedia dan dapat digunakan kembali. Jika fasilitas vital ini dipindahkan ke luar Aceh, maka manfaat ekonomi lokal yang mestinya bisa menghidupkan Banda Sakti, Muara Satu, hingga Blang Mangat akan hilang begitu saja.
Bagi Dahlan, shore base bukan sekadar terminal logistik, tetapi pusat denyut ekonomi. Dari sanalah lapangan kerja akan lahir, kontraktor lokal bisa ikut serta, UMKM dapat bergerak, dan ekonomi sekitar bisa bergairah. Ia percaya bahwa membangun kembali Aceh berarti menghidupkan kembali kawasan industri Lhokseumawe sebagai pusat penggerak, bukan hanya menyediakan sumber daya bagi luar daerah. Tetapi gagasan ini tak lepas dari perdebatan. BPMA sempat membicarakan alternatif lokasi di Sabang, bahkan sejumlah kalangan menilai biaya relokasi bisa memberi peluang baru. Di sinilah seni diplomasi diperlukan agar keputusan akhir tidak sekadar teknokratis, tetapi adil dan berimbang.
Repsol resmi mengembalikan pengelolaan Blok Andaman III kepada negara pada pertengahan 2023 setelah pengeboran Sumur Rencong-1X tidak menemukan cadangan migas yang ekonomis. Keputusan ini membuat blok tersebut berstatus open area dan siap ditawarkan kembali oleh pemerintah. Meski alasan resmi terkait pada hasil eksplorasi dan biaya tinggi laut dalam, peristiwa ini juga menyisakan refleksi tentang gaya diplomasi Aceh. Muhammad Dahlan, praktisi migas, menilai bahwa interaksi dengan investor kerap masih terlalu kaku. “Negosiasi itu seni. Kadang mereka datang hanya untuk ngobrol santai dulu, bukan langsung rapat resmi. Kalau kita pasang badan keras sejak awal, mereka merasa tidak welcome,” ujarnya. Menurutnya, diplomasi yang berakar pada kearifan lokal Aceh—musyawarah, peumulia jamee atau memuliakan tamu, serta sikap persuasif—lebih sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan kelembutan sekaligus ketegasan: rahmah dalam sikap, namun tetap teguh pada prinsip. Bila kultur ini dibawa ke meja perundingan, besar kemungkinan investor merasa dihormati, sekaligus memahami bahwa Aceh memiliki arah yang jelas.
Meski demikian, persoalan yang sering muncul dari industri adalah kesenjangan. Irwandar, mantan staf Humas PT Arun NGL yang kini aktif di Yayasan Usaha Lestari Indonesia, menegaskan hal ini dengan jernih: “Kesenjangan itu hukum alam. Yang penting adalah bagaimana kita mengelolanya.” Ia mengingatkan bahwa dalam masyarakat industri, jurang kaya-miskin adalah keniscayaan, bukan anomali. Yang membedakan hanyalah cara suatu bangsa menanganinya. Norwegia, misalnya, mampu menjadikan dana migas sebagai tabungan negara melalui sovereign wealth fund yang dinikmati lintas generasi. Nigeria gagal karena distribusi yang timpang, sementara Qatar menekan kesenjangan lewat reinvestasi sosial dan fasilitas publik. Dari perbandingan ini, jelas bahwa kesenjangan tidak harus menjadi sumber konflik. Justru ia bisa menjadi ruang pembelajaran bila ditangani dengan mekanisme yang tepat.
Di titik inilah Irwandar menawarkan solusi konkret: pemetaan sosial yang rutin. Menurutnya, setiap tiga bulan harus ada pemetaan kondisi masyarakat sekitar industri. “Jika tidak dipetakan, kita terus tertinggal,” katanya. Pemetaan yang dimaksud bukan survei formal dengan angka statistik kaku, melainkan radar dinamis yang membaca aspirasi warga, potensi konflik, dan perubahan nilai budaya. Forum musyawarah gampong bisa menjadi ruang validasi, dayah dan ulama memberi legitimasi moral, sementara sanggar budaya berfungsi sebagai radar nilai. Jika sebuah tradisi melemah, itu bisa menjadi tanda dini adanya perubahan sosial yang patut diperhatikan.
Prinsip ini selaras dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya musyawarah dan keadilan. Ulama berperan bukan hanya sebagai simbol, tetapi sebagai penjaga moral agar setiap kebijakan tidak melenceng dari maslahah. Dalam konteks lingkungan, konsep ini juga menemukan bentuknya. Sejak 2011, PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) sudah menerapkan mekanisme Payment for Ecosystem Services (PES), yakni imbal jasa lingkungan dengan membayar penggunaan air dari DAS Peusangan serta mendukung reboisasi. WWF Indonesia menegaskan bahwa model ini telah memberi dampak positif baik pada kualitas lingkungan maupun kehidupan sosial masyarakat di sekitar. Jika model ini diperluas ke sektor migas, maka industri bukan hanya memberi kontribusi fiskal, tetapi juga tanggung jawab ekologis yang nyata.
Dahlan melihat ke depan dengan optimisme. Baginya, temuan Andaman bukan hanya tentang eksplorasi, tetapi peluang membangun generasi baru. “Andaman harus melahirkan Dahlan-Dahlan baru,” katanya. Ia mendorong lahirnya program pelatihan vokasional khusus untuk lulusan lokal agar siap masuk ke rantai industri migas, dari teknisi hingga manajemen. Dengan begitu, Aceh tidak lagi sekadar menyumbang sumber daya, melainkan juga menyumbang tenaga profesional berkelas dunia. Di saat yang sama, potensi hilirisasi gas bisa menghidupkan kembali industri PIM dan sektor petrokimia, membuka peluang produk bernilai tambah dan lapangan kerja lebih luas. Namun, strategi teknis ini hanya akan berarti bila sejalan dengan pemetaan sosial yang rutin dan komitmen ekologis yang konsisten. Dalam bahasa agama, pembangunan sejati adalah pembangunan yang menyambung maslahat duniawi dengan keberkahan ukhrawi.
Kini, pilihan ada di tangan kita. Aceh dapat mengulang masa lalu: mengejar produksi, membiarkan masyarakat jadi penonton, dan melupakan lingkungan. Atau, Aceh bisa menempuh jalan baru: menyatukan strategi industri yang rasional, rasionalitas sosial yang realistis, dan keberlanjutan lingkungan yang berakar pada nilai Islam. Aceh telah memiliki modal: infrastruktur eks-Arun, cadangan gas Andaman, jaringan dayah dan ulama, serta praktik imbal jasa lingkungan yang sudah terbukti. Semua itu adalah bahan dasar bagi arsitektur tata kelola baru yang inklusif, adil, dan lestari.
Mengelola migas secara adil adalah bagian dari ibadah sosial. Allah SWT mengingatkan dalam Al-Qur’an bahwa setiap amanah akan dimintai pertanggungjawaban. Jika sumber daya Aceh dikelola dengan adil, maka ia bukan sekadar angka dalam neraca perusahaan, melainkan ladang kebaikan yang memberi manfaat pada rakyat lintas generasi. Pilihan hari ini akan menjadi warisan esok. Apakah gas Andaman hanya akan menerangi pabrik-pabrik jauh di luar Aceh, atau juga menyinari rumah-rumah penduduk, sekolah, dayah, dan masjid di tanah ini?
Sejarah memberi peringatan, tetapi juga memberi peluang. Dengan menyatukan suara praktisi seperti Dahlan, refleksi sosial dari Irwandar, dan praktik ekologis seperti PES, Aceh dapat menapaki jalan baru yang tidak sekadar menambang energi bumi, tetapi juga menyalakan energi sosial dan spiritual. Inilah kesempatan untuk membuktikan bahwa bumi Aceh, dengan segala luka dan harapannya, mampu menjadi contoh bagi dunia: bahwa industri besar bisa berjalan seiring dengan nilai agama, budaya, dan keberlanjutan.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.