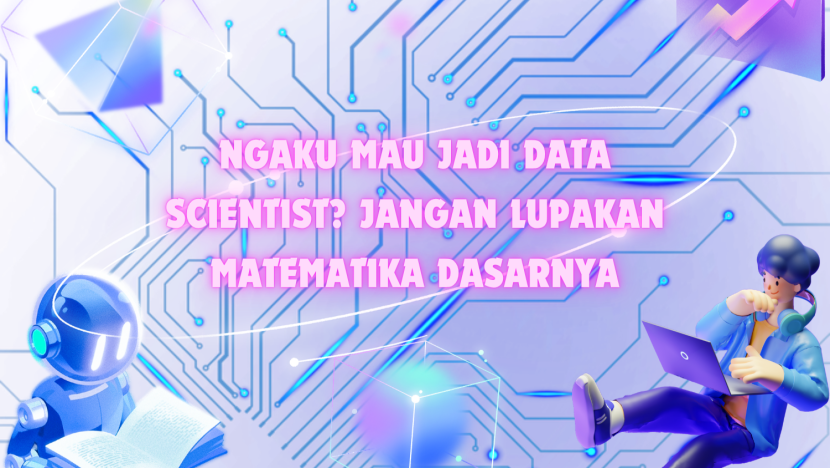Dr. H. Dana, M.E., M.I.Kom
Dr. H. Dana, M.E., M.I.Kom
Membaca Ulang Akar Demo Buruh
Agama | 2025-08-28 17:23:44
Indonesia kembali dihadapkan pada rangkaian persoalan yang seakan tidak ada habisnya. Setiap kali satu masalah mulai mereda, masalah baru sudah muncul menggantikannya. Realitas ini sesungguhnya mencerminkan sunnatullah kehidupan, bahwa selama manusia masih hidup di dunia, tantangan, konflik kepentingan, ketidakpuasan dan tuntutan keadilan akan selalu hadir. Kehidupan sosial-ekonomi tidak pernah berada dalam kondisi statis, melainkan senantiasa bergerak dinamis.
Demonstrasi buruh yang terjadi akhir-akhir ini, tidak bisa dipandang hanya sebagai ekspresi sesaat dari kelompok pekerja, melainkan sebagai gejala sosial yang sangat kompleks. Teriakan para buruh tentang upah yang layak, jaminan kerja, dan perlindungan masa depan, sesungguhnya merepresentasikan akumulasi kegelisahan panjang atas sistem ekonomi yang dirasa belum mampu menghadirkan keadilan. Ironisnya, pada saat yang sama sebagian wakil rakyat justru memperlihatkan sikap yang tidak peka terhadap realitas ini, sehingga jurang antara buruh sebagai rakyat dengan elit politik terlihat semakin melebar.
Dalam sistem ekonomi kapitalis, buruh sering diposisikan sekadar sebagai faktor produksi. Buruh dihitung dalam rumus biaya, diukur melalui efisiensi, dan bisa dipangkas bila dianggap mengurangi keuntungan. Itulah sebabnya ketika buruh menuntut hak yang lebih adil, ancaman yang kerap muncul adalah pemutusan hubungan kerja (PHK). Seolah-olah buruh hanyalah sebuah beban yang bisa dihilangkan kapan saja demi menjaga neraca laba perusahaan. Efisiensi diartikan sebagai upaya mencapai hasil maksimal dengan biaya minimal. Dalam praktiknya, itu berarti menekan biaya tenaga kerja, kontrak jangka pendek, outsourcing, bahkan pemutusan hubungan kerja massal dianggap sah demi menjaga keuntungan. Di atas kertas angka laba bisa meningkat, namun di lapangan, buruh justru semakin terhimpit.
Islam menghadirkan pandangan yang sangat berbeda. Dalam perspektif Islam, buruh bukanlah sekadar angka atau alat produksi, melainkan manusia yang memiliki martabat. Pekerja adalah subjek pembangunan, bukan objek yang bisa digeser sesuka hati. Nabi Muhammad SAW bersabda, “Allah Ta’ala berfirman, ada tiga jenis orang yang Aku menjadi musuh mereka pada hari kiamat seseorang yang bersumpah atas nama-Ku lalu mengingkarinya, seseorang yang menjual orang yang telah merdeka, lalu memakan hasil penjualannya (harganya) dan seseorang yang memperkerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya, namun tidak memberi upahnya” (HR Al-Bukhari). Hadits ini menunjukkan bahwa Islam menempatkan pekerja pada posisi yang mulia, dengan hak yang wajib dipenuhi tanpa penundaan.
Dalam ekonomi Islam, efisiensi tidak dipahami hanya sebatas angka laba, melainkan pada sejauh mana manfaat (maslahah) yang dihasilkan lebih besar daripada mudharat. Jika suatu kebijakan mengorbankan kesejahteraan pekerja, maka itu bukan efisiensi, melainkan kezhaliman. Islam menempatkan buruh bukan sekadar faktor produksi, tetapi sebagai manusia yang memiliki martabat dan hak yang harus dijaga.
Begitu pula dengan kesejahteraan. ekonomi kapitalis biasanya mengukurnya dengan angka-angka statistik indikator makro, seperti GDP per kapita atau daya beli. Namun angka-angka itu sering tidak mewakili kenyataan di lapangan, buruh yang bekerja penuh waktu tetap kesulitan mencukupi kebutuhan dasar. Sementara itu, Islam memandang kesejahteraan sebagai kondisi yang utuh, mencakup kecukupan materi, keadilan dalam distribusi, waktu istirahat yang layak, kesempatan beribadah, dan rasa aman akan masa depan.
Lebih jauh lagi, Islam memandang penyediaan lapangan kerja sebagai tanggung jawab sosial. Bahkan, sebagian ulama menyebut bahwa membuka kesempatan kerja termasuk fardhu kifayah, yaitu kewajiban kolektif yang harus dipenuhi oleh umat. Jika ada sebagian yang mampu melakukannya, maka kewajiban itu gugur bagi yang lain. Namun, bila tidak ada yang menyediakan, maka seluruh masyarakat menanggung dosa sosial karena membiarkan pengangguran dan kemiskinan merajalela.
Konsep fardhu kifayah inilah yang menjadi jembatan untuk memahami betapa besar tanggung jawab kolektif terhadap buruh. PHK semestinya tidak dijadikan senjata untuk menekan pekerja, karena penyediaan lapangan kerja bukan sekadar urusan untung-rugi bisnis, tetapi kewajiban moral dan spiritual. Di sinilah letak bedanya, ekonomi kapitalis menilai pekerja dari sisi produktivitas, sementara Islam menempatkan buruh dalam kerangka ibadah dan penghormatan terhadap kemanusiaan.
Lalu muncul pertanyaan, bagaimana konsep ini diterapkan jika banyak perusahaan di negeri ini dimiliki oleh non-Muslim? Di sinilah umat Islam perlu mengambil peran lebih besar. Menyediakan lapangan kerja tidak harus selalu menunggu negara atau menunggu modal besar, melainkan bisa dimulai dari dorongan umat untuk mendirikan usaha, koperasi, maupun industri kecil menengah yang mampu menyerap tenaga kerja. Kewirausahaan dalam Islam bukan sekadar mencari keuntungan, melainkan ibadah sosial yang memberi manfaat luas.
Dengan semangat fardhu kifayah, umat Islam didorong untuk menjadi pencipta lapangan kerja, bukan sekadar pencari kerja. Negara juga memiliki peran penting, yakni memastikan regulasi yang adil, mencegah eksploitasi, serta mendorong tumbuhnya usaha-usaha yang sesuai dengan prinsip keadilan. Apabila umat Islam mampu bangkit dengan kesadaran kolektif ini, maka penyediaan lapangan kerja akan menjadi bagian dari perjuangan bersama, bukan lagi beban segelintir pihak.
Pada akhirnya, demonstrasi buruh yang kita lihat hari ini seharusnya tidak dipandang semata sebagai konflik kepentingan antara pekerja dan pengusaha. Lebih dari itu, demo buruh adalah cermin kegagalan kolektif dalam menunaikan tanggung jawab sosial. Islam mengingatkan bahwa bekerja adalah hak asasi manusia, sementara menyediakan lapangan kerja adalah kewajiban bersama. Jika umat mampu menghidupkan kembali semangat fardhu kifayah dalam pembangunan ekonomi, maka buruh tidak lagi perlu turun ke jalan untuk memperjuangkan haknya, karena masyarakat sudah menempatkan mereka pada posisi yang mulia sejak awal.
Apakah kita akan terus membiarkan demonstrasi demi demonstrasi berlangsung sebagai cermin kegagalan sistem, ataukah kita berani beralih pada paradigma yang lebih adil, yang memuliakan buruh, dan menempatkan manusia di atas sekadar angka-angka keuntungan?
Wallahu a’lam bish-shawab
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.