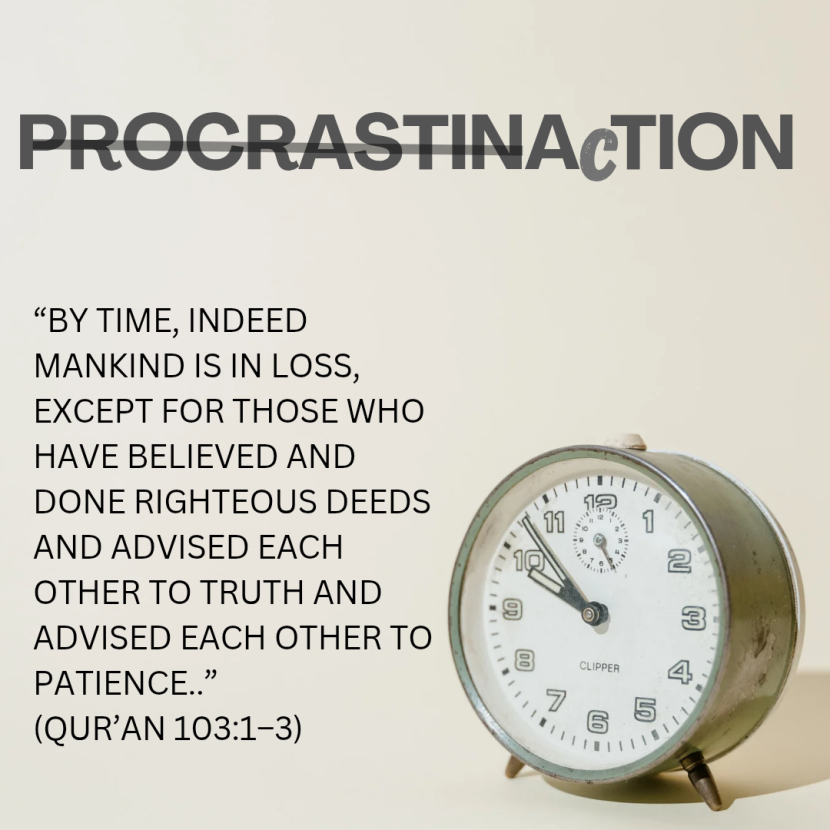Galuh Enggar
Galuh Enggar
Belenggu Sunyi: Krisis Eksistensi dan Kesepian Emosional dalam Novel Belenggu
Sastra | 2025-05-08 14:47:49
Belenggu (1938) karya Armijn Pane sering dibaca sebagai kisah cinta segitiga antara Sukartono, Tini, dan Yah. Namun, di balik lapisan permukaan itu, tersimpan tema yang sangat mendalam dan jarang dikupas: krisis eksistensial dan kesepian emosional yang membelenggu tokoh-tokohnya. Ketiganya bukan sekadar tokoh dalam kisah roman, melainkan simbol dari manusia modern Hindia Belanda yang terperangkap dalam kebingungan identitas, keterasingan, dan kehampaan batin.
Krisis Eksistensial: Ketika Identitas Tak Lagi Jelas
Tokoh Sukartono, seorang dokter yang dihormati masyarakat, pada dasarnya adalah individu yang menderita krisis eksistensial. Di permukaan, ia tampak mapan dan berhasil, tetapi dalam batinnya, ia kesepian, merasa tak dimengerti, dan kehilangan koneksi dengan dunia sekitarnya. Ia sering termenung, tidak puas dengan istrinya (Tini), dan kemudian mencari kenyamanan emosional pada Yah seorang perempuan yang secara sosial dianggap “tidak pantas”.
Dalam teori Viktor Frankl (Logotherapy), manusia tidak akan puas hanya dengan materi atau status, tetapi membutuhkan “makna” dalam hidupnya. Sukartono mengalami kehampaan makna. Ia menjalani hidup secara mekanis—memeriksa pasien, pulang, makan, dan menghadapi konflik dengan istrinya. Ketika ia mencoba menemukan makna dalam hubungan dengan Yah, ternyata itu pun hanya menjadi pelarian sementara.
Kehampaan dan Kesepian Emosional
Belenggu bukan hanya menggambarkan konflik sosial atau moral, tetapi juga penderitaan batin yang mendalam. Sukartono dan Tini hidup serumah tetapi terpisah batin. Mereka tidak lagi berkomunikasi sebagai pasangan. Yang tersisa hanyalah perasaan jengkel, kecewa, dan sunyi. Ini adalah gambaran klasik dari emotional loneliness kesepian bukan karena sendirian secara fisik, tetapi karena merasa tidak dipahami atau tidak terhubung secara emosional dengan orang terdekat.
Yah, di sisi lain, juga mengalami kesepian akut. Ia menjalani hidup sebagai perempuan yang tidak lagi diterima oleh masyarakat. Ia merindukan kedekatan, pelukan, dan pengakuan sebagai manusia yang layak dicintai. Oleh karena itu, meskipun ia tampak seperti “penggoda” dalam cerita, sesungguhnya ia adalah sosok yang rapuh dan haus kasih sayang.
Eksistensialisme dan Absurdnya Hidup
Dalam pandangan eksistensialisme Sartre, manusia bebas menentukan hidupnya, tetapi kebebasan itu membawa beban: kita harus bertanggung jawab atas pilihan kita. Sukartono terjebak dalam situasi ini. Ia ingin keluar dari belenggu pernikahannya yang kosong, tetapi ketika mencoba mencintai Yah, ia tetap merasa bersalah dan tidak menemukan kepuasan batin. Ia bebas, tetapi tidak bahagia.
Ini menciptakan absurditas hidup yang diteorikan Albert Camus: manusia mencari makna dalam dunia yang sebenarnya tidak menawarkan jawaban pasti. Sukartono terus mencari, tetapi setiap pilihan hanya menimbulkan luka baru. Dalam satu adegan, ia bahkan membandingkan dirinya dengan anjing di tempat sampah, menunjukkan betapa dalam perasaan terasing dan rendah dirinya.
Belenggu sebagai Simbol Batin
Judul Belenggu bukan sekadar metafora hubungan cinta yang rumit. Belenggu dalam novel ini adalah simbol dari segala batasan batin manusia: rasa tanggung jawab yang menghambat kebebasan, moralitas sosial yang menekan pilihan pribadi, dan suara hati yang terus mempertanyakan setiap keputusan.
Ketiga tokoh dalam novel ini hidup dalam “belenggu” psikologis: Sukartono dibelenggu oleh rasa bersalah dan kehampaan, Tini dibelenggu oleh idealisme emansipasi yang membuatnya jauh dari suami, dan Yah dibelenggu oleh masa lalu dan identitasnya sebagai perempuan “gagal”. Tak satu pun dari mereka yang benar-benar bebas—dan di situlah letak kekuatan tragis novel ini.
Kesimpulan
Belenggu adalah novel tentang manusia yang kesepian dan kehilangan arah. Dalam konteks Indonesia awal abad 20, novel ini mencerminkan keresahan kaum intelektual modern yang sedang mengalami transisi budaya, nilai, dan makna hidup. Dengan pendekatan eksistensial dan psikologis, novel ini mengajak kita merenung: bahwa belenggu paling berat bukanlah yang datang dari luar, melainkan dari dalam diri sendiri dari pertanyaan yang tak kunjung dijawab: siapa aku, mengapa aku hidup, dan apakah aku bahagia?
Referensi
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.