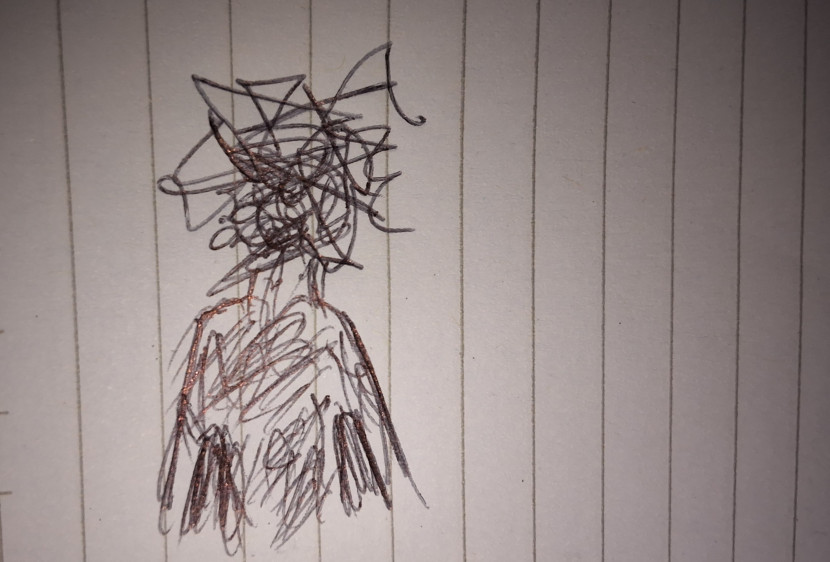Syahrial, S.T
Syahrial, S.T
Senja Terakhir di Tanjung Perak
Sastra | 2024-11-23 09:09:58
Riska memandang jauh ke arah dermaga Tanjung Perak yang mulai diselimuti kabut senja. Semburat jingga di langit berpadu dengan riak air laut yang berkilauan, menciptakan pemandangan yang biasanya akan membuatnya terpesona. Namun sore ini, keindahan itu justru terasa menyayat hati. Duduk di bangku kayu yang sudah dimakan usia, ia mengeluarkan secarik kertas dari dalam tasnya—surat terakhir dari Andika yang diterimanya pagi tadi. Aroma khas pelabuhan—campuran antara air laut, solar, dan makanan dari warung-warung sekitar—menari-nari di udara, mengingatkannya pada kencan pertama mereka di tempat ini tiga tahun lalu.
Jam di menara pelabuhan menunjukkan pukul 16.30 WIB, tepat tiga jam sebelum kapal yang membawa Andika ke Makassar akan berangkat. Suara deru mesin kapal dan teriakan para porter berbaur dengan detak jantungnya yang tak beraturan. Setiap detik yang berlalu terasa seperti jarum yang menusuk-nusuk dadanya, mengingatkan bahwa waktu kebersamaan mereka semakin menipis.
"Maafkan aku, Riska. Beasiswa ini adalah kesempatan sekali seumur hidup." Begitu kata Andika saat mengabarkan kepindahannya ke Makassar untuk melanjutkan studi kedokteran dua minggu lalu. Kalimat itu terus terngiang di telinga Riska, berputar seperti kaset rusak yang tak bisa dihentikan. Ia masih ingat bagaimana tangannya gemetar saat itu, bagaimana ia berusaha tersenyum meski hatinya remuk, bagaimana ia mencoba terlihat tegar meski air matanya nyaris tumpah.
Angin pesisir meniup helai-helai rambut Riska yang tak terikat, membawa aroma garam yang familiar ke hidungnya. Matanya memanas mengingat tiga tahun kebersamaan mereka yang harus berakhir karena jarak. Di kepalanya berputar kenangan-kenangan manis: tawa mereka di Taman Bungkul, berburu makanan di sepanjang jalan Kembang Jepun, atau sekadar duduk berdua di tepi pantai Kenjeran sambil memandang matahari terbenam. Surabaya-Makassar, bukan jarak yang dekat untuk hubungan jarak jauh di tahun 1997, di mana telepon masih menjadi barang mewah dan internet belum menjamah kehidupan sehari-hari.
Sesekali matanya melirik ke arah gerbang pelabuhan, berharap menemukan sosok yang familiar di antara hiruk-pikuk orang yang berlalu-lalang. Setiap kali pintu taksi terbuka, jantungnya berdegup kencang, berharap Andika akan muncul. Tapi setiap kali pula, yang keluar adalah orang lain, membuat harapannya jatuh seperti ombak yang pecah di bebatuan pelabuhan.
"Mbak pesan apa?" Sebuah suara mengejutkan Riska dari lamunannya. Seorang pedagang asongan dengan gerobak berisi minuman dingin berhenti di depannya. Wajahnya yang ramah dihiasi senyum tulus, kontras dengan kegalauan yang sedang berkecamuk di hati Riska.
"Air mineral saja, Mas," jawab Riska pelan, suaranya sedikit serak karena menahan tangis.
"Sepertinya Mbak sedang ada masalah?" tanya pedagang itu sambil menyerahkan sebotol air mineral. Matanya memancarkan ketulusan yang membuat Riska merasa aman untuk berbagi.
Riska tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. "Tidak apa-apa, Mas. Hanya sedang menunggu seseorang." Ia menggigit bibirnya, berusaha menahan gelombang emosi yang mengancam akan meledak.
"Oh, saya Dani," ujar pedagang itu memperkenalkan diri. Suaranya yang tenang membawa ketenangan tersendiri di tengah kekacauan pikiran Riska. "Sudah tiga tahun jualan di pelabuhan ini. Sering lihat orang-orang dengan ekspresi seperti Mbak—menunggu kepergian atau kedatangan seseorang yang special."
Ada sesuatu dalam cara Dani berbicara yang membuat Riska merasa nyaman. Mungkin karena senyumnya yang tulus, atau karena matanya yang memancarkan kebijaksanaan di balik usianya yang masih muda.
"Saya Riska," balasnya. "Pacar saya akan berangkat ke Makassar malam ini. Kuliah kedokteran."
"Ah, pantas. Tapi Mbak Riska tahu tidak? Setiap perpisahan itu seperti pintu yang terbuka. Di baliknya selalu ada hal baru yang menunggu."
Riska mengernyitkan dahi. "Maksudnya?"
"Tiga tahun lalu, saya juga ditinggal pacar saya kuliah ke Jogja. Rasanya seperti dunia runtuh. Tapi kalau dia tidak pergi, saya mungkin tidak akan pernah memberanikan diri memulai usaha sendiri. Sekarang, selain jualan di sini, saya juga punya warung kopi kecil di Kenjeran."
Jam di menara berdentang lima kali. Riska melirik arlojinya—masih ada dua setengah jam sebelum keberangkatan Andika.
"Saya permisi dulu, Mbak. Masih harus keliling," pamit Dani. "Jangan terlalu sedih. Kadang Tuhan punya rencana yang lebih indah di balik setiap perpisahan."
Sepeninggal Dani, Riska membuka kembali surat dari Andika. Ada sebaris kalimat yang belum sempat dibacanya tadi pagi: "Mungkin ini bukan akhir, tapi awal dari sesuatu yang baru untuk kita berdua."
Pukul 18.45 WIB, Andika akhirnya muncul dengan koper besarnya. Wajahnya terlihat lelah, tapi matanya berbinar saat melihat Riska.
"Maaf membuatmu menunggu lama," ujarnya.
Riska menggeleng. "Tidak apa-apa. Justru aku bersyukur datang lebih awal. Ada seseorang yang mengajarkanku arti dari sebuah perpisahan."
"Oh ya? Siapa?"
"Seorang pedagang asongan bernama Dani. Dia bilang, setiap perpisahan adalah pintu menuju hal baru yang lebih baik."
Andika tersenyum. "Dia benar. Ini bukan akhir, Riska. Ini awal yang baru—untukmu, untukku."
Riska mengangguk, merasakan beban di hatinya mulai terangkat. "Berjanjilah untuk meraih mimpimu, Andika. Aku juga akan mulai mengejar mimpiku sendiri."
"Kamu mau melanjutkan kuliah desain grafismu?"
"Ya, dan mungkin membuka studio kecil. Entahlah, tiba-tiba aku merasa semua mungkin terjadi."
Pengumuman keberangkatan kapal mulai terdengar. Andika memeluk Riska untuk terakhir kalinya.
"Terima kasih untuk tiga tahun yang indah," bisik Riska.
"Terima kasih sudah mengajarkanku arti cinta yang sesungguhnya," balas Andika.
Saat kapal mulai bergerak meninggalkan dermaga, cahaya lampu-lampu kapal memantul di air yang gelap, menciptakan tarian cahaya yang menenangkan. Riska tidak lagi merasakan kesedihan yang mencekik. Air matanya mengalir, tapi kali ini bukan air mata kepedihan—melainkan air mata penerimaan dan harapan. Di matanya, cahaya-cahaya pelabuhan yang mulai menyala tampak seperti bintang-bintang yang menuntun jalan menuju lembar baru dalam hidupnya.
Burung-burung camar terbang rendah di atas air, mengiringi kepergian kapal dengan teriakan mereka yang khas. Langit senja telah berganti menjadi kanvas gelap bertabur bintang, seolah alam turut memberi restu pada perpisahan ini. Riska menghirup dalam-dalam udara malam yang mulai terasa dingin, membiarkan aroma laut mengisi paru-parunya—dan untuk pertama kalinya hari itu, ia bisa bernapas dengan lega.
Di kejauhan, ia melihat gerobak Dani yang perlahan menghilang di antara kerumunan, seperti malaikat yang telah menyelesaikan tugasnya. Riska tersenyum, menyadari bahwa terkadang guru terbaik dalam hidup datang dalam bentuk yang tak terduga—bahkan dari seorang pedagang asongan yang bijak di sore yang sendu di Pelabuhan Tanjung Perak. Malam itu, di bawah langit Surabaya yang bertabur bintang, Riska belajar bahwa setiap akhir adalah awal yang baru, dan setiap perpisahan membawa hadiah tersendiri—hadiah berupa kesempatan untuk tumbuh dan menemukan diri sendiri.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.