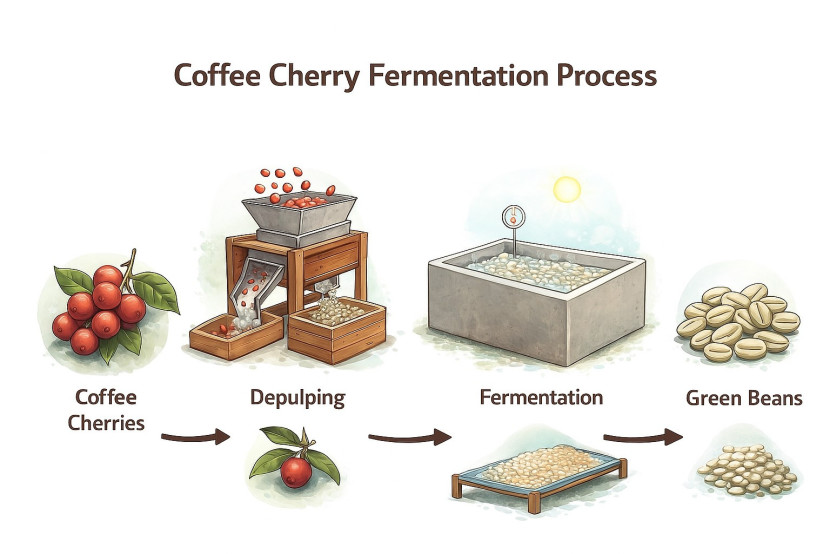Syahrial, S.T
Syahrial, S.T
Sepotong Roti dan Secangkir Kopi
Sastra | 2024-10-25 05:04:19
Waktu menunjukkan pukul enam pagi ketika Adi membuka matanya. Sinar matahari yang menyusup melalui celah gorden menjadi alarm alaminya setiap hari. Dia bangun, meregangkan tubuh, dan berjalan menuju dapur kontrakan kecilnya di lantai dua sebuah rumah tua di kita Manggar. Suara pedagang sayur yang mulai berkeliling dan deru motor yang berlalu-lalang di depan rumahnya menjadi musik pengiring pagi yang sudah begitu familiar di telinganya.
Rutinitas paginya selalu sama: menyeduh secangkir kopi hitam dan memanggang sepotong roti tawar. Sederhana, terlalu sederhana malah. Namun pagi ini, entah mengapa, pikirannya melayang jauh ke masa lalu, ke momen-momen yang dulu dia anggap biasa saja. Mungkin karena semalam dia bermimpi tentang ayahnya, atau mungkin karena usianya yang semakin mendekati kepala empat membuatnya lebih sering merenung.
Sepuluh tahun yang lalu, saat masih tinggal di rumah orang tuanya, sarapan pagi selalu menjadi ritual yang ramai. Ibunya akan bangun paling pagi, menyiapkan nasi goreng atau bubur ayam. Wangi bawang goreng dan kecap manis akan menguar dari dapur kecil mereka, membangunkan seluruh penghuni rumah tanpa perlu alarm. Ayahnya akan duduk di kursi favoritnya, kursi rotan tua yang selalu berderit ketika diduduki, membaca koran sambil sesekali berkomentar tentang berita terkini. Adiknya akan tergesa-gesa sarapan karena selalu bangun kesiangan, hampir tersedak karena makan terlalu cepat, membuat ibu mengomelinya setiap pagi.
Dulu, Adi sering mengeluh tentang menu sarapan yang itu-itu saja. Dia bahkan sering melewatkan sarapan dengan alasan terburu-buru atau diet. "Nasi goreng lagi, Bu?" keluhnya saat itu, tidak menyadari betapa berharganya moment-moment itu. Sekarang, di usianya yang ke-35, dengan rutinitas sebagai staff administrasi di sebuah perusahaan distributor, dia justru merindukan kesederhanaan itu. Merindukan ocehan ibunya yang memaksa mereka menghabiskan sarapan, merindukan komentar-komentar ayahnya tentang politik yang dulu dianggapnya membosankan.
Uap dari kopi hitamnya mengepul, mengingatkannya pada aroma kopi tubruk buatan ibunya. Tidak seperti kopi sachet instan yang kini dia nikmati, kopi tubruk ibunya adalah kopi biasa yang dibeli di warung kelontong. Tapi entah mengapa, rasanya selalu sempurna di lidahnya. Mungkin karena ibunya selalu tahu takaran yang pas untuknya - tidak terlalu manis, tidak terlalu pahit. Atau mungkin karena kopi itu selalu disajikan dengan kasih sayang yang tak terucap.
Roti panggang di piringnya mengingatkannya pada bekal yang selalu disiapkan ibunya saat dia masih sekolah. Sandwich sederhana dengan selai stroberi atau cokelat, yang sering dia tukar dengan jajan di kantin. Kadang dia malu karena teman-temannya membawa bekal yang lebih mewah - ayam goreng, nugget, atau sushi. Sekarang, dia bisa membeli makanan di food court mall setiap hari, tapi tak ada yang bisa menandingi rasa sandwich buatan ibu. Bahkan roti gosong yang kadang tidak sengaja terlalu lama dipanggang oleh ibunya terasa lebih nikmat dari menu-menu mahal yang pernah dia coba.
Adi menghela napas panjang. Matanya menerawang ke luar jendela, memandang deretan rumah dan warung-warung yang mulai buka. Para tetangga mulai terlihat keluar rumah, ada yang menyapu halaman, ada yang hendak berangkat kerja. Dulu, pemandangan dari rumahnya hanyalah deretan rumah tetangga dan sebuah pohon mangga tua di halaman. Pohon yang sama tempat dia dan adiknya sering memanjat dan bermain, meski selalu dimarahi ibu karena takut mereka jatuh. Setiap musim mangga tiba, mereka akan berlomba siapa yang bisa memetik mangga paling banyak. Kadang mereka juga bersembunyi di balik pohon itu saat bermain petak umpet dengan anak-anak tetangga.
Setiap akhir pekan, ayahnya akan mengajak keluarga piknik sederhana di taman kota atau sekadar makan bakso di warung langganan. Uang jajan mereka memang pas-pasan, tapi ayahnya selalu menyisihkan sedikit untuk membeli es krim cornetto yang akan mereka bagi berempat. Tidak ada yang istimewa, tapi tawa dan canda selalu menghiasi setiap momen. Kini, akhir pekannya diisi dengan lembur mengerjakan laporan atau sekadar tidur seharian karena kelelahan. Kadang dia menghabiskan waktu di sendirian, menonton film atau makan di restoran cepat saji, tapi entah mengapa semua terasa hambar.
Jam dinding menunjukkan pukul setengah tujuh. Sebentar lagi dia harus berangkat ke kantor. Perjalanan yang akan memakan waktu hampir satu jam. Gajinya memang pas-pasan, cukup untuk hidup sederhana. Tapi entah mengapa, pikirannya justru kembali pada momen ketika dia menerima gaji pertamanya sebagai guru les privat semasa kuliah. Nominal yang kecil, tapi kebanggaan yang dia rasakan saat bisa membelikan ibunya sebuah daster baru tak ternilai harganya. Wajah berbinar ibunya saat menerima hadiah itu masih terekam jelas dalam ingatannya.
Adi menyesap kopi terakhirnya yang sudah mulai dingin. Matanya menatap foto keluarga yang terpajang di dinding ruang makan kecilnya. Foto itu diambil lima tahun lalu, saat terakhir kali mereka berkumpul lengkap sebelum ayahnya meninggal. Mereka tampak bahagia, berdiri di depan rumah tua mereka di Bandung. Rumah yang kini sudah dijual untuk membiayai pengobatan ayahnya. Dalam foto itu, mereka semua tersenyum lebar, tidak menyadari bahwa itu akan menjadi foto keluarga terakhir mereka yang lengkap. Ayahnya mengenakan kemeja favoritnya, kemeja biru yang sudah agak pudar tapi selalu dipakainya di acara-acara penting.
Air mata menggenang di sudut matanya. Bukan karena sedih, tapi karena baru sekarang dia menyadari bahwa kebahagiaan sejati ternyata tersembunyi dalam hal-hal sederhana yang dulu dia anggap biasa. Dalam secangkir kopi tubruk buatan ibu, dalam sandwich bekal sekolah, dalam tawa di bawah pohon mangga tua, dalam piknik sederhana di taman kota. Dalam celotehan ayahnya tentang politik, dalam omelan ibunya tentang kamar yang berantakan, dalam pertengkaran kecil dengan adiknya memperebutkan remote TV.
Dia meraih ponselnya, mencari nomor ibunya di daftar kontak. Sudah tiga bulan mereka tidak bertemu karena biaya transportasi yang mahal dan waktu libur yang terbatas. Mungkin sudah saatnya dia menyisihkan sedikit uangnya untuk pulang, meski hanya untuk menikmati secangkir kopi tubruk dan mendengarkan cerita-cerita lama ibunya. Untuk memeluk ibunya yang semakin renta, untuk mengunjungi makam ayahnya, untuk duduk di bawah pohon mangga tua itu sekali lagi.
Karena kini dia paham, bahwa kebahagiaan tidak selalu hadir dalam bentuk gaji besar atau jabatan tinggi. Terkadang, kebahagiaan justru bersembunyi dalam hal-hal kecil yang kita anggap remeh. Hal-hal yang bila sudah berlalu, akan kita rindukan dan sadari betapa berharganya. Dalam rutinitas sederhana yang dulu kita keluhkan, dalam momen-momen biasa yang ternyata luar biasa.
Adi beranjak dari kursinya, bersiap menghadapi hari dengan pemahaman baru. Bahwa mulai hari ini, dia akan lebih menghargai setiap momen sederhana dalam hidupnya. Karena siapa tahu, sepuluh tahun lagi, momen-momen inilah yang akan dia rindukan.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.