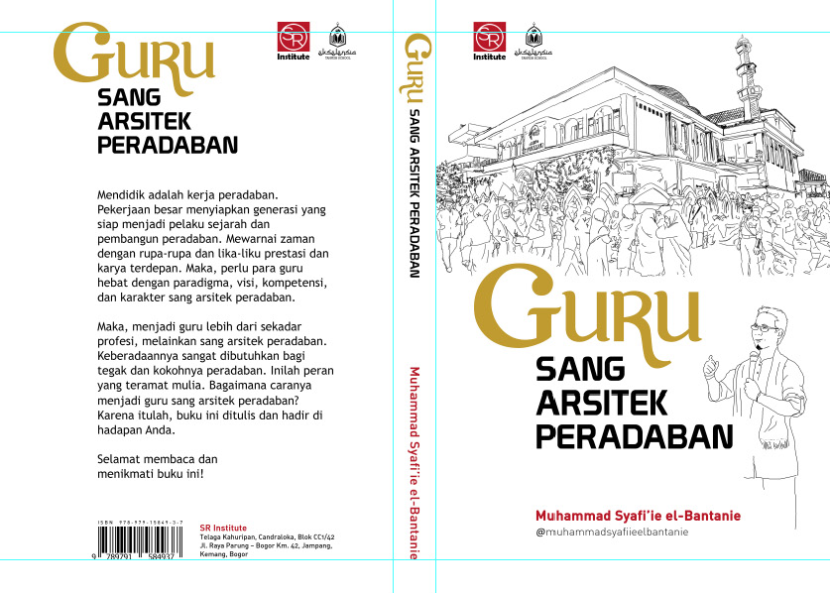June Cahyaningtyas
June Cahyaningtyas
Pendidikan Lingkungan, Dulu dan Sekarang
Eduaksi | 2024-08-20 21:19:42Puluhan tahun berlalu sejak pendidikan Lingkungan dipromosikan di tahun 1977 dan diubah namanya menjadi Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan (Education for Sustainable Development/ESD) di tahun 2002, namun dunia bisa melihat ketidakefektifannya. Fenomena perubahan iklim dan pemanasan global adalah buktinya. Di ranah pendidikan, upaya memperbaikinya tentu telah dilakukan, tapi sampai sejauh mana efektivitasnya? Mari kita cermati.
Sampai dengan pandemi Covid-19 terjadi, upaya penyebaran informasi merupakan gambaran dari pendekatan pendidikan, termasuk Pendidikan Lingkungan, di sekolah-sekolah publik. Tidak hanya itu, di ruang-ruang publik, kita disuguhi pemandangan tempat sampah berwarna-warni, masing-masing dengan fungsi penampungan jenis sampah yang berbeda. Namun, sebagaimana kita bisa rasakan sendiri dampaknya, membangun kesadaran melalui penyebaran informasi tanpa praktik yang nyata adalah angan-angan belaka. Lihat saja bagaimana kita terbiasa mencampur aduk sampah sisa makanan dengan sampah kemasan plastik, padahal yang satu mudah terurai dan yang lainnya sulit terurai.
Upaya untuk mengoreksi pendekatan pendidikan yang menganggap pemahaman pengetahuan dapat dicapai melalui transmisi informasi dari pendidik kepada peserta didik pun kemudian dilakukan dengan memasukkan kegiatan praktik ke dalam proses pembelajaran di sekolah. Hal ini berlaku pula untuk kegiatan pembelajaran lingkungan, yang dalam penerapannya banyak bergantung pada Program Adiwiyata. Program yang diinisiasi Kementerian Lingkungan Hidup di tahun 2006 ini telah banyak diikuti sekolah-sekolah di Indonesia, baik yang berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun Kementerian Agama.
Setidaknya ada empat instrumen pokok yang digunakan untuk menentukan penerapan program Adiwiyata di sekolah, yakni kebijakan sekolah, kurikulum belajar, kegiatan pendukung, serta sarana prasarana. Pertama, kebijakan yang berwawasan lingkungan, yang dikaitkan dengan visi dan orientasi sekolah dalam memajukan SDM yang berwawasan lingkungan, mengalokasikan anggaran untuk kegiatan lingkungan, ataupun menerapkan upaya hemat energi. Kedua, pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan, yang dilakukan mengembangkan model pembelajaran praktik dan lintas disiplin yang mendorong pengetahuan dan kesadaran lingkungan hidup, serta menekankan penghargaan atas budaya dan keterlibatan sekolah pada penyelesaian masalah di lingkungannya. Ketiga, kegiatan pendukung dilakukan dengan menyediakan kegiatan ekstrakulikuler di sekolah serta melakukan aksi lingkungan dengan mitra sekolah. Keempat, pengelolaan sarana pendukung sekolah yang ramah lingkungan dilakukan dengan mendorong upaya penghematan, menyediakan akses makanan sehat, dan mengembangkan sistem pengelolaan sampah.
Namun, sejak tahun 2010, lewat penelitian etnografis yang dilakukan pada sekolah di berbagai kota di Indonesia, sejumlah sarjana telah memperingatkan bahwa pengadopsian kegiatan Adiwiyata kerap kali justru membawa sekolah terjebak pada upaya-upaya administratif belaka. Alih-alih dimaknai sebagai tanggung jawab yang perlu dijabarkan dalam kebijakan dan program yang terstruktur dan terarah, pengadopsian Adiwiyata lebih sering berhenti di tingkat pengakuan atau penghargaan atas kemampuan menajerial sekolah. Sementara korelasi di antara pengadopsian Adiwiyata di sekolah dengan dorongan warga sekolah untuk berperilaku ramah lingkungan tidak benar-benar dapat dibuktikan.
Sejak awal 2000an, banyak sarjana setuju bahwa ketidakefektifan pendidikan lingkungan di sekolah-sekolah publik di dunia muncul dari sistem pendidikan itu sendiri, yang kesulitan untuk membebaskan diri dari cengkeraman sistem ekonomi global. Di Indonesia, kita bisa melihatnya dari ketundukan kurikulum pada pasar kerja, orientasi pendidikan untuk menciptakan daya saing ekonomi, serta fokus pembelajaran pada kemampuan kognitif abstrak. Bahkan, jika kita cukup jeli, kita juga bisa melihatnya dari bagaimana buku-buku teks pelajaran dan pidato pemerintah selalu mengelu-elukan sumber daya alam Indonesia yang kaya melalui pernyataan “Indonesia, penghasil minyak sawit utama di dunia” atau “Indonesia, negeri yang kaya bahan tambang,” dan “Indonesia, negeri yang kaya dengan wisata alam”, seakan-akan seluruh kekayaan itu akan terus ada dan tidak akan habis dimanfaatkan. Padahal, semua ucapan itu tidak lebih dari mantra-mantra yang dirapal untuk melenakan kita sebagai pendengarnya, selagi menormalisasi eksploitasi alam yang tengah terjadi. Itu artinya, program apa pun yang ditawarkan, perubahan metode dan kurikulum apa pun yang hendak diterapkan, selama tidak ada perubahan pada orientasi pendidikan untuk melestarikan kehidupan dan menjaga hak masa depan, maka akan sulit bagi kita untuk mengharapkan fungsi kritis dari pendidikan--dan munculnya alternatif--terhadap sistem pasar.
Namun, tidak ada pendidikan yang benar-benar bisa berjalan sendiri. Pendidikan, yang berpusat pada generasi masa depan, selalu memerlukan teladan dari kebijakan-kebijakan yang dibuat generasi sebelumnya. Tidak adil rasanya, menuntut generasi masa depan untuk membangun sikap dan perilaku hidup lestari, jika generasi pendahulunya justru mengeluarkan kebijakan eksploitasi alam besar-besaran dan bersikap sekehendak hati. Sampai kapan mau begini?

June Cahyaningtyas
Dosen, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional UPN Veteran Yogyakarta
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.