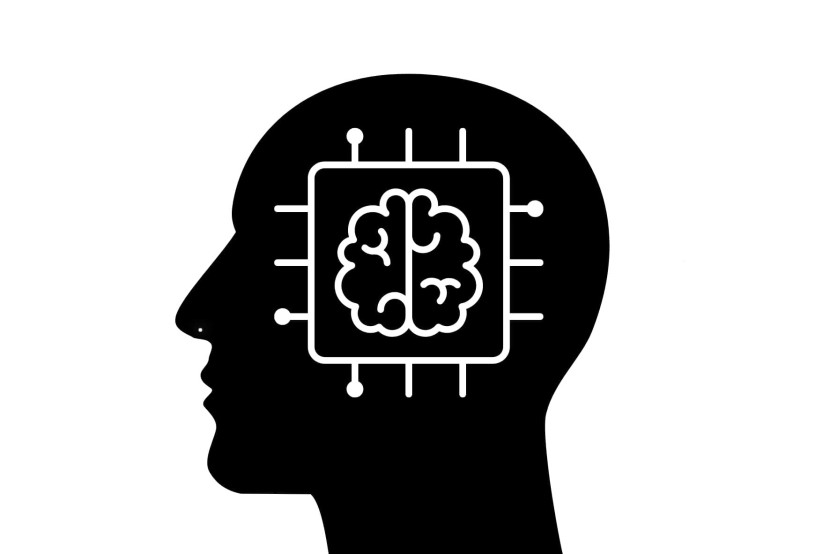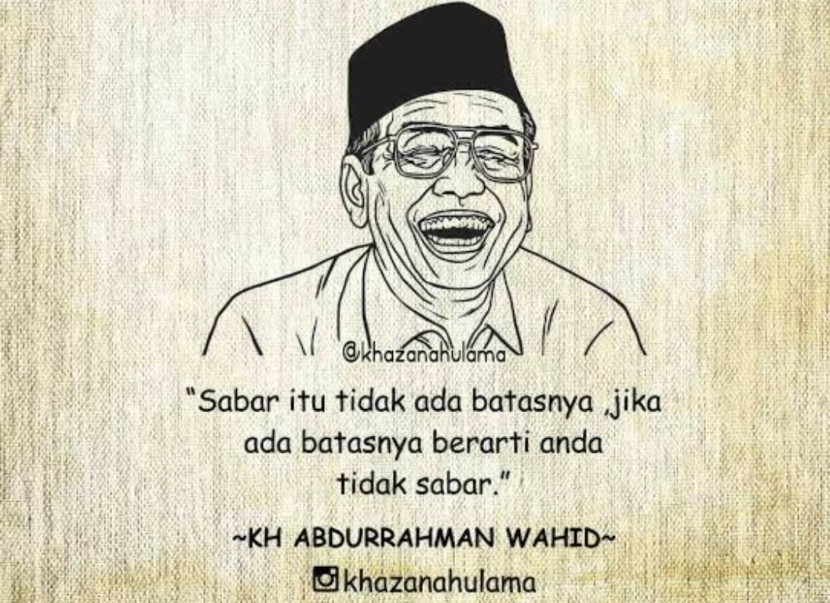Muhammad Ivan
Muhammad Ivan
Masa Depan Berita: Peran dan Tantangan AI dalam Jurnalisme Investigasi
Teknologi | 2023-08-20 16:37:15Dalam sebuah pernyataan di tahun 2015, Presiden Propublica Richard Tofel, menyebut bahwa revolusi digital telah mengubah, bahkan bisa disebut menghancurkan model bisnis yang dihasilkan oleh hampir semua jurnalisme berkualitas pada seperempat abad setelah Watergate. Menurutnya ini adalah masalah yang sangat akut untuk jurnalisme investigatif karena sebagian besar jurnalisme investigatif terbaik diproduksi oleh surat kabar.
Sebagaimana dicontohkan Tofel saat kejadian Badai Sandi, bahwa Red Cross yang mengatakan kepada wartawan ProPublica bahwa tindakan yang diambil oleh badan amal internasional sebagai tanggapan atas Badai Sandy merupakan serangkaian rahasia dagang. Sebagai tanggapan, ProPublica menempatkan dua wartawan penuh waktu dan bekerja sama dengan NPR (National Public Radio) untuk meluncurkan penyelidikan yang pada akhirnya menuduh Red Cross dari donor yang menyesatkan tentang penggunaan kontribusi mereka, mengalihkan kendaraan tanggap darurat untuk keperluan hubungan masyarakat, membuang 30% dari makanannya pada hari-hari awal setelah badai, dan mengirimkan truk kosong hanya untuk dilihat.
 Alexa dari Pixabay" />
Alexa dari Pixabay" />
Jelas, jurnalisme investigatif mungkin menjadi salah satu cara paling efektif untuk mencegah korupsi dan mengungkapkan kesalahan di seluruh masyarakat, dan analisis terbaru menunjukkan bahwa itu salah satu yang paling hemat biaya (Hamilton, 2016). Ruang berita surat kabar mungkin menyusut, tetapi mereka telah mendapat manfaat dari bekerja dalam kemitraan dengan startup yang didedikasikan semata-mata untuk pelaporan investigasi jangka panjang. Ini termasuk organisasi-organisasi Inggris seperti Bureau of Investigative Journalism (BIJ) dan Centre for Investigative Journalism. BIJ bekerja dengan kelompok media nasional untuk menghasilkan cerita yang sangat penting.
Peran Artificial Intellegence
David Kaplan mengamati bahwa jurnalis investigatif dapat memiliki efek jera, seperti orang-orangan sawah, serta efek pengawas, mengungkap kejahatan yang faktualitasnya tidak dapat disangkal. Dalam era digital, peran artificial intellegence (AI) tak dapat diabaikan. Terkhusus investigasi diharapkan menjalankan tanggung jawab jurnalistik yang menekankan pada disiplin verifikasi, menyajikan informasi kepada pembaca dengan cara yang jelas dan dapat dimengerti, dan untuk menjelaskan validitasnya.
Sementara semua jurnalisme yang baik harus diperiksa fakta dan dikontekstualisasikan, jurnalis investigasi adalah "kekuatan khusus" dari profesi ini. Mereka dikerahkan untuk lebih dalam dan sistematis ke dalam masalah daripada rekan kerja mereka (Hume, 2017). Salah satu hal yang banyak membedakan in-depth reporting dan investigative reporting adalah ada atau tidak adanya hipotesis (Harsono, 1999).
Idenya adalah bahwa AI akan mengurangi biaya produksi jurnalisme investigatif dengan mengganti beberapa jenis tenaga kerja manusia yang membosankan atau mahal dengan perhitungan murah. Sudah menjadi fakta internasional bahwa Global Investigative Journalism Network Executive Director David E. Kaplan’s definitive 2013 survey for the Center for International Media Assistance, Global Investigative Journalism: Strategies for Support (CIMA, January 14, 2013) menyimpulkan bahwa hanya 2% dari hampir $ 500 juta yang dihabiskan untuk bantuan media internasional setiap tahun digunakan untuk jurnalisme investigatif. Dia prihatin bahwa para donor mungkin begitu tertarik pada perangkat digital dan data baru yang menarik sehingga mereka mungkin gagal untuk mendukung pelaporan investigasi sistematis, yang juga membutuhkan elemen manusia, untuk menggali rahasia menggunakan teknik forensik, dan memberikan makna dan konteks.
María Teresa Ronderos (GIJN, 2019) mengemukakan bahwa perkembangan ini membuat banyak orang dalam profesi jurnalistik khawatir. Kecerdasan Buatan (AI) akan meninggalkan mereka tanpa pekerjaan. Tetapi, ketimbang takut akan hal itu, jika jurnalis merangkul AI maka itu akan membantu pekerjaan jurnalistik yang semakin kompleks, mengglobal dan kaya informasi (GIJN, 2019).
Menurut Laporan Tow Center 2017, beberapa outlet media di Amerika Serikat sudah menggunakan AI untuk melakukan pengecekan fakta. Reuters, misalnya, menggunakan Pelacak Berita untuk melacak berita terbaru di media sosial dan memverifikasi integritas tweet. Serenata de Amor, sekelompok penggemar teknologi dan jurnalis dari Brasil, menggunakan robot bernama Rosie untuk melacak setiap penggantian yang diklaim oleh anggota Kongres negara itu dan menyoroti alasan yang membuat beberapa pengeluaran menjadi mencurigakan (GIJN, 2019).
Ada banyak cara lain di mana algoritma membantu jurnalis, mulai dari membuat potongan video yang kasar, hingga mengenali pola suara dan mengidentifikasi wajah di tengah kerumunan. Mereka dapat diprogram untuk mengobrol dengan pembaca (chatbots) dan menjawab pertanyaan.
Sampai beberapa tahun yang lalu, pada dasarnya ada tiga model jurnalisme investigatif. Ini termasuk 1) wartawan di organisasi berita yang mapan, seperti tim Spotlight Boston Globe; 2) tim pemogokan kecil yang didanai secara independen yang bekerja dengan media arus utama terutama untuk menyebarkan berita, seperti pekerjaan ProPublica dengan The New York Times; dan 3) organisasi nirlaba independen yang mempublikasikannya sendiri. Dan sekarang ada model keempat: jaringan jurnalis yang kuat dan terkoordinasi ini, seperti Pusat Internasional untuk Jurnalisme Investigasi yang berpusat di Washington dan Proyek Pelaporan Kejahatan dan Korupsi yang Terorganisir (OCCRP) di Sarajevo. Global Investigative Journalism Network (GIJN) mendukung keempat jenis jurnalis investigasi, tetapi memiliki dampak khusus dengan model ketiga dan keempat, di mana organisasi nirlaba bekerja baik secara mandiri maupun dalam jaringan lintas batas, menciptakan paparan seperti Panama Papers yang dapat menjadi penting "secara lokal," yaitu, baik secara lokal maupun global. Saat ini, Global Investigative Journalism Network (GIJN) telah berkembang menjadi jaringan pendukung pengembangan kapasitas dari 145 organisasi jurnalisme investigasi nirlaba di 62 negara.
Tren Media Sosial dan Hoaks
Dari laporan berjudul "Essential Insights Into Internet, Social Media, Mobile, and E- Commerce Use Around The World" yang diterbitkan tanggal 30 Januari 2018, dari total populasi Indonesia sebanyak 265,4 juta jiwa, pengguna aktif media sosialnya mencapai 130 juta dengan penetrasi 49 persen. Data tambahan dalam buku The State of Social Media and Messaging in Asia Pacific: Trends and Statistics (2017) menunjukkan bahwa tiga dari empat orang Indonesia menggunakan Internet juga menggunakan Facebook. (Angka itu bahkan lebih tinggi sebagai persentase dari total pengguna media sosial di Indonesia - 94%). Ini adalah salah satu penetrasi Facebook tertinggi tingkat di Asia Tenggara dan peringkat Indonesia (dengan 78 juta Facebook pengguna) keempat dalam pengguna Facebook global berdasarkan negara.
Tren saat ini, media sosial telah menjadi platform media komunikasi yang digemari masyarakat. Jejaring sosial seperti whatsapp, facebook, twitter, dan youtube hanya beberapa dari banyak aplikasi komunikasi yang bertebaran dalam jagad internet. Jejaring tersebut mempertemukan teman lama yang bertahun-tahun tak berkabar, hingga menyapa teman baru dengan keunikannya masing-masing. Dengan jejaring sosial, kita memperbaharui ilmu pengetahuan hingga mengupdate perkembangan berita-berita terkini, dalam dan luar negeri.
Dengan jumlah akun aktif pengguna secara global, yakni Facebook 1,9 milyar, WhatApp 1,2 milyar, YouTube 1 milyar, Facebook Massenger 1 milyar, Instagram 600 juta, Tumblr 550 juta, dan Twitter 319 juta. Dengan kekuatan jumlah seperti ini, media sosial merupakan ladang surga bagi pedagang, ladang popularitas untuk mereka yang ingin cepat tenar, dan ladang komodifikasi bagi penebar berita bohong (hoaks) yang sangat eksplosif merusak masyarakat.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ‘hoaks’ adalah ‘berita bohong.’ Dalam Oxford English dictionary, ‘hoaks’ didefinisikan sebagai ‘malicious deception’ atau ‘kebohongan yang dibuat dengan tujuan jahat’. Pengelabuan (deception) ini tidak lebih berfungsi hanya sebagai sarana perpanjangan tangan kelompok tertentu untuk mencetak “keuntungan” sebesar-besarnya. Apalagi dalam konteks politik, hoaks tidak semata muncul dari hasrat individu belaka, melainkan dibuat secara teroganisir untuk menjelek-jelekan pihak lain. Arena perpolitikan merupakan hajatan yang sangat rentan hoaks. Di negara semaju Amerika pun, hoaks akan tetap berkibar sembari pemerintah dan masyarakat terus bersinergi memberantas berita dan informasi yang tak dapat dipertanggungjawabkan.
Kebenaran adalah tunggal atau tidak abu-abu, namun kebohongan dapat menjadi kebenaran asalkan sesuai dengan logika dan harapan yang dibohongi. Era ini disebut Post-Truth (paska kebenaran). Era paska kebenaran merupakan suatu masa di mana masyarakat lebih terpengaruh dengan opiniopini publik berdasarkan daya tarik emosionalnya, tanpa memandang apakah fakta itu nyata atau obyektif. Dalam kata lain, masyarakat hanya ingin mengetahui apa yang sesuai dengan ketertarikan emosionalnya semata.
‘hoaks’ atau ‘fake news’ bukan sesuatu yang baru dan sudah muncul pada zaman Johannes Gutenberg menciptakan mesin cetak pada tahun 1439. Sebelum zaman internet, ‘hoaks’ bahkan lebih berbahaya dari sekarang karena sulit untuk diverifikasi. Disinilah, peran
pemerintah, instansi pendidikan, akademisi, dan masyarakat serta netizen yang masih memiliki hati nurani untuk bersinergi membentengi negeri ini dari hoaks. Pendekatan lunak melalui literasi dan edukasi berkelanjutan dapat dilakukan dengan sinergi tersebut. Selain UU ITE, pemerintah Indonesia memiliki pendekatan keras bagi platform yang mendistribusikan atau gagal menghapus konten berita palsu. Pendekatan keras dilakukan pemerintah Indonesia yang masuk dalam katagori hate speech seperti termuat dalam KUHAP (Pasal 156-157).
Kebijakan terbaru, pemerintah mewajibkan setiap pemilik nomor telepon seluler melakukan registrasi ulang dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sampai Maret 2018. Kartu akan otomatis non aktif apabila registrasi tidak dilakukan. Kementerian Dalam Negeri mencatat sebanyak 35,29 juta pengguna ponsel yang melakukan registrasi NIK dalam kartu perdana yang mereka miliki. Padahal pengguna kartu perdana telepon selular di Indonesia mencapai 128 juta.
Perkembangan tersebut faktanya tidak hanya menghadirkan hal-hal positif, melainkan banyak distorsi dan bahaya laten yang berdampak pada individu dan publik. Dalam ranah pemerintahan, UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diterbitkan guna menghindari halhal negatif berdampak lebih besar lagi. Sampai Agustus 2017, sudah ada 205 kasus menjerat netizen dan pengguna layanan digital di Indonesia karena produk hukum ini.
Terakhir, Baiq Nuril, seorang tenaga kependidikan dijerat Pasal 27 Ayat 1 UU ITE karena dianggap mentransmisikan informasi elektronik yang muatannya dinilai melanggar kesusilaan. Mahkamah Agung kemudian memberi vonis hukuman 6 bulan penjara dan denda Rp 500 juta karena dianggap melanggar Pasal 27 Ayat 1 juncto Pasal 45 Ayat 1 UU Nomor 11/2008 tentang ITE. Saat ini, Nuril tengah menunggu keputusan amnesti dari Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, DPR telah menyetujui pertimbangan amnesti yang hendak diberikan.
Amnesti presiden memang kabar baik bagi Nuril seorang, namun akan banyak korban dari UU ITE yang dipandang masih multitafsir tersebut. Revisi UU ITE perlu dilakukan, karena sebagai bagian dari upaya melindungi hak warga negara untuk mengekspresikan pendapat publik yang tengah terancam maupun intimidasi dari pihak lain.
Seperti yang dijelaskan Daniel Pascoe, pemberian amnesti – yang sering diberikan kepada sekelompok orang dan bukannya perorangan - tidak "menuntut pengakuan bersalah secara implisit". Amnesty mengembalikan orang terpidana "ke posisi seolah-olah mereka tidak dihukum pertama kali dengan 'melupakan' daripada 'memaafkan'".
Dalam konteks jurnalistik, UU No 11 Tahun 2008 disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 21 April 2008, kemudian direvisi pada 27 Oktober 2016 oleh DPR RI menjadi UU Nomor 19 Tahun 2018 tentang ITE.
Kendati telah mengalami revisi, UU ini telah menjerat banyak korban. Dari monitoring Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet),tercatat 245 laporan kasus ITE sejak 2008 hingga 2018. Di antaranya ada upaya pemidanaan 14 jurnalis dan 7 media dengan pasal karet UU tersebut.
Pasal yang paling banyak digunakan adalah Pasal 27 ayat 3 UU ITE tentang Pencemaran Nama Baik (15 aduan), Pasal 28 ayat 2 UU ITE tentang Penyebaran Kebencian (2 aduan) dan Pasal 310-311 KUHP tentang Pencemaran Nama Baik (2 aduan), kemudian Pasal 156 KUHP tentang SARA (1 aduan) serta pasal lainnya (1 aduan). SAFEnet menilai, dijeratnya jurnalis dan media dengan UU ITE adalah bentuk krimininalisasi yang melanggar UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Dalam dilema jurnalis untuk menyatakan kebenaran, namun tanpa ditopang kode etik jurnalistik, maka akan lebih banyak jurnalis yang dijerai UU ITE. Pasal 7 ayat (2) (UU 40/1999 tentang Pers), jurnalis adalah profesi yang memiliki dan harus menaati Kode Etik Jurnalistik. Masih banyak jurnalis yang inkompetensi, pelanggaran etika jurnalistik, kualitas SDM (tak sesuai standar perilaku), ceroboh, terlalu percaya diri, dan keberpihakan media serta pemberitaan Belum lagi, kasus jurnalis dalam bertugas banyak yang mengalami kekerasan. Tindakan kekerasan pada jurnalis, dari catatan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia yang diolah tim Lokadata Beritagar.id, sejak 2006 hingga 2019 mencapai 708 kasus.
Dalam news making criminology, Hall (1979, 1980) menggunakan istilah populisme otoriter untuk menjelaskan bagaimana Thatcherism memanfaatkan ketakutan dan kecemasan publik untuk mempopulerkan solusi neoliberal untuk masalah ekonomi dan politik, termasuk hukum dan ketertiban. Kondisi ini persis bagaimana UU ITE membatasi gerak atau naluri jurnalisme warga maupun jurnalis media dalam memberitakan sesuatu, termasuk elite pemerintahan. Kuasa dan kedekatan elite politik dan hukum masih cukup kuat untuk memilih dan memilah siapa yang harus dibela dan dihukum.
Di era digital, posting di situs media sosial dapat meningkatkan risiko dan peluang bagi jurnalis dan blogger. Pada 2011, empat blogger dibunuh di Nuevo Laredo, Tamaulipas. Pada saat yang sama, karena kurangnya liputantentang kejahatan terorganisir di organisasi berita yang sudah lama berdiri di kawasan ini, situs media sosial seperti Facebook dan Twitter memberikan peluang bagi jurnalis dan warga untuk menginformasikan diri mereka sendiri (Cave 2011; Correa-Cabrera dan Nava 2013). Bahkan salah satu wartawan asal Texas mengungkapkan dalam penelitian Bustamante (2014) “saya biasanya tidak mentweet ketika saya di sana [di Meksiko]; Saya biasanya melakukannya setelah saya kembali ... saya tidak ingin melukis target di mana saya berada. Saya tidak ingin diculik atau dibunuh atau apalah”.
Demi melindungi diri dari jebakan UU ITE maupun tekanan dari pihakyang merasa dirugikan oleh jurnalis, maka sudah sepantasnya sejak awal profesi jurnalis dimulai, maka Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menjadi bagian terikat dalam perlindungan jurnalis baik sebagai saksi maupun korban dan kesejahteraan diri dan keluarganya.
Sumber berita dalam konteks ini berupa jurnalisme data dapat ditopang secara lebih efektif dan efisien melalui AI, namun penetrasi digital yang begitu kuat, memudahkan jurnalis dalam melacak berbagai sumber dengan sekali klik. Jika kecerdasan mesin (AI) diterapkan pada jurnalisme investigatif, sangat mungkin memonitor feed global untuk berita penting, menemukan pola yang relevan secara sosial di antara set data yang beragam, dan bahkan mungkin menulis cerita yang dihasilkan (Hansen et al. 2017; Marconi dan Siegman 2017).
Franklin (2014) menyatakan bahwa "Era media digital" adalah menyaksikan inovasi dan perubahan radikal di semua aspek jurnalisme, menciptakan kesulitan ekonomi untuk media lama dan mencari model bisnis alternatif untuk mendanai jurnalisme berkelanjutan untuk masa depan.
Tow Center for Digital Journalism mengungkapkan bahwa meningkatnya ketersediaan data, dengan segala sesuatu mulai dari media sosial hingga data pemerintah, memungkinkan pelaporan yang sebelumnya tidak mungkin — masih menyajikan jebakan. Wartawan harus hati-hati menilai kredibilitas jenis sumber baru ini, terutama di mana AI terlibat. Banyak peserta konferensi menekankan berpikir kritis tentang data.
Untuk mengambil satu contoh, jurnalis yang menggunakan Twitter sebagai platform media sosial pilihan mereka harus berhati-hati mengandalkannya untuk menganalisis perilaku, pemikiran, dan perasaan masyarakat. Meskipun alat dan data pengembang Twitter sangat mudah untuk dikerjakan, para jurnalis tidak boleh melihatnya secara eksklusif, karena platform ini populer secara tidak proporsional dengan mereka yang bekerja dalam politik dan media.
#hutrol28 #lombanulisretizen #republikawritingcompetition
Daftar Pustaka
Andreas Harsono, 20-24 Februari 1999. Investigative Reporting. Makalah untuk pelatihan investigative Reporting. Makalah untuk pelatihan investigative reporting yang diadakan oleh tabloid mahasiswa Bulaksumur, UGM, Yogyakarta.
Bob Franklin .(2014). The Future of Journalism. Journalism Studies, 15:5, 481-499, DOI: 10.1080/1461670X.2014.930254
C. and McLaughlin, E. (2017). ‘News Power, Crime and Media Justice’, A. Liebling, L. McAra and S. Maruna (eds.) Oxford Handbook of Criminology, sixth edition, Oxford: Oxford University Press
Cave, Damien. 2011. “Mexico Turns to Social Media for Information and Survival.” The New York times, September 24
http://www.nytimes.com/2011/09/25/world/americas/ mexico-turns-totwitter-and-facebook- for-information-and-survival.html?_r=0
Correa-Cabrera, Guadalupe, and Jose´ Nava. 2013. “Drug Wars, Social Networks and the Right to Information: The Rise of Informal Media as the Freedom of Press’s Lifeline in Northern Mexico.” In A War That Can’t Be Won: A Journey through the War on Drugs, edited by Tony Payan, Ellen Hume and Susan Abbott. The Future of Investigative Journalism: Global, Networked and Collaborative
HALL, S. (1979). The Great Moving Right Show. Marxism Today. January, 14–20.
HALL, S. (1980). Popular Democratic vs. Authoritarian Populism: Two Ways of Taking Democracy Seriously. in A. Hunt (ed.) Marxism and Democracy, London: Lawrence and Wishart.
Jonathan Stray. (2019). Making Artificial Intelligence Work for Investigative Journalism, Digital Journalism, DOI: 10.1080/21670811.2019.1630289
Lana Birbrair . 15, April 9, 2015. ProPublica’s Richard Tofel ’83 surveys the evolving business model of underwriting investigative journalism in the digital era (video)
Marconi, Francesco, and Alex Siegman. (2017). The Future of Augmented Journalism: A Guide for Newsrooms in the Age of Smart Machines. New York, NY: Associated Press Greer,
María Teresa Ronderos . 22 Januari 2019. How Innovative Newsrooms Are Using Artificial Intelligence
Policy Exchange Forum. June 13, 2017. Columbia Journalism School. Organized by the Tow Center for Digital Journalism and the Brown Institute for Media Innovation
Rommy Roosyana. Jurnalis dibayangi jerat UU ITE. Sumber: https://beritagar.id/artikel/berita/jurnalis-dibayangi-jerat-uu-ite Diakses tanggal 09 April 2019 pukul 09.00
Roy Greenslade. While newsrooms have shrunk, investigative journalism is thriving . https://www.theguardian.com/media/commentisfree/2019/mar/31/investigative- journalism-is-far-from-dead-its-thriving. Diakses tanggal 09 April 2019 pukul 09.00
Stratton G, Powell A and Cameron R .(2017). Crime and Justice in Digital Society: Towards a ‘Digital Criminology’?. International Journal for Crime, Justice and Social Democracy 6(2): 17‐33. DOI: 10.5204/ijcjsd.v6i2.355.
https://www.cnbcindonesia.com/news/20190503170743-4-70432/emas-grasberg-habis-2019- ini-kisah-tambang-legenda-freeport
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.