 Prof. Dr. Budiharjo, M.Si
Prof. Dr. Budiharjo, M.Si
Bajingan Tolol dan Pendidikan Etika Digital
Politik | 2023-08-04 11:39:45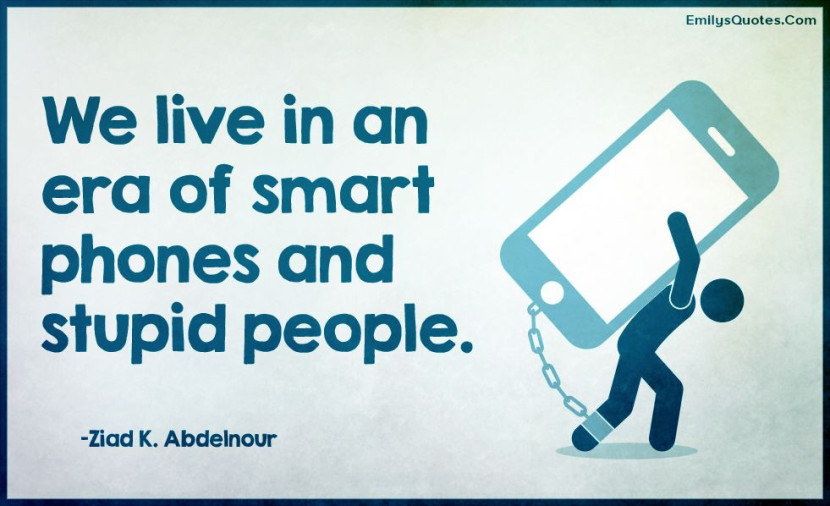
Smartphone acapkali tidak dibarengi dengan hadirnya smart people. Gambaran ini terjadi di era kehidupan manusia saat semakin pesatnya teknologi informasi. Ada adagium menarik yang pernah diangkat oleh National Geographic dalam program televisi Science of Stupid. Program yang dibawakan oleh Manish Paul itu mempertanyakan fenomena Smartphone vs Stupid People (SvSP). Fenomena yang menjadikan manusia bertindak bodoh padahal di genggaman tangannya ada teknologi mutakhir yang bisa melakukan apa saja. Tindakan bodoh yang kadang mampu merenggut nyawanya, seperti main hp saat menyetir mobil.
Fenomena SvSP itu terjadi di banyak negara, khususnya ketika twitter dan media sosial lainnya sudah masuk dalam ruang privat kita. Di tahun politik, suhu semakin panas karena saling serang dengan kata-kata caci maki menghiasi ruang maya. Komunikasi politik pun dibangun atas narasi kebencian yang bisa saja melahirkan perang sesungguhnya. Mengapa hal ini tak kunjung usai? Padahal kita sebenarnya sudah melalui berbagai Pemilu?
Prof Jeremy Harris Lipschults memiliki teori menarik yang diungkapnya dalam buku berjudul "Social Media Communication: Concept, Practices, Data, Law and Ethics." Menurutnya, sosial media pada awalnya dibuat hanya sekedar narsisme manusia. Namun, dia berkembang menjadi hal yang luar biasa dengan melibatkan banyak aspek. Komunikasi sosial media saat ini menjadi bisnis besar, serta menjadi alat baru yang digunakan untuk kepentingan ekonomi dan politik.
Militer dan kekuatan sipil menggunakan media sosial untuk pengelolaan komunitas yang besar. Baik komunitas yang tampak atau pun komunitas hantu (ghost community). Lipschutlz yang juga blogger untuk Huffington Post ini menekankan regulasi media sosial yang menabrak dua sisi, antara kebebasan berpendapat dan aktivitas pengawasan ketat Pemerintah. Ini menjadi lagu lama yang dihadapi oleh banyak negara. Jika menutup akses media sosial akan berhadapan dengan "people power". Namun, jika dibiarkan melahirkan kegaduhan yang tidak berkesudahan.
Apa solusinya? Menurutnya, perlu dibangun etika digital yang melahirkan smart people. Sebenarnya, hampir sama dengan berbagai disiplin ilmu, etika adalah norma yang menjadi batasan dalam beraktivitas. Dalam berbisnis ada etika yang tidak boleh dilanggar. Dalam agama apalagi. Sangat banyak larangan bagi pemeluknya. Dalam berkomunikasi pun demikian, ada batasan norma yang jika dilanggar maka itu bisa saja menyinggung orang lain.
Charles Ess dalam bukunya "Digital Media Ethics" memaparkan ada lima hal penting yang harus diperhatikan. Menurutnya, penerapan etika digital ini sangat sulit, meski bukan suatu hal yang mustahil. Pertama, privasi merupakan hal yang tidak boleh dilanggar. Siapa pun yang bermain dengan media digital, baik media mainstream ataupun sosial media, hendaknya tidak menyerang pribadi.
Kedua, penghormatan terhadap nilai tradisi dan keberagaman. Begitu besarnya coverage (jangkauan) media sosial, sehingga melewati batas ruang dan waktu. Ini menjadikan pengguna untuk selalu berhati-hati ketika menggunakan sosial media, tidak menyinggung nilai yang dianut oleh kelompok masyarakat tertentu. Ess memberi contoh tentang bahayanya sikap tidak menghormati nilai, seperti kasus penghinaan kartun Nabi Muhammad yang dimuat Jyllands Posten pada 2006. Hal itu mengundang reaksi kekerasan di seluruh dunia yang berakhir tragis bagi pembuatnya.
Ketiga, menghargai hak cipta. Ini adalah problem serius ketika seseorang dengan tanpa bersalah menggunakan konten buatan orang lain dan menjiplaknya. Semua paham bahwa hal itu adalah ilegal, namun media sosial menjadikannya sebagai hal lumrah.
Keempat, mengedepankan dialog solutif ketimbang caci maki. Media sosial sejatinya adalah untuk membangun komunikasi yang berjarak. Fungsi ini perlu dikembalikan karena saat ini medsos lebih menjadi medan perang ketimbang wahana silaturahim.
Kelima, penggunaan identitas resmi. Banyaknya akun anonim di media sosial sejatinya melahirkan permasalahan kompleks. Ini perlu ditertibkan dan menjadi pegangan bagi pengguna media sosial bahwa apa yang dia bagikan kelak bisa dipertanggungjawabkan.
Dalam konteks Indonesia, term "Bajingan Tolol" tidak lahir dari ruang hampa. Sebelumnya term itu gaduh, sudah banyak peristiwa-peristiwa serupa yang sebenarnya mengundang kemarahan publik. Namun, yang terjadi adalah perbedaan sikap dari aparat dan pihak Pemerintah itu sendiri. Kita tentu tidak ingin hal ini berlarut-larut. Mari kita menjadi smart people sebagaimana semakin canggihnya smartphone yang kita miliki.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.











