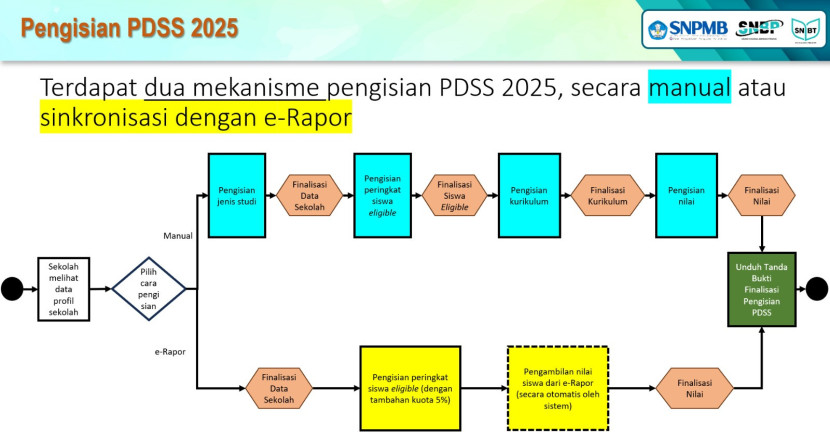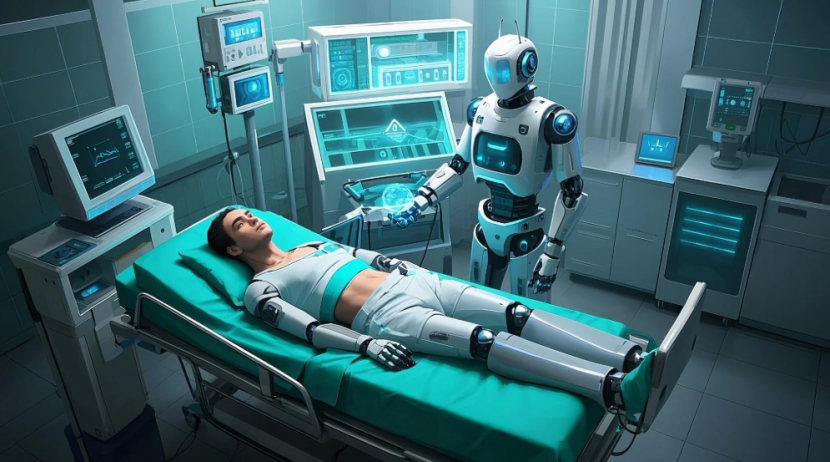Gina Sonia
Gina Sonia
Budaya Indis dan Peran Besar Perempuan Pribumi
Sejarah | 2022-11-30 21:52:07
Budaya Indis muncul dari fenomena pernikahan antara pejabat Belanda atau orang-orang Eropa secara umum yang bertugas di Hindia Belanda dengan wanita pribumi. Dari fenomena inilah, terjadi percampuran darah yang melahirkan keturunan campuran, serta menumbuhkan budaya dan gaya hidup Belanda-Pribumi atau yang biasa disebut budaya Indis. Dalam perkembangannya budaya Indis selalu menyesuaikan dengan keadaan. Mereka menerima sumbangan secara terus menerus dari kebudayaan Indonesia (khususnya Jawa) dan Eropa sepanjang waktu.
Pada awal kedatangan bangsa Belanda ke Nusantara, orang-orang Belanda atau Eropa pada umumnya membaur dengan penduduk setempat. Pembauran disini lebih merujuk kepada para tentara VOC dan pejabat Belanda di Hindia Belanda yang hidup membujang karena tidak adanya kehadiran wanita Eropa. Jumlah perempuan Eropa sangat sedikit dan tidak mampu memenuhi jumlah penduduk laki-laki Eropa. Masalah tersebut mendorong mereka mengambil perempuan Pribumi sebagai pasangan.
Pada awalnya, yakni sekitar tahun 1600-an, pergundikan dilarang oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Jan Pieterszoon Coen. Coen khawatir praktik menyimpang ini akan menjadi suatu ancaman terhadap keberadaan pemerintahan kolonial. Coen lalu mendatangkan perempuan Eropa. Para perempuan Eropa yang akan didatangkan ke Hindia Belanda itu diutamakan para gadis muda yang bersikap baik dan diutamakan yang pernah dididik secara ketat di panti asuhan. Coen akhirnya memutuskan untuk membawa perempuan lajang Eropa ke Hindia Belanda dan mempunyai kewajiban menikah dengan para pegawai VOC. Sebagai kompensasinya, mereka akan mendapat pelayaran gratis serta mas kawin.
Tapi beberapa waktu setelahnya pelarangan ini sudah tidak berlaku. Karena kenyataan bahwa sangat sulit untuk melakukan pengiriman perempuan dari Belanda ke Nusantara sehingga praktek ‘pernyaian’ hendaknya dibiarkan saja. Kalaupun ada, kebanyakan perempuan lajang yang didatangkan dari Eropa untuk kawin dengan pejabat VOC hanya membuat masalah. Karena merasa superior dan derajat mereka lebih tinggi dari penduduk asli, mereka bertindak sesuka hati seperti mabuk-mabukan dan tindakan-tindakan lain di luar aturan Tuhan.
Hal ini membuat lebih dari setengah jumlah keseluruhan laki-laki Eropa di koloni hidup bersama gundik pribumi dalam 25 tahun terakhir pada abad ke 19 atau sekitar tahun 1875-an. Para lelaki Eropa yang memilih praktik pergundikan secara sadar tahu bahwa hal itu bertentangan dengan moral Kristen yang mereka anut. Tetapi bagaimanapun, kebutuhan akan perempuan tidak dapat dielak, bahwa laki-laki tidak dapat hidup tanpa perempuan. Dari segi kesehatan, anggapan umum saat itu menyebut bahwa iklim tropis serta makanan kaya bumbu pedas khas Hindia Belanda mudah mendorong munculnya libido para lelaki Eropa. Pendapat-pendapat tersebut seolah membenarkan praktik pergundikan yang dilakukan oleh lelaki Eropa.
Dalam mengambil seorang perempuan pribumi, lelaki Eropa tidak hanya mengutamakan perempuan-perempuan lajang, tetapi juga ada yang sudah bersuami. Orang-orang Eropa biasanya memberikan sejumlah uang kepada kerabat atau suami dari perempuan yang dia ambil sebagai gantinya. Bahkan, terdapat kasus dimana seorang Nyai bisa “dialihkan” kepada lelaki Eropa lain. Ada pula yang berhubungan melalui perkawinan campuran sah. Pada paruh kedua abad kesembilan belas, jumlah pernikahan campuran sudah banyak, bahkan menyumbang sekitar 10-13% dari jumlah total perkawinan yang tercatat pada periode 1865-1878 dan proporsi perkawinan campuran naik ke puncaknya pada tahun 1925.
Akibat yang ditimbulkan dari laki-laki yang hidup dengan perempuan pribumi adalah memiliki anak dengan kebudayaan campuran. Mereka diasuh sejak kecil oleh budak-budak dengan begitu banyak pelayanan dan perintah. Bagi perempuan dari kalangan atas (mampu), biasanya mereka menggunakan jasa budak dan pelayan pribumi, membiarkan anak-anak mereka diasuh dan dirawat tanpa campur tangan Ibu. Selain anak, suami/istri juga mendapatkan pengaruh budaya Jawa dengan gaya Eropa. Hal ini dapat dipahami sebagai perubahan kultural yang terjadi melalui pertemuan yang terus menerus dan intensif antara orang Eropa dan pribumi sehingga mampu mempengaruhi dua kelompok kebudayaan yang berbeda. Bagaimanapun, budaya Indis bukan semata-mata budaya Jawa, tetapi hasil penyesuaian dengan budaya Eropa. Budaya Indis dapat berkembang dalam keluarga yang diterima, bukan dari keluarga yang diisolasi dan dikucilkan.
Dalam kehidupannya dengan perempuan-perempuan pribumi, baik sebagai gundik maupun istri sah, mereka biasanya tetap memegang budaya pribuminya. Budaya tersebut dapat dilihat dari berbagai bidang, mulai dari pakaian, arsitektur bangunan, makanan, hingga hiburan. Terlebih, banyak perempuan pribumi yang menerima posisi tinggi setelah menikah dengan lelaki Eropa. Hal ini sangat berkontribusi dalam perkembangan budaya Indis di Batavia. Nyonya kalangan atas diperlakukan dengan penuh hormat, mereka tidak perlu khawatir dengan tugas-tugas rumah tangga karena memiliki banyak pelayan. Selain berurusan dengan para pedagang, mereka juga mengawasi perkebunan atau pabrik-pabrik milik suaminya.
Dalam kehidupan sehari-hari antara sesama anggota keluarga, mereka menggunakan Bahasa tersendiri yaitu, Indisch Dutch, yang merupakan percampuran Bahasa Belanda dengan bahasa Indonesia lama. Di pagi hari, orang-orang Eropa terbiasa minum kopi, tidur siang mengenakan piyama batik dan saling berkunjung satu sama lain. Hal ini sangat berbeda dari sifat individual yang biasa orang-orang Eropa miliki. Mereka biasa menggunakan serambi depan untuk menyambut tamu dan bercengkrama dengan tetangga. Dulu, orang-orang Eropa jarang mandi dan mengganti baju serta bekerja terus sampai sore, namun pada paruh akhir abad ke-19 para pegawai VOC mengenakan pakaian kolonial berwarna putih dan keluar kantor jam 14.00 siang.
Dari segi pakaian, perempuan pribumi terbiasa memakai kebaya dan kebiasaan itu biasanya akan diteruskan kepada anak-anak mereka. Para perempuan muda mengenakan sarung yang dipakai untuk menggantikan pakaian dalam dan kebaya menggantikan kemeja dalam perempuan, hanya ketika di rumah. Sebagian Lelaki Belanda memakai piyama batik ketika tidur dan mereka juga tidur menggunakan guling.
Dari segi makanan, lama kelamaan lidah orang Eropa menjadi terbiasa dengan makan makanan Hindia. Roti yang menjadi makanan utama bangsa Eropa semakin lama tergantikan dengan nasi, makanan pokok di Hindia Belanda. Kebiasaan makan nasi dari generasi ke generasi pada akhirnya menjadi budaya tersendiri dalam ruang lingkup kehidupan orang orang Belanda, yang kemudian memunculkan istilah khusus “rijsttafel”, yakni cara penyajian makanan berurutan dengan pilihan hidangan dari berbagai daerah di Nusantara dengan bahan utama yaitu nasi dan aneka hidangan samping.
Selain perempuan (istri/gundik), penyebaran budaya Jawa di kalangan orang Eropa juga dapat melalui eksistensi juru masak dan pengasuh Jawa. Untuk sebuah keluarga Belanda yang paling sederhana sekalipun memiliki 1 sampai 6 pelayan yang hidup menurut kebiasaan Jawa bersama anak dan istrinya, dengan demikian seorang Belanda biasa hidup setidaknya dengan 12 pribumi. Orang Eropa memiliki kebiasaan bermalas-malasan, itulah alasan mengapa budaya Indis disalurkan melalui pembantu-pembantu wanita yang mengasuh dan membesarkan anak-anak. Budaya-budaya Jawa yang biasa mereka lakukan seperti makanan, pakaian, obat-obatan rumah tangga (jamu), kepercayaan tertentu pada hantu, roh halus dan ilmu hitam (guna-guna), hingga mengunyah sirih.
Perkembangan kebudayaan Indis secara perlahan-lahan berakhir bersamaan dengan runtuhnya kekuasaan Belanda ke tangan Jepang. Budaya Indis mengalami kemunduran ketika Perang Dunia II berkecamuk, melumpuhkan gaya hidup mewah orang-orang Indis. Sulitnya hidup masa perang menghentikan segala aktifitas dari kebudayaan ini (Soekiman, 2014: 12).
Sumber Rujukan:
Soekiman, D. (2014). Kebudayaan Indis dari Zaman Kompeni sampai Revolusi. Depok: Komunitas Bambu
Taylor, Jean Gelman. (2009). Kehidupan sosial di Batavia: orang Eropa dan Eurasia di Hindia Timur. Jakarta: Masup
Locher-Scholten, Elsbeth. 1992. “The Nyai in Colonial Deli: A Case of Supposed Mediation”, in: Sita van Bemmelen et al. (ed), Woman and Mediation in Indonesia. Leiden: KITLV Press: 265-280.
Milone, P. D. (1967). Indische Culture, and Its Relationship to Urban Life. Comparative Studies in Society and History, 9(4), 407–426.
Gultom, A.Z. (2020). “Kebudayaan Indis sebagai Warisan Budaya Era Kolonial.” Warisan: Journal of History and Cultural Heritage, 1(1), 20-26
Hibatullah, M.I. (2021). “Harga diri dan prasangka: masyarakat multikultural di Batavia abad 17 sampai 19.” Historiography: Journal of Indonesian History and Education, 1(4), 405-418
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.