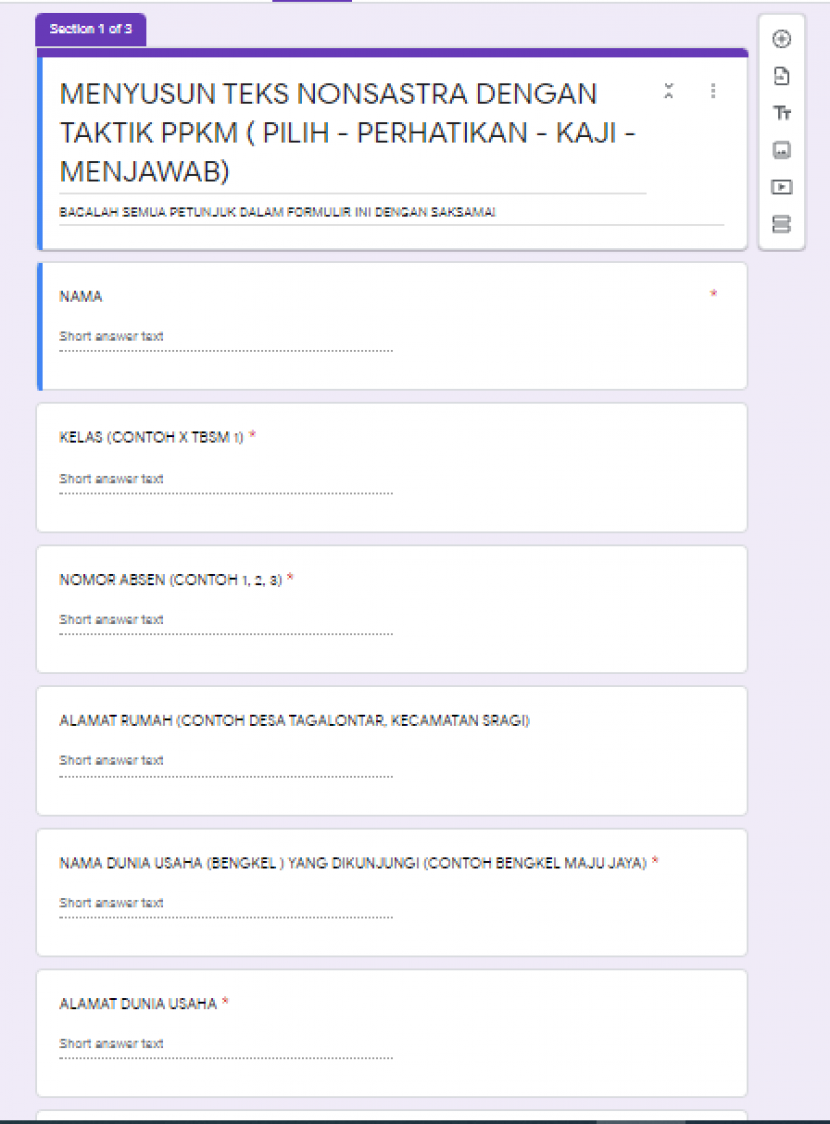Anicetus Windarto
Anicetus Windarto
Potret Pendidikan Generasi Pandemi
Guru Menulis | 2021-09-23 10:12:46A. Windarto
Peneliti di Litbang Realino, Sanata Dharma, Yogyakarta
Sudah setahun sejak belajar di sekolah dialihkan menjadi daring, nyaris tiada masalah yang cukup berarti yang menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Bahkan kebanyakan anak usia sekolah justru tampak senang dengan model pembelajaran tanpa ruang kelas itu. Buktinya, belajar di sekolah tetap berjalan seperti biasa, meski ada juga yang tersendat-sendat lantaran terbatasnya fasilitas pendukung seperti jaringan internet, pulsa, telepon genggam, atau komputer. Namun, pada umumnya sekolah tidak pernah absen, apalagi lenyap di tengah pandemi.
Kenyataan ini memperlihatkan bahwa sekolah masih menjadi bagian penting dan menentukan dalam masyarakat. Dengan kata lain, tanpa sekolah seakan-akan tiada kehidupan. Dalam arti ini, kehidupan yang ditandai dengan beragam kemajuan dan menunjukkan sebuah peradaban. Pada titik itulah, sekolah seolah-olah telah menjadi wahana untuk terbebas dari kebarbaran.
Padahal sejarah justru mencatat bahwa tiada peradaban tanpa dibangun di atas kebiadaban. Jadi, sekolah sesungguhnya tidak membuat orang menjadi semakin manusiawi, tetapi sebaliknya malah cenderung hewani. Contohnya, keserakahan yang tampil dalam wajah koruptif telah mengakibatkan kesengsaraan yang tiada duanya. Kesengsaraan akibat keserakahan itu memang tidak berdampak dengan segera, namun lambat laun dapat menciptakan kerusakan yang luar biasa. Sebagai perbandingan, kekayaan alam, seperti hutan atau tambang, jika dieksploitasi tanpa batas niscaya akan menghasilkan kerusakan alam yang tak tertanggungkan.
Meski sekolah daring telah dirancang dengan jeli, khususnya di tengah pandemi, namun pembelajaran secara digital (online) itu ternyata masih beraroma konvensional (offline). Itu artinya, pembelajaran yang dilakukan tampaknya hanya memindahkan materi belaka. Buktinya, beragam tugas yang dibebankan pada guru dan siswa ujung-ujungnya hanya untuk mengejar prestasi dengan berorientasi pada nilai atau angka belaka. Itulah mengapa pembelajaran tidak lebih dari sekadar mendapatkan nilai setinggi-setingginya dengan menghalalkan segala cara. Akibatnya, kebiasaan untuk meniru atau menjiplak karya orang lain menjadi perilaku yang sedemikian banal, bahkan dimaklumi.
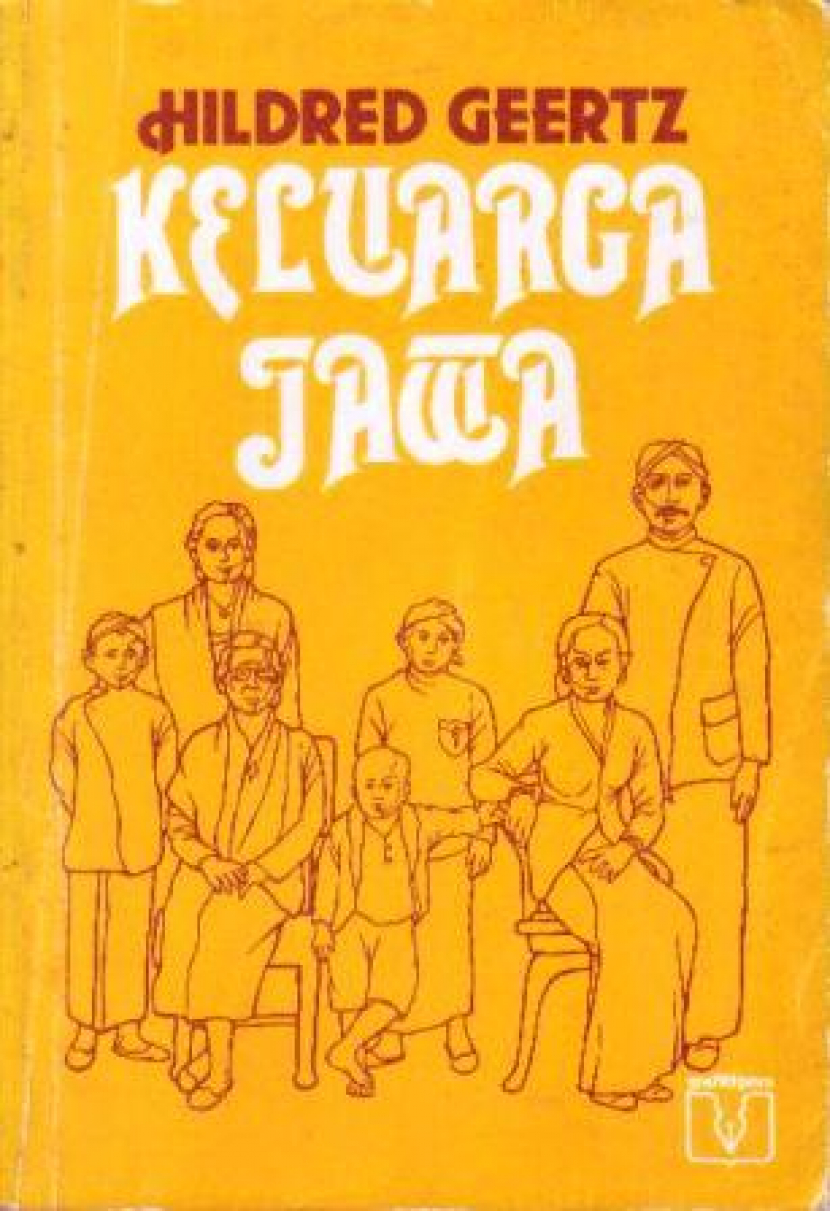
Cukup jelas bahwa meniru adalah bagian dari budaya yang berakar dari pendidikan dalam keluarga. Hal itu telah dikaji oleh Hildred Geertz dalam bukunya yang berjudul Keluarga Jawa (Grafiti Pers, 1983) yang menunjukkan bahwa "nurun" atau meniru memang diajarkan kepada anak-anak agar tidak keliru, bahkan salah, saat mengerjakan sesuatu. Sebab risiko yang harus ditanggung dari suatu kekeliruan atau kesalahan adalah rasa malu (isin). Hal ini bukan terkait dengan akibat dari hukuman fisik, seperti berdiri di depan kelas misalnya, yang mesti dijalani, melainkan adanya "rasa" yang tak mudah dilupakan, apalagi dihilangkan, dalam konteks hidup masyarakat berbudaya Jawa. Di sini penting untuk dicatat bahwa bagi orang Jawa, mereka yang masih kanak-kanak atau asing dengan kebudayaan Jawa akan dicap dengan identitas "belum Jawa" (durung Jawa). Itu artinya, mereka akan selalu mendapat pengajaran, atau jika perlu penghajaran, yang diperlukan agar tidak menjadi kurang ajar alias tahu diri dengan posisinya secara hirarkis.
Dalam konteks ini, seorang hamba dituntut untuk patuh pada tuannya bukan semata-mata karena perkara bawahan dan atasan, tetapi lantaran rasa "hormat pada yang dituakan" (respect to the eldest). âRasaâ seperti ini ditanamkan sejak awal dalam keluarga terutama pada diri anak-anak terhadap bapaknya. Sebab bapak adalah sosok yang dianggap mampu memberi perlindungan dan penjagaan yang menciptakan keamanan dan ketertiban (rust en orde). Itulah mengapa seorang bapak yang ketahuan korupsi misalnya, tidak akan dicela, bahkan dihina, oleh anaknya, melainkan tetap dipandang sebagai pahlawan yang rela berkorban demi anak buahnya. Jadi, bapak tidak pernah keliru, apalagi salah, namun karena anak-anaknyalah yang sesungguhnya tidak tahu diri dan terlalu banyak tuntutan. Maka tak heran jika ada peribahasa yang menggambarkan bahwa apapun yang dilakukan oleh anak, bapaklah yang harus menanggung segalanya. Anak polah, bapak kepradah, demikianlah bunyi dari peribahasa itu.
Proses pengajaran "nurun" atau meniru yang pada mulanya berbasis pada nilai-nilai respektif itu kini telah ditunggangi hanya oleh kepentingan sesaat dan sepihak belaka. Ironisnya, kepentingan seperti itu justru difasilitasi lewat segenap perangkat IPTEK yang di masa pandemi begitu dimanfaatkan secara optimal. Berkat jasa dari teknologi komunikasi modern, pendidikan untuk generasi di era pandemi menjadi semakin diberi berbagai kemudahan, termasuk untuk "nurun". Dengan teknologi "salin dan tempel" (copy and paste), segala yang diperlukan dapat dipenuhi sebagaimana yang diinginkan. Dalam bahasa teknologi Microsoft yang berlaku dan masih diakui hingga saat adalah apa yang kau lihat, itulah yang kau dapatkan (what you see, what you get).
Hanya masalahnya, teknologi seperti itu sekadar bernilai ekonomis belaka. Artinya, kalkulasi yang diharapkan dari hal itu cenderung bersifat efektif dan operatif. Dengan kata lain, tiada lagi yang ingin dikejar dan diraih, kecuali hasil yang cepat dan instan tanpa perlu bersusah-payah menjalani prosesnya. Akibatnya, tak perlu lagi rasa malu jika terjadi kekeliruan atau kesalahan yang disebabkan oleh teknologi "nurun". Bukankah hal itu dapat dialami oleh siapapun, kapanpun, dan di manapun lantaran teknologi bersifat lintas batas dan tak mengenal ârasaâ, apalagi berbudaya? Inikah potret dari generasi yang sedang menjalani pendidikan dan masih akan terus dihantui oleh pandemi?
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.