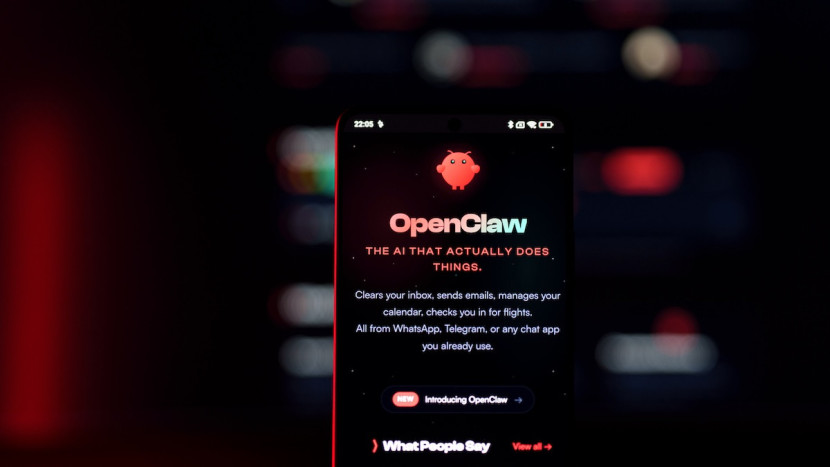saman saefudin
saman saefudin
Puasa, Perjuangan Manusia Menemukan Bahagia (Bagian Terakhir)
Agama | 2022-04-11 10:12:42
Tulisan bagian pertama bisa dibaca dii link berikut.
Sebagai sesuatu yang melekat dalam fitrah penciptaan manusia, nafsu sejatinya berwajah ganda. Ibarat dua sisi mata uang, merangkum potensi baik dan buruk sekaligus.
Pada satu sisi, nafsu adalah sebuah perangkat yang dibutuhkan manusia untuk menjaga kelangsungan hidupnya (survive) hingga berkembang biak, serta mengembangkan tata kehidupannya menjadi sedemikian maju melalui imajinasi dan daya kreatifnya.
Di era kejayaan Islam di Andalusia, sekitar abad 7-10 M, konon masyarakatnya telah membangun sistem saluran air bawah tanah yang terhubung ke rumah-rumah. Umat Islam telah dikenal dengan tradisi mandi, meski sampai abad 13 sebagian masyarakat Eropa masih hidup nomaden dan menganggap mandi justru sebagai biang penyakit., Dari mana para ilmuwan Muslim mendapatkan inspirasi membangun jaringan air bersih bawah tanah itu? Ternyata mereka terinspirasi oleh imajinasi tentang surga yang digambarkan Alquran: mengalir di bawahnya sungai-sungai.
Secara fisik, manusia mungkin lebih ringkih dari binatang, kalah cepat kekuatan larinya dari anjing dan kuda. Maka nafsu menuntunnya untuk menciptakan kendaraan darat yang kecepatannya bahkan sekian ratus tenaga kuda. Manusia memang tak bisa terbang, tetapi ia ingin seperti elang yang terbang melintasi samudra. Maka muncullah keinginan menciptakan teknologi terbang, dari Abbas Ibnu Firnas di era Andalusia, sampai akhirnya Wright bersaudara sukses menerbangkan pesawat untuk pertama kalinya pada Desember 1903.
Yang menjadi problem adalah ketika nafsu dan ambisi manusia menjadi liar dan tak terkendali, semata menuruti keserakahan yang tak ada habisnya. Kita kadang sulit membayangkan bagaimana perusahaan-perusahaan kayu yang membabat habis hutan, melakukan pembakaran hutan secara sengaja ataupun tak sengaja, lalu perusahaan-perusahaan tambang yang telah merusak alam dan menyisakan lubang-lubang raksasa. Bayangkan, betapa banyak kerugian dan derita yang ditinggalkan untuk masyarakat dan anak cucu kelak.
Lantas, bagaimana mengontrol nafsu? Apakah hasrat dan angan-angan manusia bisa dikendalikan? Dengan cara apa? Salah satu jawaban yang logis dan berakar historis adalah lelaku puasa.
Selain kurban dan shalat (sujud), puasa memang tercatat sebagai ibadah tertua yang dilakukan umat manusia. Puasa telah disyariatkan sejak Nabi Isa, Daud, Musa, dan bahkan era Nabi Nuh As, meski dengan kaefiyah yang berbeda-beda tentunya (QS.2: 183). Pun ritual puasa tidaklah ekslusif Islam, melainan juga dijumpai umat agama lain seperti Hindu, Budha, hingga penghayat kepercayaan.
Puasa ramadan yang disyariatkan Allah sejatinya adalah sebuah momentum bagi orang beriman untuk mereposisi nafsunya. Bahwa setelah 11 bulan kita bergelut dengan dinamika nafsu, saatnya kembali berlatih menjadi pengendalinya, drive your own car.
Di bulan ramadan, gambaran terbaik untuk belajar konsep kebahagiaan itu adalah saat momentum berbuka puasa. Siapapun yang berpuasa sejak fajar, melewati siang yang mungkin panas menyengat, pastilah menantikan saat berbuka; ketika yang halal kembali diperbolehkan untuk dilakukan. Saat itulah setiap orang yang berbuka akan merasakan bahagia, sebagaimana bunyi hadits Nabi Saw;
“Bagi orang yang melaksanakan puasa ada dua kebahagiaan; kebahagiaan ketika berbuka, dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Rabbnya.” (muttafaq alaihi)
Lihatlah betapa sederhananya konsep bahagia bagi manusia. Saat kumandang adzan maghrib, hati orang yang berpuasa teramat bahagia. Bahkan, kebahagiaan itu teramat simpel diraihnya, mungkin dengan segelas teh, tiga biji kurma, atau satu potong kue, gorengan, dan lainnya. Kenapa ia bahagia, karena itulah yang dibutuhkan saat berbuka.
Tetapi apa jadinya kalau sore hari Anda ngabuburit berburu menu takjil? Mungkin semua menu terasa menggoda, ingin dibeli semuanya untuk berbuka. Padahal, saat berbuka kita hanya butuh sedikit, yang lain mungkin tak termakan.
Maka puasa ramadan sejatinya adalah sebuah prototype ihwal perjuangan manusia menemukan kebahagiaan. Bahwa tidaklah kebahagiaan itu diperoleh dengan memenuhi semua keinginan, melainkan sebaliknya, yakni mengontrol diri atas keinginan-keinginan yang tak ada ujungnya. Maka cukuplah bahagia dengan memenuhi kebutuhan yang mungkin sedikit dan sederhana, karena selebihnya mungkin hanya keinginan yang kalaupun dikejar pastilah tak ada habisnya.
Dalam hal ini, Imam Syafii menawarkan konsep kecukupan atau kepuasan (istighna). Bahwa perasaan cukup dan puas bukanlah karena mampu memenuhi semua keinginan, melainkan justru berusaha agar semakin banyak hal yang tidak diingini. Dalam bahasa Gus Baha, hal ini juga dirumuskan dalam sudut pandang lain yang keren; “Islam adalah agama yang tidak didikte oleh materi”. Artinya, Islam justru mendorong manusia untuk mencapai kemerdekaan eksistensialnya, yang laku dan batinnya tidak terombang-ambing oleh situasi.
Seorang Muslim hanya boleh didikte Allah, bukan keinginan atau nafsunya. Prinsip dan nilai ini bukan hanya ideal, melainkan juga indah dan karenanya bisa melahirkan kebahagiaan. Namun demikian, pada kenyataannya tentu tidaklah mudah mengimplementasikan nilai-nilai ideal ini, khususnya di alam modern yang kapitalistik seperti sekarang ini.
Secara umum, alam pikir manusia modern justru dituntun oleh keinginan dan angan-angannya, utamanya hasrat memiliki, hasrat konsumsi yang hedonis. Bahkan, hebatnya sistem kapitalime saat ini, hasrat memiliki dan konsumsi ini didesain sedemikian masifnya sehingga manusia modern sesungguhnya sadar atau tidak dikendalikan pilihan keinginannya sebatas apa yang tersaji dalam etalase industri hasrat dan kepuasan. Manusia modern menjadi kurang merdeka untuk menentukan identitas dirinya. Identitas manusia modern direduksi hanya pada apa yang dimiliki, apa yang dikonsumsi. Orang berlomba-lomba untuk merealisasikan kepemilikan pribadi, mengejar ingin dan angan yang tak ada ujungnya.
Problem masyarakat modern ini telah banyak diulas oleh para teoritisi sosial kritis, salah satunya Erich Fromm dari Mazhab Frankfurt. Dalam bukunya “To Have or To Be”, Erich Fromm mencoba menyajikan dua motif eksistensial manusia modern, yakni memiliki (having) atau menjadi (being), sebagai kritik atas kecenderungan masyarakat modern yang disebut Fromm terlampau didominasi oleh modus having.
Masyarakat modern hidup dalam dominasi kebendaan yang akut, dengan orientasi pemenuhan hasrat kepuasan atas materi. Modus kepemilikan ini bahkan pada akhirnya menjelma menjadi penanda identitas manusia modern, sehingga sejatinya mencerabut manusia dari nilai eksistensialnya sebagai manusia. Pada akhirnya, modus memiliki ini menjadikan manusia modern tak ubahnya seperti sistem yang mereka anut sendiri, yakni kapitalisme yang tamak dan cenderung eksploitatif. Sebab orang modern hanya fokus pada pemenuhan kepuasan dirinya. Pun finally, modus memiliki membuat kehidupan manusia modern sejatinya terkontrol oleh industri atau para produsen hasrat dan kepuasan. Alih-alih seolah merdeka memilih dan menentukan keinginan-keinginannya, manusia modern justru didikte boleh kebendaan itu sendiri, seperti apa yang disampaikan Gus Baha.
Sebagai solusi, Fromm menawarkan modus being sebagai cara menjaga kewarasan di alam modern yang hedonis ini. Melalui konsep masyarakat being ini, Erich Fromm seolah ingin menegaskan kembali peran akal budi, aktif menggunakan dan mengolah batin (pikiran) nya, tidak terjebak dalam kehidupan yang mekanik. Selain ditandai dengan karakter mandiri, bebas, dan kritis, masyarakat being juga memberi ruang bagi hasrat tinggi dalam giving and sharing, serta bahkan berkurban satu sama lainnya.
Maka dengan ibadah puasa, semestinya kesadaran kita tak melulu terjebak pada modus to have, melainkan justru to be. Karena dari laku puasa, menahan keinginan, kita menjadi belajar skala prioritas tentang apa yang sesungguhnya kita butuhkan untuk bahagia. Ya seperti saat berbuka itu. Kalau kebutuhan itu telah terpenuhi, maka kita bisa mengalokasikan kelebihan yang kita punya untuk para tetangga atau orang-orang yang selama ini terbiasa lapar karena memang kekurangan. Dan lagi-lagi, di setiap kesempatan kita memberi dan berbagi, kita juga akan merasakan kebahagiaan tertentu, seperti saat berbuka puasa. []
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.