 Muliadi Saleh
Muliadi Saleh
Tarawih, Fleksibilitas Syariat dan Kedalaman Spiritual Ramadan
Agama | 2026-02-12 15:24:02Oleh: Muliadi Saleh, Ketua DKM Masjid Fatimah dan Sekretaris Dewan Pengarah DPP IAPIM

Ramadan selalu menghadirkan suasana yang khas. Masjid hidup kembali pada malam hari, ayat-ayat suci bergema lebih panjang, dan umat Islam menemukan ritme spiritual yang berbeda dari bulan-bulan lainnya. Di tengah tradisi itu, salat tarawih menjadi salah satu penanda paling kuat. Namun, di balik praktik yang tampak seragam, sebenarnya terdapat fleksibilitas teknis yang luas dalam syariat Islam. Fleksibilitas inilah yang sering luput dipahami—padahal ia justru menunjukkan wajah Islam yang ramah terhadap kondisi manusia.
Dalam praktik mayoritas umat Islam, terutama di lingkungan mazhab Syafi’i, tarawih lazim dilaksanakan 20 rakaat ditambah 3 witir. Tradisi ini merujuk pada kebijakan Khalifah Umar bin Khattab RA yang mengumpulkan kaum Muslimin dalam satu imam untuk qiyamul-lail Ramadan. Sejak itu, praktik tersebut menyebar luas dan menjadi kebiasaan dominan di dunia Islam, termasuk dalam mazhab Hanafi dan Hanbali. Tetapi sejarah fikih juga mencatat adanya riwayat 8 rakaat, bahkan variasi lain, yang menunjukkan bahwa sejak masa sahabat pun jumlah rakaat tarawih tidak tunggal. Ini bukan kontradiksi, melainkan bukti ruang ijtihad dalam ibadah sunah.
Karena tarawih bukan ibadah dengan ketentuan jumlah rakaat yang qath’i (pasti), maka yang dijaga sesungguhnya adalah esensi qiyamul-lail: berdiri di hadapan Allah pada malam Ramadan. Angka rakaat menjadi sarana, bukan tujuan. Di sinilah syariat memperlihatkan keseimbangannya—tegas pada prinsip, lentur pada teknis.
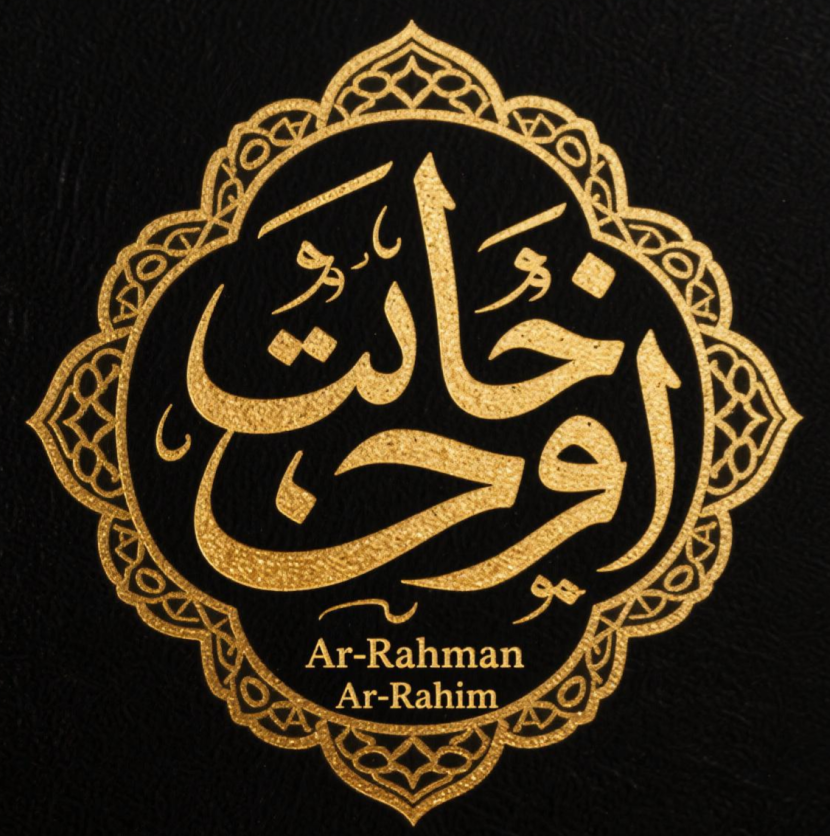
Fleksibilitas serupa tampak pada bacaan Al-Qur’an dalam salat malam. Tidak ada ayat Al-Qur’an yang menetapkan satu halaman per rakaat atau satu juz per malam. Praktik membaca satu juz setiap malam agar khatam selama Ramadan hanyalah metode praktis yang berkembang dalam tradisi umat. Al-Qur’an sendiri justru memberi prinsip umum: “Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur’an” (QS. Al-Muzzammil: 20). Ayat ini mengandung pesan psikologis sekaligus spiritual—bahwa ibadah tidak boleh mengabaikan kemampuan manusia.
Ayat lain menegaskan kualitas bacaan: “Dan bacalah Al-Qur’an itu dengan tartil” (QS. Al-Muzzammil: 4). Tartil berarti perlahan, benar, dan menghadirkan makna. Penekanan pada tartil menunjukkan bahwa kedalaman spiritual tidak selalu identik dengan panjang bacaan. Bacaan singkat yang meresap bisa lebih menggetarkan jiwa daripada bacaan panjang yang tergesa.
Realitas kontemporer memberi contoh konkret tentang fleksibilitas ini. Ketika pandemi Covid-19 melanda dunia, otoritas Masjidil Haram dan Masjid Nabawi melakukan penyesuaian durasi tarawih. Jumlah rakaat sempat diringkas, bacaan dipersingkat, target khatam Al-Qur’an diturunkan. Langkah tersebut bukan perubahan hukum ibadah, melainkan pengaturan teknis demi kemaslahatan jamaah. Dalam kerangka maqashid syariah, ini berkaitan dengan prinsip hifz an-nafs—menjaga keselamatan jiwa sebagai salah satu tujuan utama syariat.
Menariknya, sebagian pola ringkas itu tetap bertahan setelah pandemi mereda. Banyak jamaah merasa durasi yang lebih singkat memberi keseimbangan baru: tarawih tetap berjalan, tetapi ada ruang lebih luas untuk ibadah personal seperti tahajud, zikir, atau tilawah mandiri. Fenomena ini menunjukkan bahwa fleksibilitas ibadah bukan sekadar respons darurat, melainkan bagian dari dinamika hidup umat.
Dalam perspektif fikih, kelonggaran teknis ibadah selalu berjalan berdampingan dengan ketegasan prinsip. Misalnya dalam wudhu menurut mazhab Syafi’i: hal-hal yang membatalkannya relatif jelas—keluarnya sesuatu dari qubul atau dubur, hilangnya akal seperti tidur nyenyak atau mabuk, bersentuhan kulit dengan lawan jenis non-mahram, serta menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Prinsip kesucian dijaga ketat karena ia syarat sah salat. Tetapi setelah syarat terpenuhi, cara pelaksanaan ibadah sunah seperti tarawih tetap terbuka untuk variasi sesuai kemampuan.
Di sinilah letak kebijaksanaan syariat. Tidak semua aspek agama diperlakukan sama. Yang prinsip dijaga kokoh, yang teknis diberi ruang adaptasi. Jika semuanya kaku, agama bisa terasa memberatkan. Jika semuanya longgar, agama kehilangan arah. Islam berdiri di antara dua kutub itu—tegas sekaligus welas asih.
Sayangnya, dalam praktik sosial keagamaan, fleksibilitas ini kadang terlupakan. Tarawih terkadang berubah menjadi simbol identitas kelompok. Ada yang merasa paling benar dengan 20 rakaat, ada pula yang menilai 8 rakaat lebih autentik. Bahkan panjang pendek bacaan bisa menjadi bahan penilaian sosial. Padahal inti tarawih bukan kompetisi durasi, melainkan kualitas kehadiran hati.
Kesalahpahaman semacam ini sering berakar pada kecenderungan manusia mencari kepastian simbolik. Angka rakaat dan panjang bacaan mudah dilihat, sementara kekhusyukan sulit diukur. Maka yang kasat mata sering dijadikan standar, meski belum tentu mencerminkan kedalaman spiritual. Di sinilah pentingnya literasi fikih sekaligus kedewasaan spiritual agar umat tidak terjebak pada formalitas semata.
Tarawih seharusnya menjadi ruang pendidikan spiritual kolektif. Ia melatih disiplin, kebersamaan, sekaligus empati. Imam belajar mempertimbangkan kondisi jamaah; jamaah belajar toleran terhadap variasi praktik. Ketika fleksibilitas dipahami, masjid menjadi ruang inklusif—ramah bagi yang kuat berdiri lama maupun yang hanya mampu sebentar.
Dari perspektif sosial, fleksibilitas ibadah juga menunjukkan bahwa Islam selalu dialogis dengan realitas. Sejarah mencatat bagaimana praktik keagamaan menyesuaikan kondisi zaman tanpa kehilangan esensinya. Dari kebijakan Umar bin Khattab RA hingga pengaturan ibadah di masa pandemi, semuanya menunjukkan bahwa agama tidak berada di ruang hampa. Ia hidup bersama manusia, merespons kebutuhan, dan menjaga kemaslahatan.
Lebih jauh lagi, fleksibilitas tarawih mengandung pesan spiritual yang dalam. Ramadan bukan sekadar memperbanyak aktivitas ritual, tetapi memperdalam kesadaran ilahiah. Jika tarawih dipersingkat, bukan berarti kualitas Ramadan menurun. Bisa jadi justru ada kesempatan lebih luas untuk munajat personal—tahajud sunyi, zikir tanpa sorot sosial, tilawah yang lebih reflektif.
Kadang yang dipendekkan adalah ritual berjamaahnya, agar percakapan pribadi dengan Allah menjadi lebih panjang. Di situlah Ramadan menemukan makna terdalamnya: bukan sekadar ramai di masjid, tetapi juga hening di relung jiwa.
Dalam kerangka maqashid syariah, fleksibilitas teknis ibadah sebenarnya bertujuan menjaga keseimbangan hidup manusia. Ibadah tidak dimaksudkan merusak kesehatan, mengabaikan keluarga, atau menimbulkan konflik sosial. Ia justru hadir untuk memperbaiki kualitas hidup, menghadirkan ketenangan batin, dan memperkuat solidaritas sosial.
Tarawih, dengan segala variasinya, adalah contoh nyata bagaimana syariat memadukan spiritualitas dan realitas. Ia tidak memaksa semua orang berada pada standar fisik yang sama. Orang tua, pekerja, pelajar, bahkan musafir memiliki ruang masing-masing untuk tetap terhubung dengan Allah tanpa merasa terbebani.
Akhirnya, yang perlu terus dihidupkan adalah kesadaran bahwa ibadah bukan sekadar rutinitas formal. Ia adalah perjalanan pulang. Rakaat yang banyak tidak otomatis mendekatkan jika hati absen. Sebaliknya, rakaat yang sedikit bisa bermakna mendalam jika dijalani dengan kesadaran penuh.
Ramadan mengajarkan bahwa kualitas kehadiran lebih penting daripada kuantitas gerakan. Tartil lebih utama daripada tergesa. Khusyuk lebih bernilai daripada panjang durasi. Dan fleksibilitas syariat adalah rahmat agar setiap manusia, dengan segala keterbatasannya, tetap memiliki jalan menuju Tuhan.
Maka mungkin yang perlu kita rawat bukan perdebatan angka rakaat, melainkan keluasan hati menerima perbedaan. Bukan panjang pendek bacaan, tetapi kedalaman makna yang kita tangkap. Sebab pada akhirnya, Allah tidak menghitung halaman yang kita baca, melainkan keikhlasan yang kita bawa.
Di situlah tarawih menemukan hakikatnya: bukan sekadar salat malam Ramadan, tetapi latihan menjadi manusia yang lebih lapang—dalam ibadah, dalam pikiran, dan dalam kehidupan sosial. Sebuah fleksibilitas yang bukan tanda kelemahan agama, melainkan bukti kasih sayang Tuhan kepada hamba-Nya.
Wallahu A'lamu Bissawab!
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.










