 Zahwa Ayni Sabilah
Zahwa Ayni Sabilah
Flexing di Ruang Digital: Ketika Ekspresi Diri Mengusik Kesehatan Mental Remaja dan Etika Bermedia
Eduaksi | 2025-12-24 16:19:12Kemajuan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam pola interaksi sosial masyarakat. Media sosial kini menjelma sebagai ruang publik baru yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga menjadi wadah pembentukan identitas dan citra diri. Salah satu fenomena yang semakin menonjol di ruang digital adalah flexing, yaitu perilaku memamerkan kekayaan, gaya hidup mewah, atau capaian tertentu secara berlebihan. Jika ditelaah lebih jauh, fenomena ini tidak sekadar berkaitan dengan ekspresi personal, melainkan memiliki keterkaitan erat dengan kesehatan mental remaja serta nilai-nilai etika bermedia yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Sebagai bagian dari generasi remaja yang tumbuh dan hidup berdampingan dengan media sosial, saya memandang flexing sebagai gejala sosial yang layak mendapat perhatian kritis. Remaja berada pada fase pencarian jati diri dan pembentukan karakter, sehingga lingkungan sosial termasuk ruang digital memiliki pengaruh besar dalam membentuk cara pandang terhadap keberhasilan, kebahagiaan, dan nilai diri. Ketika media sosial didominasi oleh konten pamer kemewahan, ukuran keberhasilan pun cenderung bergeser ke arah yang semakin materialistis.
Perilaku flexing umumnya ditampilkan melalui unggahan foto atau video yang menonjolkan simbol status sosial, seperti kendaraan mewah, barang bermerek, atau gaya hidup eksklusif. Dalam batas tertentu, konten semacam ini sering dipahami sebagai bagian dari kebebasan berekspresi. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa paparan berlebihan terhadap konten pamer kekayaan dapat memicu perbandingan sosial yang tidak sehat, khususnya di kalangan remaja. Teori perbandingan sosial menjelaskan bahwa individu cenderung menilai dirinya dengan membandingkan diri dengan orang lain. Di media sosial, proses perbandingan tersebut menjadi timpang karena realitas yang ditampilkan sering kali telah dikurasi dan dibingkai secara selektif.
Dampak flexing terhadap kesehatan mental remaja tidak dapat diabaikan. Sejumlah riset mengungkapkan bahwa konsumsi konten semacam ini berkorelasi dengan meningkatnya kecemasan, perasaan rendah diri, serta tekanan psikologis. Remaja yang belum memiliki kematangan emosional maupun kestabilan ekonomi berpotensi merasa tertinggal dan gagal, meskipun persepsi tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi kehidupan yang sebenarnya. Dalam jangka panjang, situasi ini dapat mengikis rasa syukur, menumbuhkan iri hati, dan melemahkan daya tahan mental.
Ditinjau dari nilai-nilai sosial dan keagamaan yang dijunjung tinggi dalam masyarakat Indonesia, fenomena flexing patut menjadi bahan refleksi bersama. Budaya pamer bertentangan dengan prinsip kesederhanaan, empati, dan tanggung jawab sosial. Ketika ruang digital dipenuhi oleh glorifikasi kemewahan, solidaritas sosial berpotensi melemah, sementara kesenjangan psikologis antarmasyarakat semakin melebar.
Di sisi lain, aktivitas di ruang digital Indonesia juga berada dalam kerangka regulasi UU ITE yang bertujuan menjaga ketertiban, etika, dan keamanan dalam aktivitas elektronik. Namun, dalam praktiknya, undang-undang ini kerap menuai perdebatan karena dianggap mengandung pasal-pasal multitafsir yang berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Fenomena flexing sendiri tidak secara langsung melanggar UU ITE selama tidak memuat unsur penipuan, ujaran kebencian, atau pencemaran nama baik. Meski demikian, konflik kerap muncul ketika konten flexing memancing kritik atau sindiran publik yang kemudian berujung pada pelaporan hukum.
Bagi remaja, situasi tersebut menciptakan ruang digital yang serba dilematis. Di satu sisi, media sosial mendorong ekspresi diri, tetapi di sisi lain, ancaman sanksi hukum membuat ruang dialog menjadi kaku dan penuh kehati-hatian. Akibatnya, UU ITE kerap digunakan sebagai instrumen penyelesaian konflik sosial yang sejatinya berakar pada persoalan etika dan rendahnya literasi digital, bukan semata-mata pelanggaran hukum.
Dalam pandangan saya sebagai remaja, persoalan flexing, kesehatan mental, dan UU ITE perlu disikapi secara bijaksana dan proporsional. Keberadaan hukum memang penting untuk menjaga ketertiban, tetapi tidak dapat berdiri sendiri tanpa diimbangi dengan pembinaan moral dan penguatan literasi digital. Prinsip hukum sebagai *ultimum remedium* perlu ditegaskan agar pendekatan pidana tidak menjadi pilihan utama dalam merespons dinamika sosial di ruang digital.
Oleh karena itu, diperlukan upaya kolektif untuk menciptakan ruang digital yang lebih sehat dan beradab. Pertama, penguatan literasi digital berbasis nilai harus ditanamkan sejak dini, khususnya di kalangan remaja. Literasi ini tidak hanya mencakup aspek teknis, tetapi juga kesadaran etis, empati sosial, serta pemahaman tentang kesehatan mental. Remaja perlu dibimbing untuk menyadari bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh pengakuan virtual maupun simbol materi.
Kedua, evaluasi berkelanjutan terhadap implementasi UU ITE perlu dilakukan agar sejalan dengan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan hak asasi manusia. Penegakan hukum harus mampu membedakan antara kritik yang konstruktif dan tindakan yang benar-benar merugikan pihak lain. Selain itu, platform media sosial dan media massa memiliki tanggung jawab moral untuk mendorong hadirnya konten yang lebih edukatif, inspiratif, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.
Pada akhirnya, flexing bukan sekadar tren di media sosial, melainkan cerminan tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi, kesehatan mental remaja, dan etika bermedia. Tanpa sikap yang arif, fenomena ini berpotensi merusak tatanan sosial dan melemahkan karakter generasi muda. Dengan pendekatan yang menekankan nilai, tanggung jawab, dan kebijaksanaan, ruang digital Indonesia dapat menjadi ruang yang tidak hanya bebas secara hukum, tetapi juga sehat, bermoral, dan bermartabat.
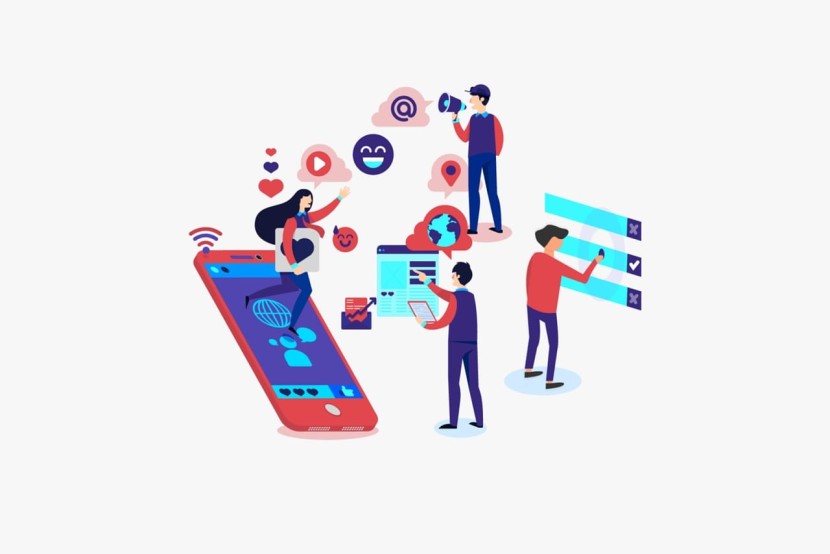
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.











