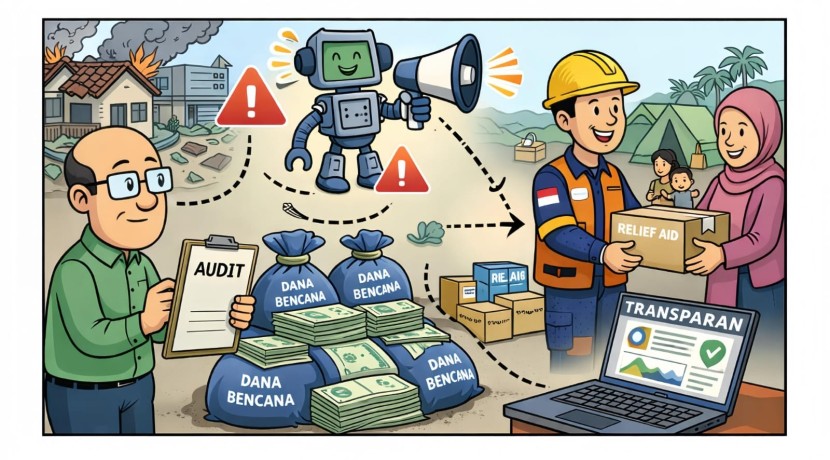Ananda Atikah Az Zahra
Ananda Atikah Az Zahra
Banjir Sumatra: Bencana Politik yang tak Diakui
Politik | 2025-12-17 05:53:00
Bencana besar kembali menghantam Sumatra. Cerita yang muncul sama, rumah hanyut, jaringan komunikasi terputus, warga terisolasi, dan bantuan terlambat datang. Tetapi ada satu pola lain yang juga selalu berulang, bencana sebesar ini yang jarang sekali menjadi sorotan nasional.
Setiap kali bencana muncul, narasi yang disampaikan ke publik hampir selalu berhenti pada dua hal, “cuaca ekstrem” atau “curah hujan yang tinggi.” Namun kita semua tahu, terutama bagi yang mengikuti perkembangan lingkungan hidup selama satu dekade terakhir, bahwa banjir di Sumatra tidak lahir semata-mata dari awan gelap. Ada faktor lain yang jauh lebih menentukan, faktor yang sebenarnya berada dalam kendali manusia, yaitu kebijakan tata kelola lingkungan dan pengelolaan ruang hidup.
Dalam berbagai laporan lembaga lingkungan, terlihat jelas bahwa deforestasi di Sumatra terjadi dalam skala yang tidak kecil. Hutan yang dulu menjadi penyangga air dan pelindung tanah kini terpecah menjadi blok-blok perkebunan sawit, tambang, dan kawasan industri. Alih fungsi lahan yang sporadis, ditambah lemahnya pengawasan terhadap izin pemanfaatan hutan, menciptakan kondisi ekologis yang rentan. Ketika curah hujan meningkat, tanah yang kehilangan vegetasi tak lagi mampu menahan air. Sungai tak punya ruang, dan limpasan air hanya punya satu arah yaitu pemukiman warga. Hal ini semakin memperjelas bahwa apa yang terjadi di Sumatra hari ini adalah hasil dari puluhan tahun keputusan politik yang serampangan.
Ini bukan lagi persoalan warga yang membuang sampah sembarangan atau menebang satu-dua pohon di halaman rumah. Ini adalah masalah kebijakan ruang, keputusan politik, dan prioritas pembangunan. Banyak izin pelepasan kawasan hutan diberikan selama bertahun-tahun atas nama kepentingan ekonomi, tetapi risiko ekologisnya ditanggung oleh masyarakat di hilir.
Ironisnya, ketika banjir datang, beban moral justru kembali diarahkan ke warga, “Kurang disiplin”, “Tidak menjaga lingkungan”, atau “Perlu edukasi kebersihan”. Sementara itu, skala kerusakan yang lahir dari keputusan struktural sering tidak disebutkan sama sekali. Kebijakan yang memengaruhi jutaan hektar ruang hidup jarang dipersoalkan, tetapi perilaku individu dievaluasi habis-habisan. Ketimpangan narasi ini tentunya bukanlah sebuah kebetulan, ini bagian dari bagaimana masalah lingkungan diletakkan di ruang publik, terlihat sederhana, seolah apolitis, padahal sangat politis.
Satu hal yang perlu kita pertanyakan adalah minimnya perhatian nasional. Ketika bencana besar terjadi di Jakarta atau Jawa Barat, sajian berita berlangsung berhari-hari. Namun ketika tragedi melanda Sumatra, Papua, atau wilayah luar jawa lainnya, liputan sering kali terputus-putus dan mengalir lambat. Padahal dampaknya sama, bahkan sering lebih berat karena infrastruktur penanganan bencana di wilayah luar Jawa tidak
sepadat pusat. Ini menunjukkan bahwa bencana bukan hanya soal geografi. Ia juga soal prioritas. Soal siapa yang lebih dianggap penting. Soal daerah mana yang diberi ruang lebih besar dalam percakapan nasional.
Dalam situasi seperti ini, dampak psikologis pada masyarakat kerap luput dibicarakan. Warga yang kehilangan rumah berulang kali hidup dalam ketidakpastian yang menguras energi emosional. Banyak yang mengigau “air, air, banjir” di malam hari, mereka mengalami kecemasan akan hujan, seolah bencana berikutnya hanya menunggu giliran.
Kerentanan itu diperparah oleh situasi di lapangan. Ada warga yang dilaporkan kehilangan harta benda karena dicuri saat mereka mengungsi, dan hoaks mengenai ancaman tsunami juga sempat memicu kepanikan massal, yang mengakibatkan anak-anak hingga orang tua berlarian tanpa arah, beberapa terjatuh dan terinjak. Dampak-dampak ini mungkin tidak tertangkap kamera, tetapi ia memengaruhi cara masyarakat dalam memaknai keamanan dan masa depan mereka di negara ini.
Dalam kondisi seperti ini, warga justru menjadi pihak pertama yang bergerak. Komunitas lokal membuka dapur umum, Influencer menggalang donasi bahkan ada yang turun langsung ke lokasi, dan relawan bekerja tanpa banyak sorotan. Mereka mengisi ruang kosong yang seharusnya diisi negara. Bukan karena negara tidak mampu, tetapi karena penanganan bencana sering kali tidak berada di puncak daftar prioritas, baik dari sisi anggaran maupun kesiapan sistem.
Kita tidak bisa terus memandang bencana sebagai kejadian alamiah semata. Banjir di Sumatra adalah penanda bahwa ruang hidup kita dikelola dengan logika yang tidak berpihak pada keberlanjutan. Ketika hutan ditebang tanpa perhitungan, ketika izin konsesi diberikan tanpa pengawasan, dan ketika aliran sungai dipersempit oleh pembangunan, maka bencana hanyalah soal giliran.
Sebagai generasi muda sekaligus calon penerus bangsa, kita berhak mengkritisi sekaligus bertanya, masa depan seperti apa yang sedang dibangun jika keselamatan manusia saja bisa dikompromikan demi keuntungan jangka pendek? Orang-orang yang mengambil keputusan mungkin tidak lagi ada dalam dua puluh atau tiga puluh tahun mendatang. Tetapi kita akan tetap hidup di sini, di tengah cuaca yang makin ekstrem, udara yang kian kotor, dan banjir yang semakin sering.
Di tengah semua itu, solidaritas warga terbukti menjadi garda terdepan. Ini bukan sekadar slogan “warga bantu warga.” Ini kenyataan yang sedang terjadi, masyarakat menjadi penopang utama ketika pemerintah belum mampu hadir sepenuhnya.
Banjir di Sumatra bukanlah sekadar bencana alam. Banjir di Sumatra adalah cerminan bagaimana keputusan politik membentuk cara kita menghadapi krisis ekologis, dan jika kebijakan ini tidak diubah, kita hanya tinggal menunggu waktu sampai tragedi berikutnya tiba dengan skala yang lebih besar.
Penulis:
Ananda Atikah Az Zahra
Mahasiswa Psikologi Universitas Airlangga
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.