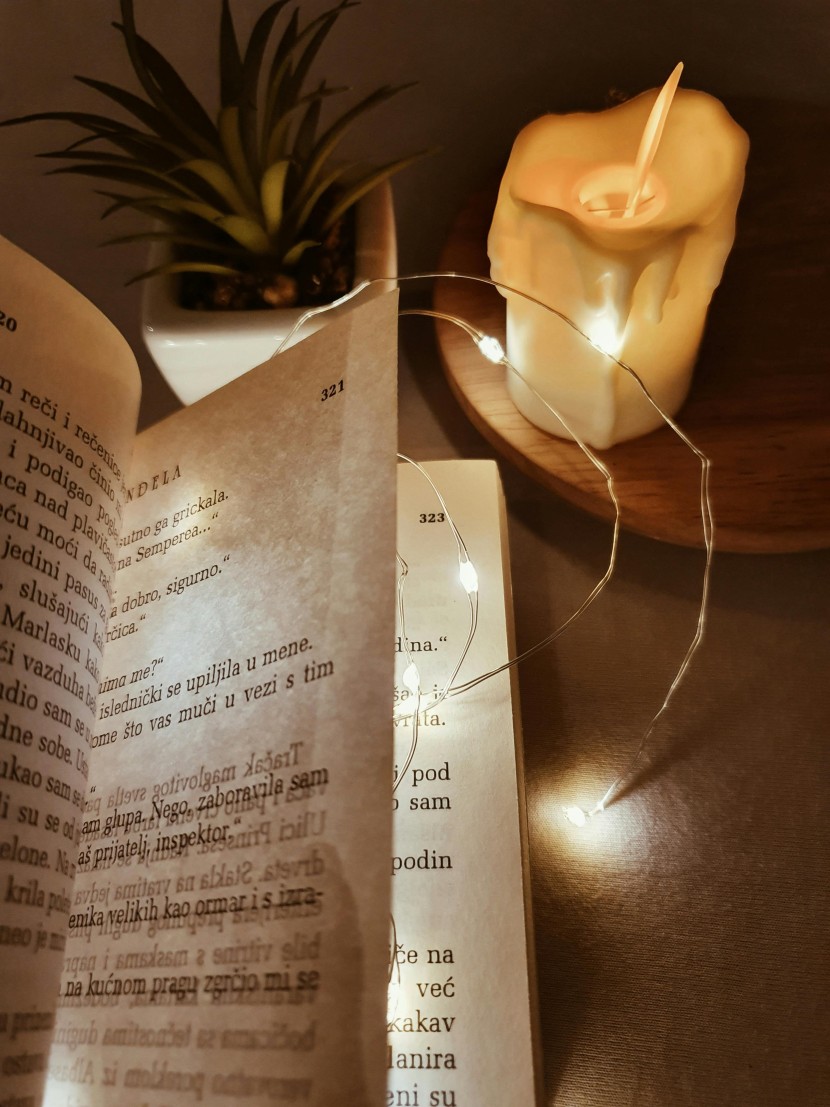Lulu Naura Nur Syahidah
Lulu Naura Nur Syahidah
Di Antara Arsip dan Api: Kekerasan yang Sah, Kekerasan yang Ramai
Sastra | 2026-01-04 21:18:16
Cerpen Bagaimana Saya Bertemu Orang yang Telah Saya Eksekusi karya Era Ari Astanto dan cerpen Merebut Tanah karya Supartika sama-sama mengangkat tema kekerasan, tetapi melalui jalur penceritaan yang tampak berlawanan. Cerpen Era Ari Astanto bergerak dalam ruang sunyi, administratif, dan nyaris steril, dengan tokoh utama seorang eksekutor negara yang menjalankan tugasnya tanpa emosi. Sebaliknya, cerpen Supartika menghadirkan kekerasan dalam ruang komunal yang riuh, penuh teriakan, amarah, bau arak, dan api, melalui konflik antara individu dan adat. Meski berbeda secara suasana dan bentuk, kedua cerpen ini bertemu pada satu persoalan mendasar: kekerasan yang dilegitimasi oleh sistem kekuasaan, baik negara maupun adat, selalu menyingkirkan manusia sebagai subjek.
Perbandingan kedua cerpen ini jarang dibahas secara mendalam karena pembacaan umumnya berhenti pada tema besar, seperti kritik terhadap negara dalam cerpen Era Ari Astanto dan konflik adat versus individu dalam cerpen Supartika. Padahal, jika ditelaah lebih jauh, kedua teks sastra ini sama-sama memperlihatkan cara kerja kekuasaan yang menormalisasi kekerasan, serta bagaimana tubuh manusia direduksi menjadi objek yang sah untuk disingkirkan.
Perbedaan paling mencolok antara kedua cerpen terletak pada wajah kekerasan yang ditampilkan. Dalam Bagaimana Saya Bertemu Orang yang Telah Saya Eksekusi, kekerasan hadir tanpa amarah. Tokoh “Petugas” mengeksekusi terpidana mati layaknya rutinitas teknis, seperti mengantar surat atau menyelesaikan administrasi. Ia tidak bertanya tentang keadilan, tidak menimbang moralitas, dan tidak membenci korbannya. Kekerasan dijalankan atas nama prosedur dan keputusan hukum. Negara, dalam cerpen ini, tampil sebagai mesin rapi yang mengubah pembunuhan menjadi aktivitas legal dan sah.
Sebaliknya, dalam Merebut Tanah, kekerasan justru tampil berisik dan emosional. Amuk massa yang menyerang rumah Sudarma didorong oleh kemarahan kolektif atas nama adat dan martabat bersama. Teriakan “bakar” dan “bunuh” menjadi simbol bagaimana kekerasan dilepaskan secara terbuka dan dirayakan sebagai tindakan pembelaan. Jika dalam cerpen Era Ari Astanto kekerasan disenyapkan oleh birokrasi, maka dalam cerpen Supartika kekerasan justru dilegalkan oleh solidaritas komunal.
Namun, perbedaan bentuk ini tidak menghasilkan perbedaan dampak. Dalam kedua cerpen, korban sama-sama kehilangan statusnya sebagai manusia utuh. Bijukan dan Sitifu direduksi menjadi berkas yang harus “ditutup”, sementara Sudarma direduksi menjadi simbol pengkhianatan adat. Dengan cara yang berbeda, kedua sistem kekuasaan tersebut menyingkirkan individu dari ruang kemanusiaannya.
Sudut lain yang jarang disorot adalah kemiripan cara kerja negara dan adat dalam kedua cerpen. Negara dalam cerpen Era Ari Astanto tidak digambarkan sebagai kekuasaan yang brutal secara kasat mata, melainkan sebagai sistem arsip: ada saksi, dokumentasi, surat kematian, dan peti mati. Semuanya tampak sah dan tak terbantahkan. Bahkan ketika kematian itu dipertanyakan, saat orang yang telah dieksekusi muncul kembali, sistem tetap berjalan seolah tidak ada yang keliru. Kebenaran administratif lebih penting daripada realitas kemanusiaan.
Hal serupa tampak dalam cerpen Supartika. Adat tidak hadir sebagai nilai luhur yang melindungi warganya, melainkan sebagai kekuatan mayoritas yang menekan individu. Keputusan paruman adat dan suara orang banyak menjadi alat legitimasi untuk mencabut hak seseorang, bahkan nyawanya. Dalam konteks ini, baik negara maupun adat berfungsi sebagai mesin kebenaran tunggal yang tidak memberi ruang bagi suara personal.
Persamaan lain yang penting terletak pada representasi tubuh manusia. Dalam cerpen Era Ari Astanto, tubuh nyaris tidak memiliki makna. Ia bisa ditembak, digantikan, bahkan dimanipulasi demi kepentingan sistem. Tubuh menjadi bukti administratif, bukan entitas hidup. Sementara itu, dalam cerpen Supartika, tubuh justru sangat hadir: tubuh yang gemetar, berdarah, kepanasan, dan terancam mati terbakar. Namun kehadiran tubuh ini tidak memberi kuasa apa pun; tubuh hanya menjadi sasaran kekerasan kolektif.
Kedua cerpen ini juga memperlihatkan bentuk trauma yang berbeda. Tokoh “Petugas” mengalami kehancuran eksistensial. Ia mempertanyakan realitas kematian dan perannya dalam sistem negara. Traumanya bersifat sunyi, personal, dan tak bisa dibagikan. Sebaliknya, Sudarma mengalami trauma sosial yang konkret: kebenaran hukum yang ia perjuangkan justru berujung pada kehancuran hidupnya. Dalam kedua kasus tersebut, kepatuhan pada sistem tidak pernah benar-benar melindungi manusia.
Dengan demikian, pembacaan perbandingan terhadap Bagaimana Saya Bertemu Orang yang Telah Saya Eksekusi dan Merebut Tanah membuka pemahaman baru bahwa kekerasan paling berbahaya bukanlah yang paling brutal, melainkan yang telah dinormalisasi. Ketika pembunuhan bisa disebut prosedur, dan pembakaran bisa disebut pembelaan adat, manusia kehilangan ruang untuk mempertanyakan keadilan.
Melalui dua cerpen ini, Era Ari Astanto dan Supartika sama-sama menyampaikan kritik tajam terhadap sistem kekuasaan yang merasa berhak menentukan hidup dan mati. Pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan sekadar hukum atau tradisi, melainkan kemampuan manusia untuk tetap melihat sesamanya sebagai manusia, sebelum semuanya terlambat.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.