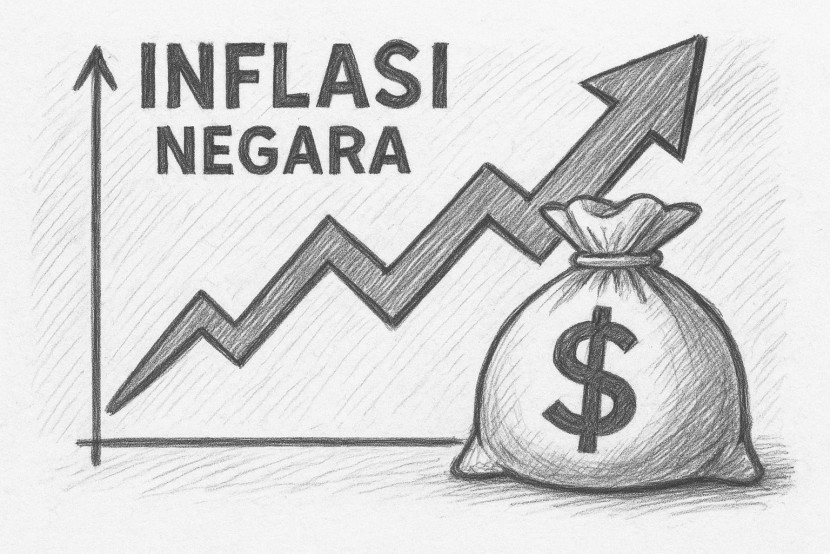Ana Fras
Ana Fras
Magang Berbayar dan Kapitalisme yang Lupa Makna Kerja
Kebijakan | 2025-10-23 07:35:56
Ada sesuatu yang getir dalam berita baik. Pemerintah meluncurkan Program Magang Nasional 2025 dengan janji manis: gaji setara UMR, peluang bagi fresh graduate, dan harapan baru di tengah lesunya lapangan kerja. Sekilas terdengar progresif, nyaris humanis. Tapi seperti banyak hal dalam politik ekonomi modern, keindahannya berhenti di permukaan.
Bank Dunia baru saja menyebut bahwa satu dari tujuh anak muda Indonesia menganggur. Angka yang mestinya jadi alarm, kini justru dijadikan pembenaran bagi program yang menormalisasi kenyataan: bahwa negara sudah menyerah, dan pasar diminta menambal kegagalannya.
Kita hidup di masa ketika bekerja bukan lagi soal martabat, melainkan survival. Magang berbayar, betapa pun dikemas dengan bahasa partisipatif, pada dasarnya adalah kompromi sosial: cara sistem mempertahankan legitimasi, tanpa benar-benar mengubah struktur yang menindas.
Kelas Baru: Mereka yang Menunggu Giliran
Dalam logika kapitalisme, tenaga muda adalah sumber energi murah. Mereka haus pengalaman, tak banyak menuntut, dan siap bekerja keras demi sekeping janji “exposure”. Di sinilah magang menjadi paradoks: ia memberi kesempatan sambil menciptakan generasi pekerja sementara ; mereka yang hidup dalam ruang tunggu panjang menuju pekerjaan yang tak kunjung tiba.
Mereka bukan penganggur, tapi juga belum pekerja. Status sosialnya cair, ekonominya rapuh. Ia adalah cermin paling jujur dari ketimpangan struktural: di satu sisi perusahaan memanen produktivitas, di sisi lain negara berbangga karena berhasil menekan angka pengangguran, meski hanya di atas kertas.
Kita terlalu sering melupakan bahwa sistem ini memang dirancang untuk mempertahankan jarak antara yang punya modal dan yang punya waktu. Yang kaya membeli waktu dengan uang, yang miskin menjual waktunya demi bertahan hidup.
Ketika Kerja Kehilangan Jiwa
Dalam struktur ekonomi kapitalis, kerja direduksi menjadi transaksi. Nilainya diukur dengan jam, bukan makna; dengan upah, bukan manfaat sosial. Tidak heran bila banyak anak muda merasa kelelahan sebelum benar-benar memulai hidup. Mereka belajar bahwa kerja bukan lagi panggilan, tapi kompetisi; bukan sarana aktualisasi, melainkan instrumen akumulasi.
Kita menyaksikan generasi yang tumbuh di antara algoritma dan utang, di mana “berhasil” berarti punya cukup uang untuk membayar tagihan dan cukup waktu untuk menertawakan nasib sendiri di media sosial.
Negara yang Absen, Pasar yang Rakus
Negara seolah hadir—melalui program, regulasi, insentif—namun pada hakikatnya absen. Ia bertindak seperti manajer proyek, bukan pengurus rakyat. Ia menilai rakyat sebagai data, bukan manusia. Maka, alih-alih memperkuat ekonomi riil, negara memilih mengontrak perusahaan untuk mempekerjakan warganya.
Di titik ini, politik ekonomi kehilangan arah moralnya. Ia tak lagi bertanya “apa makna kerja bagi manusia”, tapi “berapa nilai kerja bagi investor.” Negara berubah fungsi: dari pelindung menjadi penyedia tenaga murah bagi pasar global.
Bayangan Sistem yang Lebih Manusiawi
Namun sejarah selalu memberi jalan bagi perenungan. Dalam peradaban yang menempatkan manusia di pusatnya, kerja bukanlah beban ekonomi, melainkan ibadah sosial. Ia bukan sekadar cara mencari nafkah, tapi bagian dari tanggung jawab moral untuk menegakkan kesejahteraan bersama.
Di sana, negara tidak sekadar mengatur, tapi menjamin. Distribusi harta bukan hasil belas kasih, melainkan kewajiban sistemik. Kekayaan tidak boleh berhenti di tangan segelintir orang, sebab keseimbangan sosial adalah bagian dari etika publik.
Itu bukan utopia religius; itu adalah rasionalitas moral yang pernah menjadi fondasi peradaban besar—dan bisa jadi, satu-satunya cara keluar dari siklus absurditas ekonomi hari ini.
Epilog
Magang berbayar hanyalah gejala kecil dari penyakit besar bernama kapitalisme. Ia bukan solusi, melainkan penundaan penderitaan. Selama orientasi ekonomi masih berpusat pada modal, bukan manusia, selama kerja hanya dianggap instrumen produksi, bukan ekspresi nilai, maka setiap kebijakan akan berakhir sama: tampak bijak, tapi kehilangan jiwa.
Dan ketika negara sibuk mengelola statistik, generasi mudanya perlahan kehilangan harapan—bahwa kerja bisa berarti sesuatu selain bertahan hidup.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.