 Riska Putri Ersa Bella
Riska Putri Ersa Bella
Antara Kuota dan Kultur: Menakar Peluang Perempuan Jepang, Indonesia, dan Belanda di Dunia Politik
Politik | 2025-10-13 19:27:21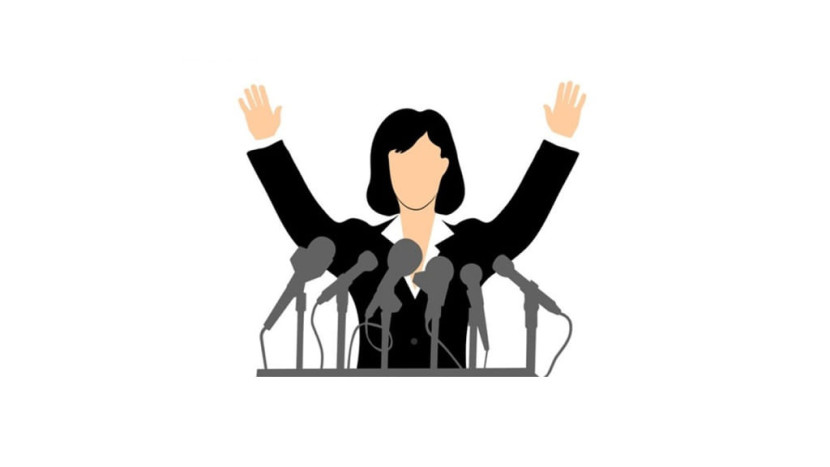
Isu Gender merupakan masalah sosial dan politik yang secara konsisten menarik perhatian seluruh dunia. Menurut Judith Butler (1990) dalam Gender Trouble, gender bukan sebuah realitas biologis melainkan sebuah konstruksi sosial dimana membentuk tingkah laku, peran, dan ekspektasi masyarakat baik kepada laki-laki maupun perempuan. Ketika ketidaksetaraan gender terjadi maka pada saat struktur sosial dan politik menempatkan wanita dalam posisi yang lebih rendah atau jauh kebawah, termasuk dalam aspek kekuasaan dan proses pengambilan keputusan.
Dalam konteks politik, Anne Philips (1995) dalam The Politics of Presence menekankan bahwa representasi yang deskriptif dan substantif sangat penting. Bukan hanya jumlah dari perempuan saja yang hadir, tetapi juga partisipasi aktif mereka dalam merumuskan sebuah kebijakan.
Sejak tahun 19998, setelah adanya reformasi, Indonesia telah mulai menggunakan langkah proaktif supaya jumlah perempuan di DPR meningkat. Keluarnya UU No 10 Tahun 2008, setiap partai politik mengharuskan daftar calon anggota legeslatif terdapat Perempuan.
Kebijakan tersebut telah memperbesar jumlah perempuan di DPR. Dari yang awalnya tahun 2004 11,8% kemudian saat pemilu 2024 kurang lebih tercatat 22%. Akan tetapi meskipun adanya kuota yang sudah mempermudah akses, nyatanya banyak kandidat perempuan masih diletakkan di posisi ”tidak strategis” dalam daftar partai, yang mengakibatkan kemungkinan sedikitnya mereka terpilih.
Di sisi lain, budaya patriarki masih berdiri kokoh di tingkat lokal. Dalam banyak situasi, keberadaan perempuan khususnya di politik sering kali terkait dengan sosok laki-laki, suami, ayah, atau pemimpin partai. Figur-figur seperti Sri Mulyani, Tri Rismaharini, dan Khofifah Indar Parawansa membuktikan bahwa perempuan mampu menjangkau struktur yang didominasi laki-laki, tetapi mereka-mereka ini masih penjadi pengecualian, bukan norma.
Sebagai negara yang sudah berkembang, Jepang menghadirkan sebuah pertentangan yang menarik yaitu perekonomian yang sudah canggih namun memiliki politik yang konservatif. Menurut Inter Parliamentary Union (IPU, 2024), perempuan hanya menduduki10,3% kursi di dewan rendah dan 26% di dewan tinggi.
Ternyata salah satu sumber permasalahannya berada pada nilai-nilai tradisional ”Ryousai Kenbo” (良妻賢母) “istri yang baik, ibu yang bijak” hal ini masih mempengaruhi harapan dari Masyarakat terhadap Perempuan. Dunia politik dipandang sebagai wilayah laki-laki, sedangkan Perempuan diharapkan untuk levbih memperhatikan urusan keluarga (rumah).
Berbeda dengan Indonesia, Jepang masih belum menerapkan kebijakan kuota yang bersifat wajib. Inisiatif perubahan seperti program Womenomics yang dicetuskan Sinzo Abe lebih focus pada peningkatan keterlibatan ekonomi, dibandingkan politik. Figur seperti gubernur Tokyo Yuriko Koike merupakan salah satu pengecualian yang sulit diungkap, yang berhasil menerobos batatas an patriarki dalam ranah politik Jepang.
Kultur politik yang bersifat hierarkis dan system partai yang didominasi laki-laki memperkuat kekuasaan laki-laki. Di dalam parlemen, ada norma-norma sosial yang menyulitkan perempuan untuk berbicara dengan tegas, kuat tanpa mendapatkan cap ”tidak feminim”. Maka, tantangan yang dihadapi Jepang bukan berasal dari atauran hukum, melainkan dari hambatan-hambatan budaya dan norma-norma sosialyang sudah mengakar.
Kali ini berbeda dengan Indonesia dan Jepang, negara kincir angin yaitu Belanda dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat kesetaraan gender paling tinggi di dunia, dianggap sebagai negara yang baik bagi perempuan. Menurut World Economic Forum (2024), perempuan menduduki 48% kursi di parlemen tanpa kebijakan kuota. Budaya egaliter yang telah ada sejak abad ke-20, bersama dengan pendidikan gender yang diberikan sejak dini, telah menciptakan suasana sosial yang mendukung partisipasi perempuan dalam dunia politik.
Tahun 1970-an gerakan feminis di Belanda, seperti Dolle Mina, memperjuangkan kesetaraan dalam bidang kerja dan politik. Oleh karena itu, saat ini banyak perempuan yang menduduki jabatan strategis, seperti Sigrid Kaag, mantan Menteri yang menolak budaya politik yang maskulin serta mendorong pendekatan politik yang mengedepankan etika dan empati.
Keseuksesan yang diraih oleh Belanda ini menunjukkan bahwa transformasi budaya memiliki nilai-nilai yang setara dengan perubahan struktural. Adanya kebijakan kuota bukanlah satu-satunya solusi sistem sosial yang mendukung pemerataan jauh lebih efektif dan akan berjangka panjang.
Indonesia memiliki kuota minimum 30% meningkatkan kehadiran perempuan secara resmi budaya patriarki dan struktur partai tertutup. Jepang tanpa kuota, budaya tradisional partisipasi rendah di dalam DPR norma sosial dan pandangan tradisional mengenai gender. Belanda tanpa kuota resmi, budaya setara representasi hampir seimbang tantangan minim terhadap partisipasi tinggi di tingkat eksekutif. Tanpa adanya perubahan dalam aspek budaya dan kelembagaan, kuota hanya menghasilkan representasi simbolik, bukan kekuasaan yang nyata. Hal ini terlihat di Indonesia banyak Perempuan “terlibat” dalam ranah politik, namun sedikit yang “berpengaruh”. Sementara itu, Jepang bahkan belum sepenuhnya membuka kesempatan karena struktur siosialnya masih enggan menerima perubahan. Di sisi lain Belanda memberikan contoh bahwa budaya yang setara dan dukungan dari Masyarakat bisa menghasilkan kesetaraan politik tanpa adanya tekanan dari hukum. Keberhasuilan tersebut tergantung pada system partai yang jelas dan Masyarakat yang menghargai perbedaan.
Perbandingan ini menunjukan bahwa pencapaian kesetaraan gender dalam bidang politik tidak dapat dilakukan hanya dengan menerapkan system kuota atau peraturan tertentu. Meskipun kuota sangat penting seperti yang terlihat di Indonesia, hal itu tidak akan berarti tanpa adanya perubahan dalam nilai sosial yang mendorong Perempuan untuk terus berpartisipasi dan didengar. Pelajaran dari Jepang menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi tidak selalu berbanding lurus dengan kemajuan sosial. Sementara itu, Belanda adalah contoh yang menunjukan bahwa pendidikan untuk kesetaraan dan budaya yang egaliter adalah landasan jangka Panjang untuk mewujudkan politik yang adil dan inklusif.
Dari perbandingan Indonesia, Jepang, dan Belanda, bisa disimpulkan bahwa kuota politik hanya jalan awal, sedangkan budaya adalah arena utama dalam perjuangan untuk kesetaraan gender.
Indonesia sedang mengalami refprmasi yang mendalam, Jepang masih terikat pada nilai-nilai tradisional, sementara Belanda telah menunjukan bahwa perubahan dalam budaya dapat menciptakan demokrasi yang setara tanpa adanya tekanan dari hukum. Partisipasi politik Perempuan tidak hanya memperkuat system demokrasi, tetapi juga membantu menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan berorientasi pada kemanusiaan. Seperti yang diungkapkan Kofi Annan, “Ketika Perempuan berkembang, seluruh Masyarakat juga mendapatkan manfaatnya”. Apabila Perempuan memiliki hak suara yang setara di legislative, demokrasi akan menjadi lebih komprehensif ini bukan sekedar tentang siapa yang berbicara, melainkan juga siapa yang didengar.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.











