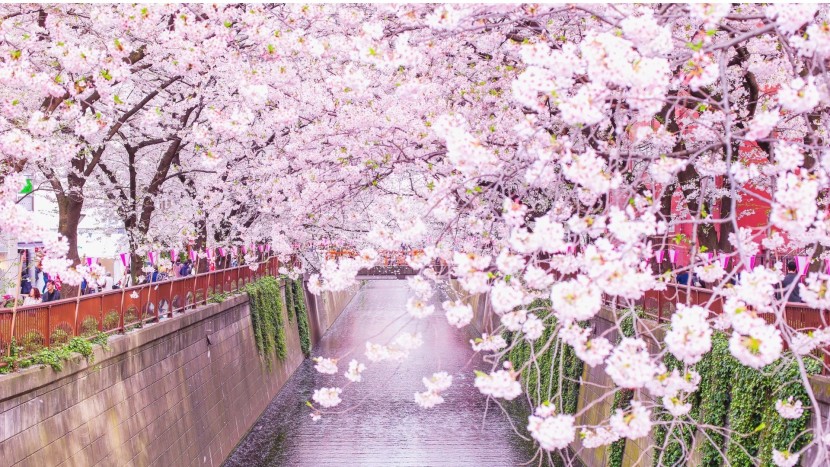Ari J. Palawi
Ari J. Palawi
Mendengar Indonesia: Membangun Karakter Melalui Seni, Nilai, dan Kesadaran
Humaniora | 2025-10-04 17:42:29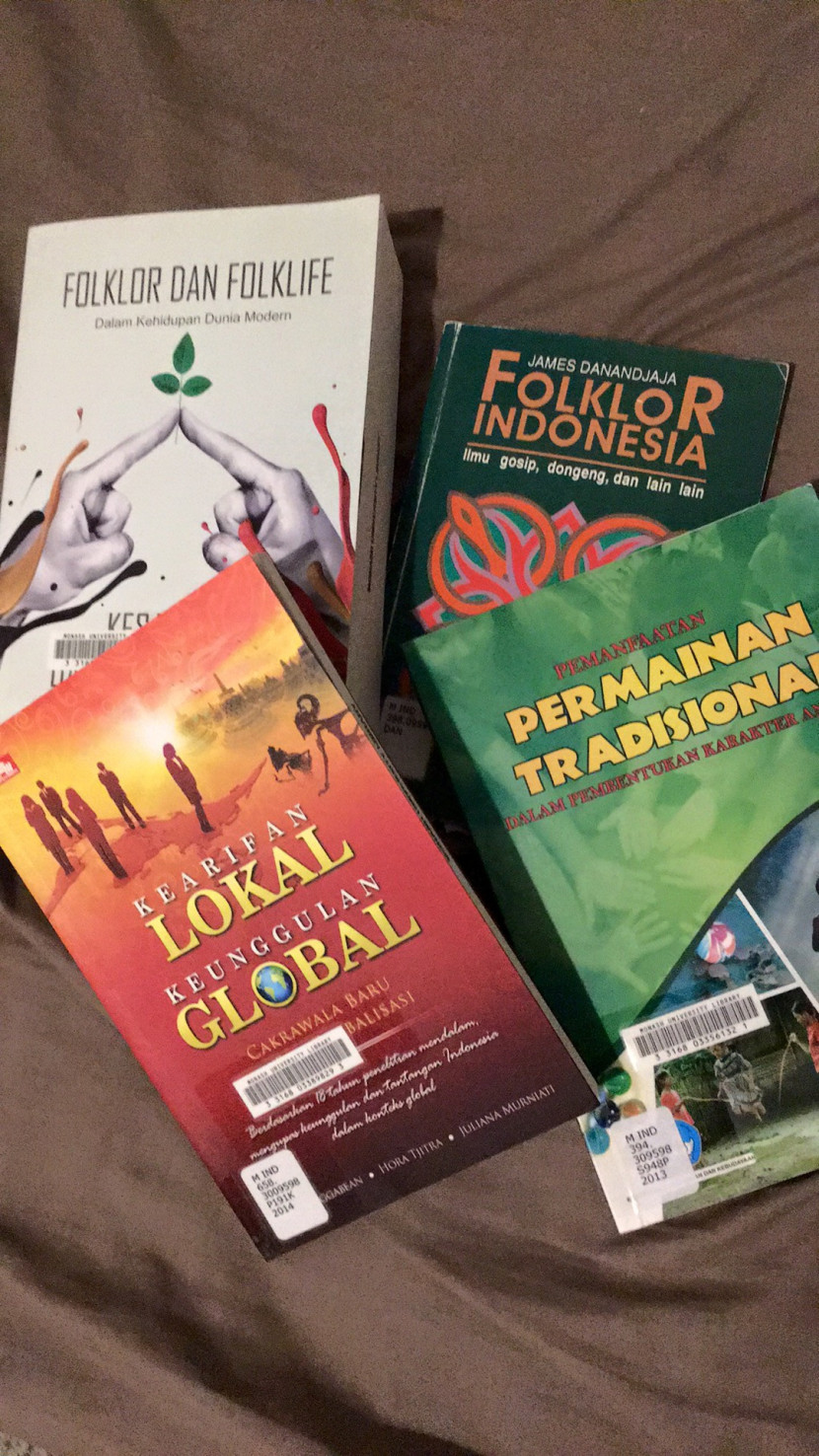
Di dunia yang bergerak secepat kedipan layar, kemampuan untuk mendengar menjadi langka. Kita hidup di tengah suara yang berlimpah, tetapi miskin makna. Semua berbicara, sedikit yang menyimak. Padahal, kebijaksanaan lahir bukan dari seberapa keras seseorang berbicara, melainkan dari seberapa dalam ia mau mendengarkan.
Dalam pandangan Islam, mendengar bukan hanya kemampuan indera, tetapi kecerdasan hati. Al-Qur’an memuji mereka “alladzīna yastami‘ūna al-qaula fayattabi‘ūna ahsanah”—orang-orang yang mendengarkan dengan cermat dan mengikuti yang terbaik dari apa yang mereka dengar (QS. Az-Zumar:18). Mendengar berarti memilah, merenung, dan memilih kebaikan; bukan sekadar menyerap, tapi menghidupkan yang bernilai.
Kearifan itu sesungguhnya telah lama hidup di tengah budaya kita. Dalam gamelan, setiap penabuh belajar menahan diri, karena harmoni hanya lahir bila semua suara saling memberi ruang. Dalam rapa’i Aceh, satu kesalahan kecil bisa memecah seluruh irama—sebuah pelajaran sederhana tentang tanggung jawab sosial. Dalam pantun Melayu, kritik disampaikan dengan keindahan bahasa; ketajaman disamarkan dalam kelembutan. Semua itu bukan sekadar kesenian, melainkan cara berpikir yang beradab.
Namun kini, banyak dari nilai itu mulai pudar. Kita kehilangan kebiasaan mendengar yang mendalam. Suara digital yang riuh membuat kita terbiasa bereaksi cepat, bukan berpikir jernih. Padahal dalam diam, pikiran menemukan bentuk, dan hati menemukan arah. Keheningan bukan kekosongan; ia adalah ruang bagi kesadaran tumbuh.
Seni dan budaya menawarkan cara untuk menemukan kembali keseimbangan itu. Melalui musik, manusia belajar bahwa keindahan menuntut disiplin; melalui tarian, manusia memahami bahwa kebebasan sejati lahir dari keteraturan; melalui puisi dan cerita rakyat, manusia belajar bahwa kata bisa menjadi jembatan, bukan senjata. Seni bukan pelarian dari realitas, tetapi cara mengolahnya agar lebih manusiawi.

Pendidikan seni sesungguhnya bukan sekadar pelatihan keterampilan, tetapi pembentukan karakter. Anak yang belajar memainkan alat musik belajar tentang sabar dan teliti; penari belajar tentang ritme tubuh dan tanggung jawab pada ruang; pelukis belajar tentang fokus dan kesederhanaan. Semua itu membentuk kebiasaan batin: disiplin, empati, dan rasa hormat terhadap waktu. Dalam bahasa Islam, nilai ini adalah ihsan—berbuat dengan sebaik-baiknya, dalam hal sekecil apa pun.
Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan.” Dalam kehidupan modern, keindahan bukan hanya rupa, melainkan kualitas perilaku: integritas, kejujuran, dan manfaat. Maka, setiap karya yang lahir dari niat baik—sebuah lagu, tulisan, atau gerak tari—bisa menjadi amal jika memperindah akhlak. Seni menjadi cara berdakwah yang lembut: mengajak tanpa menggurui, menyentuh tanpa menghakimi.

Kini kita memerlukan pergeseran cara pandang: dari sekadar mengonsumsi budaya menjadi pencipta nilai. Dari hanya menikmati bunyi, menjadi manusia yang sadar makna di baliknya. Kita perlu membangun budaya baru: budaya mendengar, membaca, dan berkarya dengan kesadaran. Mendengar untuk memahami, membaca untuk mencerahkan, dan berkarya untuk memberi manfaat. Tiga hal sederhana ini dapat menjadi inti peradaban baru—berakar di masa lalu, berorientasi pada masa depan.
Kita bisa memulai dari hal kecil. Dengarkan kisah orang tua, pelajari lagu daerah, tulis ulang cerita rakyat dengan gaya modern, atau abadikan ritual kampung menjadi film pendek. Setiap tindakan kecil yang dilakukan dengan cinta adalah bagian dari kerja kebudayaan. Karena sejatinya, kebudayaan tidak diwariskan dengan kata-kata, melainkan dengan kebiasaan yang dijalani.
Dalam dunia pendidikan, pendekatan seperti ini dikenal sebagai experiential learning—belajar melalui pengalaman. Islam telah lebih dulu mengajarkannya sebagai amal saleh: ilmu yang hidup karena diamalkan. Generasi yang hanya diajari teori akan tahu, tapi tidak selalu peka. Generasi yang diajak mengalami akan tumbuh menjadi manusia yang sadar dan tangguh.

Seni juga mengajarkan kebijaksanaan sosial. Seorang pemain musik tahu kapan harus tampil dan kapan menahan diri. Ia tahu bahwa diam bukan berarti tidak berperan, karena jeda pun adalah bagian dari harmoni. Dalam kehidupan, kesadaran seperti ini membentuk pribadi yang tidak mudah reaktif, tidak terjebak dalam egonya, dan tahu cara menjaga keseimbangan antara kata dan diam.
Nilai-nilai seperti amanah (jujur), tawazun (seimbang), dan ihsan (berbuat baik dengan keindahan) yang tumbuh dari ajaran Islam dan tradisi Nusantara sesungguhnya adalah fondasi bagi masyarakat modern yang beradab. Jika nilai-nilai itu dihidupkan dalam ruang pendidikan dan seni, maka kita sedang menyiapkan generasi yang tidak hanya cerdas intelektual, tetapi juga matang secara moral dan spiritual.
Pendidikan yang berakar pada budaya dan spiritualitas bukan romantisme masa lalu, tetapi strategi masa depan. Dunia hari ini memerlukan manusia yang bisa berpikir rasional sekaligus berperasaan halus, yang bisa bekerja efisien tanpa kehilangan empati. Di tengah krisis nilai dan kebingungan identitas global, bangsa yang mengenal akar dan tahu arah akan tetap kokoh berdiri.

Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat kebudayaan Islam yang kreatif, inklusif, dan progresif. Tapi potensi itu hanya bisa tumbuh jika kita mulai menata ulang perilaku: belajar mendengar lebih dalam, berpikir lebih jernih, dan berkarya dengan kesadaran. Tidak ada kemajuan sejati tanpa kebijaksanaan, dan tidak ada kebijaksanaan tanpa kemampuan mendengar.
Karena pada akhirnya, besar seseorang bukan diukur dari seberapa tinggi ia terbang, tetapi seberapa indah ia menjaga nada hidupnya agar tetap selaras—dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan dirinya sendiri.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.