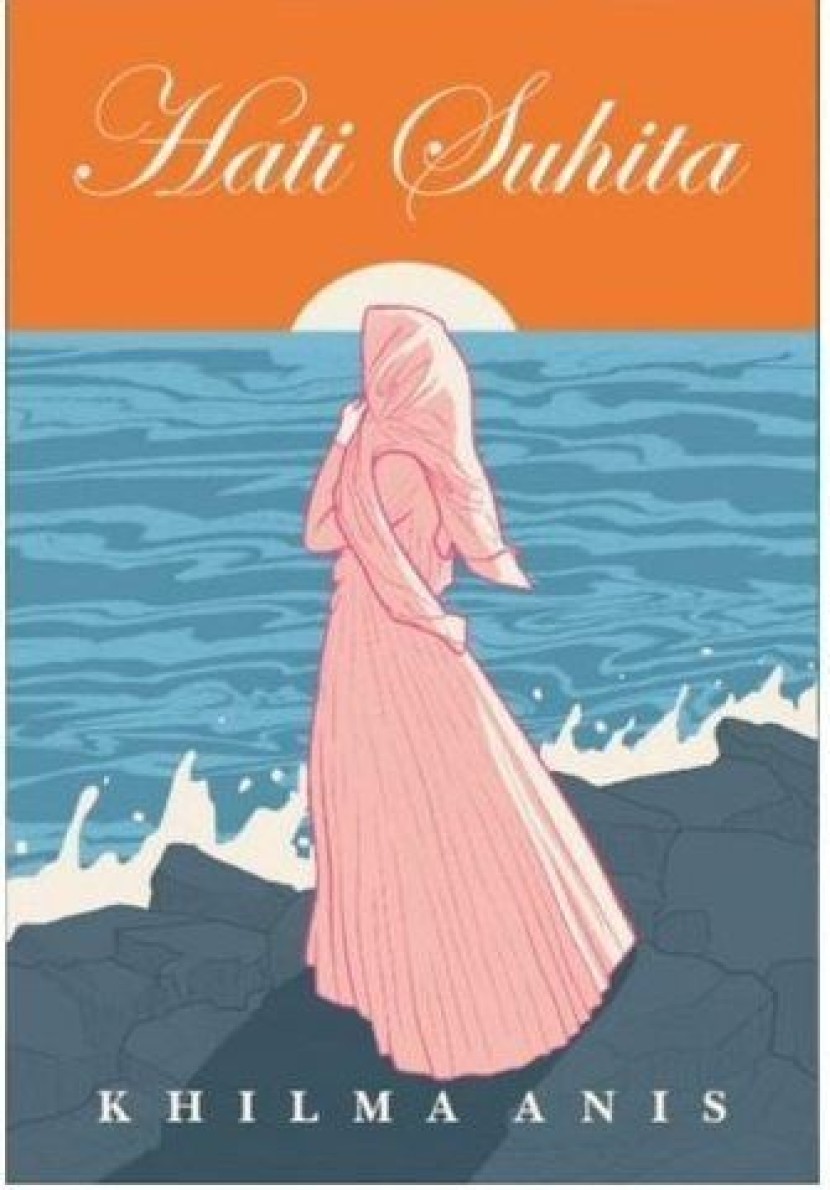Nur Rizka Laila
Nur Rizka Laila
Rapiah dan Corrie, Dua Wajah Perempuan Terjajah dalam Novel Salah Asuhan
Sastra | 2025-05-20 08:38:00Novel Salah Asuhan karya Abdoel Moeis bukan hanya kisah cinta lintas budaya antara Hanafi dan Corrie. Ia adalah refleksi sosial-politik dari zaman kolonial, ketika sistem patriarki dan kolonialisme bekerja sama dalam menindas perempuan. Dua tokohnya, Corrie dan Rapiah, menjadi potret paling gamblang dari bagaimana perempuan baik pribumi maupun Indo-Eropa diperlakukan sebagai “yang lain” dalam sistem kekuasaan ganda: sebagai perempuan dan sebagai subjek jajahan.
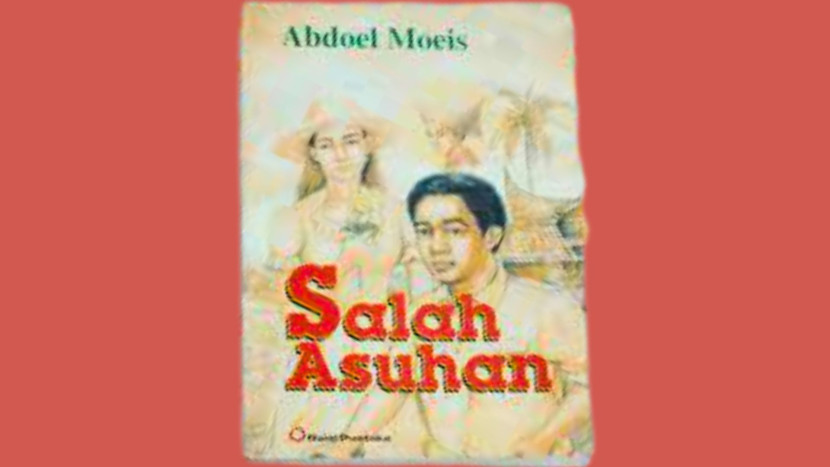
Rapiah, Perempuan Pribumi yang Dibungkam
Rapiah adalah perempuan Minangkabau yang dijodohkan oleh ibu Hanafi demi balas budi. Ia tidak pernah punya suara dalam memilih pasangan, bahkan dalam rumah tangganya sendiri. Rapiah tunduk pada adat dan pada suaminya yang kasar. Ia adalah representasi dari apa yang disebut Gayatri Spivak sebagai subaltern, yaitu kelompok masyarakat yang tidak punya ruang untuk bersuara dalam sistem dominan.
Kutipan berikut menunjukkan bagaimana Rapiah diposisikan sebagai objek tak berdaya:
"Hanafi makin lalu-lalang kepada Rapiah, yang akhirnya dipandangnya bukan lagi 'istri', melainkan 'babu' yang diberikan kepadanya dengan paksa."
Di sini, status Rapiah diturunkan menjadi pelayan. Bukan karena kesalahannya, tapi karena sistem yang menempatkan perempuan sebagai pelengkap bukan subjek yang merdeka. Bahkan ketika ia dihina di depan umum, Rapiah hanya menangis dan tetap bertahan.
"Tetapi istri yang sabar itu sudah tunduk menangis saja, bagaikan insaf akan dirinya."
Dalam perspektif Chandra Mohanty, perempuan seperti Rapiah sering kali direduksi dalam narasi kolonial sebagai sosok pasif dan tunduk, padahal kenyataannya lebih kompleks. Ketundukan Rapiah adalah bentuk keterpaksaan dalam sistem yang membungkam.
Corrie, Perempuan Indo yang Dibuang Karena Cinta
Di sisi lain, Corrie adalah perempuan Indo-Eropa yang sejak awal digambarkan cerdas, modern, dan mandiri. Namun ketika ia menikah dengan Hanafi seorang pribumi ia langsung kehilangan privilese kolonialnya. Komunitasnya mencibir, pekerjaannya terancam, bahkan suaminya sendiri menuduhnya berzina tanpa bukti.
"Aku menuduh engkau berlaku hina di dalam rumahku ini!" – kata Hanafi kepada Corrie.
Tuduhan itu bukan sekadar bentuk konflik rumah tangga, tapi cerminan bagaimana perempuan tetap menjadi objek kecurigaan dan penghakiman moral, bahkan oleh orang yang mereka cintai.
"Badanku rusak, uangku habis, bangsaku melihat kepadaku sebagai kepada najis, itulah namanya 'membuang diri'." – Corrie.
Pernyataan Corrie ini sarat makna. Ia menunjukkan bahwa perempuannya kehilangan semua hal yang membuatnya “berharga” di mata masyarakat karena keputusan menikahi laki-laki pribumi. Dalam kacamata feminisme postkolonial, Corrie terjebak dalam identitas liminal tidak sepenuhnya diterima sebagai orang Eropa, dan tidak pula diterima sebagai pribumi.
Dua Perempuan, Dua Luka, Satu Sistem
Corrie dan Rapiah berbeda dalam kelas sosial dan ras, tapi keduanya sama-sama mengalami diskriminasi sistemik. Mereka adalah wajah dari perempuan yang dijajah secara ganda: oleh kolonialisme dan patriarki. Hal ini ditegaskan oleh teori Mohanty bahwa perempuan tidak bisa dipukul rata pengalamannya, karena ras, kelas, dan sejarah kolonial membentuk pengalaman unik bagi masing-masing.
Dalam kisah Corrie, kita melihat bagaimana perempuan yang menyeberang batas sosial akan dibuang dari dua sisi. Sementara Rapiah, meski tinggal di zona “yang diterima adat”, tetap tak memiliki kuasa untuk bicara. Keduanya ditindas oleh standar dan sistem yang tidak memberi ruang untuk suara perempuan.
Menyuarakan yang Dibungkam
Abdoel Moeis mungkin tidak secara eksplisit menyatakan kritik feminisme dalam Salah Asuhan, namun kisah Corrie dan Rapiah adalah bukti bahwa sastra dapat menjadi medan perlawanan terhadap ketimpangan. Seperti kata Gayatri Spivak dalam esainya Can the Subaltern Speak?, "yang dibungkam harus diberi ruang untuk bersuara." Dan Salah Asuhan memberi ruang itu bagi kita untuk mendengarkan suara-suara yang selama ini dipinggirkan.
Dengan membaca karya sastra seperti Salah Asuhan melalui lensa feminisme postkolonial, kita tidak hanya mengkaji persoalan sejarah dan budaya, tetapi juga menghidupkan kembali suara perempuan yang selama ini ditenggelamkan oleh sejarah dominan. Sudah saatnya kita mengakui, mendengar, dan belajar dari suara-suara yang selama ini "tidak dianggap".fi makin lalu-lalang kepada Rapiah, yang akhirnya dipandangnya bukan lagi 'istri', melainkan 'babu' yang diberikan kepadanya dengan paksa."
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.